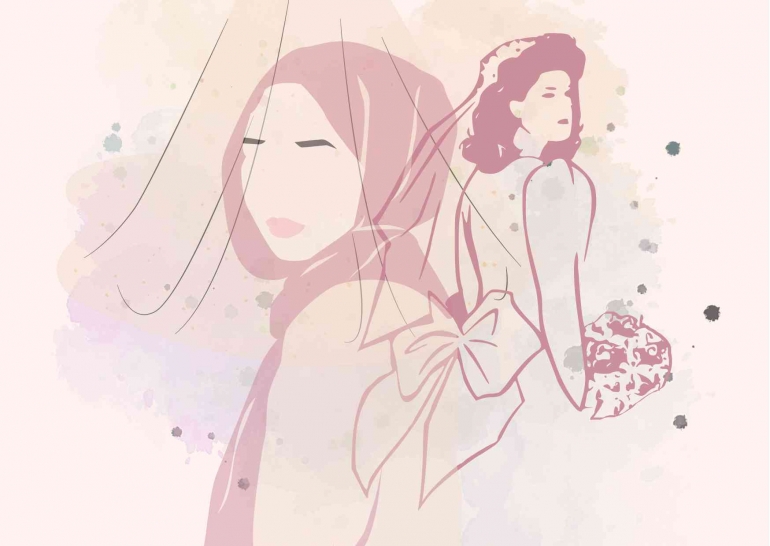Entah berapa helai kertas bertumpuk di meja belajar, yang besok-besok bisa saja bertambah lagi jumlahnya. Entah berapa pesan yang masuk ke ponsel, yang mirisnya mengantar pesan yang sama, itu dan itu lagi.
Selepas lebaran, menjadi hari-hari yang paling tak menyenangkan bagiku, pada masa inilah musim pengantin dimulai. Dan entah sejak kapan pertanyaan perihal pernikahan menjadi kian melekat padaku di hari lebaran hingga musim pengantin tiba.
Jika para petani di desa takut pada musim kemarau yang menyebabkan kekeringan, dan warga di kota yang takut musim hujan karena dapat mendatangkan banjir, maka satu musim lagi yang paling aku takuti, musim pengantin.
Terkadang aku merasa sebal dengan surat-surat beraneka ukuran, warna, dan rupa itu. Meski beragam, intinya tetap satu, isinya tetap sama; sama-sama mengabarkan sebuah kabar yang kerap kali membuat ibuku kepanasan, ya, pernikahan.
Tak apalah jika pesannya masuk ke ponselku, ibu tidak akan melihatnya, tidak akan mengetahuinya. Tapi, jika siang hari surat itu datang ke rumah, tentu saja ibu yang selalu menerima langsung di tangannya. Lalu menumpukkannya di meja belajar dalam kamarku, dan ia akan sudah bersiap dengan raut wajah tegang, rahangnya mengeras, ekspresinya jelas menuntut sesuatu dariku.
"Bu,"
"Kapan kamu menyusul?"
"Maksud ibu?"
"Tuh!" Ibu hanya memberi isyarat dengan satu gerakan dagunya, mengarah ke arah meja belajar di kamarku yang terbuka pintunya. Aku mengerti, setumpuk undangan itu sudah sangat jelas merangkum satu tanya; kapan aku akan menyusul menikah?
Ya, ibu sudah berdiri di depan kamarku. Tahu kapan aku pulang, ibu selalu menungguiku akhir-akhir ini.
"Bu..."