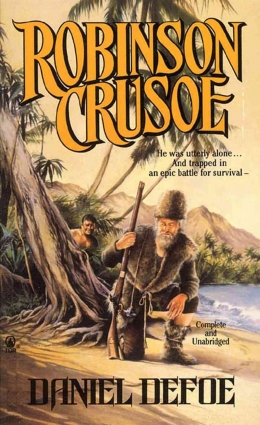Muncul keyakinan yang semakin menguat bahwa krisis ekologis global yang menjumpai manusia dan kemanusiaan hari ini merupakan salah satu titik balik paling kritis yang dihadapi peradaban manusia. Penyebab dari trend ini diyakini oleh beberapa pihak berada dalam kecenderungan destruktif yang menciptakan ketidakberimbangan ekologis.
Basis ketidakberimbangan ini bisa diarahkan kepada banyak kekuatan, tetapi secara luas bisa direduksi pada sedikit trend utama, intensitas konsumsi manusia yang berlipatganda... dikombinasikan sedikitnya kehendak untuk... memahami betapa kebiasaan kita hari ini sedang memroduksi permasalahan di hari esok. (Leigh 2005: 3)
Masalah Ekologis dalam Ranah Kultural: Telisik Historis
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin sering kita dengar para pakar lingkungan mengharapkan keseriusan para pemimpin dunia untuk terlibat aktif dalam usaha mengurangi percepatan krisis global yang mengancam bumi dan semua penghuninya.
Seperti dikatakan Leigh dalam kutipan di atas pelipatgandaan jumlah manusia berdampak secara langsung kepada pelibatgandaan konsumsi yang memunculkan permasalahan serius dalam aspek produksi dan ekspansi di lahan subur dan hutan. Massifikasi asap, sampah, dan polutan lainnya semakin tak terkendali.
Hasrat untuk mengenakan simbol-simbol kemewahan seperti perhiasan dari logam mulia meningkatkan aktivitas pertambangan yang mendapatkan legalitas dari banyak negara. Bangunan-bangunan tinggi semakin memperburuk efek rumah kaca bagi atmosfer bumi.
Kekhawatiran para pakar tersebut semakin menguat ketika mengetahui kurang adanya keseriusan dalam mengurangi dampak krisis ekologis yang dialami manusia. Tentu saja, permasalahan ekologis bukan hanya menjadi ‘konsumsi’ manusia-manusia abad ke-21.
Paling tidak, sejak era kolonial dan industri di Eropa, nalar dan praktik ekspansionis manusia terhadap keliaran dan kekayaan alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi semakin menguat.
Para intelektual yang bergerak dalam ranah kebudayaan juga tidak tinggal diam dalam menyikapi persoalan tersebut. Para pendukung Romantisisme di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, cukup antusias melancarkan kritik pedas terhadap nalar Pencerahan sebagai landasan modernisme yang dianggap membatasi pikiran manusia dalam hukum rasioanlisme, mekanisasi, dan teknologisasi.
Para penggiat aliran dan gerakan ini menelusuri ketidakterbatasan alam dan suasana kehidupan manusia-manusia biasa di perdesaan sebagai alternatif untuk menguji kemampuan kreatif dan tanggung jawab kultural para intelektual, termasuk para sastrawan di dalamnya (Day 1995; Riasanovsky 1995; Schneider 2007; De Paz 2007).
Gerakan ini lahir dari rahim modernisme, tetapi pada akhirnya, menjadi ‘anak nakal’ yang mengkritik nalar modern yang membelenggu kebebasan manusia. Rasionalitas dan teknologi mengekang kemampuan tanpa batas manusia, termasuk menelusuri kemisteriusan alam.

Eksplorasi yang luar biasa terhadap kekuatan alam menjadikan Romantisisme gerakan yang banyak melahirkan karya-karya sastra, filsafat, dan seni rupa yang mengekspos keluarbiasaan alam, meskipun tidak dalam wacana kerusakan ekologis sebagai akibat peningkatan aktivitas ekspansionis dan eksploitasi dalam ranah industri.
Sayangnya, para penulis Romantik memang tidak tertarik untuk terlibat dalam persoalan lingkungan akibat polusi industrial, kumuhnya pemukiman di wilayah urban, mulai berkurangnya lahan pertanian.
Alih-alih, mereka memilih menggunakan transendentalisme untuk membandingkannya dengan pola pikir positivistik-mekanistik dan materialistik yang sebenarnya membelenggu kemampuan berpikir manusia. Meskipun demikian, karya-karya mereka diposisikan sebagai pintu masuk untuk membincang hubungan manusia dengan alam atau lingkungan di dalam karya sastra.
Penyair William Wordswoth, misalnya, sangat tertarik mengeksplorasi hubungan alam non-manusia dengan pikiran manusia alih-alih dia berada di alam dan untuk alam. Ia jarang mendeskripsikan alam secara detil, alih-alih memilih merefleksikan pengalamannya atau pengalaman orang lain tentang alam.
Lebih dari itu, apa yang Wordsworth maknai secara mendalam bukanlah alam sebagaimana yang dilindungi oleh kaum envionmentalis kontemporer. Alam Romantik tidak pernah secara serius terancam, dan dalam keadaan normal bisa jadi miskin terkait keragaman biologis; alih-alih, ia dicintai karena keluasan, keindahan, dan ketahanannya.
Dengan memfokuskan kepada pemandangan adiluhung, utamanya alam pegunungan, Romantisisme Wordsworthian bisa jadi mengalihkan alam dari tempat-tempat yang lebih penting dan secara ekologis berada dalam tekanan yang luar biasa tetapi kurang digambarkan, seperti rawa (Garrard 2004: 43).
Hal yang berbeda dituliskan oleh John Clare, penyair Romantik yang berasal dari kelas pekerja. Dia mengekpsos sensilibitas ekologis terkait tanaman, binatang, dan kehidupan manusia-manusia lokal dalam konteks ekonomi pedesaan yang berada dalam proses penghancuran oleh pembatasan, hilangnya tanah publik.
Jonathan Bate, seorang ekokritijus, menegaskan bahwa puisi-puisi Clare menawarkan sudut pandang bahwa yang puitik atau sastrawi bisa dipahami memberikan pengalaman “pengganti” dan “penyegar” terhadap makna-makna alam yang hilang dalam kesadaran manusia modern yang teralienasi dari jiwanya.
Melalui citra puitik kemanunggalan dengan jagat bisa dirasakan secara langsung, ketimbang harus larut dalam nostalgia (Clark 2011: 21-22).
Praktik kolonialisme Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika ikut berkontribusi bagi munculnya perubahan lanskap alam dan permasalahan ekologis karena eksploitasi hutan untuk usaha pertanian dan perkebunan seperti kapas, kakao, karet, juga industri pertambangan yang jelas-jelas ikut mengubah lanskap wilayah jajahan (Ross 2017).
Manusia-manusia rasional Eropa melampaui rasa takut mendatangi tempat-tempat baru yang mereka klaim sebagai wilayah taklukan; membuat batas yang melindungi koloni-koloni baru mereka dari gangguan warga pribumi irasional.

Kisah Robinson Crusoe (Defoe, 1719) yang terkenal itu, setidaknya, memberikan gambaran bagaimana manusia Eropa dengan logika modern masuk ke jantung peradaban Timur; menguasai alam serta menaklukkan manusia dan budayanya.
Boehmer (2005: 18) memosisikan Robinson Crusoe sebagai teks paradigmatik awal yang menuturkan pengalaman kolonial Eropa secara apik. Seorang pelaut terdampar di sebuah pulau terpencil, untuk menangkal rasa cemas tentang hal yang tidak diketahuinya, ia membangun pemukiman kecil.
Ia mengklaim memiliki tanah itu, membangunnya berdasarkan tradisi Protestan serta memagarinya dengan pagar tinggi. Crusoe membuat konvensi dan aturan berdasarkan ingatannya, menggunakan alat yang ia selamatkan dari kapalnya yang hancur. Dalam ketiadaan masyarakat, menulis jurnal menjadi caranya mengobjektisikasi dan mengkonfirmasi realitas di sekitarnya.
Ia juga melatih burung beo-nya berbicara dengannya dengan memanggil namanya sendiri. Tentu saja, baik burung beo maupun rumah sederhananya tidak mampu mencipta-ulang pengalaman akan rumah.
Pagar yang melindungi mendeklarasikan kerapuhannya. Tak masalah seberapa sering Crusoe, layaknya kolonialis, menegaskan realitas dirinya dan memapankan haknya terhadap ‘kerajaan’ di pulau yang ia tempati, yang tidak diketahui tetap memunculkan kecemasan, direpresentasikan oleh rasa takutnya terhadap kanibalisme.
Ini menjelaskan tujuan Crusoe untuk menjadikan salah satu penyintas dari ritual kanibal yang ia beri nama “Friday” sebagai diri yang akan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang belum diketahuinya.
Dalam nalar manusia kulit putih, wilayah asing yang sesungguhnya sudah ada penghuninya pun bisa diklaim sebagai kekayaan mereka, termasuk di dalamnya adalah kekayaan alam dan manusi-manusia pribumi-kanibal
Betapa banyak kerusakan alam, penderitaan manusia, dan eksploitasi ekonomi yang berlangsung di era kolonial. Namun, sekali lagi, kondisi itu tidak diungkapkan. Konstruksi ideologi “pemagaran/pembatasan wilayah” ala Crusoe menjadi trend yang berkembang dalam sastra Inggris pada abad ke-18 hingga ke-19 ketika kekuatan kolonial sedang mengkosolidasi dirinya di muka bumi.
Banyak karya yang merepresentasikan narasi terkait pemagaran dan kondisi kacau-balau dari tanah biadab yang tak berpagar (Marzec 2007: 3-4). Subjek-subjek yang berada dalam wilayah yang dipagari ataupun secara metaforis menjadi teritori penjajah secara geografis, bisa mengembangkan kehidupan agrikultural, perkebunan dan aktivitas budidaya lain yang bisa menyejahterakan.
Sementara, mereka, orang-orang awam, yang berada di luar garis batas pemagaran adalah subjek biadab yang tidak memiliki kapasitas melakukan proyek modernitas. Rujukan tersebut bukan sekedar merefleksikan fenomena historis. Sebaliknya mereka mengindikasikan perluasan di mana novel Inggris dituliskan di tengah-tengah formasi imperial baru tanah jajahan.
Mengikuti poros semantik Robinson Crusoe yang dibangun dengan oposisi biner “Eropa-beradab vs non-Eropa-tak-beradab”, para penulis “sastra kolonialis” menghamparkan gugus naratif dalam bentuk genre petualangan (adventure) berdimensi politiko-ideologis yang diposisikan sebagai mitos yang menghidupkan kekaisaran Inggris di muka bumi.
Sastra kolonialis merupakan karya sastra yang secara khusus mendukung ekspansi kolonial yang dikalukan manusia-manusia Eropa Barat. Sebagai karya, ia ditulis oleh dan untuk orang-orang Eropa yang menjajah tentang tanah-tanah non-Eropa yang mereka dominasi.
Sastra kolonialis me-nubuh-kan sudut pandang imperialis yang memosisikan superioritas warga dan budaya kulit putih sekaligus menegaskan hak mereka untuk menguasai bangsa-bangsa lain yang diposisikan inferior (Boehmer 2005: 3).

Perjalanan menuju wilayah baru menjadi medan menantang bagi para petualang kulit putih untuk melampaui batas-batas geografis, mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan di seberang lautan sekaligus menjadi penunjuk bagi perluasan peradaban melalui praktik kolonialisme oleh manusia kulit putih (Brantlinger 2009: 30-31).
Dalam situasi diskursif demikian, warga pribumi dikonstruksi menyerahkan wilayah mereka beserta isinya kepada penjajah kulit putih dan memberikan ruang kepada perkembangan peradaban Barat-superior, sedangkan mereka diposisikan sebagai manusia-manusia pribumi yang tengah sekarat.
Alam lingkungan yang cukup kaya dan manusia pribumi yang sudah ditundukkan menjadikan eksploitasi sebagai praktik dan keyakinan akan kebesaran dan kebenaran nalar Eropa, sehingga para penulis karya sastra bergenre petualangan tidak punya kesadaran ideologis untuk mempermasalahkan fakta pergeseran lanskap ekologis di wilayah jajahan.
Sayangnya, tidak banyak penulis besar Inggris di era Victoria yang berkenan merepresentasikannya dalam karya mereka. Kolonialisme bagi mereka cukup diceritakan dalam bentuk kerajinan tangan, binatang, rempah-rempah, kapas, hasil tambang, dan makanan khas dari tanah jajahan.
Dalam kategori “sastra kolonial”, mereka menjadikan wilayah dan masyarakat jajahan sebagai entitas geografi yang berjarak dari metropolitan sehingga tidak mengkonstruksi wacana yang mengerikan tentang penindasan dan perusakan alam oleh manusia-manusia Eropa bernalar modern.
Menurut Boehmer (2005: 2) sastra kolonial adalah karya tulis yang menekankan persepsi dan pengalaman kolonial, ditulis oleh para penulis metropolitan, juga para penulis kreol dan pribumi, selama masa kolonial. Sastra kolonial memasukkan pula karya yang ditulis di Inggris serta di wilayah-wilayah dunia lain.
Meskipun tidak membuat rujukan langsung dengan masalah-masalah kolonial, tulisan metropolitan, fiksi Dickens dan tulisan perjalanan Trolloper, misalnya, berpartisipasi dalam mengorganisir dan memperkuat persepsi Inggris sebagai kekuatan dominan dijagat raya. Mereka berkontribusi pada konstruksi perilaku dan sikap yang menjadikan imperialisme sebagai tatanan banyak hal.
Selain sebagai tanah di seberang lautan yang harus “dipagari” untuk kepentingan kolonialisme Eropa, lingkungan alam di wilayah jajahan juga direpresentasikan sebagai sesuatu yang liar. Keliaran (wilderness) merupakan konstruksi para penulis kulit putih untuk melabeli kehidupan yang tidak sama dengan lingkungan asal mereka.
Lingkungan Afrika, misalnya, merupakan ruang geografis yang dipenuhi oleh keberadaan aneka satwa liar, dari era kolonial hingga saat ini.
Huggan (2008: 51) menjelaskan bahwa pada era kolonial banyak bangunan naratif tentang Afrika yang menempatkannya secara kontradiksi sebagai medan untuk permainan bebas bagi fantasi penaklukan masyarakat Eropa dan kawasan yang dilindungi secara terhormat demi generasi masa mendatang.
Fantasi akan keliaran dan penaklukan masih berlangsung hingga hari ini melalui moda transformasi di mana acara-acara televisi seperti yang ditayangkan National Geographic dan Animal Planets. Kedua saluran tersebut ikut memelihara dan menyebarluaskan keliaran eksotis Afrika, Asia, dan Amerika Latin sebagai realitas yang masih ada di muka bumi.

Hal ini berbeda dengan faksi yang memosisikan satwa-satwa tersebut tidak dalam kerangka “budidaya”, tetapi menarasikan mereka dalam kerangka keliaran yang sebenarnya.
Keliaran ekologis, dengan demikian, dinarasikan berbasis pengalaman, baik dalam semangat perlindungan maupun pembiaran, untuk tetap menjaga kehadiran “yang liar” yang bisa ditonton, dibaca, dan di-fantasi-kan oleh manusia-manusia metropolitan.
Subjek Barat-lah yang mentransformasi konstruksi keliaran tersebut dalam ragam bentuknya, karena manusia-manusia Timur sendiri menganggap segala hal yang dilabeli liar sesuatu yang biasa dan lumrah.
Kepentingan ekonomi dan politik, dalam kondisi demikian, tetap berada dalam kendali manusia-manusia rasional Eropa yang tidak ingin kehilangan situs yang memelihara fantasi mereka tentang keliaran yang jauh dari ruang geografis mereka.
Dalam perkembangan kontemporer kita juga menikmati banyak karya sastra, film, dan televisi yang mengusung tema-tema kebencanaan, baik berupa tornado, aktivitas vulkanologis, banjir, tsunami, kiamat ataupun tema-tema tentang hewan liar, fauna, samudra, dan yang lain.
Semua itu mengindikasikan bahwa terdapat kesadaran kreatif dan kritis untuk menghadirkan persoalan ekologis sebagai basis karya kreatif.
Di satu sisi, kita bisa membaca realitas kultural tersebut sebagai pengakuan bahwa kalau tidak hati-hati kemampuan rasionalitas manusia-manusia modern untuk menemukan teknologi dan menaklukkan alam, seliar apapun, akan menghadiahi manusia penghuni planet dengan banyak kemudahan dan kemajuan hidup.
Namun, di sisi lain, kecanggihan rasionalitas yang disalahgunakan juga bisa menyebabkan kerusakan atmosfer bumi, banjir, erosi, pencemaran udara, masalah limbah, dan lain-lain. Bagaimanapun juga, sastrawan adalah manusia-manusia yang hidup dalam ruang kultural tempat di mana ia berjumpa dan berinteraksi dengan banyak individu dan persoalan sehari-hari.
Termasuk di dalamnya persoalan-persoalan lingkungan yang berlangsung dalam masyarakat dunia hari ini. Dalam konteks kehidupan manusia di abad 20 hingga 21 saat ini, bermacam krisis lingkungan kembali mengancam kehidupan sebagai akibat kerakusan manusia, baik melalui keganasan mesin dan teknologi, perang, ataupun pengetahuan-pengetahuan ekspansionis yang merusak tatanan alam.

Itulah mengapa, ekokritisisme (ecocriticism), meskipun kehadirannya secara resmi di era 1990-an telat dibandingkan perspektif teoretis lainnya, menjadi salah satu perspektif yang dewasa ini cukup diperhatikan dalam kajian sastra, film, televisi, musik, dan bidang-bidang lainnya.
Dalam catatan Glotfelty (1996: xvii-xviii), pada era 1980-an sebenarnya sudah muncul beberapa peneliti yang secara kolaboratif memunculkan kajian terkait isu lingkungan dan sastra, meskipun belum memunculkan istilah ecocriticism, melainkan kajian sastra lingkungan.
Tahun 1985, Frederick O. Waage mengeditori sebuah bunga rampai berjudul Teaching Environmental Literature: Materials, Methods, and Resource yang memasukkan deskripsi perkuliahan dari 19 pakar berbeda serta bertujuan mengembangkan kehadiran yang lebih besar dari concern kesadaran terhadap isu lingkunan dalam ranah kajian sastra.
Alicia Nitecki menerbitkan The American Nature Writing Newsletter yang memfokuskan pada penerbitan esai singkat, review buku, catatan perkuliahan, dan informasi kajian tulisan tentang alam dan lingkungan. Perkembangan tersebut pun mendapatkan respons dari beberapa perguruan di AS di mana mereka mulai memasukkan isu-isu kesastraan ke dalam kurikulum kajian lingkungan mereka.
Beberapa di antara mereka juga mendirikan program studi baru yang difokuskan kepada budaya dan alam. Beberapa prodi Sastra Inggris mulai menawarkan konsentrasi minor, sastra dan lingkungan. Pada tahun 1990 University of Nevada, Reno, membuat posisi akademis baru, Sastra dan Lingkungan.
Apa yang tidak kalah pentingnya adalah munculnya beberapa tulisan tentang alam dan sastra lingkungan dalam beberapa program konferensi tahunan sastra.
Salah satu yang menjadi tonggak adalah pertemuan MLA (Modern Language Association) 1991 di mana Harold Fromm mengorganisir sesi khusus bertajuk “Ecocriticism: The Greening of Literary Studies” dan Simposium Sastra Amerika yang diketuai oleh Glen A. Love dengan topik “American Nature Writing: New Contexts, New Approaches”.
Tonggak formal dari menguatnya kajian sastra dan lingkungan adalah pendirian Association for the Study of Literature and Environment (ASLE) di sela-sela pertemuan tahunan Association of Western Literature, 1993.
Adapun missi yang diusung adalah “memromosikan pertukaran ide dan informasi terkait sastra yang menimbang hubungan antara manusia dan jagat alam” serta “mendorong tulisan baru tentang alam, pendekatan tradisional dan inovatif terhadap sastra lingkungan, dan riset lingkungan antardisiplin”.
Pembentukan ASLE menarik banyak akademisi sastra sehingga banyak di antara mereka yang menulis isu-isu lingkungan dalam karya sastra.
Posisi akademis ekokritisisme semakin menguat ketika Patrick Murphy pada tahun 1993 membuat jurnal baru ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment dengan tujuan “menyediakan forum untuk kajian kritis sastra dan seni pertunjukan yang berasal dan ditujukan untuk pertimbangan lingkungan.”

Sebagai perspektif dalam memahami persoalan-persoalan ekologis dalam produk kultural, ekokritisisme memosisikan segala sesuatu yang non-manusia sama pentingnya dalam konteks dan pertimbangan manusia, karena tanpa kehadiran mereka, manusia dan jagatnya tidak akan eksis (Love 2003: 1).
Tentu saja, struktur naratif dan konstruksi diskursif dalam sebuah karya akan sangat tergantung bagaimana visi pengarang atau pandangan dunia (vision du monde) yang juga bersifat kompleks karena berkaitan dengan posisi pengarang dalam struktur dan sistem sosial serta kondisi historis masyarakat.
Hegemoni kapitalisme (neoliberal) dalam kehidupan masyarakat di seluruh planet, misalnya, mendorong massifnya eksploitasi sumberdaya alam untuk kepentingan perkebunan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Kerusakan secara massif bukan lagi menjadi ancaman, tetapai kenyataan yang sudah berlangsung.
Bencana banjir dan longsor adalah kenyataan destruktif yang semata-mata terjadi kerakusan manusia. Namun, di sisi lain, kampanye kesejahteraan yang bisa diperoleh negara dan rakyat dari eksploitasi alam juga semakin menggila, sehingga batas antara ancaman dan keuntungan menjadi kabur serta mendorong lahirnya pemakluman. Dalam kompleksitas tersebut, seorang penulis memang akan diuji.
Mempertemukan Jagat Tekstual dan Isu Lingkungan
Ekokritisisme memang relatif dinamis dalam membangun konsep-konsepnya. Dinamis di sini saya maknai sebagai “adanya keterbukaan” dalam menumbuhkan kerangka teoretis sehingga memungkinkan berkembangnya cara pandang multidisplin yang semakin memperkaya kajian.
Salah satu dampak yang cukup signifikan adalah beragamnya definisi, landasan berpikir, dan konsep-konsep teoretis yang ditawarkan banyak penulis, meskipun memiliki kesamaan dalam mengeksplorasi isu-isu ekologis dalam teks kultural.
Ekokritisisme merupakan kajian multidisplin yang mengeksplorasi hubungan antara sastra atau teks kultural lainnya dan lingkungan fisik di mana pendekatan berpusat-bumi menjadi acuan untuk meneliti karya-karya sastra ataupun karya-karya kultural lain seperti seni pertunjukan, film, tayangan televisi, iklan, musik, dan yang lain (Glofetly 1996: xviii-xix; Marland 2013: 846).

Premis utama yang diusung adalah bahwa budaya manusia terhubung dengan jagat fisik dan terpengaruh olehnya, sehingga apa yang dikaji adalah keterhubungan manusia, budaya, dan alam, khususnya yang dikonstruksi sebagai artifak dalam teks.
Secara sederhana bisa dikatakan bahwa sebagai bidang kajian, kritik ekologis menjejakkan satu kakinya dalam hamparan jagat narasi dan kaki lainnya di hamparan tanah dengan beragam kompleksitasnya, sedangkan sebagai wacana teoretis ia menegosiasikan keterhubungan antara manusia dan non-manusia.
Definisi-definisi lain yang diberikan para pakar tidak jauh berbeda dengan pendapat Glotfelty tersebut. Kerridge, misalnya, melihat ecocriticism berperan untuk mengevaluasi dan mengkritisi teks dan ide-ide terkait koherensi dan kegunaan mereka sebagai tanggapan terhadap krisis lingkungan (dikutip dalam Garrard, 2004: 4).
Sementara, Gerrard (2004: 5) memosisikan ekokritisisme sebagai kajian tentang hubungan manusia dan non-manusia, sepanjang sejarah budaya manusia dan memerlukan analisis kritis terkait istilah “manusia” itu sendiri. Mengapa demikian? Manusia adalah subjek dan entitas hidup yang selalu bergerak dan berubah secara dinamis dalam kehidupan.
Dinamika tersebut membentuk bermacam varian sistem sosial, ideologi, bahasa, seni, maupun budaya yang bersifat kompleks. Artinya, kehidupan manusia bukanlah realitas independen yang terbebas dari bermacam konteks. Demikian pula ketika mereka berimajinasi dan menulis tentang alam dalam karya fiksi maupun non-fiksi, sebenarnya mereka tidaklah melakukan kerja nir-kepentingan.
Begitupula ketika sebagian mereka memutuskan mengeksploitasi alam dan segala yang ada di dalamnya, manusia bukanlah subjek yang sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya untuk survive. Alih-alih terdapat kepentingan ekonomi maupun politik yang lebih besar. Tidak heran kalau pertambangan mineral di Indonesia banyak ‘dikawal’ oleh para komisaris atau CEO mantan jendral.
Dalam konteks itulah, “manusia” dalam eksokritisisme tidak boleh diposisiskan sekedar seabagai subjek pelaku karena mereka tetap terhubungan dengan sistem, wacana, pengetahuan, ideologi, dan kepentingan yang menjadi pijakan eksistensinya dalam kehidupan ini.
Itulah mengapa kajian ini bersifat unik karena kedekatannya dengan ilmu ekologi, meskipun ia tidak bisa secara langsung memberikan solusi untuk permasalahan ekologis, tetapi, sebagaimana dikatakan Garrard (2004:6), bisa mendefinisikan, mengeksplorasi, dan, bahkan, menyelesaikan permasalahan ekologis dalam makna yang luas.

Teks-teks kultural, termasuk sastra, film, musik, seni pertunjukan, dan yang lain, memiliki kemampuan untuk menghadirkan subjek manusia, masyarakat, dan persoalan lingkungan dalam dunia imajiner yang melampaui wacana umum yang berkembang dalam kehidupan nyata.
Pengertian-pengertian tersebut menunjukkan adanya tugas ekologis karya sastra yang sudah seharusnya merespons persoalan-persoalan ekologis karena sastra tidak hanya memiliki tanggung jawab tekstual, dalam artian membentuk dirinya sebagai keutuhan—dan tanggung jawab sosial, tetapi juga menjalankan tanggung jawab ekologis.
Prinsip keterhubungan antara alam dan manusia itu pula yang bisa dieksplorasi menjadi banyak pertanyaan yang berimplikasi pada keragaman kerangka teoretis dan metodologis dalam perkembagan ekokritisisme. Glofetly (1996: xix) mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang ikut memunculkan dinamika dan kompleksitas dalam kajian ini.
Bagaimana alam direpresentasikan dalam karya kultural? Peran apa yang dimainkan latar fisik dalam alur cerita di sebuah karya? Apakah peran yang bisa dimainkan secara konsisten dengan kearifan ekologis? Bagaimana metafor kita tentang tanah mempengaruhi kita memperlakukannya? Bagaimana bisa kita mengkategorikan tulisan tentang alam sebagai genre?
Terkait, ras, kelas, dan gender, haruskan tempat menjadi kategori kritis baru? Apakah lelaki menulis tentang alam berbeda dengan apa yang dilutis perempuan? Dalam cara apa literasi mempengaruhi hubungan manusia dengan jagat alam? Bagaimana konsep keliaran berubah dari waktu ke waktu?
Dalam cara apa krisis lingkungan merembes ke dalam sastra kontemporer dan budaya pop? Pandangan tentang alam apa yang menginformasikan laporan pemerintah AS, iklan perusahaan, dokumenter alam di televisi serta bagaimana efek retorik?
Bagaimana sain terbuka bagi analisis sastra/kultural? Penyuburan-saling lintas seperti apa yang memungkinkan antara kajian sastra dan wacana lingkungan dalam hubungannya dengan disiplin seperti sejarah, filsafat, psikologi, seni dan etika?
Paparan pertanyaan di atas mengindikasikan bahwa ekokritisisme bukan sekedar memosisikan penghadiran gambaran naratif tentang gunung, sungai, danau, rawa, alam perdesaan, lembah, sawah, ataupun pencemaran yang menjadi fenomena global.
Lebih dari itu, bagaimana memahami semua persoalan itu dalam perspektif yang mempertemukan kemungkinan-kemungkinan saling-melintasi antara disiplin sastra, budaya, dan ekologi serta varian-varian displin lain yang bisa dimasukkan, seperti kajian gender, antropologi, sosiologi, semiotika, wacana, retorika, feminisme, dan yang lain.

Mengapa? Karena ekokritisisme tidak hanya ingin berkontribusi kepada pengayaan kajian naratif, tetapi juga memiliki “visi politik” untuk mengungkap beragam kepentingan dan ideologi besar yang ikut memunculkan banyak permasalahan alam di planet bumi yang dinarasikan dalam sebuah karya.
Setidaknya, dengan pilihan kritis, para penikmat teks-teks kultural akan mendapat sudut pandang baru bahwa ada persoalan penting yang mungkin tidak terbahasakan dalam percakapan sehari-hari tetapi bisa ditangkap dan diungkap secara naratif ataupun retoris dalam karya sastra, misalnya.
Mendudukkan landasan berpikir yang menjadikan ecocriticism hadir dalam ranah kajian sastra dan budaya dengan semangat multidisplin berdimensi politik ekologis menjadi penting agar kita tidak dibingungkan oleh banyaknya paradigma yang berkembang selama beberapa dasawarsa terakhir.
Dorongan moral di balik ekokritisisme, bagaimanapun juga, berkomitmen untuk mengambil beberapa pendirian... terkait isu besar hubungan seperti apa yang harus dimiliki manusia dengan jagat alam. Hal itu merupakan tuntutan filosofis, bahkan religius, yang cukup besar, sehingga tidak mengejutkan banyak esai ekokritis yang gagal. (Clark 2011: 5)
Dengan menghadirkan idiom “dorongan moral” sekaligus “tuntutan filosofis” dan “tuntutan religius”, Clark tampak berusaha mengingatkan bahwa apa-apa yang dilakukan para ekokritikus bukanlah sesuatu yang main-main, yang hanya merayakan metafor-metafor yang mengkonstruksi alam dengan segenap isinya.
Alih-alih, mereka memiliki tugas kritis yang bukan hanya menghubungkan gugusan gunung dan laut di dalam karya sastra dan produk kultural lainnya dengan realitas kontekstual yang menunjukkan permasalahan-permasalahan sebenarnya yang dihadapi manusia.
Mereka juga bisa memberikan alternatif berpikir kepada para pembaca sastra dan penikmat kritik sastra bahwa manusia harus “mengambil sikap” terkait model hubungan dengan lingkungan. Mengapa demikian? Sangat mungkin teks-teks kultural terhubung dengan krisis air bersih ataupun semakin berkurangnya hutan tropis yang menghadirkan bermacam metafor kepada para pembaca.
Pengalaman-pengalaman imajinatif sekaligus diskursif dalam membaca, setidaknya, bisa menumpuk imajinasi yang lebih beragam terkait bagaimana manusia memahami dan menhubugnkan subjektivitasnya dengan kepentingan.

Sangat mungkin berkembangnya berbagai-macam krisis lingkungan dan semesta alam disebabkan oleh kegagalan manusia dalam mengembangkan imajinasi terkait permasalahan tersebut. Padahal, dari kearifan lokal hingga pengetahuan barat, alternatif untuk membangun imajinasi sudah disajikan. Sayangnya, banyak manusia yang mengabaikannya.
Bergthaller (dikutip dalam Clark 2015: 18) mengatakan bahwa gagasan terkait “kegagalan membangun imajinasi” sebagai akar krisis ekologis memberikan peluang kepada sastra untuk berkontribusi. Bagaimanapun juga karya sastra merupakan rumah imajinasi manusia yang memiliki peran cukup dominan untuk memahami krisis.
Apa yang sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan dalam ekokritisisme adalah persoalan kehadiran lingkungan dalam jagat-kata dalam kaitannya dengan jagat-nyata.
Menurut Buell (2005: 30-31) mayoritas ekokritikus berusaha memosisikan teks yang mereka rujuk sebagai pembiasaan lingkungan fisik serta bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, terlepas dari keunikan representasi tekstual dan mediasi mereka dengan ideologi dan faktor sosiohistorisnya.
Tidak mengherankan kalau muncul kecenderungan yang tampak kuno yang menempatkan lingkungan dalam moda ‘realistis’ representasi serta terlalu asyik mempermasalahan ketepatan faktual representasi lingkungan sehingga seringkali gagal menempatkan sebuah karya dalam konteks historis nyata.
Di satu sisi, terdapat sebagian ekokritikus yang mengabaikan revolusi pemikiran pascastrukturalisme dengan anggapan tidak ada konstruksi lingkungan yang bisa dibaca secara gamblang dan terlalu subjektif karena mengandalkan refleksi-diri peneliti terhadap dinamika kebahasaan yang ada dalam teks. Sementara, sebagian yang lain memilih untuk berada dalam poros anti-mimetik.
Tidak mengherankan ketika muncul gagasan untuk memulihkan realisme, mereka yang berada dalam poros anti-mimetik menganggapnya sebagai pembatasan terhadap tulisan lingkungan sekaligus fokus yang menggelikan dan dalam banyak hal palsu, karena tradisi mimesis mengandalkan kesamaan representasi dengan objek yang direpresentasikan.
Dana Phillips adalah salah satu pemikir ekokritisisme yang secara jeli mempertanyakan apakah kebenaran ekologi terdapat dalam karya sastra.
Phillips (1999: 578) menjabarkan bahwa banyak ekokritikus tidak menyukai perbincangan tentang sifat representasi sebagai perhatian utama teori sastra kontemporer, sehingga muncul anggapan bahwa mereka menjadi bagian dari kelompok neokonservatif. Apa yang membuat mereka kurang bersimpati adalah salah satu dalil pascastrukturalis bahwa alam dikostruksi oleh budaya.
Keterkonstruksian alam mengindikasikan bahwa prinsip kehadiran alam dalam karya yang diposisikan merepresentasikan alam yang sebenarnya sudah tidak mewadahi lagi.
Karena prinsip “konstruksi” menghadirkan kompleksitas representasional yang melebihi atau melampaui realitas alam itu sendiri serta membawa kepentingan-kepentingan partikular yang dimainkan melalui wacana dan permasalahan terkait lingkungan.
Pengabaian terhadap perkembangan teori pascastruktural, dengan demikian, menunjukkan sifat reaksioner para ekpkritikus sekaligus kekurangmampuan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kebenaran ekologis dalam teks sastrawi dan kultural.
Terlepas dari perdebatan tersebut, banyak teks sastra dan karya kultural merupakan konstruksi yang melewati kompleksitas imajinasi dalam merespons permasalahan lingkungan yang dihadapi manusia. Sudah sepatutnya, para ekokritikus mengungkapkannya secara komprehensif, termasuk model tekstual serta kuasa dan kepentingan yang ada dalam permasalahan lingkungan dalam jagat tekstual.
Daftar Bacaan
Boehmer, Elleke. 2005. Colonial and Postcolonial Literature: Migrant Metaphors, Second Edition. Oxford: Oxford University Press.
Brantlinger, Patrick. 2009. Victorian Literature and Postcolonial Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Buell, Lawrence. 2005. The Future of Environmental Criticism: Environmental Crisis and Literary Imagination. New Jersey: Blakwell.
Clark, Timothy. 2011. The Cambridge Introduction to Literature and the Environment. Cambridge: Cambridge University Press.
Day, Aidan. 1995. Romanticism. London: Routledge.
De Paz, Alfredo. 2007. “Innovation and modernity”. Dalam The Cambridge History of Literary Criticism, Volume 5, Romanticism. Ed. Marshal Brown. Cambridge: The Cambridge University Press.
Garrard, Greg. 2004. Ecocriticism. London: Routledge, 2007.
Glotfelty, Cheryll. 1996. “Introduction.” Dalam Cheryll Glotfelty & Harold Fromm (Eds). The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Georgia (US): The University of Georgia Press. Hlm. xv-xxxvii.
Huggan, Graham. 2008. Interdisciplinary Measures: Literature and the Future of Postcolonial Studies. Liverpool: Liverpool University Press, 2008.
Love, Glen A. Practical Ecocriticism: Literature, Biology, and the Environment. Charlottesville: University of Virgnia Press.
Leigh, Peter. “The ecological crisis, the human condition, and community-based restoration as an instrument for its cure”. Ethics In Science And Environmental Politics, April, 2005: 3-15.
Marzec, Robert P. 2007. An Ecological and Postcolonial Studies of Literature: From Daniel Defoe to Salman Rusdhie. Hampshire (UK): Palgrave MacMillan.
Phillips, Dana. 1999. Ecocriticism, Literary Theory, and the Truth of Ecology. Baltimore: John Hopkins University Press.
Riasanovsky, Nicholas V. 1995. The Emergence of Romanticism. Oxford: Oxford University Press.
Ross, Corey. 2017. Ecology and Power in the Age of Empire: Europe and the Transformation of the Tropical World. Oxford: Oxford University Press.
Schneider, Helmut J. 2007. “Nature.” Dalam The Cambridge History of Literary Criticism, Volume 5, Romanticism. Ed. Marshal Brown. Cambridge: The Cambridge University Press.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H