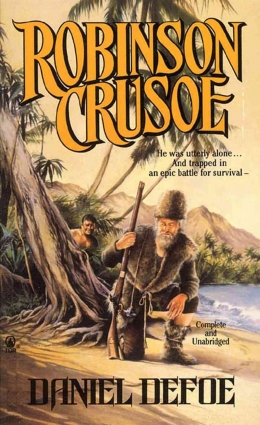Lebih dari itu, bagaimana memahami semua persoalan itu dalam perspektif yang mempertemukan kemungkinan-kemungkinan saling-melintasi antara disiplin sastra, budaya, dan ekologi serta varian-varian displin lain yang bisa dimasukkan, seperti kajian gender, antropologi, sosiologi, semiotika, wacana, retorika, feminisme, dan yang lain.

Mengapa? Karena ekokritisisme tidak hanya ingin berkontribusi kepada pengayaan kajian naratif, tetapi juga memiliki “visi politik” untuk mengungkap beragam kepentingan dan ideologi besar yang ikut memunculkan banyak permasalahan alam di planet bumi yang dinarasikan dalam sebuah karya.
Setidaknya, dengan pilihan kritis, para penikmat teks-teks kultural akan mendapat sudut pandang baru bahwa ada persoalan penting yang mungkin tidak terbahasakan dalam percakapan sehari-hari tetapi bisa ditangkap dan diungkap secara naratif ataupun retoris dalam karya sastra, misalnya.
Mendudukkan landasan berpikir yang menjadikan ecocriticism hadir dalam ranah kajian sastra dan budaya dengan semangat multidisplin berdimensi politik ekologis menjadi penting agar kita tidak dibingungkan oleh banyaknya paradigma yang berkembang selama beberapa dasawarsa terakhir.
Dorongan moral di balik ekokritisisme, bagaimanapun juga, berkomitmen untuk mengambil beberapa pendirian... terkait isu besar hubungan seperti apa yang harus dimiliki manusia dengan jagat alam. Hal itu merupakan tuntutan filosofis, bahkan religius, yang cukup besar, sehingga tidak mengejutkan banyak esai ekokritis yang gagal. (Clark 2011: 5)
Dengan menghadirkan idiom “dorongan moral” sekaligus “tuntutan filosofis” dan “tuntutan religius”, Clark tampak berusaha mengingatkan bahwa apa-apa yang dilakukan para ekokritikus bukanlah sesuatu yang main-main, yang hanya merayakan metafor-metafor yang mengkonstruksi alam dengan segenap isinya.
Alih-alih, mereka memiliki tugas kritis yang bukan hanya menghubungkan gugusan gunung dan laut di dalam karya sastra dan produk kultural lainnya dengan realitas kontekstual yang menunjukkan permasalahan-permasalahan sebenarnya yang dihadapi manusia.
Mereka juga bisa memberikan alternatif berpikir kepada para pembaca sastra dan penikmat kritik sastra bahwa manusia harus “mengambil sikap” terkait model hubungan dengan lingkungan. Mengapa demikian? Sangat mungkin teks-teks kultural terhubung dengan krisis air bersih ataupun semakin berkurangnya hutan tropis yang menghadirkan bermacam metafor kepada para pembaca.
Pengalaman-pengalaman imajinatif sekaligus diskursif dalam membaca, setidaknya, bisa menumpuk imajinasi yang lebih beragam terkait bagaimana manusia memahami dan menhubugnkan subjektivitasnya dengan kepentingan.