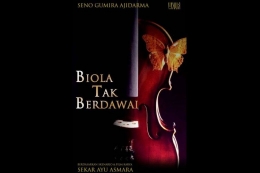AWAL(-AN)
Industri film Indonesia di era 2000-an awal ditandai dengan hadirnya film tentang perempuan dan ke-perempuan-an yang “berdaya”. Saya memaknai kata berdaya sebagai kondisi di mana perempuan mampu memaknai-ulang aspek-aspek ke-perempuan-annya sebagai bentuk perjuangan dan resistensi di tengah-tengah hegemoni patriarki.
Film-film tentang ke-perempuan-an yang berdaya memang masih menggunakan alur naratif dan teknik-teknik film arus utama. Namun demikian, sudah muncul keberanian untuk menghadirkan wacana tandingan melalui struktur dunia naratif yang mampu menawarkan sudut pandang baru untuk memahami permasalahan yang dihadapi perempuan dalam praktik sosio-kultural.
Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam struktur dunia naratif film juga tidak jauh berbeda dari permasalahan keseharian, seperti penderitaan perempuan akibat kuasa laki-laki dan kompleksitas ke-ibu-an perempuan.
Artinya, perjuangan dan resistensi perempuan yang disuguhkan tetap mengedepankan “kesadaran populis” yang tidak jauh dari kode-kode kultural dan permasalahan yang ada dalam masyarakat.
Memahami perjuangan dan resistensi sebagai negosiasi yang mengarah kepada pertarungan ideologis melalui representasi perempuan merupakan topik khusus yang akan saya kupas dalam tulisan ini. Titik-berangkat saya adalah membaca representasi perempuan ketika mereka menjadi tokoh utama yang terlibat dalam permasalahan-permasalahan pelik.
Untuk sampai dalam konteks pertarungan ideologis tersebut, saya akan bersandar pada beberapa pertanyaan berikut: (1) bagaimana tokoh perempuan memahami permasalahan yang terjadi, baik berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan atau laki-laki?; (2) mampukah tokoh perempuan menyelesaikan permasalahannya dengan kekuatan sendiri ataukah ada kehadiran tokoh-tokoh lain, baik laki-laki ataupun perempuan?; dan, (3) bagaimana pandangan dan sikapnya dalam memaknai kehadiran tokoh laki-laki?
Salah satu film yang menarik untuk ditelaah dengan cara pandang di atas adalah Biola Tak Berdawai (Ayu Sekar Asmara, 2002, selanjutnya disingkat BTB). Film ini menawarkan teknik filmis dan wacana ke-ibu-an perempuan dengan cara pandang baru.
Sudut pengambilan gambar, simbol dan adegan terkait persoalan seksual, serta teknik narasi yang diwarnai dengan dialog atau kalimat yang mencampur antara aspek populer dan idealis merupakan teknik filmis baru yang menjadi karakteristik dari film ini.
Terkait dengan persoalan tematik, BTB menghadirkan kekuatan perempuan dalam menghadapi permasalahan lampau dengan tidak harus meratapinya, tetapi melalui tindakan yang mampu membuatnya kuat dalam menjalani kehidupan dan juga mampu menghadirkan kehidupan bagi pihak lain yang kalah dan dikalahkan.
MEMAKNAI-ULANG DOSA MASA LALU
Secara umum film ini menceritakan kehidupan Renjani yang menjadi ibu asuh bagi anak-anak difabel ataupun sakit parah yang dibuang atau dititipkan oleh orang tua mereka. Terdapat dua faktor yang mendasari pilihan ideologis tersebut.
Pertama, ketika berada dalam kereta menuju Yogyakarta untuk menenangkan pikiran akibat masalah yang dihadapinya, ia bertemu dengan seorang perempuan yang disuruh membuang anak cacat oleh orang tuanya sendiri.
Kedua, Renjani pernah mengalami peristiwa yang menimbulkan trauma dan penderitaan fisik, yakni ketika ia dipaksa untuk melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak dikehendakinya akibat tindakan guru balet yang memperkosanya, sehingga untuk menebus dosa itu ia memutuskan untuk menjadi ibu asuh. Dua faktor itulah yang mendorongnya untuk menggunakan rumah warisan neneknya sebagai rumah asuh bagi anak-anak cacat ataupun sakit parah.
Mbak Wid juga punya alasan traumatik masa lampau yang membuatnya rela mengabdikan kepandaiannya sebagai dokter untuk merawat anak-anak yang diasuh Renjani. Dia adalah anak seorang perempuan yang menjadi pelacur demi menyekolahkan Mbak Wid.
Dalam praktiknya, siibu seringkali ‘kebobolan’ (hamil) dan digugurkan agar tetap bisa menjalani profesinya. Dengan kata lain, Mbak Wid mengabdikan dirinya bagi kerja kemanusiaan: demi menebus dosa lampau sang ibu.
Dalam sebuah dialog, Renjani menganggap Dewa, salah satu anak difabel yang ia asuh, sebagai pengganti anak yang tidak pernah ia lahirkan dan hanya berada dalam rahimnya sebelum diaborsi dan Mbak Wid sangat kecewa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Renjani.
Perkataan Renjani tentang Dewa yang mungkin bisa menggantikan anaknya serta kemarahan Mbak Wid karena mengetahui tindakan aborsi yang dilakukan Renjani, memperlihatkan beroperasinya wacana tentang kehadiran anak bagi seorang perempuan yang sangat penting, meskipun ia tidak pernah menghendakinya: perempuan sebagai ibu.
Posisi ibu bagi perempuan, bagaimanapun juga, telah menyebar dalam formasi diskursif seperti seorang perempuan harus rela mengandung, merawat, dan menjaga janin dalam kandungannya sehingga ia akan lahir dengan selamat.
Formasi diskursif tersebut mewujud dalam sistem sosial, keagamaan, pendidikan, maupun media hingga melahirkan person-person, aparatus, dan kebijakan yang berhak membicarakannya seperti bidan, dokter, ahli agama, maupun panduan-panduan bagi ibu hamil maupun menyusui.
Sepanjang sejarah manusia, figur ibu adalah perempuan itu sendiri yang harus mengandung, melahirkan, dan membesarkan bayi sehingga bisa meneruskan cerita kehidupan yang bersifat domestik (Reed, 2006: 58-66).
Wacana-wacana tersebut menjadi aturan-aturan yang mengendalikan pola pikir dan tindakan subjek perempuan dan laki-laki dalam masyarakat mengenai peran ke-ibu-an perempuan.
Kedua tokoh perempuan dalam BTB menjadi subjek bagi pengetahuan ke-ibu-an yang tetap berlangsung dalam masyarakat hingga saat ini dan menjadi kuasa untuk ‘mengkotak’ perempuan dalam pemahaman awal domestikisasi.
Namun demikian, dalam konteks Indonesia, menjadi ibu adalah sebuah tanggung jawab yang memang diemban perempuan karena posisi tersebut dianggap sebagai pilihan dan kehormatan untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi.
Tidak mengherankan, kalau Mbak Wid marah ketika mendengar pernah menggugurkan kandungannya, Mbak Wid marah, sampai harus menghamburkan kartu tarot dan mengumpat. Mbak Wid berhak mengumpat bahkan menganggap Renjani “sinting” karena telah membunuh anak yang seharunya berhak menikmati kehidupan.
Sampai di situ, Mbak Wid dikesankan telah masuk dalam jejaring relasi kuasa patriarki yang memosisikan perempuan sebagai sekedar ibu yang harus menghidupi anak-anaknya. Kondisi itulah yang menjadikan Renjani menyesal dan harus ketakutan, "menutup telinga", ketika Mbak Wid ‘memarahinya’ karena ia telah menjadi liyan yang melawan peran biologisnya.
Renjani memang bersalah karena berani melawan peran ibu bagi perempuan yang secara turun-temurun disosialisasikan dan diyakini sebagai rezim kebenaran. Penggambaran rasa takut dan penyesalan yang dialami Renjani serta kemarahan Mbak Wid mewacanakan Renjani benar-benar telah salah dengan tindakannya di masa lampau; membunuh calon anaknya sendiri.
Dengan bentuk narasi tekstual tersebut, makna tentang ibu dan ke-ibu-an yang diemban perempuan hadir dan mewacanakan hakekat perempuan yang memang sudah selayaknya menjadi ibu yang mengandung, melahirkan, merawat dan membesarkan anaknya.
Alasan Renjani melakukan dan membiarkan aborsi berlangsung, meskipun akhirnya berakibat tragis bagi kehidupannya, merupakan persoalan tersendiri yang menarik untuk didiskusikan. Ketika menjadi balerina, Renjani hanya “memikirkan tarian balet” sehingga ia “tidak pernah memikirkan laki-laki apalagi cinta”.
Pilihan untuk tidak memikirkan cinta, apalagi melahirkan seorang anak, merupakan wujud kontestasinya sebagai perempuan yang semestinya bisa dan berhak menggeluti profesi yang dikehendaki serta tidak semata-mata menjadi ibu yang harus mengurusi anak.
Tindakan aborsi menjadi hak dia untuk mempertahankan dirinya sebagai makhluk yang mempunyai kehendak otonom untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.
Menggugurkan janin dalam kandungannya merupakan satu upaya resisten yang dilakukan Renjani demi ‘menghilangkan’ sesuatu yang menjadi paksaan dan beban dalam menjalani kehidupan, meskipun, pada akhirnya, ia harus mengekspresikan penyesalannya setelah mengetahui kehadiran Dewa dan teman-temannya dalam kehidupannya di Yogya. Dengan demikian, sampai dengan peristiwa tersebut, film ini masih berusaha menghadirkan wacana ideologis tentang peran ke-ibu-an.
“Perasaan bersalah” memang menandakan ketidakmampuan Renjani untuk keluar dari jerat-jerat kuasa patriarki melalui pewacanaan peran perempuan sebagai ibu yang dikontraskan dengan perbuatan dosa yang terjadi pada masa lampau sebagaimana yang diakui oleh Renjani.
Meskipun demikian, dalam adegan berikutnya, film ini meyuguhkan wacana menarik yang dilontarkan Mbak Wid terkait penyikapan dosa masa lampau dan bagaimana dengan kedewasaan pikiran mereka memahami keberadaan dosa yang lebih besar dibandingkan aborsi yang dilakukan Renjani serta profesi pelacur dan aborsi yang dilakukan Ibu Mbak Wid.
Mbak Wid secara tegas mengkontestasi pemaknaan dosa yang dilontarkan Renjani dan banyak dipahami sebagai kebenaran oleh masyarakat. Memang Renjani berdosa karena telah membunuh bayi dalam kandungannya, tetapi apa yang dialami Mbak Wid dengan masa kecilnya, terutama dengan perilaku melacur sang ibu, bisa jadi lebih berat.
Di-aborsinya calon-calon adik Mbak Wid merupakan dosa besar, tetapi ada alasan-alasan yang melatarbelakanginya. Pun sampai sekarang, wacana dan praktik aborsi masih debatable, sehingga di samping melakukan kontestasi dalam memaknai dosa, dialog di atas juga menawarkan satu pandangan alternatif bahwa aborsi tidak bisa digeneralisir secara hitam-putih; tidak semata-mata dari aspek agama atau medis, tetapi juga kepentingan dan pilihan (pro choice).
Apa yang diungkapkan merupakan wacana tandingan yang dimasukkan oleh sineas terhadap makna dosa karena selalu ada alasan yang melatarbelakanginya, tetapi dengan terlebih dahulu mengakui akan dosa tersebut. Label dosa yang diberikan kepada tindakan aborsi Renjani, misalnya, bukanlah kesalahan mutlaknya.
Dia melakukannya karena kehamilannya disebabkan pemerkosaan. Renjani adalah korban kekerasan seksual sebagai akibat kuatnya sistem patriarki dalam masyarakat, sampai-sampai seorang guru balet laki-laki yang sangat dipercayai tega melakukan perbuatan yang menyakitkan itu.
Dengan demikian, ungkapan Mbak Wid mewacanakan keharusan untuk mencari akar permasalahan dalam pemaknaan dosa. Perempuan yang melakukan aborsi memang bersalah, tetapi ketika janin itu hadir sebagai akibat kekerasan seksual, apakah ia tidak berhak menggugurkannya?
Mbak Wid sendiri tidak bisa melupakan masa lampaunya, pengalaman menyaksikan dosa yang dilakukan ibunya dengan ‘mempekerjakan’ tubuh serta membunuh calon adik-adiknya, agar bisa terus bekerja demi masa depan Mbak Wid yang lebih baik.
Cerita Mbak Wid tentang masa lampaunya merupakan keberanian untuk membongkar pemaknaan stereotip tentang pelacur dan semua tindakan haramnya. Ibunya memang penuh dengan dosa apalagi setelah membunuh calon adik-adiknya, tapi Mbak Wid tidak pernah mau menyalahkan perilaku tersebut karena sang ibu melakukannya itu semua untuk membesarkan dan menyekolahkannya.
Adanya pengakuan akan dosa yang dilakukan ibunya, sekali lagi, menjadi ekspresi bagi pengakuan kebenaran yang berasal dari pengetahuan agama yang sudah menjadi nalar ideologis bersama dalam masyarakat; bahwa melacur maupun aborsi itu dosa dan betapa hinanya perempuan yang melakukan perbuatan itu.
Stigmatisasi perempuan yang melacur selalu identik dengan dunia hitam yang penuh dosa memang sudah menjadi rezim kebenaran dalam masyarakat, sehingga mereka perlu diregulasikan ke dalam kompleks-kompleks pelacuran yang khusus maupun “dikejar-kejar” dalam operasi ketertiban yang digelar polisi, polisi pamong praja, serta gerombolan laskar berlabel agama tertentu yang mengaku menegakkan panji-panji aqidah.
Dalam perbincangan dan interaksi sosial, pelacur adalah sosok liyan yang sudah selayaknya dieksklusi dan dimarjinalkan dari kehidupan sosial karena kehadirannya hanya menjadi cacat moral serta mengganggu ketertiban umum.
Ketegasan dan kekuatan pilihan untuk tidak menyalahkan atau menghakimi dosa-dosa yang sudah diperbuat ibunya menunjukan hadirnya makna yang sengaja dikontestasikan oleh sineas terhadap rezim kebenaran tentang pelacur dan dosanya.
Melacur dan membunuh janin memang dosa yang memalukan dalam relasi sosio-kultural, tetapi masalahnya masyarakat seringkali berkacamata kuda dalam menilai persoalan tersebut.
Selalu ada alasan-alasan yang melatarbelakanginya dan mereka tidak berdiri sebagai entitas otonom tetapi selalu lahir dari konstruksi sosio-kultural masyarakat. Perbandingan yang dilakukan Mbak Wid dengan kisah Drupadi yang ditelanjangi oleh Kurawa demi menyelamatkan Pandawa menjadi penegas bagi pilihan yang dilakukan sang ibu.
Drupadi adalah ‘ibu’ bagi ‘anak-anaknya’, Pandawa, karena ia ‘rela’ tubuhnya ditelanjangi sebagai taruhan Pandawa dan Kurawa di meja judi, demi menyelamatkan mereka. Drupadi dan ibu Mbak Wid, dengan demikian, berada dalam posisi yang sama untuk menyelamatkan sebuah masa depan. Untuk mendukung wacana tersebut, sineas BTB menghadirkan adegan flash back.
Ruang tamu di rumah Mbak Wid remaja. Dinding bambu berlubang sehingga cahaya matahari menembusnya. Tampak meja kayu kecil di samping dinding itu. Sebuah kendi (wadah air putih dari tanah, pen) di atasnya. Ruang tamu itu dekat dengan kamar tidur ibunya. Cahaya remang abu-abu tampak dari kamar itu.
Siluet ibunya bersama lelaki tampak separuh. Mbak Wid remaja membaca sebuah komik, mengenakan kaos putih. Komik Mahabarata yang menceritakan Durupadi dikerubuti kesatria Kurawa. Mbak Wid remaja tetap memegang komik, matanya menatap kamar ibunya. Ia murung, tapi tidak menangis. Kamar ibunya, masih tampak remang abu-abu. Ibunya dipeluk salah satu pelanggannya.
Pemunculan adegan flash back sebagai pengiring cerita masa lampau Mbak Wid merupakan pelogikaan naratif tentang ketepatan keputusannya untuk tidak menyalahkan sang ibu atas perbuatannya. Kemiskinanlah, sebagaimana ditandakan oleh dinding bambu berlubang, yang menjadikan sang ibu melacur demi untuk membesarkan anak yang dicintainya.
Mbak Wid remaja sudah biasa dengan aktivitas si ibu dan ia lebih memilih untuk “serius” membaca Mahabarata yang dari dalamnya ia mendapatkan perbandingan dari apa yang dilakukan oleh ibunya dengan apa yang dialami Drupadi. Penggambaran wajah Mbak Wid remaja ingin memberikan suasana batin yang dilingkupi “kesedihan”, tapi tidak ada tangisan.
Dalam masa pertumbuhan, sangat wajar ketika ia mempunyai perasaan tersebut, meskipun ia tetap tidak bisa menolak atau menyalahkan ibunya atas semua yang ia lihat karena itu semua dilakukan demi untuk membesarkan dan menyekolahkannya.
Pemilihan adegan yang cenderung menggunakan pencahayaan temaram abu-abu, merupakan penandaan visual untuk mendukung dan memperkuat kewajaran dari tindakan sang ibu dan respon memaklumi dari Mbak Wid remaja.
Secara konotatif, pemberian cahaya abu-abu ketika sang ibu sedang melayani tamu di kamar tidur menandakan keberadaannya dalam “ruang abu-abu” yang mana batas antara “hitam” dan “putih”, antara “dosa” dan “pahala” menjadi kabur.
Tidak ada justifikasi salah dan benar yang bisa diberikan kepada sang ibu ketika berada dalam ruang itu karena ia mempunyai alasan kuat untuk lebih mengedepankan masa depan dan kebahagiaan anaknya.
Kenyataan itu pula yang dialami Drupadi ketika dengan sadar ia merelakan dirinya ditelanjangi oleh Kurawa dalam cerita Mahabarata. Di balik peristiwa itu, terdapat kepentingan yang lebih besar yang mesti diselamatkan melalui tindakan-tindakan berani dalam ruang abu-abu.
Mbak Wid remaja juga memilih ‘sikap abu-abu’ dengan tidak menyalahkan dan memberontak terhadap perbuatan sang ibu karena itu semua dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi masa depannya, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya sepakat.
Membesarkan dan menyekolahkan Mbak Wid menjadi alasan ideologis bagi sang ibu untuk melacur, karena ketika ia tidak melacur, apa yang bisa ia lakukan, sementara (mungkin?) ia tidak mempunyai keahlian lain. Ketika calon-calon adiknya dibiarkan hidup, tentu saja Mbak Wid susah untuk meneruskan sekolah hingga menjadi seorang dokter anak.
Narasi tersebut menghadirkan satu pesan resisten "melacur dan aborsi" sebagai bentuk perjuangan. Kalau sudah demikian, apakah si ibu harus disalahkan untuk melacur dan mengaborsi janin-janinya? Dengan kata lain, melacur dan melakukan aborsi, sebenarnya, tidak harus dipersalahkan ketika ada alasan-alasan logis yang mendasarinya, begitu pula aborsi yang telah dilakukan Renjani.
IBU SEBAGAI KEHIDUPAN
Dalam memberikan wacana tandingan terhadap konsepsi dosa, aborsi, dan ke-pelacur-an, BTB tidak hanya berhenti pada satu titik kritis belaka. Dosa yang mereka alami ataupun mereka saksikan di masa lampau, memang, pada satu sisi, melahirkan trauma maupun penderitaan fisik, tetapi hal itu tidak harus menjadikan mereka terus meratapi atau menjadikannya beban hidup berkepanjangan.
Apalagi, sampai menjerumuskan mereka ke dalam tindakan destruktif, seperti melakukan balas dendam terhadap pihak yang pernah menyakiti mereka, sebagaimana banyak direpresentasikan dalam film-film di era Orba.
Pilihan untuk tidak meratapi apa yang sudah terjadi memberikan “kekuatan baru” bagi Renjani dan Mbak Wid untuk memainkan peran “ke-ibu-an” demi ‘menghidupkan kehidupan yang sudah hampir mati’.
Renjadi memilih untuk menjadi ‘ibu’ sekaligus pemilik rumah asuh bagi anak-anak cacat atau berpenyakit serius yang dibuang oleh keluarganya. Sementara, Mbak Wid menjadi dokter sukarelawan yang merawat secara medis anak-anak tersebut.
Dalam sejarah pemikiran feminis, perdebatan seputar ibu dan peran ke-ibu-an terkait dengan opresi yang dialami perempuan sebagai akibat dari sistem seks dan jender menempati posisi dominan, terutama yang berlangsung diantara para pemikir feminis radikal.
Menurut Tong (2006: 69), terdapat beberapa konsep feminisme radikal. Pertama, perempuan secara historis merupakan kelompok teropresi yang pertama. Kedua, opresi terhadap perempuan bersifat paling menyebar pada hampir setiap masyarakat di dunia dan bersifat yang terdalam, sulit dihapuskan dengan perubahan sosial lain, misalnya dengan penghapusan masyarakat kelas.
Ketiga, opresi terhadap perempuan menyebabkan penderitaan paling buruk bagi korban, meskipun penderitaan yang ditimbulkan muncul dengan tidak disadari karena adanya prasangka seksis, baik dari pihak opresor maupun dari pihak korban. Keempat, opresi terhadap perempuan memberikan model konseptual untuk memahami bentuk opresi lainnya.
Menurut pandangan feminis radikal-libertarian, pilihan menjadi ibu dengan fungsi reproduksi alamiahnya dianggap kembali menyuburkan akar opresi jender yang terjadi pada diri perempuan akibat dari sistem seks/jender yang sudah terkonstruksi dan menyatu dalam kehidupan kultural danreligius yang dihegemoni oleh kelas patriarki (Tong, 2006: 69).
Sementara, dalam pandangan feminis radikal-kultural, perempuan tidak harus membebaskan dirinya dari peran ibu biologis dan lari ke reproduksi buatan dan lebih memposisikan reproduksi alamiah sebagai sebuah kekuatan bagi perempuan yang membedakan mereka dengan laki-laki (Tong, 2006: 111).
Perdebatan di atas memunculkan pemikiran kritis untuk mempersoalkan kembali konsep ibu dan ke-ibu-an, terutama terkait dengan inferioritas perempuan dan superioritas laki-laki.
Bagi feminis radikal-libertarian, peran ke-ibu-an secara biologis hanyalah mitos yang dikonstruksi secara sosio-kultural berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni: (1) semua perempuan perlu menjadi ibu; (2) semua ibu memerlukan anak-anaknya; dan, (3) semua anak memerlukan ibunya (Tong, 2006: 113).
Mitos-mitos seputar ibu dan ke-ibu-an itulah yang kemudian melahirkan inferioritas perempuan terhadap laki-laki, tidak hanya dalam ranah domestik, tetapi lebih jauh lagi, dalam ranah publik (masyarakat dan negara), baik dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat kapitalis kontemporer: sebuah transformasi ideologi patriarki, tentu saja dengan partikularitas konteksnya masing-masing (Keller, 2005: 100; Cyba, 2005).
Adapun pemikir feminis radikal-kultural, meskipun tidak menyalahkan sepenuhnya analisis libertarian tentang peran ibu yang menjebak perempuan dalam rutinitas domestik selama hampir 24 jam, tetap berpandangan bahwa kesadaran perempuan untuk memahami fungsi tubuh dan peran ke-ibu-an yang bisa dimainkan dalam mengasuh anak, di mana mereka mendapat porsi yang lebih besar, akan menjadi sumber bagi kuasanya untuk berbuat lebih banyak bagi kehidupan (Tong, 2006: 119-122).
Pemahaman para pemikir feminis radikal-kultural menemukan kontekstualisasinya, misalnya, dalam beberapa kajian seputar ibu dan ke-ibu-an serta peran strategisnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara yang menghasilkan konsep “kesamaan jender” dalam konteks lokalitas masing-masing.
Atkinson & Errington (dikutip dalam Ong & Peletz, 1995) menjelaskan bahwa di negara-negara Asia Tenggara yang mempunyai budaya insular (melihat ke dalam) lebih menekankan kesamaan jender dan usaha untuk saling melengkapi. Perempuan juga memiliki hak prerogatif, kekuatan dan potensi spiritual, dan sebagian besar keistimewaan yang dinikmati oleh laki-laki.
Peletz (1996) dalam kajiannya tentang jender di masyarakat Melayu menjelaskan bahwa pada masa awal periode 1450-1680 perempuan sangat aktif dalam ritual komunal sepertihalnya yang terjadi wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara. Perempuan dengan kapasitas reproduktif dan regeneratifnya memperoleh kekuatan magis dan ritual yang sulit ditandingi laki-laki.
Kondisi itu berubah pada masa-masa akhir periode tersebut, ketika Islam dan juga “agama-agama besar lainnya” (terutama Budha dan Kritianitas) yang tidak menyediakan basis tekstual bagi partisipasi perempuan berkembang di Asia Tenggara.
Secara umum, posisi ritual tertinggi dari keyakinan dominan tersebut lebih banyak ditempati laki-laki, yang mengendalikan ritual komunal pada level tertinggi. Peran ritual perempuan secara progresif menurun dan peran mereka lebih banyak berkaitan dengan shamanisme dan pemanggilan arwah.
Dalam konteks masyarakat Jawa, menurut Brenner (1995), sebelum berkembangnya wacana ke-priyayi-an yang menyatu dengan wacana kolonial serta nilai-nilai dogmatis tentang jender dari agama resmi yang lebih merendahkan posisi strategis ibu dalam keluarga, para perempuan lebih banyak mengatur kehidupan keluarga terkait dengan fungsi ke-ibu-annya dan juga terkait dengan manajemen keuangan keluarga di mana laki-laki tidak banyak berperan.
Selain itu, perempuan juga melakukan aktivitas perdagangan di pasar maupun aktivitas pertanian di sawah/ladang. Dengan posisi tersebut, seorang ibu Jawa sebenarnya mempunyai kuasa dominan dalam kehidupan keluarga maupun sosial-ekonomi, tetapi wacana priyayi dan kolonial telah menjadikan peran sosial ibu, terutama dalam aktivitas perdagangan di pasar menempati posisi rendahan.
Perdebatan wacana di atas menunjukkan bahwa , “menjadi ibu” atau “tidak menjadi ibu” pada dasarnya bersifat ideologis serta melibatkan tidak hanya pertarungan antara pemaknaan biologis tubuh dan seksualitas perempuan, tetapi juga bagaimana sistem sosio-kultural ikut mempengaruhi pilihan tersebut.
Persoalan ibu dan keibuan secara naratif juga hadir dalam ketetapan hati Renjani dan Mbak Wid dalam memilih menjadi ‘ibu’ dan sekaligus memberikan wacana alternatif tentang pemaknaan ke-ibu-an sebagaimana banyak berkembang dalam masyarakat.
Lebih dari itu, pilihan ideologis yang dipilih kedua tokoh tersebut mampu melampaui perdebatan wacana-wacana di atas, dengan memasukkan beragam sudut pandang penalaran yang menjadi dasar pilihan tersebut.
Pilihan menjadi ibu bagi Renjani tidak murni berkaitan dengan fungsi biologisnya, tetapi tidak berarti ia menolak untuk menjadi ibu secara biologis. Ekspresi penyesalan dan pengakuan akan dosa masa lampaunya menjadi penanda betapa sebenarnya juga mau menjadi ibu dalam pengertian biologis.
Dalam konteks ini, ia tidak bisa dikatakan bersepakat dengan pemikiran feminis radikal-libertarian yang memperjuangkan pembebasan perempuan dari konsep ibu biologis, tetapi juga tidak bisa dianggap menyetujui pendapat feminis radikal-kultural yang mengedepankan ibu biologis dan peran strategisnya.
Pertimbangan untuk ‘menghidupkan’ dan ‘memberi kehidupan’ demi kemanusiaan merupakan alasan kuat bagi mereka untuk menjadi ibu. Renjani dalam mengatakan:
“Saya pindah dari Jakarta. Dalam perjalanan di kereta saya bertemu seorang ibu yang menggendong bayi cacat. Sebenarnya ia bukan anaknya, ia hanya disuruh seseorang untuk membuang anak itu ke Jogja. Rumah ini warisan nenek saya. Awalnya saya bingung, rumah sebesar ini akan saya apakan. Lalu, saya teringat sama ibu yang di kereta. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan rumah ini sebagai tempat untuk bayi-bayi cacat yang dibuang oleh keluarganya.”
Ungkapan tersebut menandakan betapa ia memilih untuk menggunakan rumah warisan neneknya sebagai rumah bagi anak-anak difabel yang dibuang keluarganya agar mereka bisa merasakan kehidupan dunia, meskipun harapan mereka tinggal sedikit.
Anak-anak difabel yang dibuang merupakan penanda bagi mereka yang tidak mempunyai harapan hidup lagi, karena sejak bayi harus berpisah dari ibu dan keluarga yang seharusnya merawat dan membesarkan mereka sebagai manusia yang punya hak untuk hidup.
Pernyataan Renjani sekaligus menjadi kritik keras terhadap keluarga yang membuang atau menitipkan anak-anaknya karena lahir dalam kondisi fisik tidak normal atau tidak sehat. Anak-anak itu dianggap sebagai aib yang bisa membuat malu dan turunnya harga diri orang tua.
Di samping itu, kelahiran mereka seringkali diasumsikan sebagai hilangnya bentuk perhatian orang tua, terutama siibu, ketika si anak masih berada dalam kandungan, lagi-lagi perempuan dipersalahkan.
Terlepas dari anggapan-anggapan general tersebut, mereka merupakan amanah Tuhan yang seburuk apapun harus tetap disyukuri dan dibahagiakan melalui usaha-usaha untuk menyembuhkannya, meskipun dalam kehidupan tetap tidak bisa sesempurna kawan-kawan lainnya.
Kesediaan Renjani untuk merawat mereka sekaligus menjadi kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak banyak berpihak kepada anak-anak cacat atau yang menderita sakit parah, terutama yang berasal dari keluarga miskin.
Kalau Renjani dan Mbak Wid saja bisa melakukannya, sudah semestinya pemerintah bisa membuat kebijakan strategis untuk menyelamatkan, atau, minimal, menumbuhkan harapan hidup bagi mereka yang sebenarnya berhak hidup dan merasakan kebahagiaan di “secuil tanah surga ini”.
Renjani dengan masa lalunya yang begitu menyakitkan ternyata memilih tidak berhenti pada proses dan pengalaman meratapi dosa. Ia mampu melakukan satu tindakan untuk ‘memberikan harapan hidup’ bagi mereka yang secara medis divonis tidak bisa bertahan lama dan secara sosial diasingkan oleh keluarga yang seharunya bertanggung jawab.
“Kemungkinan hidup mereka memang tipis, tapi selama jantung mereka masih berdetak dan mereka masih bernafas harus ada yang memikirkan mereka sampai ajal mereka tiba,” tutur Renjani.
Keyakinan dan pilihannya untuk ‘memberikan kehidupan’, minimal sebelum ajal menjemput anak-anak tersebut, menegaskan kemauan dan keoptimisan dalam memperlakukan mereka, sehingga tidak harus menyerah kepada mekanisme medis ataupun takdir.
Pertimbangan untuk berbagi dalam konteks kemanusiaan, selama mereka masih bernafas, lebih menjadi pertimbangan utamanya. Mereka yang punya keterbatasan secara medis juga harus diperhatikan, sehingga, mungkin, akan muncul keajaiban karena mereka ada yang memperhatikan secara manusiawi.
Keyakinan Renjani untuk ‘memberikan kehidupan’, pada dasarnya menghadirkan kembali pengetahuan klasik tentang peran seorang perempuan dalam melahirkan dan melangsungkan kehidupan di bumi, tidak semata-mata sebagai ibu secara biologis, tetapi sebagai ibu transendental yang menghadirkan kehidupan awal di muka bumi, sebagaimana diceritakan dalam legenda-legenda penciptaan manusia.
Konsep tersebut dalam legenda maupun dongeng biasa disebut sebagai Tellus Mater/ Terra Mater atau Mother of Earth,Ibu Bumi yang bisa ditemukan di seluruh dunia dalam bentuk serta varian yang beragam.
Konsep Ibu Bumi merupakan bentuk penghargaan umat manusia terhadap “bumi” yang telah melahirkan dan memberikan kehidupan kepada umat manusia. Perempuan diposisikan sebagai makhluk sakral yang mempunyai kualitas yang sama dengan Ibu Bumi karena kemampuan reproduksinya (Eliade, 2002: 142-150).
Dalam konteks Indonesia juga bisa ditemukan legenda serupa, meskipun mewujud dalam cerita yang berbeda. Masyarakat mengenal adanya dongeng kehidupan di muka bumi yang berasal dari benih padi yang berasal dari kematian Dewi Sri, yang dikenal dengan beragam nama maupun cerita yang menyertainya (Anoegrajekti dan Effendy, 2004: 8).
Kepercayaan terhadap keluhuran dan keagungan Dewi Sri dalam membantu kehidupan di muka bumi dengan padi dan kesuburan yang diberikannya, menjadikan para petani (baca: masyarakat agraris) menghormatinya sebagai sosok yang harus dipuja dalam ritual-ritual agraris.
Kepercayaan akan Terra Mater ataupun Dewi Sri, pada dasarnya, menekankan kemampuan perempuan untuk memberikan energi kehidupan bagi umat manusia.
Kekukuhan hati Renjani untuk menemani anak-anak cacat dan sakit parah, yang dengan demikian berusaha ‘menjaga’ dan ‘memperpanjang’ kehidupan mereka yang dikalahkan dalam pemaknaan ideal manusia, merupakan representasi dari pengetahuan kesuburan yang menyebar dalam masyarakat. Renjani dalam konteks ini merupakan representasi kehadiran Dewi Sri.
Kekuatan untuk ‘memperpanjang’ kehidupan tersebut, misalnya, bisa dijumpai dalam adegan-adegan yang menggambarkan bagaimana Renjani menyayangi Dewa dengan mengajaknya ke “sawah” dan ke “pantai” serta menyayanginya dalam praktik keseharian di rumah.

Sementara, tangan kirinya berusaha menyentuh pasir. Dia mengenakan baju berwarna abu-abu berlengan tiga perempat dan rok hitam warna panjang. Di ruang tamu dengan duduk sambil mengelus kepala Dewa. Dia mengenakan baju hitam. Tindakan-tindakan tersebut, dengan demikian, memosisikan Dewa sebagai anak normal, tanpa menghiraukan vonis dokter yang mengatakan Dewa hanya akan bertahan 4 bulan.
Penggambaran tersebut secara eskplisit menunjukkan kasih sayang Renjani terhadap Dewa dan sekaligus mempertegas perannya sebagai ibu yang berhasil menjalankan peran ke-ibu-an untuk menumbuhkan semangat kehidupan. Tindakan Renjani yang mengajaknya “pergi ke sawah dan menyusuri pematang” memperkuat energi kehidupan yang dialirkannya kepada Dewa.
Sawah dalam pemahaman masyarakat agraris merupakan situs kesuburan yang dengan hasil-hasil panennya mampu memberikan modal bagi masyarakat untuk terus melanjutkan kehidupan di muka bumi.
Renjani ingin menunjukkan kepada Dewa bahwa akan selalu ada “kesuburan” (menandakan energi positif) yang hadir dalam kehidupan manusia, betapapun sulitnya kehidupan itu sendiri.
Renjani, dengan demikian, adalah “sawah” itu sendiri yang dengan kesungguhannya merawat Dewa dan memunculkan kesuburan bagi Dewa untuk terus bertahan dan pada masa mendatang bisa menjadi manusia yang siap menghadapi dunia dan segala tantangannya. Sebagaimana nasehatnya kepada Dewa:
“Kamu tahu asal kupu-kupu? Dari telur yang ditetaskan ibunya akan muncul ulat. Itu yang sering kamu lihat di daun pisang, lalu ulat akan merajut kepompong, sebagai rumah dimana tempat dia tidur. Beberapa lama kemudian sang ulat pun terbangun dari tidurnya dan siap meninggalkan rumahnya.
Tapi, hidupnya sudah berubah. Dia akan muncul sebagai kupu-kupu yang cantik. Cantik ya? Dan, kupu-kupu pun akan terbang untuk keliling dunia. (menerawang ke atas sembari ceriah) Kamu juga, nanti kamu akan terbang untuk bisa melihat dunia."
Selain mencurahkan kasih sayangnya, Renjani juga melakukan tindakan-tindakan konkrit untuk terus memunculkan semangat kehidupan dalam diri Dewa. Salah satunya adalah dengan memberinya stimulus dengan menarikan tarian balet, setelah ia mengetahui Dewa memainkan sepatu balet yang sudah lama disimpannya.
Bagi Renjani yang pernah mengalami kejadian buruk yang berkaitan dengan balet (diperkosa gurunya), keputusan itu bukanlah persoalan mudah. Namun, demi Dewa, ia rela mengenakan sepatunya kembali sembari menarikan beberapa gerakan balet, sejenak melupakan semua peristiwa traumatik masa lampau yang sebenarnyanya menyakitkan.
Keputusan untuk memakai kembali sepatu balet adalah pilihan berat yang harus diambil Renjani. Bagaimanapun, sepatu itu merupakan representasi dari satu kenangan pahit yang pernah ia alami. Apalagi, harus menarikan gerakan tari yang pernah mendorong guru yang dikaguminya memperkosanya.
Namun, demi Dewa ia rela melakukannya. Rupanya Dewa memberikan respon atas apa yang dilakukan Renjani, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tarian balet ternyata berhasil memberikan ‘sinyal kehidupan’ bagi Dewa.
Peristiwa itu dengan jeli merepresentasikan semangat “betapa dalam penderitaan, seorang perempuan sebenarnya masih bisa ‘memberikan kehidupan’ kepada manusia lain”.
Karena “di balik kematian Dewi Sri yang menyedihkan, ia masih mampu menumbuhkan tanaman-tanaman yang kelak mampu mempertahankan kehidupan di muka bumi”. Bentuk adegan-adegan dengan praktik diskursif tentang ibu dan ke-ibu-an, berhasil menjadi submitos yang menghadirkan konsepsi ibu dan keibuan yang dimaknai kembali oleh seorang perempuan.
Dengan semangat serupa, Mbak Wid memilih untuk menjadi dokter anak. Dia bisa saja menjadi dokter komersial yang mampu mendatangkan kekayaan material. Namun, keinginan untuk menyelamatkan anak-anak yang berarti ‘memberikan kehidupan’ demi menebus dosa masa lampau ibunya berhasil memantapkan hatinya untuk berbeda dari para dokter anak kebanyakan.
“Saya telah bersumpah pada diri saya sendiri, bahwa saya akan menjadi dokter anak. Menyelamatkan anak-anak. Biarlah ibu saya membunuh anak-anak, janin adik-adik saya. Biarkanlah saya menebus dosa-dosa ibu saya. Menyelamatkan anak-anak.”
“Sumpah” Mbak Wid tentu bukan sekedar “sumpah kosong” karena ia menindaklanjutinya dengan tindakan konkrit; menjadi dokter yang berhasil menyelamatkan nyawa anak-anak, meskipun tidak semua anak-anak di rumah asuh yang bisa diselamatkan.
Saya melihat apa yang dilakukan Mbak Wid sebagai gugatan terhadap realitas medis kekinian di mana biaya pengobatan semakin mahal sehingga banyak anak-anak dari keluarga jelata yang meninggal karena tidak mampu membayar biaya pengobatan yang cukup tinggi.
Artinya, masih ada yang lebih bijak bagi seorang dokter anak di samping semua komersialitasnya, yakni keikhlasan untuk berbagi dengan sesama yang menderita sehingga kehidupan akan tetap bisa dilanjutkan.
Dengan menyelamatkan anak-anak, Mbak Wid juga berusaha “menebus dosa” lampau sang ibu yang membunuh calon adik-adiknya. “Penebusan dosa” merupakan salah satu ajaran agama Katolik.
Konsep ini secara eksplisit mengajarkan bahwa seorang yang telah berbuat dosa harus melakukan “pengakuan dosa” untuk kemudian menebusnya dengan membayar sejumlah uang kepada pihak Gereja dan hal itu harus dilakukan oleh si pendosa sendiri.
Dalam tradisi sebagian besar pemeluk Islam juga berkembang ritual tahlilan untuk mendoakan almarhum sehingga Sang Pencipta mengampuni dosa-dosanya. Melalui sosok Mbak Wid yang hendak menebus dosa ibunya, film ini menyuguhkan kembali tradisi-tradisi tersebut, meski dengan praktik yang berbeda.
Ajaran penebusan dosa bisa jadi memang benar, tetapi ada hal urgen yang bisa dilaksanakan dari sekedar “membayar sejumlah uang” ataupun “mengadakan tahlilan”, yakni melakukan tindakan nyata yang mampu mendatangkan kebahagiaan kepada dan bagi orang lain, sesuai dengan konteks dosa yang telah dilakukan. Dalam konteks berbeda, Mbak Wid juga telah berhasil memaknai kembali ibu dan ke-ibu-an dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya.
MENOLAK KEHADIRAN LAKI-LAKI SEBAGAI PILIHAN
Pilihan Renjani sebagai ibu menjadikannya terus mengusahakan kesembuhan bagi Dewa dan salah satunya dengan mengajaknya menonton konser biola di pelataran Candi Prambanan.
Ia berharap Dewa bisa memberi respon terhadap permainan musik biola. Kehadirannya di konser itu membuatnya kenal dengan seorang pemain biola bernama Bhisma yang berasal dari salah satu akademi seni di Yogyakarta.
Bhisma ternyata juga mempunyai perhatian terhadap Dewa. Kondisi itulah yang menjadikan Renjani dan Bhisma semakin dekat. Bahkan, Bhisma merasakan kehadiran Renjani sebagai cinta yang mampu melahirkan karya-karya kreatif, meskipun Renjani tidak serta-merta menerima cinta nya.
Pada awalnya, Renjani memang menaruh perhatian kepada Bhisma apalagi setelah melihat perlakuannya kepada Dewa. Bhisma melakukan tindakan-tindakan nyata untuk ikut membahagiakan Dewa, salah satunya dengan memberikan penggesek biolanya kepadanya.
Selepas pulang dari sebuah gubuk, ketika mereka membicarakan apa-apa yang telah dilakukan Renjani serta nasib anak-anak yang kurang beruntung itu, untuk melatih respons Dewa terhadap orang-orang dekatnya, Bhisma memainkan biola sementara Renjani menari balet dan mereka berhasil.
Rasa senang atas keberhasilan tersebut membuat Bhisma memeluk Renjani. Bhisma memegang dagu Renjani yang tengah menatapnya. Renjani memeluk pinggang lelaki muda itu sehingga menciptakan suasana romantis. Karena tidak ingin larut, Renjani akhirnya memilih dan melepaskan pelukan itu.
Kegembiraan akan respons yang diberikan Dewa terhadap apa yang mereka lakukan berdua, menjadikan Renjani untuk sesaat larut dalam suasana romantis sehingga ia juga menikmati pelukan Bhisma. Tidak berselang lama, kesadarannya segera muncul dan memberikan kekuatan untuk lepas dari pelukan itu.
Adegan tersebut sekaligus menjadi mitos-kedua bagi munculnya wacana tandingan bahwa perempuan memang, pada dasarnya, mudah larut dalam tindakan romantis yang diciptakan seorang laki-laki, baik atas nama cinta maupun kegembiraan tertentu, tetapi ia bisa menggunakan nalarnya untuk keluar dari tindakan romantis itu.
Perempuan sebenarnya bisa ‘melawan’ dan melepaskan diri dari ikatan romatis yang akan menjebakknya dalam permainan laki-laki dengan bermacam alasan logis yang melatarbelakanginya. Penegasan untuk tidak terikat dengan laki-laki, diungkapkan kembali ketika Mbak Wid menanyakan hubungan Renjadi dan Bhisma ketika mereka berada di ruang tamu.
Renjai mengatakan, “saya 8 tahun lebih tua dari dia”, “saya merasa telah sampai pada masa depan saya”, dan “saya merasa sudah mapan”. Ungkapan tersebut merupakan kode naratif yang menjadi alasan logis pertama yang menjadikannya tidak mau menerima kehadiran seorang pria seperti Bhisma.
Wacana yang dikembangkan Renjani terkait perbedaan usia 8 tahun, tak ayal, menghadirkan pengetahuan yang sudah berkembang dalam masyarakat bahwa idealnya perempuan itu harus lebih muda dibanding laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya.
Di balik pembenaran itu, ia sebenarnya mempunyai wacana lain tentang sampainya ia pada “masa depan” (Dewa dan anak-anak lain di rumah asuhnya) yang menjadikannya merasa sudah “mapan”.
Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa bukan sekedar usia yang menjadikan seorang perempuan tidak menerima laki-laki, tetapi konsep “masa depan” dan “kemapanan” bisa menjadi pertimbangan yang lebih signifikan.
Kemapanan itu sendiri bukanlah konsep yang harus diukur dengan materi. Lebih dari itu, kemapanan bagi seorang perempuan, seperti Renjani, merupakan sebuah praktik keterlibatan di mana ia bisa menggunakan apa yang dimilikinya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.
Renjani memang tidak bisa menolak segala kebaikan Bhisma terhadap Dewa sebagai sesuatu yang, di satu sisi, sangat ideal dari seorang laki-laki dan, di sisi lain, sudah sangat jarang ditemukan dalam masyarakat kontemporer.
Keseriusan Bhisma untuk membantunya dalam mengusahakan kesembuhan buat Dewa, sebenarnya menunjukkan kualitas kebaikan dan kemanusiaan di balik cintanya untuk Renjani.
Sebagai lelaki muda, pada dasarnya, Bhisma mampu mendapatkan cinta perempuan-perempuan muda yang mungkin lebih cantik dari Renjani. Namun demikian, masih ada “ketakutan” lain yang memperkuat penolakan Renjani.
Ia sendiri tidak mengungkapkannya kepada Mbak Wid yang dengan gigih berusaha meyakinkan untuk menerima kehadiran Bhisma karena kebaikan dan keseriusan yang ditunjukkan lelaki muda itu.
Ketakukan, dengan demikian, menjadi kode yang memunculkan teka-teki tentang apa yang sebenarnya disembunyikan Renjani dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Renjani berikutnya. Kode tersebut, sebenarnya muncul secara berulang-ulang; berupa mimpi-mimpi akan masa lalunya yang terus memunculkan rasa sakit di rahimnya ketika habis mengalami mimpi-mimpi traumatik tersebut.
Adegan-adegan mimpi dan rasa sakit yang menyertainya, menjadi kode simbolik yang sekaligus kode semik betapa Renjani sebenarnya mengalami trauma yang begitu berat sehingga terbawa dalam mimpi. Lebih parah lagi, mimpi-mimpi itulah yang menghasilkan rasa sakit dalam rahimnya muncul setelah bangun dari tidur.
Dengan kata lain, ia sebenarnya mempunyai masalah dengan rahimnya yang disebabkan aborsi pada masa lalunya dan perasaan traumatik melalui mimpi-mimpi masa lampaunya menjadikan penyakit tersebut semakin parah.
Adegan-adegan di atas sekaligus menegaskan kembali pengetahuan medis bahwa aborsi bisa saja menimbulkan penyakit kronis di kandungan, semisal kanker, karena ketidakbenaran prosedur operasi yang dilakukan.
Lagi-lagi, korbannya adalah perempuan yang dikalahkan oleh kuasa laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Di tengah-tengah penderitaan itu ia tidak ingin merepotkan dan memberi beban kepada orang lain—dalam hal ini Bhisma—karena dengan menjalin hubungan cinta si laki-laki akan lebih menderita ketika sewaktu-waktu ia meninggal.
Dengan penjelasan di atas, pilihan Renjani untuk sendiri dengan menolak kehadiran laki-laki didasari beberapa pertimbangan logis, yakni: (1) ia tidak ingin terjebak dalam hubungan romantis yang mungkin akan menimbulkan penderitaan; (2) ia merasa sudah mapan dengan Dewa dan anak-anak asuh lainnya; (3) ia menderita penyakit di rahim yang sewaktu-waktu bisa merenggut nyawanya; dan, (4) ia tidak ingin menjadikan orang lain menderita akibat penyakitnya itu.
Pertimbangan-pertimbangan itu menandakan bahwa sebelum membuat satu keputusan, perempuan mempunyai pertimbangan yang lebih matang berdasarkan rasionalitas dan perasaaan serta tidak hanya didasari pertimbangan romantis sesaat.
Dengan demikian, bentuk-bentuk adegan di atas menjadi submitos yang menghadirkan kekuatan rasionalitas dan hati perempuan dalam memandang kehadiran laki-laki sesuai dengan konteks partikular.
Renjani, akhirnya, memang harus menemui ajalnya. Namun, kematian bukanlah “kata akhir” untuk menutup dan mengakhiri cerita kehidupan di muka bumi. Mbak Wid dan Bhisma memang mengalami duka mendalam atas kematian Renjani, tetapi mereka bisa belajar untuk lebih mencurahkan perhatian kepada anak-anak yang harus diperjuangkan kehidupannya.
Bhisma, misalnya, lebih banyak mencurahkan energi kreatifnya untuk terus mengusahakan kesembuhan Dewa dan juga anak-anak asuh lainnya dengan komposisi-komposisi biola yang ia ciptakan.
Di akhir film ini, Bhisma didampingi Dewa mengunjungi makam Renjani dan mempersembahkan komposisi "Biola Tak Berdawai" yang dipesan secara khusus oleh Renjani. Adegan tersebut sekaligus menekankan bahwa di balik kematian Renjani ada cerita kehidupan yang harus terus diperjuangkan.
Renjani, berdasarkan paparan-paparan di atas, merupakan representasi dari Dewi Sri yang kematiannya tetap mampu memberikan kehidupan kepada manusia di muka bumi dengan padi dan tanaman pangan lainnya. Renjani juga merupakan representasi kehadiran Ibunda Theresa yang meskipun sudah meninggal, ia tetap menjadi inspirasi banyak orang untuk terus memberikan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan sentuhan kehidupan dari seorang ibu.
Perempuan akan tetap menjadi ibu yang selalu dikenang dan memberikan energi-energi baru setelah kematiannya. Ibu adalah peran luhur yang mampu menjadikan perempuan sebagai kekuatan yang signifikan dalam proses kehidupan di muka bumi ini. Bentuk adegan tersebut menghadirkan makna ibu dan wacana ke-ibu-an yang akan selalu berlanjut, meski ajal menjemput.
PEREMPUAN YANG TETAP BERDAYA: SIMPULAN
BTB dengan beragam representasi filmisnya menghadirkan kembali makna ibu dan wacana ke-ibu-an dalam perspektif yang lebih luas dan kritis. Film ini dengan apik menghantarkan pemahaman kita bahwa menjadi ibu merupakan pilihan ideologis yang mampu ‘memberikan kehidupan’ dan menjadi nilai tawar bagi seorang perempuan, meskipun ia tidak ikut melahirkan anak-anak yang dirawatnya.
Representasi perempuan sebagai ibu dalam BTB memberikan pemahaman kritis tentang keyakinan, kekuatan, dan perjuangan seorang perempuan sebagai ibu non-biologis yang tetap mampu memberikan kehidupan kepada anak-anak yang dirawatnya. Posisi Renjani sebagai 'ibu' merupakan resistensi terhadap wacana yang memosisikan perempuan korban perkosaan tidak berdaya traumatis dan cenderung terjebak dalam dunia gelap pelacuran, sebagaimana banyak direpresentasikan dalam film-film Orba.
Dengan kembali kepada kodrat ke-ibu-an, seorang perempuan sebenarnya mampu terus menunjukkan peran dominannya dalam kehidupan dengan merawat anak-anak terlantar ataupun melakukan hal-hal positif lainnya. Dalam konteks ini, Renjani merupakan representasi perempuan kultural yang tetap memposisikan dirinya sebagai ibu.
Pilihan menjadi ibu bagi anak-anak difabel dan sakit keras merupakan pilihan untuk berkontestasi, berdaya, dan memberdayakan dalam kehidupan. Seorang perempuan tidak harus menjalani profesi atau bertingkah seperti para laki-laki, tetapi dengan menjadi ibu bagi mereka yang membutuhkan sentuhan keperempuanan dan keibuan.
Kesendirian dan kemandirian perempuan merupakan satu tawaran wacana lain yang perlu dicermati. Ketidakmauan Renjani untuk menerima kehadiran Bhisma sebagai pendamping dalam mengarungi sisa kehidupannya, bukanlah pilihan tanpa alasan.
Perasaan terlalu tua untuk Bhisma yang masih muda, pencapaiannya sebagai seorang ibu bagi anak-anak yang menderita, dan sakit yang dideritannya merupakan alasan-alasan logis yang dikembangkan dalam film ini.
Alasan tersebut merepresentasikan kuatnya pengaruh pemikiran ideal dalam masyarakat Indonesia tentang sebuah hubungan serius antara dua insan. Di satu sisi hal itu berbeda dengan alasan-alasan para feminis radikal-libertarian Barat yang berargumen bahwa kehadiran laki-laki hanya akan melanjutkan situs penderitaan bagi perempuan.
Di sisi lain, alasan-alasan tersebut juga bersikap resisten terhadap pandangan ideal dalam masyarakat yang mengharuskan perempuan terikat dan mengikatkan dirinya dengan laki-laki dalam sebuah ikatan pernikahan yang dianggap sakral dan agung. Seorang perempuan memang tidak harus terjebak dalam hubungan sejenis ketika harus menjalani kehidupan tanpa laki-laki, tetapi dengan bermacam alasan logis, ia juga bisa memutuskan untuk sendiri dengan tetap pada fungsi strategisnya sebagai seorang ibu.
DAFTAR BACAAN
Anoegrajekti, Novi dan Bisri Effendy, “Mengangan Dewi Sri, Membayang Perempuan”, dalam Srinth!l, No.7, 2004.
Asmara, Sekar Ayu. 2003. Biola Tak Berdawai. Jakarta: Kalyana Shira Film.
Brenner, Suzanne A. 1995.“Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gender and Self-Control”, dalam Ong, Aihwa, and Michael G. Peletz (Eds). Bewitching Women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia. Berkeley: University of California Press. Diunduh dari: http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4x0nb2bf/, 24 Maret 2006.
Cyba, Eva.2005. "Social Inequality and Gender". http://www.jsse.org/2005-2/pdf/inequality_cyba.html.
Eliade, Mercia. 2002. Sakral dan Profan (terj. Nuwanto). Yogyakarta: Fajar Pustaka.
Keller, Catherine. 2005. “Menuju Suatu Posmodernitas Pospatriarkal”, dalam David Day Griffin (Ed). Visi-visi Posmodern, Spiritualitas dan Masyarakat (terj. A. Gunawan Admiranto). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Ong, Aihwa dan Michael G. Peletz. 1995. “Introduction”, dalam Aihwa Ong dan Michael G. Peletz (Eds).1995. Bewitching Women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia. Berkeley: University of California Press. Versi on line diunduh dari: http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4x0nb2bf/, 24 Maret 2006.
Tong, Rosemarie Putnam. Feminist Thought, Pengantar Paling Komperhensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis (terjemahan Aquarini P. Prabasmoro). Yogyakarta: Penerbit Jalasutra.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H