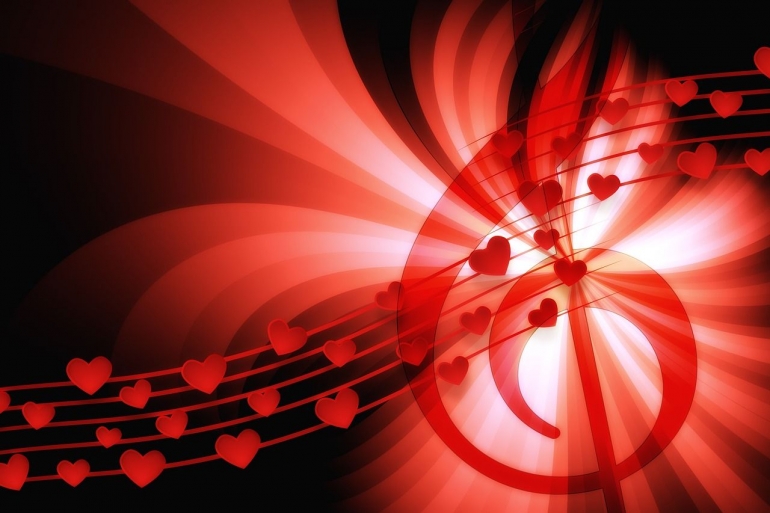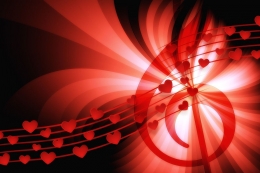"Datanglah ke rumah sakit, dan kau akan bersyukur."
Pesan mendiang Mamanya terpatri kuat di hati Calvin. Tak seperti kebanyakan orang yang benci rumah sakit, Calvin menganggapnya bagai rumah kedua. Ia mencintai bangunan putih beraroma obat itu, sama seperti ia mencintai rumah mewahnya di lereng bukit sana.
Di rumah sakit, ia melihat cinta. Cinta tulus paramedis pada pasien, cinta pembesuk pada pasien, cinta keluarga pada orang sakit, dan cinta pada Tuhan. Rumah sakit menjadi rumah doa. Tiap hari, doa-doa dari berbagai agama terlantun indah di sini.
Sejak kecil, Calvin mengakrabi rumah sakit. Berkali-kali ia telah menjadi pasien, pembesuk, dan anak big boss. Ya, rumah sakit besar ini milik Mama-Papanya.
Saat turun dari mobil, beberapa staf rumah sakit menyapanya. Seorang petugas sekuriti menerima kunci mobilnya. Dua suster dan seorang dokter melempar pandang penuh arti, ramah bercampur khawatir. Ah, Calvin benci tatapan itu. Mengapa semua orang harus mengkhawatirkannya? Calvin Wan tak suka dikhawatirkan.
"Saya masih kuat berjalan sendiri." tolak Calvin halus saat seorang suster menawarinya kursi roda.
Pria berjas hitam itu melangkah ke lantai tiga. Melewati sal demi sal. Menangkap bermacam suara: tangis, tawa, jeritan, muntahan, erangan, dan ratapan. Di unit Onkologi, Dokter Tian menyambutnya.
"Ah, Calvinku. Kau nekat sekali. Menyetir mobil sendiri...itu bahaya."
Calvin tersenyum, pelan menyahuti. "Supir saya sakit, Dokter. Mana tega saya membiarkannya tetap bekerja?"
"Nice boss. Ayo mulai."
Terapi itu, jarum-jarum suntik itu, menusuk lengannya. Terpancar kesakitan di mata sipit bening itu. Calvin bertekad tetap kuat. Ia harus kuat, demi seseorang yang masih membutuhkannya.
"Berapa banyak lagi jumlah pasir waktu saya?" tanya Calvin di sela kesakitannya.
"Calvinku, jangan paksa ayah keduamu ini mendahului takdir Allah."
Tujuh jam. Ya, tujuh jam Calvin merelakan tubuhnya ditusuk rasa sakit. Usai terapi, ia mengunjungi unit pediatri. Memeluk anak-anak yang kesakitan itu. Membacakan cerita untuk mereka. Menidurkan mereka di pangkuannya. Melunasi biaya pengobatan agar anak-anak miskin ini tetap memiliki harapan untuk sembuh.
**
Telah tiba waktunya
Untukku menyatakan padamu
Sebenarnya apa yang kurasa
Maafkan hati ini
Yang tak bisa berhenti menyayangimu
Walau ku tak bisa menjadi milikmu
Juga sebagai yang tercinta di hidupmu
Kekasih yang kucinta
Kekasih yang kumau
Ku tahu saat ini
Kau masih ragu
Maafkan hati ini
Yang tak bisa berhenti menyayangimu
Walau ku tak bisa menjadi milikmu
Juga sebagai yang tercinta di hidupmu
Maafkan hati ini
Yang tak bisa berhenti menyayangimu
Walau ku tak bisa menjadi milikmu
Juga sebagai yang tercinta
Sungguh bukan maksudku
Untuk memaksamu menjadi milikku
Yang selama ini sudah menemaniku
Untuk sebagai yang tercinta
Di hatiku (Nikita Willy-Maafkan).
Udara dingin menyergap. Angin mendesau kencang, memburaikan rambut panjangnya. Wanita itu terus bermain piano. Bibirnya terkatup rapat. Mengabaikan tamparan angin di balkon terbuka ini.
Sesaat kemudian, petir bergemuruh. Sang wanita bergaun putih bergerak ketakutan di kursinya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Beranjak dari balkon pun tak bisa.
Petir terus menggelegar. Lantai marmer bergetar. Pagar balkon bergemeretak. Cahaya kilat menyambar. Tapi, apa gunanya untuk wanita itu? Bola matanya tidak menangkap seberkas cahaya.
Mendengar gelegar petir saja membangkitkan ketakutannya. Ia memeluk dirinya sendiri, tanpa sadar bibirnya bergetar memanggil sepotong nama.
"Calvin...Calvin, kamu dimana?"
Sudah berjam-jam malaikat tampan bermata sipitnya itu pergi. Hanya terapi dan menjenguk anak-anak, katanya. Mengapa lama sekali?
"Ya, Allah, jagalah Calvin. Lindungi dia, peluklah dia dengan cahaya cintaMu. Jangan hilangkan dia. Aku butuh Calvin..."
Doa itu terlontar begitu saja. Sepotong doa yang selalu terucap kala pria pendamping hidupnya itu lama tak berada di sisinya.
Cuaca makin buruk. Hujan deras mengguyur perbukitan. Diikuti gempita petir memecah langit. Gaun putih si wanita cantik membasah. Ia meenekapkan tangan di dada. Kristal bening berhamburan dari mata birunya.
"Calvin, kamu dimana?" isaknya putus asa.
"Aku di sini, Silvi."
Sebuah suara bass bertimbre berat tapi empuk merobek tirai kesedihannya. Sepasang tangan hangat menyelimutkan syal ke tubuhnya. Silvi tergugu. Mengusap kasar air matanya.
"Dari mana saja kau?! Tidak usah pulang saja sekalian!" bentak Silvi.
Calvin tersenyum sabar. "Seperti yang kukatakan tadi pagi, Princess."
"Berhenti memanggilku seperti itu!"
"Nope. You're still my Princess, today and forever."
Silvi tertunduk dalam. Sedih, marah, dan takut mengguncang perasaannya.
Anak-anak listrik di langit sana menyemburkan kilatan. Silvi gemetar ketakutan. Calvin memeluknya.
"Lepaskan aku! Lepas!" Wanita Manado Borgo itu berteriak.
Pelukan Calvin begitu lembut dan hangat. Wangi khas Calvin terhirup di hidung Silvi. Sejak dulu, wangi tubuh Calvin tak pernah berubah: Blue Seduction Antonio Banderas.
"Aku akan tetap memeluk putri cantik yang takut petir ini sampai ia tenang."
Calvin, sungguh hanya Calvin yang memahami Silvi. Dia memahami tanpa menghakimi.
Sejurus kemudian, Silvi mencakar tangan Calvin. Kuku lancip berkuteks merahnya terhujam, menimbulkan luka kecil. Ia belum puas. Ia menampar pipi pria yang telah menjaganya selama beberapa tahun itu. Memar kebiruan tercetak mulus di sana.
"Lukai aku, asal jangan lukai dirimu sendiri." ujar Calvin pelan. Ia ikhlas, amat ikhlas dilukai istrinya.
"Dimana kamu saat pertama kali aku buta, Calvin Wan?! Dimana kau saat kontrakku diputus agency itu! Kau tak sedikit pun memberikan waktu untukku!"
Wanita yang lahir di awal musim gugur itu terisak. Ia histeris, kehilangan kontrol diri, dan melukai Calvin. Sakit hatinya, frustrasi jiwanya, putus asa hidupnya karena dikurung kegelapan.
"Silvi...my Princess, aku percaya orang yang kehilangan penglihatan masih bisa menjadi model. Aku akan membantumu. Kau pasti bisa meraih impianmu."
Lembut, lembut sekali Calvin menenangkan Silvi. Pria berhati malaikat itu tak setengah-setengah. Demi Silvi, ia menyerahkan perusahaannya untuk diurus sepupunya. Kini Calvin memilih menjadi blogger dan trader. Agar lebih mudah untuk mensupport istrinya.
Dalam pelukan Calvin, Silvi menumpahkan kegalauannya. Kegalauan bertemu ketenangan. Kesedihan bertemu penghiburan. Ketidakrelaan bertemu keikhlasan. Kecantikan bertemu kelembutan. Manado Borgo bertemu Tionghoa. Kaukasoid bertemu oriental. Mata biru bertemu mata sipit. Gaun putih bertemu jas hitam. Silvi Tendean bertemu Calvin Wan.
Lelah menangis, Silvi tertidur. Calvin menggendongnya ke kamar. Membaringkan Silvi di ranjang, menyelimutinya, lembut mencium keningnya.
"Selamat tidur, Princess. Aku mencintaimu."
Jemari lentik Silvi mencengkeram tangan Calvin. Dalam tidurnya, ia mengigau.
"Calvin, jangan tinggalkan aku."
"Aku tidak akan pergi selama kau masih membutuhkanku."
Ditatapnya wajah Silvi lekat-lekat. Cantik, lebih dari sekedar cantik. Silvi adalah Princessnya Calvin. Seburuk apa pun tingkah Silvi, Calvin takkan meninggalkannya. Calvin akan terus mencintai Silvi hingga ia berhenti bernafas.
**
Malam melarut. Kamar tidur mewah bernuansa broken white itu sunyi. Tak bisa tidur, Calvin menikmati sepi. Menatap wajah cantik Silvi tak puas-puasnya.
Hatinya melagukan mada syukur. Syukur karena Allah masih memberinya hidup dan kesempatan untuk merawat Silvi sekali lagi. Entah masih ada esok untuknya atau tidak.
Dentingan piano Calvin tak membangunkan Silvi. Nampaknya ia begitu kelelahan. Calvin bermain piano selama beberapa saat. Setelah itu, ia beranjak menyeduh teh dan menyalakan komputernya. Meneruskan rutinitasnya sebagai blogger. Menulis tentang kapitalisme dan keadilan sosial.
Tengah sibuk merangkai kata, tetiba Calvin terbatuk. Darah mengalir bersama dahak. Tulang punggungnya seakan tertarik, sakit sekali.
Ribuan jarum jahat menusuk punggungnya. Tidak, jangan sekarang. Tulisannya belum selesai. Izinkan ia bertahan sebentar lagi.
Bentuk pemaksaan dirikah? Tidak. Calvin terus menulis sambil terbatuk-batuk. Serangan itu lebih sering terjadi. Berat, menyakitkan, tetapi ia jalani dengan ikhlas.
Darah itu menetes ke atas keyboard. Beberapa bercak merah menodai tangannya. Sebentar lagi selesai, sungguh sebentar lagi.
Hanya sekedar berbagi.
Kalimat penutup untuk tulisannya. Ya, selesai. Tinggal melabeli. Jeda sejenak. Ia berhenti untuk menyesap teh. Berharap sakitnya pergi.
Calvin belum letih melawan penyakitnya. Ia bertahan demi Silvi, demi perusahaannya, demi pembaca websitenya. Hanya demi mereka, sungguh hanya demi mereka.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H