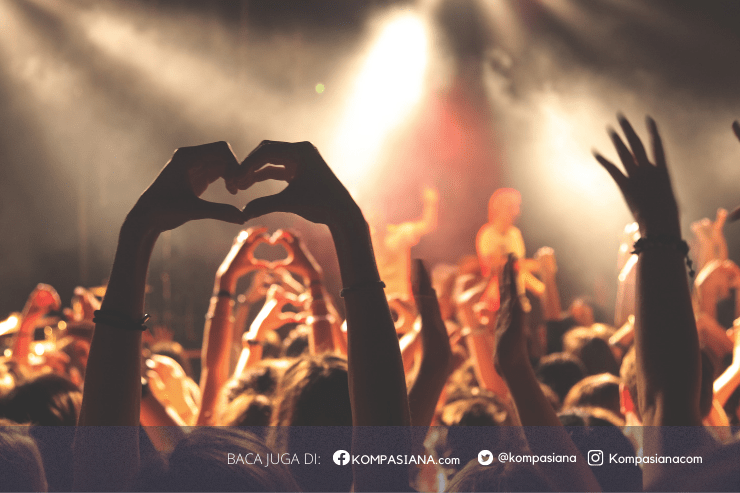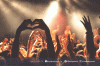Without music, life would be a mistake
Friedrich Nietzche
Kutipan Nietzche di atas mungkin ada benarnya, bayangkan jika peradaban manusia tidak pernah menemukan musik, bisa jadi hidup tidak lagi menyenangkan dan tanpa warna. Namun bagaimana jika sepanjang hidupnya Nietzche disuguhi musik-musik pop kontemporer yang berisikan ratapan-ratapan cinta, saya pikir mungkin Nietzche akan merevisi kalimatnya sendiri.
Dewasa ini, kawula muda edgy mulai mendengarkan kembali lagu yang mendayu-dayu, seperti Kangen Band, Armada, Ada Band dst yang sebelumnya telah ditempatkan ke dalam daftar hitam anak muda edgy di tahun 2000an, karena mulai dari penampilan personil dan liriknya yang menye-menye dianggap cringe, kamseupay dan tidak merepresentasi anak muda di zamannya (terutama anak muda di kota) yang lebih mengidolakan Rolling Stone, Gun's n Roses, Nirvana, The Sigit, Linkin Park dst.
Di tahun 2000an mereka menganggap musik pop seringkali tidak relevan untuk menggugah selera musik anak muda di zaman itu. Artinya selera musik dalam negeri perlu mencontoh budaya-budaya musik luar, yang dimulai dari kesesuaian penampilan, pemilihan lirik, susunan nada dan distorsi.
Tetapi kemudian ketika menengok musik dalam negeri yang tidak nyambung dengan gaya berpakaian Emo membawakan lagu menye-menye dan mendayu-dayu, barang kali itu menjadi penyebab mengapa anak muda di tahun 2000an lebih menyukai genre punk, rock, hardcore dst.
Namun persoalan mengenai jenis genre musik yang dalam tanda kutip, dianggap lebih keren daripada genre lainnya menjadi fenomena yang menarik untuk dibahas.
Tulisan ini hendak mengulas tentang mengapa musik pop menjadi musik yang nir-maknawi dan dangkal dengan membedah secara singkat beberapa lirik lagunya, serta membahas tentang relasi antara pasar-seniman-penikmat musik agar setidaknya mampu melihat secara objektif apa yang terjadi di balik ratapan kesedihan cinta yang selama ini kita dengar.
Untuk memulai pembahasan barangkali kalian pernah menonton atau setidaknya sepintas melihat scene dalam film 500 Days Summer. Dikisahkan dalam sebuah lift, Tom sedang mendengarkan lagu yang dibawakan oleh The Smiths, berjudul There Is a Light That Never Goes Out dengan menggunakan headset.
Masuklah seorang remaja perempuan bernama Summer ke dalam lift, selang beberapa detik kemudian, secara spontan Summer mengutarakan bahwa dirinya menyukai The Smith, Summer mengatakan:
"I love The Smiths".
"Sorry?" balas Tom.
"I said I love The Smiths. You, you have good taste in music", tandas Summer dalam percakapannya dengan Tom.
Dalam percakapan tersebut Summer mengatakan bahwa Tom punya selera yang baik dalam menikmati musik. Summer, secara tidak langsung mengatakan "selera yang baik" menunjukan terdapat "selera yang buruk" dalam menikmati sebuah karya seni.
Tetapi mari kita ber-huznudzon terhadap perkataan Summer, anggap saja tujuan utama Summer mengatakan demikian dilatarbelakangi oleh kesamaan akan selera musik alternatif rock.
Namun bagaimana jika tujuan Summer mengkalsifikasikan genre musik ke dalam struktur hierarki? Ini merupakan persoalan epistemologis tentang bagaimana suatu kategori musik dianggap baik atau buruk termasuk dari proses penciptaan karya sang seniman.
Ketika menikmati musik, salah seorang teman pernah membuka pertanyaan mengenai nada dahulu atau lirik terlebih dahulu? Tentu bagi saya yang awam tentang proses penciptaan nada akan kebingungan menjawab pertanyaan itu dan lebih memilih untuk mengedepankan lirik, sebab bahasa merupakan variabel utama untuk dapat mengetahui dengan jelas makna, posisi, dan maksud dari sang seniman menyampaikan pesannya dengan diiringi nada yang ia dibentuk.
Tetapi, toh, kicauan burung di pagi hari juga mengasyikan untuk di dengar meskipun kita tidak mengetahui maksud dari kicauan sang burung. Jika demikian, harmonisasi nada tanpa adanya vocal atau lirik yang mengisi dalam rentetan nada-nada itu juga dapat dimaknai dengan mengkaitkannya pada pengalaman empiris sang penikmat musik.
Mungkin oleh sebab ini seseorang mengklasifikasikan jenis-jenis musik ke dalam struktur hierarkis melalui medium yang dinamakan lirik. Jika demikian, kita perlu bersepakat dengan kritik tajam yang dilontarkan oleh Remy Sylado tentang musik pop. Melalui artikel yang berjudul "Musik Pop Indonesia: Satu Kebebalan Sang Mengapa"[1] yang ditulis pada tahun 70-an, Remy dengan lugas menandaskan bahwa persoalan terdegradasinya musik pop terletak pada lirik yang tidak memantik kita untuk berpikir dan merefleksikan aspek etis dan estetis, seolah subjek dalam musik tersebut tidak memiliki kapabilitas untuk memaknai realitas hidup dan kehidupannya; melalui "sang mengapa?" mereka hanya mampu bertanya dan enggan untuk berfikir tentang bagaimana menyikapi kehidupan yang banal ini, tujuannya? Agar mudah didengar dan sesuai dengan kepentingan cukong sebagai marketing musik yang ia ciptakan, agar bisa laris dipasaran.
"Sang Mengapa?" tanpa absen selalu hadir dalam karya musik populer terutama di Indonesia. Diksi itu acapkali digunakan seniman pop dalam merangkai untaian kata atas ketidak-terimaan subjek saat terjadi masalah dengan sang kekasih. Lirik lagu Nike Ardila yang berjudul "Sandiwara Cinta" belakangan ini naik kembali ke permukaan setelah dibawakan oleh salah satu musisi tanah air dan dinyanyikan kembali oleh kawula muda edgy pada suatu acara musik, berikut penggalan liriknya:
"Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku
Membakar jiwa yang merana
Kata manismu membuatku yakin kepadamu
Hingga membuatku terlena
Mengapa kini kurasakan lain di hatiku
Kau diam dan acuh tak acuh
Sering kau marah tanpa alasan"
Dengan diawali kata "mengapa" lirik lagu ini merupakan kebingungan subjek tentang perubahan sikap sang kekasih kepada dirinya. Kata itu terus diucapkan sebagai representasi dari keterbatasan pengetahuan dan keengganan menelaah kembali peristiwa dan relasi kuasa yang terjadi antara subjek dan kekasihnya.
Alih-alih merefleksikan kepatah-hatian, Nike justru jatuh pada fatalisme dengan menyimpulkan kebosanan dan ekspresi perasaan bencinya kepada sang kekasih. Meskipun telah diskaiti, namun subjek dalam lagu ini tampaknya berat untuk melupakan kekasih yang dicintainya.
Kelabilan ini senantiasa menghantui seniman musik pop dalam merangkai kata. Padahal, tujuan dari jatuh cinta adalah mencapai kebahagiaan, namun jika cinta membawa petaka dan pesakitan, percayalah cinta yang seperti itu tidak akan pernah membawa subjek pada kebahagiaan.
Beralih dari lagu Sandiwara Cinta, Nike Ardila, selanjutnya diksi candu "mengapa" datang dari band asal Lampung, Kangen Band, yang hari ini digandrungi oleh muda-mudi pada setiap konser musik pasca pandemi. Dengan khusyuk seraya mengaktifkan fitur flash handphone, kawula muda larut dalam penghayatan lirik-lirik patah hati Kangen Band, berikut liriknya:
"Mengapa kau tak membalas cintaku
Mengapa engkau abaikan rasaku
Ataukah mungkin hatimu membeku
Hingga kau tak pernah pedulikan aku"
Lirik diatas berjudul Pujaan Hati ciptaan Dody, gitaris Kangen Band. Memang bukan hal yang salah ketika subjek bertanya mengapa sang kekasih tidak bersikap seperti yang ia inginkan, akan tetapi masalahnya adalah ketika Kangen Band tidak hendak menelusuri jawaban atas perasaan patah hatinya.
Bicara tentang balasan cinta, Erich Fromm sejak jauh-jauh hari memberikan petuah "seseorang yang 'mencintai' memberikan kegembiraan, perhatiannya, pengertiannya, dan seluruh ungkapan dan perwujudan dari yang hidup dalam dirinya. Dia memberi bukan karena ingin menerima; jika kau mencintai tanpa membangkitkan cinta, jika dengan ekspresi kehidupan sebagai orang yang mencintai kau tak membuat dirimu sendiri sebagai orang yang dicintai, maka cintamu impoten, sungguh malang!" [2]
Fromm bermaksud menjelaskan bahwa kita sebagai seorang pecinta, seharusnya kita mengabdikan hidup pada apa yang kita cintai. Hal ini bukan berarti mengorbankan diri demi orang lain, artinya jelas, subjek meningkatkan rasa hidup orang lain dengan meningkatkan rasa hidupnya sendiri. Posisi ini lah yang luput dari lagu-lagu populer, yakni rasa cinta yang senantiasa dilandasi pada asas "kemenjadian" menjadi apapun yang ia senangi dan menerimanya.
Dengan demikian, makna cinta yang berselera pasar merupakakan cinta yang berlandaskan pada asas kepemilikan; menganggap orang lain adalah milik kita, sehingga wajib hukumnya bagi seseorang yang kita cintai untuk menuruti apa yang kita inginkan. Tak heran, kebanyakan lirik galau dalam lagu-lagu populer tidak terima terhadap perubahan sikap sang kekasih dengan dalih "aku mencintainya".
Tema cinta dalam industri musik kontemporer adalah template yang terus direproduksi, mereka mencari keuntungan dari sifat yang dialami semua umat manusia.
Bagaimana pun memang tak salah membuat lagu bertemakan tentang cinta, akan tetapi bukankah tema yang sama jika diucapkan terus menerus semakin tidak jelas maknanya?! Bahkan saking sudah terbiasa mendengarkan kata cinta, kita tidak lagi mengerti dan seringkali dengan remeh-temeh bilang "biasa, urusan cinta". Lagu-lagu yang bertemakan tentang cinta selalu laris dipasaran apalagi dibalut dengan branding media populer yang menghasilkan musik dengan easy listening, selain enak didengar penikmat musik juga relate dan merasa terwakili perasaannya.
Tak heran selama beberapa dekade ke belakang industri musik gencar memproduksi lagu-lagu semacam ini, dan mencari talenta-talenta berbakat dengan menerapkan standarisasi musik pop di mana kita tidak lagi untuk repot-repot merefleksikan secara empiris hidup kita, tujuannya? Lagi-lagi perluasan pasar untuk menghasilkan cuan.
Namun demikian, agar tidak jatuh pada over-generalisir kritik Remy perlu diperluas dengan mengajukan pertanyaan: Apakah lirik lagu bertemakan cinta dengan konotasi pertanyaan dan diiringi alunan musik yang mendayu-dayu itu selamanya bermakna dangkal? Tentu saya, sebagai penikmat musik akan menolak dengan tegas jika Remy menggeneralisir semua musik yang memiliki lirik berkonotasi pertanyaan dan tidak memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang menimpa subjek hanya lah ratapan patah hati dan penyesalan.
Suatu pertanyaan memanglah dangkal ketika tidak berpijak pada klaim-klaim ontologis, namun bagaimana jika pertanyaan-pertanyaan itu mulai mempersoalkan tentang hakikat dan abstraksi dari problematika cinta? Tampaknya kita perlu mencari angsa hitam dari proposisi dalam kritik Remy dengan menunujukan fakta bahwa tidak semua lagu dengan kalimat tanya tidak memantik kita untuk berpikir.
Lirik lagu yang berjudul "Sanggupkah" yang ditulis oleh Andy Liany, saya pikir cocok untuk menunjukan bahwa tidak semua lagu yang bertendensi kalimat tanya adalah lagu yang dinilai buruk. Sebaliknya, justru pertanyaan-pertanyaan dalam lirik lagu itu membuat kita memikirkan kembali tentang cinta yang selalu kita bicarakan setiap hari. Berikut liriknya:
"Kalau kau ragu tinggalkanlah aku
Pergilah, aku bisa mengerti
Tapi jangan paksa arahnya cinta karena keadaan dan perbedaan
Jalan masih panjang, jangan ucap janji
Nikmatilah cintamu hari ini
Sanggupkah aku hidup bersama denganmu?
Mungkinkah aku hidup tanpa ada dirimu?
Hanya waktu yang bisa jawab semua itu
Sampai kapan aku tak tahu..."
Mari kita sedikit membedah lirik lagu di atas, pertama, "Kalau kau ragu tinggalkanlah aku, pergilah aku bisa mengerti" menerangkan kelapangan dada subjek seraya menerima kepergian sang kekasih ketika ia merasa ragu terhadap kisah cintanya.
Kedua, dengan merujuk pada "Jangan paksa arahnya cinta karena keadaan dan perbedaan" di mana subjek mulai merefleksikan pengalaman perbedaan bersama sang kekasih. Entah itu perbedaan keyakinan, kelas sosial, atau perbedaan pilihan.
Namun yang pasti perbedaan dalam konteks lirik di atas menunjukan kegelisahan subjek terhadap dis-integrasi kisah asmara yang telah dibangun bersama kekasihnya. Ketiga, karena perbedaan tersebut memungkinkan perpisahan, subjek tidak ingin mengucapkan janji kepada kekasihnya, dan menyarankan "Nikmatilah saja cintamu hari ini" mencoba menatap masa depan dengan mengajukan pertanyaan 'sanggupkah' subjek menjalani hidup tanpa sang kekasih di sisinya.
Alih-alih menjawab pertanyaannya sendiri, sang subjek dalam lagu tersebut memilih biar waktu saja yang mampu menjawab perasaannya di masa depan. Bagi saya, lirik lagu di atas bukan hanya sebuah kejujuran ungkapan atas fakta yang dialami subjek, tetapi juga menjadi oase ditengah kekeringan makna cinta dalam lagu pop. Bahkan lebih jauh ia berpijak pada "keterlemparan" manusia (Dasein) ke dunia yang digagas oleh Martin Heidegger.
Kita dilahirkan untuk tidak dapat memilih tempat, ras, agama, budaya dan struktur sosial, sehingga variabel ini yang melekat pada kelahiran kita adalah tempat kita terlempar yang disebut sebagai dunia kita. Namun dari ketidak-mungkinan untuk memilih tersebut, manusia memiliki kehendak bebas, membuka pilihan-pilihan selanjutnya dalam menjalani hidup setelah menyadari dan menemukan diri di tengah keterlemparan yang tidak bisa kita pilih sebelumnya.
Bagi Heidegger keterlemparan Dasein ke dunianya bukanlah titik akhir menuju kebebasan, tetapi justru adalah awal dari keterlemparan selanjutnya. Konsep kebebasan Heidegger berada pada garis waktu "selalu sudah" yang dengan demikian, sesudah keterlemparan, tersedia pilihan terbatas untuk kita dapat memilih hingga kita menemukan keotentikan yang sesungguhnya, yakni kematian. [2] Dengan begitu manusia senantiasa tidak dapat melarikan diri dari keterlemparan di mana pada tahap selanjutnya kita dihadapkan pada keterbatasan pilihan. Demikian kebebasan memilih itu sendiri adalah hasil dari penerimaan keterlemparan kita ke dunia. Ketidak-mungkinan memilih membuat kita berbeda satu sama lain, posisi subjek dalam lirik lagu di atas memilih untuk menerima perbedaan tersebut dan enggan merubah perbedaan menjadi persamaan, untuk itu ia tak ingin memaksa kisah cintanya agar tetap bertahan.
Kembali pada urusan lirik lagu pop yang dikatakan Remy bahwa pop tidak pernah siap berfikir untuk tidak melulu bertanya. Barangkali wabil-khusus untuk lagu Sanggupkah, Andhy Liany adalah pengecualian dari kemalasan berpikir sang seniman pop. Sebuah pertanyaan tidak melulu menandakan bahwa seseorang tidak siap untuk berpikir, sebab dalam lirik lagu Sanggupkah bukan hanya persoalan Dasein yang terlempar ke dunia, tetapi ia juga terjebak pada temporalitas sebagai kesatuan masa kini, masa lalu, dan masa depan di mana manusia sebagai yang-ada bergerak, melaju, dan melakukan perjalanan. [3] Pertanyaan subjek dalam lagu Sanggupkah tidak dapat di jawab pada konteks 'masa kini' sebab keadaan yang dialami subjek tidak memungkinkan untuk menyingkap jawaban dan kepastian saat itu. Untuk itu biarlah waktu yang bisa jawab semua itu, sampai kapan? Aku tak tahu!
Mengurai Marginalisasi dalam Moda Produksi Label
Sepengetahuan saya tentang pop diambil dari kata populer, dicirikan dengan lantunan musik yang easy listening, lirik-lirik yang juga mudah dipahami, relatable, dan tak lupa terikat kontrak dengan korporasi sebagai label musik sekaligus marketing dalam memasuki industri musik agar dapat memperluas jangkauan pendengar. Karena label tidak memiliki konsumen secara langsung, biasanya label bekerja sama dengan media-media mainstream untuk memasarkan komoditasnya (lagu dan penyanyi/band) agar semua orang tahu dan bisa mendengar cuplikan musik yang sedang dirilis. Dulu semasa saya duduk di bangku sekolah dasar, ketika menonton tv menjadi kebiasaan saya setiap hari. Disela-sela nonton film/movie terdapat iklan yang menayangkan cuplikan lagu Ada Apa Denganmu, Peterpan. Itu berulang kali ditayangkan ketika iklan sedang berlangsung.
Seorang anak yang tidak mengerti informasi tentang makna lirik dan alunan musik yang dengan sopan tiba di telinganya, ingin sekali mendengarkan lagu yang di bawakan Boriel secara penuh. Namun apalah daya keterbatasan keadaan pada waktu itu, di mana penggunaan internet tidak semasif sekarang, memaksa saya untuk mantengin program musik seperti MTV Ampuh, Dahsyat, Inbox dst.
Tetapi apabila ingin menyetel lagu tersebut berdasarkan just in time, saya harus membeli disk originalnya di toko-toko kaset terdekat. Namun jika saya punya uang, saya jamin, saya akan membeli kaset originalnya. Tetapi demikian, yang saya permasalahkan sekarang bukan tentang saya mampu atau tidaknya membeli kaset, tetapi ketika saya membeli sebuah kaset, hal ini merupakan bagian dari sirkulasi kapital label musik seba gai produsen, penerbit dan agen marketing.
Tidak mengherankan dalam setiap keterbatasan selalu jatuh pada kebutuhan kebutuhan bukan hanya bagi kita untuk mendengarkan musik, tetapi kebutuhan bagi major label untuk menghasilkan nilai lebih dan keuntungannya kembali lewat rilisan lagu-lagu terbaru. Melalui ajang pencarian bakat, industri musik kala itu (bahkan hingga hari ini) sering kali mencari band dan penyanyi solo untuk masuk dalam kriteria selera pasar yang telah dibentuk oleh corak produksi kapitalisme.
Kebanyakan pengalaman seniman yang masuk dalam label punya kecenderungan untuk patuh pada selera pasar, yang dengan kata lain kebebasan seniman dalam menciptakan lagu, mestilah mengikuti selera dan tren agar dapat dibeli. Tidak ada kebebasan semacam itu, maka jangan heran jika relasi antara sang seniman dan label bukanlah kerja sama dalam konteks mutualisme, tetapi lebih kepada relasi antara buruh dan boss; borjuasi dan proletar sementara penikmat musik adalah konsumennya.
Di sini lah letak marginalisasi seniman, selain harus tunduk pada permintaan pasar di mana mereka tidak diperbolehkan membuat lagu sesuai dengan kehendak mereka, keuntungan yang didapatkan dari penjualan album mereka dihisap oleh label atau platform media musik. Seorang teman yang telah berkarya selama kurang-lebih 14 tahun dalam dunia musik dan mencoba mempertahankan keotentikan bandnya mengatakan bahwa lagu yang ia unggah dalam platform Spotify hanya menghasilkan Rp. 49,02,- dari setiap kali pemutaran lagunya.
Sementara ongkos menciptakan lagu juga cukup besar, selain memakan waktu yang cukup lama dalam membuat lirik, ia juga perlu composing, mixing dan mastering.
Sementara aplikasi Spotify telah diunduh sebanyak lebih dari 1 milyar pengguna, katakan lah setengah pengguna masuk dalam kelompok berlangganan premium dengan membayar Rp. 60,000.-/bulan.
Bayangkan berapa margin keuntungannya dan bandingkan dengan upah yang diberikan kepada seniman. Upah yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan Apple Music, Joox, Resso dan platform digital lainnya. Belum lagi jika ia masuk dalam label, tentu label juga mendapatkan income dari upah yang dibayarkan Spotify kepada seniman.
Beralih dari relasi seniman dan label, mari bahas relasi produsen dan masyarakat sebagai objek pasar (konsumen) di mana label menjejali kita dengan musik pop melalui iklan media mainstream. Selain pemasaran, salah satu faktor yang mempengaruhi selera pasar bersumber dari panjangnya waktu kerja yang dialami oleh banyak orang.
Waktu kerja menghabiskan 1/3 waktu kita hidup dalam satu hari, membuat kita tidak sempat memikirkan aspek yang disebut Remy sebagai etis dan estetis. Di sini, tampaknya label dapat dengan mudah mengkuantifikasi selera masyarakat dengan merilis lagu-lagu cinta yang semua orang bisa rasakan. Lagu-lagu yang bertemakan cinta entah bagaimana pun susunan nadanya, lirik, dan makna dalam lagu cinta itu senantiasa dapat diterima di tengah kesibukan kerja dan tekanan perusahaan.
Cinta menjadi sebuah kata yang sering kali digunakan dalam lagu pop sebagai sebuah komoditas dalam memuluskan jalan sirkulasi kapital. Kebanyakan komoditas yang dimiliki major label adalah sama yakni lagu bertemakan cinta, dan secara tidak terpisah diimposisikan oleh persaingan ekonomi dan kultural di antara para seniman dan di antara para produsen. [4] Hal ini berbeda secara eksplisit dengan persaingan antara toko A dan toko B alih-alih memiliki produk yang sama.
Tanpa perlu menjatuhkan lawan usaha masing-masing, industri musik bisa mengimposisikan suatu definisi partikular tentang selera-selera yang legitim dan kemudian jatuh ke dalam ekonomisme yang paling reduktor. [5] Bagi Bordieu, selera yang legitim ini diafirmasi oleh pengalaman subjektif yang bergerak di bawah level kesadaran kita di satu sisi, yang kemudian dibentuk oleh kapital ekonomi, budaya, dan sosial di sisi lain. Dengan demikian, Bordieu sampai pada kesimpulan bahwa selera merupakan hasil dari konstruksi sosial, selera itu dibentuk menghasilkan solipsisme yang mengafirmasi pengalaman kita secara universal yang kita anggap sebagai pengalaman yang unik.
Ya, bagaimana pun tidak lah berdosa dalam menyukai musik pop, toh kita selalu tidak berdaya di hadapan industri label, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk merubah sistem atau bahkan tidak memiliki alternatif sama sekali. Kritik Remy tentang kedangkalan makna dan kebebalan dalam musik pop, agaknya menjawab kebosanan penciptaan musik pop yang notabene mirip-mirip dan tanpa makna, meski menurut hemat saya tidak semua musik niaga adalah musik yang nir-maknawi.
Di bawah industri musik, seniman tidak lagi mandiri hanya bisa memilih untuk dieksploitasi oleh salah satu label, itu pun menggunakan logika mendang-mending. Kecuali karya itu bisa melampaui algoritma yang kemudian viral. Lebih jauh, sama halnya seperti industri manufaktur saat ini yang memiskinkan kelas pekerja. Begitu pun demikian, pasar yang dikuasai oleh industri label tentu membuat para seniman sulit untuk bersaing tanpa bernaung pada label itu sendiri. Tampaknya kita perlu membangun alternatif dari kekejaman label hari ini, sudah saatnya para seniman mengkonsolidasikan kekuatan untuk penciptaan pasar yang lebih sehat.
Para seniman sedunia, bersatulah!
Catatan kaki:
[1] Remy Sylado, Musik Pop Indonesia: Satu Kebebalan Sang Mengapa, Jurnal Prisma, 1977. Yang dikliping oleh Kineruku, bisa diakses di: https://kineruku.com/arsip-satu-kebebalan-sang-mengapa/
[2] Erich Fromm, Seni Mencintai, Basa-Basi, Jogjakarta, 2018, hal: 39.
[3] Artikel yang ditulis oleh Misbahul Huda, Waktu dan Manusia, dalam kolom LSF Discourse, yang bisa diakses di: https://lsfdiscourse.org/waktu-dan-manusia/
[4] Pierre Bordieu, Pertanyaan-pertanyaan Sosiologi, IRCiSoD, Jogjakarta, 2020, hal: 268.
[5] Ibid, hal: 269.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI