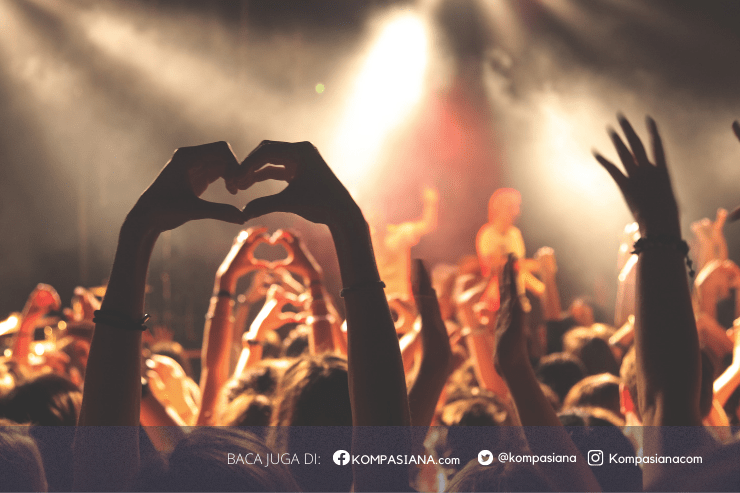Kebanyakan pengalaman seniman yang masuk dalam label punya kecenderungan untuk patuh pada selera pasar, yang dengan kata lain kebebasan seniman dalam menciptakan lagu, mestilah mengikuti selera dan tren agar dapat dibeli. Tidak ada kebebasan semacam itu, maka jangan heran jika relasi antara sang seniman dan label bukanlah kerja sama dalam konteks mutualisme, tetapi lebih kepada relasi antara buruh dan boss; borjuasi dan proletar sementara penikmat musik adalah konsumennya.
Di sini lah letak marginalisasi seniman, selain harus tunduk pada permintaan pasar di mana mereka tidak diperbolehkan membuat lagu sesuai dengan kehendak mereka, keuntungan yang didapatkan dari penjualan album mereka dihisap oleh label atau platform media musik. Seorang teman yang telah berkarya selama kurang-lebih 14 tahun dalam dunia musik dan mencoba mempertahankan keotentikan bandnya mengatakan bahwa lagu yang ia unggah dalam platform Spotify hanya menghasilkan Rp. 49,02,- dari setiap kali pemutaran lagunya.
Sementara ongkos menciptakan lagu juga cukup besar, selain memakan waktu yang cukup lama dalam membuat lirik, ia juga perlu composing, mixing dan mastering.
Sementara aplikasi Spotify telah diunduh sebanyak lebih dari 1 milyar pengguna, katakan lah setengah pengguna masuk dalam kelompok berlangganan premium dengan membayar Rp. 60,000.-/bulan.
Bayangkan berapa margin keuntungannya dan bandingkan dengan upah yang diberikan kepada seniman. Upah yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan Apple Music, Joox, Resso dan platform digital lainnya. Belum lagi jika ia masuk dalam label, tentu label juga mendapatkan income dari upah yang dibayarkan Spotify kepada seniman.
Beralih dari relasi seniman dan label, mari bahas relasi produsen dan masyarakat sebagai objek pasar (konsumen) di mana label menjejali kita dengan musik pop melalui iklan media mainstream. Selain pemasaran, salah satu faktor yang mempengaruhi selera pasar bersumber dari panjangnya waktu kerja yang dialami oleh banyak orang.
Waktu kerja menghabiskan 1/3 waktu kita hidup dalam satu hari, membuat kita tidak sempat memikirkan aspek yang disebut Remy sebagai etis dan estetis. Di sini, tampaknya label dapat dengan mudah mengkuantifikasi selera masyarakat dengan merilis lagu-lagu cinta yang semua orang bisa rasakan. Lagu-lagu yang bertemakan cinta entah bagaimana pun susunan nadanya, lirik, dan makna dalam lagu cinta itu senantiasa dapat diterima di tengah kesibukan kerja dan tekanan perusahaan.
Cinta menjadi sebuah kata yang sering kali digunakan dalam lagu pop sebagai sebuah komoditas dalam memuluskan jalan sirkulasi kapital. Kebanyakan komoditas yang dimiliki major label adalah sama yakni lagu bertemakan cinta, dan secara tidak terpisah diimposisikan oleh persaingan ekonomi dan kultural di antara para seniman dan di antara para produsen. [4] Hal ini berbeda secara eksplisit dengan persaingan antara toko A dan toko B alih-alih memiliki produk yang sama.
Tanpa perlu menjatuhkan lawan usaha masing-masing, industri musik bisa mengimposisikan suatu definisi partikular tentang selera-selera yang legitim dan kemudian jatuh ke dalam ekonomisme yang paling reduktor. [5] Bagi Bordieu, selera yang legitim ini diafirmasi oleh pengalaman subjektif yang bergerak di bawah level kesadaran kita di satu sisi, yang kemudian dibentuk oleh kapital ekonomi, budaya, dan sosial di sisi lain. Dengan demikian, Bordieu sampai pada kesimpulan bahwa selera merupakan hasil dari konstruksi sosial, selera itu dibentuk menghasilkan solipsisme yang mengafirmasi pengalaman kita secara universal yang kita anggap sebagai pengalaman yang unik.
Ya, bagaimana pun tidak lah berdosa dalam menyukai musik pop, toh kita selalu tidak berdaya di hadapan industri label, tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk merubah sistem atau bahkan tidak memiliki alternatif sama sekali. Kritik Remy tentang kedangkalan makna dan kebebalan dalam musik pop, agaknya menjawab kebosanan penciptaan musik pop yang notabene mirip-mirip dan tanpa makna, meski menurut hemat saya tidak semua musik niaga adalah musik yang nir-maknawi.
Di bawah industri musik, seniman tidak lagi mandiri hanya bisa memilih untuk dieksploitasi oleh salah satu label, itu pun menggunakan logika mendang-mending. Kecuali karya itu bisa melampaui algoritma yang kemudian viral. Lebih jauh, sama halnya seperti industri manufaktur saat ini yang memiskinkan kelas pekerja. Begitu pun demikian, pasar yang dikuasai oleh industri label tentu membuat para seniman sulit untuk bersaing tanpa bernaung pada label itu sendiri. Tampaknya kita perlu membangun alternatif dari kekejaman label hari ini, sudah saatnya para seniman mengkonsolidasikan kekuatan untuk penciptaan pasar yang lebih sehat.