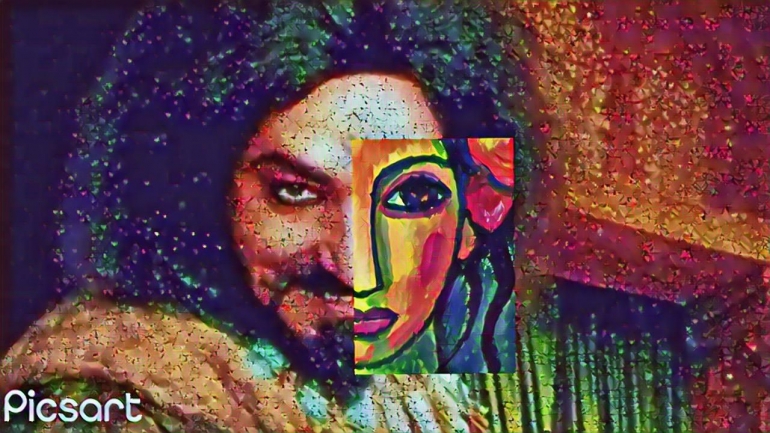Apa yang aku kuatirkan terbukti. Walaupun putaran gas motor sudah menyentuh level ngebut, bahkan sampai biyayakan, aku gagal mencapai limit. Dita terlambat aku sambangi. Bocah itu protes sampai matanya berkaca-kaca. Pesannya jelas, ia ketakutan. Sekolahnya sudah sepi. Pintu gerbang terbuka seperempat. Untung ada mbok bon-pemilik kantin-yang menemani.
"Sin! Kamu itu kok tega ya sama ponakan!". Kakakku marah hingga kepalanya berasap. Aku dirujak habis-habisan. "Kalau terjadi apa-apa bagaimana!" Aku pasrah, mengaku salah.
Lucunya, tersiar kabar, kalau aku yang mengajak Kopat ke Pacitan. Bangsat!
Racikan bumbunya menumpuk dan tambah sedap.
"Yang namanya mengajak, harus tanggungjawab". Suara-suara sengau gentayangan memenuhi langit kampung. "Harus keluar uang. Bukan yang diajak yang bayarin". Padahal kenyataannya, selembar uang merah aku cabut dari himpunannya. Namun Kopat mendahului.
"Biar aku saja". Kopat menyodorkan lembaran lima puluh ribu ke petugas SPBU. Mampir ke swalayan gantian aku yang bayarin beli minuman serta makanan.
Semenjak pulang dari perantauan, hal-hal beginian menimpaku. Dan Kopat biang keladinya.
Kepala Kopat muncul dari balik tembok pemisah antara kediamanku dengan rumahnya. Bunyi lidi menyisir tanah ternyata menarik perhatian.
"Sin"
Suaranya mengetuk cuping .
"Apa?". Kepalaku mendongak menatap tempurung Kopat yang mirip Kim Lun Hoat'ong(Hakim Roda Emas), mengkilap, hingga setitik cahaya memantul menusuk mataku. Gagang sapu kuputar-putar menunggu reaksinya.