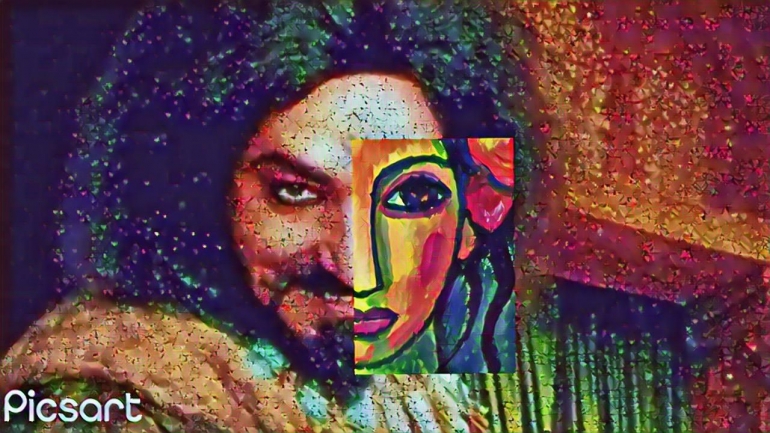Kegiatan kampung menjadi ajang rendezvous. Yang dulu pergi, beberapa diantaranya kembali kesarang: Ada yang di PHK, pindah kerja, buka usaha, dan seterusnya. Rentang waktu panjang membungkus apapun perilaku manusia. Begitupun dengan Kopat. Kedekatanku menyisir selapis demi selapis kelakuan Kopat.
"Andai aku ajak ke Pacitan, mau?"
"Nggak"
"Kenapa?"
"Hari ini jatahku menjemput Dita"
"Kan pulang sekolahnya pukul 15.30 wib?". Gila! Darimana dia tahu? "Sebentar, kok. Hanya bertemu paklik langsung pulang"
"Beneran?", tanyaku memastikan. Kopat mengangguk. Sebenarnya, jawaban yang ia katakan menyiratkan keraguan. Aku kenal betul karakter orang-orang desa secara umum. Kalau tamu datang dari jauh pasti akan disambut dan disuruh mencicipi apapun yang mereka hidangkan. Bercerita panjang merupakan kebiasaan sebagai bentuk penghormatan. Jadi, kalau hanya sebentar, itu sebuah kejahatan silaturahmi. Kopat mengajakku karena tahu hobiku touring.
Solo-Pacitan(tepatnya sebuah desa di tugu perbatasan Jateng-Jatim) butuh waktu tempuh dua sampai dua setengah jam, tergantung kondisi motor serta ketangkasan si pengendara.
Berangkatlah kami. Isi kepalaku sudah menulis rencana dasar. Kalau benar hanya sebentar, ponakanku akan aku jemput sesuai jadwal. Sayang, Kopat membuat apa yang aku rencanakan berantakan. Manusia brengsek ini ngobrol sama pakliknya mirip orang mabuk kecubung. Kode-kode yang aku kibarkan tidak digubris.
Sampai kedua kaki kami bergumul: saling sepak, menggencet dikolong meja. Sorot mataku tersiram kecemasan: putaran jarum jam terasa begitu cepat.
Dia sudah lupa daratan. Hingga aku inisiatif pamit. Pakliknya kaget, "Lho mas. Harusnya yang pamit itu Kopat. Bukan sampeyan. Dia yang berhak untuk pamit". Aku beralasan ada acara lanjutan. "Kalau ada acara tidak usah kesini. Lagi enak-enak ngobrol je". Omongan pakliknya sengak. Aku tersengat marah.