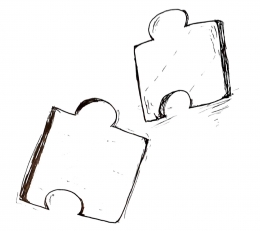Angin sore itu masih meniupnya dengan lembut. Selembut lantunan kentrung yang harmonis, menemani dan mendekap kami berdua. Di atas bumi ini, kami telah saling belajar.
Bunga putih itu telah menjadi tanda bagi kami berdua. Ikatan yang terbentuk karena ketidaksengajaan telah membuat kami saling menerima. Bapakku, engkaulah yang telah mengajariku bahwa manusia tidak ada yang sempurna.
***
Aku sadar bahwa hidupku ini adalah sebuah realita dunia dengan segala kefanaannya. Kini, aku hidup sendiri, tanpa satu persona pun yang aku kenal.
Aku menggigil di tengah sapaan angin malam. Di terminal kota Muntilan, jauh dari remang-remang cahaya lampu jalan yang seakan menunjukan kehampaan, aku terdiam sendirian.
Bukan hanya kedinginan dan sendirian, aku juga lapar. Seorang anak kecil sendirian di dalam pelukan sang malam bisa berbuat apa? Di tahunku yang ke empat belas ini aku sudah kehilangan banyak hal.
Di pojok sana ada sebuah ruko yang masih buka. Si Jahat mulai mencoba mempengaruhi isi pikiranku. Ah mana mungkin. Aku adalah anak yang baik. Namun, perutku tidak bisa ditawar.
Ia meraung meminta sesuap makanan. Setidaknya sebungkus roti. Perlahan-lahan aku menuju ke arah ruko tersebut. Aku menurunkan tubuhku di depan etalase ruko. Sepi. Tidak nampak seorang pun di sana.
Tangan kecilku mencoba mengais sebungkus roti yang nampak bersinar di etalase ruko itu. Masih sedikit jauh. Aku mengangkat kakiku sedikit.
Sedikit lagi. Ah, dapat. Aku segera menarik bungkusan roti itu. Aku melihat bungkusan roti itu seperti menemukan sebuah permata di dalam sebuah penjara. Aneh. Aku pun segera meninggalkan tempat itu.
"Heh, maling!"
Sialan. Aku ketahuan. Aku berlari, entah ke mana. Aku berlari saja. Seharusnya aku tidak mencuri. Benar apa yang dikatakan mereka semua. Mencuri adalah perbuatan tercela.
Tahu begitu aku minta dengan baik tadi. Aku masih berlari dan orang itu, wanita muda yang nampak buram di mataku masih saja mengejarku.
Aku menarik nafas dalam-dalam. Di sebelah kanan depan terlihat sebuah jalan menuju sebuah gang. Gelap. Aku mencoba menengok ke belakang. Sudah jauh, bagus. Aku segera berbelok dan masuk ke dalam gang yang gelap itu.
Di situ ada bangunan bekas. Seperti bekas kos-kosan. Aku mencoba masuk ke tempat itu tanpa pikir panjang. Tempat ini gelap, gelap sekali. Walau gelap, tempat ini bagus, terutama untuk bersembunyi. Nampak tak ada seorang pun. Aman. Aku melepas nafas lega.
"Kamu tengah lari dari apa?" Ada suara seseorang. Suara itu menggema di dalam ruangan ini. Suara yang berat dan serak. Ada bau rokok juga. Hatiku merengek. Belum selesai aku melegakan semua nafasku, sudah ada hal yang menarik kembali udara masuk ke dalam paru-paruku.
Dalam remang-remang kegelapan nampak ada seorang pria. Pakaiannya tidak terlalu bersih, mengenakan jaket kulit, ada nama 'Soelis' di jaketnya, dan wajahnya menampakkan dunia kerisauan.
"Roti itu. Kamu mencuri bukan? Jangan mencuri lagi. Dunia ini penuh konsekuensi." Pria itu bangkit dari duduknya dan membuang puntung rokoknya. Ia menghadapi diriku. Sekarang nampak jelas, jelas sekali wajahnya. Mata sipit, kumis dan jenggot tipis, rambut sedikit ikal kemerahan dan tubuhnya cungkring. Ia membawa sebuah gitar, tetapi kecil. Dia mengambil tempat di sebelahku.
"Siapa namamu?" Tanyanya padaku dengan tatapan mata penuh kewibawaan.
"Darto."
"Mengapa kau mencuri?"
"Saya lapar."
"Di mana orang tuamu?" Sontak, aku menggelengkan kepalaku. Wajahnya mengangguk paham dilengkapi matanya yang berkedip.
"Jangan mencuri. Bekerjalah jika mampu."
"Saya harus bekerja apa?"
"Ngamen?"
"Saya tidak bisa bermain musik sepertimu."
"Aku akan mengajarimu." Orang ini sebenarnya siapa? Dia ada di sini sejak awal dan berlaku misterius. Sekarang dia terlihat sok peduli kepadaku. Lebih lagi apa yang orang ini mau dariku? Dia bukan orang jahat kan?
Dalam sunyi dan gelapnya ruangan ini, dia duduk di sebelah kiriku. Dia mengambil gitar kecilnya. Dia mulai memetik senarnya. Sebuah nada harmonis mulai terdengar. Dia memulai pertunjukannya dengan nyanyian indah nan merdu.
"Lagu apa itu?" Tanyaku kepadanya.
"Bengawan Solo."
"Indah." Dia terus bermain alat musiknya dengan wajah gembira mulai terpancar. Sebuah lagu dapat membuat ruangan hampa ini menjadi bernada indah.
Tanpa bantuan sebuah lampu pun aku bisa menghayati ruangan sekitar dengan nada musik yang melantun mengalahkan keheningan purnama yang tengah menemani kami dalam bayangan yang minor. Malam yang harmonis ini terus menemani kami hingga fajar mulai merekah.
Pagi itu aku terlempar dari lelapnya tidurku. Aku terlelap di ruangan ini. Pria itu tengah berdiri, mengenakan jaketnya lalu mengambil gitar kecilnya.
"Bapak mau ke mana?"
"Aku mau berangkat bekerja."
"Bekerja?"
"Ngamen."
"Saya ingin ikut."
"Kamu tunggu di sini saja. Aku akan kembali pukul sepuluh."
***
Langit sudah membiru, biru yang cerah. Aku masih berada di ruangan ini. Bosan. Kesepian batin melamunkan fisikku. Di ruangan ini hanya ada satu ranjang di pojok. Hanya itu saja.
Aku mencoba keluar dari ruangan ini lalu keluar menuju terminal. Hanya ada lalu lalang bus dan angkutan kota saja. Hidupku ini seolah tidak ada artinya setelah aku kehilangan mereka. Aku kembali ke ruangan itu. Aku menjatuhkan tubuhku di ranjang ditemani oleh kehampaan nasib seorang anak yang kehilangan segalanya. Sekarang aku tengah belajar. Belajar menerima. Belajar menjadi hal.
***
"Bangun!"
"Eh?"
"Aku akan mengajarimu cara mendapatkan uang. Halal." Dia mengambil gitar kecilnya.
"Ini namanya kentrung, kentrung, atau apapun itu kata orang-orang." Dia memetik senar dengan lembut seolah-olah jarinya tengah menari di dalam aula yang gelap dengan bantuan cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca yang besar. Dia mengajariku segala hal tentang nada, irama, kelembutan dan perasaan. Kentrung itu, seolah menjadi tunangannya. Aku mencoba untuk membelai si pengantin itu. Dalam hatiku ada benih yang tumbuh perlahan.
"Bagus. Kamu sudah mulai paham."
"Lalu saya mengamen pakai apa?"
"Di bawah ranjang itu ada satu."
"Milikmu?"
"Bukan. Milik seorang teman, sekarang menghilang."
"Begitu ya?"
"Begitulah." Sejak saat itu aku melanjutkan kehidupanku bersamanya. Pertemuan singkat yang klise itu seolah menjadi benang merah hubungan kami berdua. Kami menjadi semakin akrab layaknya sahabat, seperti partner kerja yang mantap.
Tak seorang pun di kota ini yang dapat mengungguli kami. Menjalani waktu kehidupan dengan mengamen bersama, bersenandung dan tertawa, makan dan lapar bersama, seolah seperti getaran kentrung yang bergerak sendiri tetapi tetap harmonis. Begitulah hubungan kami berdua.
Ada suatu waktu kami tertidur di dalam bus sampai kota Semarang dan uang kami habis hanya untuk perjalanan itu, makan pun tak mampu. Terkadang kami juga ikut kelompok pengamen yang lainnya. Kedekatan kami bertambah, dan kini sudah dua bulan lebih delapan hari setelah pertemuan pertama kami. Hubungan kedekatan ini membuatku berpikir, mengapa ia begitu baik padaku?
Di halte terminal saat malam hari kira-kira pukul sembilan, aku bertanya padanya, "Mengapa kau begitu baik kepadaku?"
"Salahkah hal itu?"
"Tidak ada salahnya."
"Lantas mengapa kau bertanya seperti itu?"
"Entahlah."
"Sekarang aku akan bertanya kepada mu, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan macam apa itu? Seolah batinku mengangkat alisnya dan kebingungan. Pertanyaan seperti itu tidak pernah keluar dari mulut seorang bapak yang telah menjadi pahlawan bagi kehidupan sang anak.
"Ya, aku mengasihi engkau."
"Apakah engkau mengasihi aku?"
"Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau."
Sekali lagi ia bertanya kepada ku, "Apakah engkau mengasihi aku?" dan aku menjawabnya.
"Ya, sudah ku katakan bahwa aku mengasihi engkau." Ini benar-benar aneh bagiku. Ini adalah pertanyaan yang mudah, tetapi mengapa diriku begitu gemetar untuk menjawabnya? Seolah ada malaikat duduk di sebelahku.
"Dahulu, aku memiliki seorang anak. Perempuan. Ia amat kecil dan imut." Anak itu bernama Atik. Larasati Widyanaka. Dia lahir di hari Kamis, hari ke dua puluh bulah ke enam, pukul dua dini hari. Satu jam setelah kelahirannya ke dunia ini, ibunya wafat.
Ia hidup tanpa sosok kelembutan yang membelai tubuhnya sejak kecil. Ia hidup di bawah garis kelayakan seseorang yang hidup di bumi fana ini. Hidup dalam kesepian dan kemiskinan.
Sejak kecil ia dititipkan kepada salah seorang teman. Semuanya berjalan baik adanya. Atik tumbuh menjadi gadis yang elok nan indah tubuhnya. Ia amat pandai dan terpelajar. Namun, sebuah kejadian di jalan besar di Mertoyudan itu membuat semuanya pecah. Sebuah mobil Toyota berwarna merah tua menabrak truk yang sedang belok tanpa memberi aba-aba dengan kencang. Malam itu, surga menyambut jiwanya. Larasati Widyanaka wafat pada malam itu.
Atik yang tengah membonceng pamongnya menuju kota Semarang untuk mengikuti lomba keroncong harus berpulang menghadap Bapa yang merindukannya.
"Kentrungmu itu, sebenarnya adalah miliknya. Itu adalah benda kesayangannya." Sungguh, pria ini mengalami nasib yang amat malang. Yang Kuasa telah mengambil dua sosok penyemangat hidupnya dan ia tetap tegar menjalani hidupnya. Seberapa kuat jantungnya sehingga ia dapat menghentikan hatinya yang terlukai dengan cepatnya darah mengalir di seluruh tubuhnya?
Mengapa di dunia yang indah ini kebahagiaan selalu bergandengan dengan kekejaman? Mereka selalu berjalan bersama dan bersenggama dalam malam yang berkilau. Mengapa hidupku tidak boleh seperti mereka? Mereka selalu membiarkan seseorang merelakan kehilangan yang ia miliki.
***
Aku lahir dalam keluarga sederhana. Aku terlahir dengan nama Sudarto Gathot Basuko. Hidup di ujung daerah Bedono. Ibu dan bapakku merawatku dengan baik adanya. Hingga aku tumbuh menjadi anak baik, walau tidak terlalu pandai.
Toh, anak lelaki mana yang bisa pandai di sekolahnya bukan? Paling tidak mereka bisa mendapat peringkat tiga di kelas.
Aku menjalani hidup baik adanya. Semua berjalan berputar. Ibu dan bapakku baik saja. Walau hanya memiliki mereka, aku tetap boleh hidup dengan baik di lingkunganku. Kegelapan mulai memasuki kehidupanku. Suatu kejadian mengharuskan aku merelakan bapaku yang wafat saat sedang menjalankan proyek di Tidar.
Sejak saat itu hidupku mulai turun ke jurang kegelapan. Seminggu setelah kejadian itu, ibu memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Ia berjanji akan kembali ke rumah satu bulan lagi.
Aku, Darto hidup sendirian di rumah dengan uang tujuh ratus ribu rupiah. Tanpa sosok orang yang lebih tua momong diriku. Aku mencoba tabah hidup sendirian. Satu minggu berlalu, semua baik. Dua minggu, aku merasakan rindu. Empat minggu berlalu, aku berharap ibu kembali. Enam minggu berlalu, di mana ibuku?
Aku sudah tidak tahan dengan perlakuan dunia ini kepadaku. Aku pergi ke luar rumah. Mencari jawaban. Grabag, Magelang kota, Tidar, Mertoyudan, dan Muntilan telah aku jalani. Aku, Darto yang memiliki umur empat belas tahun hidup sendirian. Terminal kota Muntilan menjadi pemberhentianku saat ini, mungkin untuk yang terakhir kali.
***
"Boleh aku memanggilmu Bapak?"
"Dan kau, adalah anakku." Dialog itu, menyatukan kami berdua. Kami berdua kehilangan. Sekarang, kami menemukan. Kami berdua berpisah, sekarang kembali bersatu. Semua dinamika ini adalah berkat Yang Kuasa. Ia yang telah mengambil dan yang telah mengembalikan. Ia yang memberi pengalaman, dan Ia yang memberi pembelajaran.
***
Sore itu aku turun dari bis, aku telah selesai mengamen. Sekarang, aku menuju ke angkringan dekat tempat angkot biasa berjejer pada siang hari. Aku memesan segelas wedang jahe dan nyruput dengan perasaan syukur atas hidupku yang mulai membaik. Walaupun hidupku jauh dari kata layak, sebagai anak remaja. Setidaknya aku masih bisa makan, dengan uang halal.
"Pak, Pak Soelis sudah pulang belum?" Tanyaku pada penjaga angkringan itu.
"Wah, Pak Soelis belum pulang. Tadi saya sempat melihatnya menaiki angkot. Hendak ke Tidar mungkin."
"Oalah begitu toh. Terima kasih nggih pak."
"Iya nak."
Ke mana Bapak pergi? Katanya hendak mengamen sampai siang saja lalu beristirahat. Ah, mungkin Bapak sudah bangun dan hendak menikmati hutan Tidar itu. Yang banyak monyetnya.
Setelah itu, aku pun meninggalkan angkringan itu dan kembali ke tempat yang aku sebut rumah, tetapi hanyalah sebuah bekas kos-kosan yang tidak dirawat oleh pemiliknya. Setidaknya, aku punya tempat untuk pulang.
Sesudah kejadian itu, Bapak sering kali pergi saat sore hari. Entah apa yang beliau lakukan. Aku pun hanya bisa bertanya-tanya dari jauh di dasar sanubari ini. Tak elok rasanya jika aku harus bertanya secara langsung dengannya.
Pernah suatu siang aku mengikutinya secara diam-diam, tetapi sepertinya Bapak tahu bahwa aku mengikutinya, sehingga beliau tidak jadi pergi dan kembali pulang. Aku hanya bisa penasaran dengannya. Padahal hubungan kami sudah baik, amat baik, tetapi mengapa sekarang seperti ada jarak yang memisahkan kami? Ah, dunia ini aneh.
***
Sore ini aku kembali ke angkringan, di terminal. Seperti biasa aku memesan wedang jahe dan bertanya tentang bapak, kepada penjaga angkringan itu.
"Namanya juga orang tua, pasti ada keperluan. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, mungkin dia ingin merenung, atau sekadar menikmati kesendiriannya." Nasehat penjaga angkringan itu kepadaku.
Ada benarnya hal itu. Namun, Bapak adalah orang yang terbuka. Masakan ia selalu pergi secara diam-diam? Bukankah jika ada masalah sebaiknya dibahas secara bersama? Atau, apa urusanku terhadap Bapak? Ah, dialah Bapakku, aku seharusnya tidak perlu ikut campur. Namun, ia Bapak. Bapakku. Aku patut mengkhawatirkannya. Benar toh?
Dan malam itu aku terus memikirkan tentang Bapak. Seolah ada ikatan batin yang mengharuskanku memikirkan tentang Bapak. Ada apa dengan Bapak? Hanya ada satu cara yang dapat aku lakukan untuk mengetahuinya. Dan semoga, besok, aku dapat berhasil untuk menjalankan rencanaku. Dan aku menutup malamku dengan keyakinan yang mantap, aku yakin aku akan berhasil.
***
Mertoyudan? Apa yang hendak Bapak lakukan di Mertoyudan? Mengamen di kampus yang besar ini? Atau mengamen di sekolah pastor itu? Dari kejauhan, aku melihat Bapak turun dari angkot yang ia tumpangi.
"Kiri pak!" Aku langsung menghentikan laju angkot yang aku tumpangi, membayar biaya perjalananku ini, dan aku langsung melompat ke luar. Ia berjalan ke utara.
Aku mengikutinya, dari belakang. Ia berbelok ke kiri, ke jalan yang dekat kali itu. Ia terus berjalan. Dia menyebrang jalan dan masuk ke dalam sebuah lahan. Lahan apa itu? Untuk menjawab rasa penasaranku aku langsung mengikutinya, dengan perlahan-lahan.
Sebuah makam. Ya, Bapak pergi ke sebuah makam. Ia duduk di dekat sebuah kijing berwarna hitam. Aku masuk ke dalam daerah kompleks makan itu. Bapak tengah menengadah ke langit, beliau seperti menunggu sesuatu. Aku mendekatinya.
Dia mengambil gelas yang ia letakkan di samping kanannya dan mulai menyeruput minumannya itu. Aku melangkahkan kaki kiriku, dan sekarang aku berdiri tepat di sampingnya. Beliau meletakkan cangkir miliknya. Aku duduk di samping kanannya, memeluk kedua kakiku dan meletakkan daguku.
"Aku selalu memikirkannya. Dia mirip sepertimu. Kecil, ramah, dan pandai bermain kentrung. Saat pertama kali aku melihatmu, aku enggan menanggapi dirimu. Namun, sebungkus roti yang kamu bawa itu membuatku berpikir lain. Saat itu Tuhan berbisik padaku, untuk mengambilmu. Dan hari itu, Tuhan menuntun diriku untuk belajar. Belajar merelakan."
"Mengapa selama ini Bapak tidak cerita?"
"Aku ingin kamu tahu bahwa diriku bukanlah orang yang hebat. Aku seperti anak kecil, aku mudah menangis. Hanya di depanmu lah aku mampu menahan semua sayatan di hatiku."
Langit oranye itu dengan tabah menemani kami. Burung manyar yang sedang terbang itu menghiasi pemandanganku sembari aku merenung. Dunia ini indah. Bukan hanya indah, dunia ini juga kejam. Saat ini aku sedang duduk di atas lahan, milik orang yang telah berpulang. Entah di mana jiwa mereka sekarang berada.
"Sekarang, Bapak punya aku. Aku memang tidak seindah Larasati Widyanaka, tetapi aku akan berusaha menjadi anak yang baik."
"Kamu anak yang baik, dan aku ayah yang buruk."
"Bukankah Tuhan menciptakan semua baik adanya?"
"Kamu benar anakku."
Di samping kijing itu terdapat setangkai bunga. Bunga berwarna putih. Bunga yang baru tumbuh kira-kira tiga minggu yang lalu. Bunga yang masih bersih. Bunga yang amat indah. Bunga yang cantik yang menemani kekejaman dunia ini. Dan di sini, terdapat dua lelaki yang saling bercerita. Bunga itu, menjadi saksi bahwa dunia ini masih memiliki keindahannya.
Februari 2024
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H