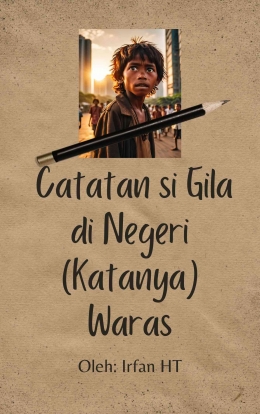Hari ini ulang tahunku. Tiga puluh tahun sudah aku mengabdi sebagai hamba Tuhan di dunia ini. Aku tak punya siapa-siapa. Keluargaku sudah tiada. Aku hanya punya raga dan napas. Itu pun sudah kusyukuri. Teman-teman yang biasa duduk menemani setiap malam sudah tak pernah kutemui lagi.
Ada yang bilang mereka sakit, lalu mati di pinggir jalan. Ada yang dititipkan di dinas sosial untuk dibina. Entah sampai kapan pembinaan itu selesai. Batang hidung mereka pun sudah tak pernah kulihat lagi. Bagiku, mereka sudah mati. Setidaknya, tak bebas seperti jiwaku.
Kuseruput sedikit kopi yang kuterima dari kedai samping kandangku. Kopi pahit buatan Mak Mijah yang hampir setiap hari gratis kudapat.
"Man, mau gorengan, ya?" tanya Mak Mijah dari bilik bambu tempat tidurku.
Aku tak menyahut. Teriakan beliau lebih keras dari sebelumnya, "Man, Mak taro di depan pintu ya?"
Kuraba-raba sekeliling tempatku bersandar. Aku menghadap tiap-tiap lobang dimana cahaya lampu jalan raya menembus kandangku. Aku sebut kandang karena memang layak disebut demikian.
Alas tidurku dari tanah liat. Kalau hujan, aku duduk ditemani oleh cacing tanah yang bergeliat. Kecoa-kecoa mungil juga hilir mudik menambah ramainya suasana hati.
Mak Mijah, perempuan tua yang tinggal di samping kandangku adalah salah satu orang yang tak pernah menganggapku gila. Wanita paroh baya itu ditinggalkan suaminya 30 tahun yang lalu karena bekerja menjadi tenaga kerja ilegal di Malaysia. Beliau selalu mengajakku bicara. Walaupun aku diam, wanita yang sepantasnya kupanggil nenek itu selalu bercerita tentang suaminya yang entah masih hidup atau sudah mati.
Beliau tak peduli dengan diamku. Mungkin akan lebih nyaman bercerita sepanjang malam tentang masa lalunya jika aku hanya menunduk dan mengangguk. Hanya orang-orang usil yang lewat mengganggu. Mereka sering berteriak dan melempari kandangku dengan botol kosong air mineral.
"Man, Mak sudah ngantuk, mau balik dulu. Jangan lupa gorengannya dihabiskan," ucap Mak Mijah setelah panjang lebar bercerita. Pintu kandangku tak ditutupnya karena seperti biasa angin kencang membanting kembali pintu yang terbuat dari kayu palet bekas yang lapuk dimakan rayap.
Seperti biasa aku tak merespon. Aku hanya tersenyum sedikit sambil berbaring menatap lobang-lobang di dinding kamar kandangku yang cahayanya semakin redup karena hujan deras turun.
Aku mengingat kembali bagaimana masa laluku sampai berada di tempat ini. Seorang Parman Sukiman, pemuda asal Jawa Tengah yang bermimpi untuk mendapatkan beasiswa kuliah di universitas ternama di Yogyakarta. Pemuda yang orang tuanya tidak mampu membayar kuliah karena kondisi ekonomi rapuh. Pemuda yang sangat berambisi, cerdas dan selalu juara saat duduk di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
Kuingat saat ayahku menitipkan pesan terakhir sebelum pergi untuk selamanya, "Man, bermimpilah yang tinggi. Kalo tak tercapai, bangunlah dari tidurmu dan terima kenyataan yang ada," ucap beliau terbata-bata.
Saat itu, kata-katanya kuabaikan begitu saja. Aku sangat berambisi untuk mencapai cita-citaku sebagai Duta Besar di negara Timur Tengah. Bukan tak beralasan, aku menguasai 5 bahasa dunia yaitu Inggris, Belanda, Jerman, Arab, dan Rusia. Semua kupelajari secara otodidak. Entahlah, mungkin Tuhan memberiku kelebihan dari orang lain dibalik kekuranganku. Bagiku, membaca saja sudah membuatku paham belajar bahasa asing.
Ayahku rajin membelikan buku-buku bajakan yang ada di pasar loak. Beliau sadar kalau aku punya minat dan bakat yang tinggi di bidang bahasa. Namun, ayahku juga sadar kalau mimpiku untuk menjadi duta besar di negara Timur Tengah tidaklah mungkin terwujud. Jangankan biaya kuliah, makan setiap hari saja keluargaku sudah sulit.
Perlahan, mataku mulai terpejam karena kantuk. Lamunan mengenai masa lalu mulai berantakan tak berarah. Kadang kuteringat dua adik kecilku yang merengek minta dibelikan mainan truk pengangkut pasir pada ayah. Kuteringat juga ibu yang sering pinjam sana sini hanya untuk bisa memasak setengah liter beras miskin dan 1 butir telor ayam dibagi untuk makan empat orang.
Kadang lamunan juga melompat ke masa pertama kali aku mengajukan beasiswa ke kampus impianku. Namun saat ingat ditolak, secara refleks tanganku mengepal dan berteriak, "Tidak...."
Jantung berdegup kencang jika aku ingat tiga kali telah mengajukan lamaran beasiswa di kampus itu. Sudah tiga kali pula aku ditolak. Sejak itu, amarah muncul jika mendengar kata beasiswa.
"Man, gak ke kampus?" teriak Mak Mijah dari balik pintu.
Seperti biasa aku terdiam tapi bergegas karena melihat sinar matahari sudah begitu terang dan menyinari seisi kandangku.
Aku tak mandi karena merasa tetap bersih. Orang-orang yang mandi setiap hari saja masih kelihatan kotor dengan kemunafikan.
Kuingat saat ada seorang wanita yang mengusirku dari gerbang rumahnya yang mewah. Sikapnya sinis karena terganggu oleh kehadiranku.
"Sana pergi, dasar orang gila," ucapnya dengan nada marah sambil menutup hidung seakan aku adalah seonggok bangkai yang menghalangi jalan masuk istana megahnya. Padahal aku sering mendengar pembicaraan orang-orang sekitar mengenai suaminya. Dia pejabat daerah namun bertindak curang terhadap jabatan yang telah diamanatkan padanya. Tidak tahu malu.
Seperti biasa aku tak menjawab. Hatiku bergumam, "Apa kau tak lebih gila, sekeluargamu bisa bangun rumah mewah ini karena suamimu makan dana bansos untuk korban bencana alam? Bukankah itu karena ambisimu untuk kaya sehingga memaksa suamimu mendekam di penjara setelah tertangkap KPK?" Aku hanya tersenyum pada wanita gila yang kujumpai pagi itu.
Kuingat lagi saat aku menuju 'kampus'. Seorang pria tua bergegas keluar dari mobil hitam sambil membetulkan resleting celananya kemudian menabrak bahu kananku saat berpapasan.
"Dasar orang gila, minggir kamu!" ucap si pria yang sudah berumur, dengan lantang ke depan wajahku sambil mendorong dada sampai tubuhku jatuh di samping trotoar.
"Bapak jahat!" terdengar suara dari balik jendela mobil itu. Suara seorang gadis yang berpakaian biru putih menangis tersedu keluar menyusul dari pintu belakang mobil. Dia memegang perutnya yang terasa sakit.
Tak lama, terdengar suara deru knalpot mobil bergegas pergi. Anak gadis itu ditinggal dan dia terus menangis di tepi jalan. Beberapa pria di sekitar lokasi kemudian ramai menghampirinya.
"Kamu kenapa, Dik?" tanya salah satu pemuda.
"Saya dipaksa, Bang,"
Penasaran si pemuda bertanya kembali, "Dipaksa apa?" Namun dia hanya terdiam.
"Udah, ayo bawa ke Polsek saja," teriak salah satu pria disana.
Beramai-ramai mereka kemudian membopong si gadis yang terus saja menangis.
Aku mendengar jelas saat dibopong, dia baru saja diaborsi karena telah hamil 3 bulan oleh pria berumur yang meninggalkannya barusan. Wajar saja kalo dia meraung kesakitan. Yang lebih mengejutkanku, orang yang menghamilinya adalah gurunya sendiri di SMP dimana dia bersekolah.
"Aku bertemu orang yang benar-benar gila hari ini," gumamku.
"Kenapa malah aku yang dianggap gila oleh mereka?" masih kubertanya-tanya dalam hati.
Tak satu pun yang menghiraukan keadaanku di samping trotoar. Kuambil tongkatku untuk berjalan. Dengan tertatih, aku lanjut menuju tujuanku pagi ini. Aku tak peduli.
Kampus tujuanku tidak jauh dari tempat tinggal. Hanya butuh waktu 30 menit. Itupun karena kakiku yang pincang. Sirene palang kereta api menjadi patokanku. Getaran terasa saat kakiku menginjak salah satu bagian rel.
Aku pun sudah tahu jika jarak kereta listrik tinggal 1 atau 1,5 km lagi untuk tiba di lokasiku berdiri. Namun begitu, penjaga palang pintu selalu berteriak waspada agar aku tetap berada di pinggiran rel.
"Awas minggir, mau mati?"
Ucapan itu sudah sering kudengar. Kadang diselingi dengan lemparan kerikil yang tak jarang mengenai bahu maupun jidatku.
Cemohan orang-orang yang sedang bermain kartu di pos ronda samping palang pintu rel sudah kuanggap biasa, "Ini orang gila mau mati ya?"
Terdengar suara terbahak-bahak dengan nada bahagia karena salah satu dari mereka menang bermain kartu.
"Alhamdulillah, ya Allah...." sambungnya seraya bertakbir berkali-kali dan mengepal uang taruhan di telapak tangannya.
"Allahu Akbar, Allahu Akbar" pekiknya lagi sambil berlari dan melompat-lompat kegirangan.
"Baru menang judi saja sudah begitu," ujar salah salah satunya.
Aku tetap tak peduli. Kulanjutkan perjalananku. Namun saat berbelok dari palang pintu yang kulewati, terdengar si penjaga berteriak kembali, "Woi, gila beasiswa kau ya." Suaranya besar dan tebal menandakan ia perokok berat.
Aku maklum kenapa dia berucapkan itu. Memang, kadang aku berjalan tanpa sadar berteriak di kerumunan orang banyak, "Aku jadi mahasiswa, aku dapat beasiswa!"
Ucapan itu terlontar tanpa sengaja saat kuteringat bagaimana pihak kampus menolak memberikan beasiswa hanya karena aku cacat.
"Tahun depan Anda mungkin bisa melamar lagi, kuota beasiswa saat ini sudah penuh," ketus salah seorang wanita yang mewawancarai.
Perasaan kecewa rasanya di luar harapan. Perguruan tinggi tempat mengenyam pendidikan seharusnya memberikan tempat khusus untuk orang-orang cacat sepertiku.
"Would you explain why I am not accepted in this campus?" kubertanya dengan bahasa Inggris untuk membuktikan kemampuan berbahasaku dalam bahasa asing. Kuingin tahu apa yang menjadi alasan sebenarnya.
"Wat is er mis?" kutanya lagi dengan bahasa Belanda.
"Bitte erklre!" sambungku dengan bahasa Jerman untuk membutuhkan jawaban. Namun, tim pewawancara yang terdiri dari 3 orang hanya terdiam. Aku tak tahu apakah diam mereka karena terpana dengan kemampuanku atau kasihan.
Salah satu pria berbisik ke rekan wanita di sampingnya, "Kuota yang satu ini uda dipesan oleh pak rektor untuk anak gadisnya."
"Ohh, begitu. Kapan tesnya?" tanya si wanita.
"Ga perlulah, anak rektor kok," bisik si pria.
Bisikan itu makin mengiris hatiku dan membuatku ingin berteriak. Hancur sudah angan-angan untuk berkuliah disana.
"Silahkan, Mas," ucap si wanita dengan lembut tandanya mengusir secara halus.
Dalam perjalanan, aku terus menghayal menjadi si anak rektor. Aku membayangkan bagaimana enaknya jadi anak pejabat. Tak perlu repot sana sini dan tak banyak perjuangan yang dilalui.
"Mas Man, ayo masuk!" seseorang membuyarkan lamunanku. Ternyata aku telah sampai ke kampusku yang baru.
Kutinggalkan lamunan. Kuletakkan tongkat di samping tumpukan buku tua. Aroma buku yang sebagian lapuk menandakan cukup lama buku-buku itu terpendam di sebuah ruangan berukuran 2 x 3 meter persegi yang pengap dan lembab.
"Obral, obral, buku murah," teriak si lelaki yang memanggilku tadi.
Pak Leo, begitulah orang-orang di pasar loak memanggilnya. Pria berkulit hitam berusia 60 tahun asal Ambon yang sudah 25 tahun lebih berjualan buku. Topi koboi berstiker burung Garuda selalu dipakainya. Tongkat dengan bendera merah putih berukuran kecil di ujungnya juga menjadi ciri khas pak Leo.
Mengagumkan, sehari ia mampu membaca lebih dari 5 buku sambil berjualan. Tak jarang buku-buku belajar bahasa asing dipinjamkan oleh pak Leo ini padaku. Banyak pengalaman berharga yang kudapatkan dari pria tua ini.
"Merah putih ini sudah mengalir dalam darahku, Man," tandas pak Leo saat pernah kutanya kenapa dia selalu membawa bendera kecil kemanapun dia pergi.
Cintanya pada dunia pendidikan sangat tinggi. Pernah kudapati beberapa kali anak-anak yang mencari buku pelajaran sekolah namun kekurangan uang untuk membayar buku bekas. Tak jarang pak Leo pun memberinya gratis.
"Kalo bukan kita siapa lagi yang bisa bantu anak-anak ini untuk mengenyam pendidikan, Man," sambungnya.
"Saat minat baca anak-anak di Indonesia masih rendah, aku ikhlaskan buku-buku ini untuk orang-orang yang masih mau membaca."
Seperti biasa, aku tak bersuara. Walaupun demikian, aku kagum dengan rasa cintanya pada tanah air. Pantas saja beliau kupanggil 'Rektor' di kampus tak bernama ini. Nilai-nilai luhur pendidikan terpatri di ruangan sempit itu. Yang lebih mengagumkan lagi, pak Rektor Leo telah memberikanku beasiswa seumur hidup dengan menggratiskanku belajar tentang wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang sangat berarti.
Tidak seperti kampus tujuanku dulu. Usahaku untuk mendapatkan beasiswa sia-sia padahal sudah 3 kali aku datang melamar dengan mempersiapkan persyaratan yang diminta. Namun, alasannya tetap sama. Kuota sudah penuh. Entah sampai kapan kuota itu kosong dan bisa kutempati. Begitu susahnya diriku untuk bisa belajar tanpa biaya pendidikan.
Rasa ambisi yang berlebihan menyurutkan keinginanku untuk pindah tujuan kampus. Aku tetap ingin belajar di tempat impian seperti cita-cita orang lain. Namun sayang, sia-sia.
(Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H