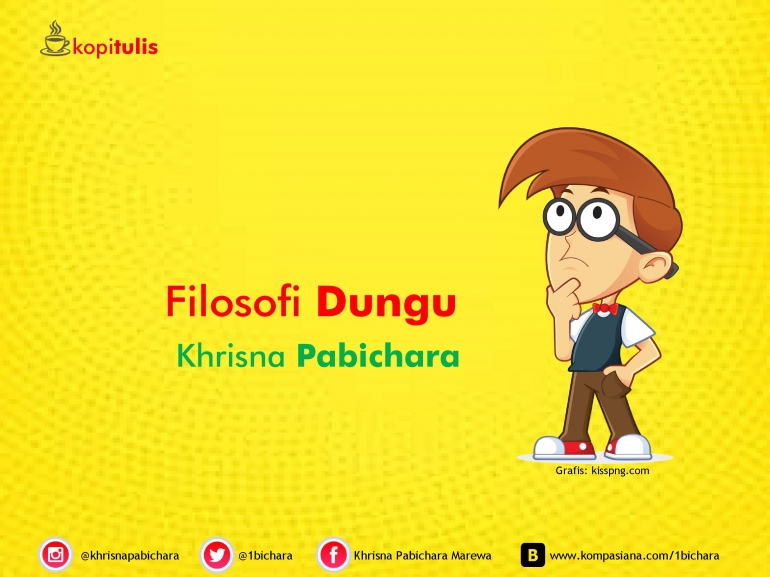Engkos berteduh sejenak di bawah rindang pohon cempedak. Senjatanya, sapu bertangkai panjang dan pengki plastik bergagang aluminium, ia letakkan di atas rumput. Tunai sudah ibadahnya selama enam jam bersama serakan sampah.
Matahari di atas pucuk cempedak menyisakan bayang-bayang. Deru kendaraan bersaing memasuki kuping, derum gas dan decit rem ikut meruyak gendang telinga, dan sahut-sahutan klakson sungguh memekakkan pendengaran. Desa Sukatawa selalu bising dan riuh. Orang-orang seperti kerasukan setan membelah jalan.
Engkos membiarkan angin mengeringkan peluhnya. Kelopak matanya memberat. Kantuk yang selama beberapa hari seolah tak mengenalnya, mendadak akrab dan sok dekat. Setelah merasa tubuhnya lebih segar, ia berdiri dan meraih kedua senjatanya.
Tidak ada yang segigih kopi untuk mengusik dan mengusir kantuk. Pikirnya. Ia berjalan sambil bersiul-siul, menyapa siapa saja yang berpapasan dengannya, melambaikan tangan kepada Encum--pemilik kedai kecil di tepi jalan utama Dukuh Doyankata, dan kembali meneruskan siulannya.
Hanya ada satu warung kopi di Dukuh Doyankata. Di situlah Engkos sering melepas penat selepas enam jam berdinas di jalanan sebagai petugas Sapubersih. Di situ pula ia kerap bercengkerama dengan penduduk Dukuh Doyankata.
Belum ada siapa-siapa di warung kopi Kang Mamat. Hanya ada senyum lontong, cengar-cengir tempe goreng, tahu isi yang cengengesan, kue bolu kering yang peringisan, gelak emping, dan seringai gelas bertelinga yang minta segera dituangi kopi.
"Kopi?" tanya Mamat tanpa menoleh.
Engkos menggeletakkan kedua senjatanya di bawah bangku panjang. "Hitam pekat, Kang."
"Sehitam dan sepekat nasib cintamu?" Mamat tergelak sambil membolak-balik pisang di wajan.
Bohlam di atas kepala Mamat berkedip-kedip. Cangkangnya tampak agak longgar dari dudukannya yang sudah menjuntai di eternit dan memperlihatkan kabel warna-warni.
Sambil mendengkus, Engkos mencomot tempe goreng dan mencocolkannya ke sambal korek yang warnanya seperti pipi gadis yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Cengar-cengir tempe goreng itu seketika sirna, seakan-akan ia menyadari bahwa kematiannya sudah di depan mata. Benar saja. Hanya dalam dua kali gigit, tempe goreng itu sudah menyesaki mulut Engkos.
Mamat meletakkan gelas di atas meja. "Elu tahu dungu?"
"Kang Mamat!"
Perantau dari Garut itu cengengesan. "Bukan. Maksud gue, arti kata dungu."
"Kata itu disematkan kepada orang yang tumpul otaknya," ujar Engkos sembari mencebis tahu isi, menjejalkannya ke mulut, dan mengunyahnya pelan-pelan. Ia mendongak dan tersenyum melihat Mamat masih berdiri di sisinya dengan mulut membentuk huruf 'o'. "Dungu setingkat di bawah bodoh. Orang bodoh masih ada secercah harapan untuk belajar."
Mamat mengangguk-angguk. "Berarti para cebong sudah kehabisan harapan belajar."
"Kata siapa?"
"Rocky Gerung."
"Kapan ia bilang begitu?"
"Semalam di tivi."
Engkos terkakak-kakak. Matanya sampai berair. "Kalaupun benar tudingan Rocky, dungu sejatinya ia sematkan pula kepada kaum kampret."
"Kenapa?"
"Ada kampret yang menyebut mustahil jalan desa sepanjang ratusan ribu kilometer dibangun dalam tempo empat tahun," ucap Engkos pelan sambil meletakkan gelas di tatakan, "kampret ini menuduh mustahil jalan desa sepanjang itu dibangun berbekal ajian simsalabim."
Mamat mencebik. "Diameter bumi juga tidak sepanjang jalan desa, kan?"
"Begini, Kang," kata Engkos pelan, "Ada dua belas dukuh di Desa Sukatawa. Setiap dukuh punya setidaknya tiga hingga lima jalan desa. Bayangkan puluhan ribu desa di seluruh Indonesia. Jika tiap desa punya sepuluh kilo jalan desa, bisa diterka panjang jalan desa di seantero Nusantara."
Mamat mencelangap. "Mmm...."
Bagi Engkos, ungkapan "mmm" sungguh memuaskan. Apalagi didesiskan dari mulut yang selama beberapa detik sebelumnya mencelangap. "Jalan-jalan desa itu tidak dibentang memanjang. Kadang berkelok, kadang memanjat bukit, kadang berjajar jika dilihat dari atas, kadang sambung-menyambung seperti urat-urat di dalam tubuh kita. Inilah perlunya kita membaca. Bukan sebatas membaca buku, melainkan juga membaca gejala semesta."

"Apa arti 'hemm' bagi Kang Mamat?"
"Sedang berpikir."
"Apa?"
"Rasa-rasanya enggak logis kalau jalan desa sepanjang itu kelar dalam empat tahun."
"Bisa jadi."
"Mustahil!"
Engkos menutup telinga ketika klakson motor bersahut-sahutan. Setelah bising reda, ia menghela napas. "Ingatkah Kang Mamat ketika jalan desa di Dukuh Gemarumpi dikerjakan?"
Mamat menjawab dengan anggukan.
"Panjang keseluruhan mencapai sepuluh kilo di lima titik dengan masing-masing dua kilo," ucap Engkos dengan mimik agak serius. "Jalan itu rampung hanya dalam empat bulan. Kelar bersamaan karena dikerjakan secara bersamaan. Jika sepuluh ribu desa pada saat bersamaan mengerjakan jalan desa sepanjang masing-masing sepuluh kilo, berarti ada kemungkinan seratus kilo jalan desa tuntas dalam waktu empat bulan."
Mamat mencelangap lagi. Kali ini tanpa diikuti "mmm" atau "hemm". Pengunjung warungnya memang bukan serombongan sarjana, segerumbul filsuf, atau sekawanan pakar, tetapi obrolan di warungnya tidak bisa dipandang sebelah mata.
Jajang, saudagar pecal ayam, sangat fasih membahas gerak-gerik peniaga pinjaman daring gara-gara ia diteror ketika cicilannya tertunda selama dua bulan. Parman, tukang gali got, lincah bercuap tentang hoaks. Jangan dikata Engkos, tukang sapu paruh waktu, wawasannya melebihi panjang tangkai sapunya.
"Berarti dungu bukan cuma hak milik kaum cebong?" tanya Mamat dengan tatapan menyelidik. Sedikit seringai mengakhiri pertanyaannya.
"Ya," seru Engkos. Suaranya tegas. "Ketika kasus operasi plastik merebak dan disangka buah tangan para pengeroyok, itu termasuk perangai 'dungu luar biasa'. Dalam bahasa Indonesia disebut 'goblok bukan kepalang'."
"Jalan desa lebih panjang dari diameter bumi?"
"Wah, itu mah kalimat brilian dari orang pintar."
"Tadi kata elu salah...."
Engkos mencongak sejenak. "Hitung-hitungnya jago. Satirenya tokcer, tetapi ada sedikit nila dungunya. Dalam bahasa Indonesia disebut bongak. Kata ini cocok bagi orang pintar yang tiba-tiba pilon demi membuai pendukung dan junjungan."
Mamat tertawa. "Mestinya ada Bang Jadi."
"Mau main catur?"
Mamat menggeleng. "Supaya diskusi lebih seru, sekalipun belakangan ini Bang Jadi sedikit bongak dan banyak pilon."

"Suatu ketika," kata Engkos, "Seno Gumira Ajidarma menulis begini. Lebih baik memiliki diri sendiri daripada memiliki semuanya, kecuali diri sendiri. Ini berlaku ketika cinta membutakan hati. Semua orang dari kubu sebelah dituding dungu atau pembohong, sementara dia juga sering berbuat dungu dan berbohong."
"Kok cinta?"
"Cinta pada golongan sendiri yang tiada terkira sehingga mata batinnya tersaput kabut benci." Engkos menatap Mamat. "Ketika seseorang menyebut bahwa jomlo dan menikah amat erat kaitannya dengan kemiskinan, lantas menyajikan data hasil riset, mengolah narasinya sedemikian rupa sehingga tampak mentereng, padahal dongok."
"Dongok?"
"Kakaknya dungu, adiknya bego." Engkos terkakak-kakak. "Tabiat dan perangai warga di suatu negara tidak bisa dipukul rata dengan perilaku penduduk negara lain. Pasti berbeda. Jadi, hasil penelitian di Amerika tidak serta-merta dianggap mewakili keadaan di negara lain."
"Siapa yang melakukan itu?"
"Kampret lagi!"
"Berarti cebong baik semua?"
Engkos tergelak-gelak hingga bahunya terguncang-guncang. "Belum tentu. Banyak cebong yang mendadak tumpul daya kritiknya ketika junjungannya salah menyampaikan data. Ada juga cebong yang menyebar hoaks ketika seorang suporter sepak bola digebuki."
"Hanya itu?"
"Cebong yang kerap menyindir orientasi seks putra Pak Prabowo, misalnya. Menanyakan di mana Pak Prabowo salat Jumat, misalnya lagi. Itu juga orang beloh alias pandir."
"Itu akibat ulah kampret." Mamat membantah. "Cebong hanya menangkis serangan."
"Alamat kebengohan atau kepandiran."
"Belum tentu."
"Membalas kekerasan dengan kekerasan berarti sama-sama melakukan kekerasan."
Mamat terpangah.

Engkos mengetuk-ngetuk meja dengan buku jari manis kanannya. Iramanya teratur dalam tempo yang sedang. "Jatuh cinta, menurut Kuntowijoyo, salah satu belenggu hidup. Seburuk atau sebusuk apa pun yang dicintai, tidak akan memengaruhi hati. Cemooh orang lain selalu ditangkal dengan kata tidak peduli atau masa bodoh atau bodoh amat. Bila sudah begitu, apa beda antara pintar dan pandir?"
Mamat mendengarkan dengan mimik terpesona. Matahari membakar jalan raya. Angin menyeruduk daun-daun. Asap dari knalpot kendaraan menyerang cuping hidung. Kopi menyusut hingga ampasnya terdengar meratap minta diganti.
Engkos kian berapi-api. "Cinta memang kita butuhkan. Naguib Mahfouz, sastrawan Mesir, berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diperbuat oleh kematian pada hati ketika cinta telah membuatnya abadi. Saya mencintai kopi, tetapi saya harus pintar-pintar menghitung seberapa gelas kopi yang saya butuhkan selama sehari. Mengapa? Saya juga butuh teh, susu, atau jus."
"Pantas dari tadi baru pesan segelas kopi."
"Tenang," ujar Engkos, "nanti saya tambah."
"Bercanda."
"Saya juga bercanda."
Kening Mamat kontan berkerut. "Balik lagi ke dungu!"
"Silakan!"
"Apa tanggapan elu atas tabiat Rocky mendungukan orang lain?"
"Ketika kita menghina dan menunjuk-nunjuk orang lain, sebaiknya kita mengingat lagi ujar-ujar leluhur. Telunjuk mengarah pada orang yang dituding, jempol abstain, sedangkan jari tengah, jari manis, dan kelingking kompak menunjuk penuding."
"Berarti tiga banding satu."
Engkos mengangguk. "Betul!"
"Berarti Rocky dungu?"
Engkos mengedikkan bahu. "Saya tidak menuduh begitu. Jangan dipelintir."
"Loh, tadi kata elu ingat ujar-ujar leluhur."
"Saya meminta Kang Mamat mengingat petuah leluhur, bukan menuduh Rocky dungu." Engkos menyeringai. "Lagi pula, ada gelagat Rocky kurang kreatif. Masih banyak kata selain dungu, tetapi ia lontarkan kata itu terus-menerus. Meminta orang berpikir dengan jalan mendungukannya, bagi saya, bukan tabiat pemikir yang kreatif."

"Ingat hikayat guru yang meminta murid-muridnya menyembelih ayam ketika tiada yang melihat?"
Mamat mengangguk.
"Itu sekadar contoh bagaimana mengajak orang lain berpikir tanpa mendungukannya."
"Gue paham," kata Mamat. "Tapi, ada satu hal yang ingin gue tanyakan."
"Silakan!"
"Elu itu sebenarnya cebong atau kampret?"
Engkos mengangkat gelas kopinya. Tegukan terakhir. Setelah itu ia berkata, "Warna bukan hanya hitam atau putih. Kang Mamat orang Sunda, tetapi lebih doyan memakai gue dan elu dibanding aing dan maneh!" [khrisna]
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H