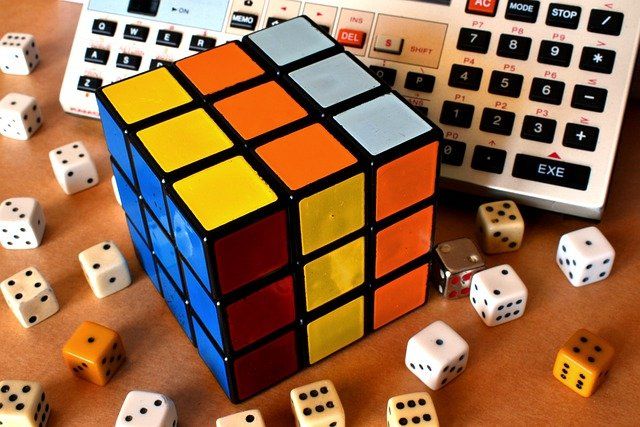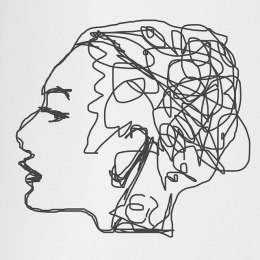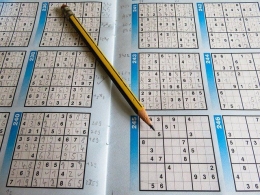Parameternya? Kelas pekerja membutuhkan dominasi logika. Sedangkan Pemikir sebaliknya, butuh daya imajinasi.
Jika meminjam rumus Einstein di atas. Maka, pendidikan di Indonesia, mengalami "ketidakseimbangan" jika kata "ketidakadilan" tak pantas diujarkan atau digunakan.
Ukurannya? Tiga Mata Pelajaran yang di-UN-kan. Pelajaran Matematika dan IPA dianggap mewakili Kutub Logika, dan hanya Bahasa Indonesia yang menjadi wakil dari Kutub Imajinasi.
Hematku, gegara ketidakseimbangan ini, maka anakku menjadi ragu memilih jurusan. Karena jika membaca potensi diri, secara logika merasa berat masuk IPA. Namun, asupan gizi di bangku sekolah tak tersedia melatih berimajinasi.
Saat di TK dan SD. Masih ada tugas menghapal lagu wajib nasional, notasi lagu daerah, memainkan alat musik, membaca atau mencipta puisi, hingga menggambar dan mewarnai. Itu pun terkadang masuk kurikulum ekstra, bukan intra kurikuler. Pada jenjang SMP ragam pembelajaran di atas sudah jauh berkurang.
Sependektahuku, pihak sekolah hingga perguruan tinggi, acapkali melakukan Tes Potensi Akademik bagi siswa atau mahasiswa. Walau terkadang dilakukan secara seremonial, kukira akan mengeluarkan hasil yang beragam.
Namun, hasil Tes Potensi Akademik belum menjadi pijakan oleh Pengambil keputusan saat menentukan kebijakan tentang penggunaan kurikulum. Wong, kurikulum yang digunakan selalu seragam, tah?
Ini menjadi aneh! Seumpama petani yang menyemai beragam benih tanaman, namun memberikan perlakuan serta perawatan pada tanaman dengan pola seragam! Akibatnya? Hasil belajar tak bisa menjadi ukuran.

Aku ingin mengajak pembaca bertamasya pada artikel-artikel yang telah ditulis oleh Tuanku eFTe.
Tak bermaksud membalas artikel yang diunggah oleh Prof Felix Tani. Biar gampang, kuambil contoh artikel tentangku (Kompasiana, 8/7/2021). Artikel itu hampir membuatku berpikir ulang, haruskah menyesal terlanjur mengaku sebagai murid?