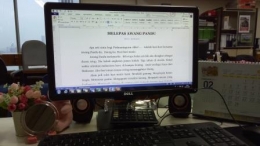“Kamu ingin aku menunggumu sampai kapan?”
Aku tak bisa menjawab. Tidak tahu jawabannya. Apakah aku menginginkan Daeng? Dia menginginkanku. Serius. Apakah aku juga begitu?
Jika aku menerima lamaran Daeng, sekarang, atau besok, aku harus siap menjadi istri yang melayaninya. Mengurus makannya, kebutuhannya, ada di rumah sepulang dia bekerja. Sebagai wartawan, bisakah?
Mungkin aku akan sering pulang larut malam, meliput di malam hari bahkan subuh. Mungkin aku tidak ada di rumah ketika dia pulang kerja selepas Ashar. Mungkin aku tak bisa bersamanya di hari libur. Dia butuh diurus. Tapi tak mengekangku di rumah. Mungkin, akupun lantas sudah terlalu lelah untuk bercinta dengannya ketika sampai di tempat tidur.
“Jika tak ada yang membuatku harus menunggu,………” Awang Pandu terhenti.
“Berlalulah….” Itu kuucapkan sangat perlahan.
Awang Pandu menatapku. Aku menunduk. Menangis. Untuk terakhir kali, Daeng-ku menggenggam jemariku. Lama sekali.
Setelah itu tak pernah ada lagi mimpi-mimpi tentang pernikahan kami. Rekening bank bersama atas namaku- yang sebetulnya berisi uangku dan uangnya, yang kami sisihkan dari penghasilan kami masing-masing setiap bulan untuk persiapan mencicil DP kredit rumah, menjadi saksi terakhir mimpi pernikahan.
Aku mentransfer kembali dana milik Awang Pandu ke rekeningnya. Meskipun dia tak pernah menyinggung sedikitpun tentang rekening bersama itu. Aku melakukannya untuk memberinya sebuah tanda kepastian. Bahwa dia tak terikat untuk menungguku. Bahwa sebaiknya dia segera mencari penggantiku. Mengharapkanku hanya akan seperti memelihara duri dalam hatinya.
Kalau saja aku memintanya menunggu. Dia akan menunggu. Rasanya ya. Tapi adilkah? Sungguhkah aku menginginkan penantian Awang Pandu-ku? Aku memilih pergi saja.
Aku ingin datang dan pergi