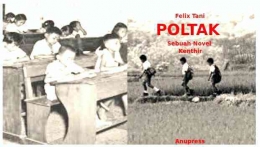Penemuan kalimat pertama. Itu bagian tersulit dalam menulis puisi. Setelah itu kalimat berikut datang sendiri.
Setidaknya begitulah pengalaman Poltak.
Setelah bait pertama diseru di bukit Holbung, bait-bait selanjutnya menjadi lebih mudah bagi Poltak.
Pada hari kesepuluh dari tenggat empat belas hari, Poltak menyerahkan konsep puisinya kepada Guru Arsenius. Dia minta saran untuk perbaikan.
Sebisanya Guru Arsenius memberi saran terkait pilihan kata, struktur kalimat, dan susunan bait-bait puisi. Sebisanya. Karena Guru Arsenius hanya seorang guru. Bukan pujangga.
"Kau bisa, kan, Poltak," sanjung Berta setelah Poltak menyerahkan naskah puisinya kepada Guru Arsenius, tepat di hari keempatbelas.
"Berkat doamulah itu, pariban," balas Poltak sambil tersenyum. Tatapan mata teduh, tak lagi tajam seperti hari-hari kemarin.
"Oi, lagak kalilah kalian namarpariban itu!" Jonder meledek.
"Jangan angek pula kau, Jonder. Tak baik itu." Guru Arsenius mengingatkan sambil tertawa kecil.
"Poltak! Apa isi puisimu itu. Kasih tahulah," tanya Alogo.
"Bah, rahasialah itu. Nanti tujuhbelas Agustus kalian tontonlah aku membacanya di lapangan Pagoda Parapat." Jawaban yang membuat seisi kelas jadi penasaran.
Jumat 17 Agustus 1973. Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-28 Kemerdekaan Indonesia di Lapangan Pagoda, Parapat.
Pola kegiatan berulang. Dimulai dengan upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dilanjutkan dengan kegiatan lomba-lomba Agustusan. Diakhiri dengan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah dan piagam.
SDN Hutabolon belum terkalahan pada lomba lari 100 meter putra. Binsar belum punya saingan.
Pada lomba lari 100 meter putri ada kemajuan. Tiur berhasil menyabet juara dua. Tahun lalu juara tiga.
Turun prestasi terjadi pada lomba tarik-tambang. Hanya mampu merebut posisi juara dua. Poltak sudah menduganya. Tanpa kehadiran Polmer, yang sudah berpulang, tim tarik tambang SD Hutabolon tak sekuat tahun lalu.
Tapi ada yang baru tahun 1973 ini. Lomba menulis dan membaca puisi perjuangan kemerdekaan.
Dilaksanakan di Pagoda, lomba ini menyedot perhatian murid-murid dan guru-guru SD sekecamatan Parapat.
Ada delapan orang peserta. Masing-masing mewakili SD Hutabolon, SD Hutagurgur, SD Sigirsang, SD Siganding SD Paropatsuhi, SD Tarabunga, SD Pardomuan, dan SD Pardolok. Setiap peserta wajib membacakan puisi karangan sendiri di hadapan dewan juri.
Dewan juri terdiri dari tiga orang. Ketuanya Frater Ambrosius, penyair dari Seminari Tinggi Parapat. Anggotanya Pak Rapolo, Penilik Sekolah Kecamatan Parapat dan Pak Nahum, seorang guru Bahasa Indonesia di SMP Parapat.
Urutan tampil peserta ditetapkan melalui undian. Poltak, wakil SD Hutabolon, mendapat nomor terakhir.
"Bah, masih lama giliranmu, Poltak," keluh Alogo.
"Baguslah itu, Alogo. Aku jadi bisa belajar dari tujuh peserta," kata Poltak sambil tertawa.
"Bah, betul juga kau, Poltak," puji Guru Arsenius. Dia takjub Poltak punya pikiran seperti itu.
"Peserta nomor delapan. Poltak Parulian dari Sekolah Dasar Negeri Hutabolon!" Terdengar pengumuman dari panitia.
Poltak melangkah tegap ke lantai pagoda. Diiring tepuk tangan dan tempik-sorak murid-murid dan guru-guru SD Hutabolon.
Di Pagoda, sosok Poltak tampak gagah dengan sortali, destar ulos di kepala, dan ulos ragidup tersampir di bahu kanan.
Dia berdiri tegak menghadap selatan. Mengadap dewan juri, Danau Toba, dan Bakkara sebagai kiblat.
"Apa judul puisimu, Nak?" tanya Frater Ambrosius sebagai formalitas.
"Sisingamangaraja Keduabelas," jawab Poltak tegas.
"Baiklah. Silahkan baca puisimu, Nak."
"Nauli."
Poltak berkonsentrasi. Memegang lembaran puisi di tangan kiri. Memejamkan mata sejenak.
Lalu terdengarlah suara bergetar, dengan tempo cepat-lambat, intonasi tinggi-rendah, diwarnai ekspresi marah, sedih, dan kagum silih-berganti.
"Ketika peluru bedil Belanda si penjajah. Menerjang Lembah Bakkara. Jantung Tano Batak. Kau tegak menghadang. Gagah melawan!
Di bawah langit duka. Darah merah mengalir di Aek Silang. Darah putih mengalir di Aek Simangira. Bertemu jadi merah-putih.
Itu darah rakyatmu. Tumpah demi Tano Batak.
Silindung takluk. Humbang takluk. Samosir takluk. Uluan takluk. Toba pun takluk. Bakkara jadi abu. Tapi kau menolak tunduk.
Dari lebat hutan Tano Batak. Kau tetap melawan. Diiring putra-putrimu. Patuan Anggi, Patuan Nagari, dan Boru Lopian.
Kau tak sudi tunduk. Hingga tetes darah terakhir.
Di saat dukamu. Pilu memeluk jasad putrimu Boru Lopian. Di tepi Aek Sibulbulon. Di sisi barat Tano Batak. Sebutir peluru bedil marsose melesat. Keji menembus kepalamu.
"Ahu Sisingamangaraja!" teriakmu. Kau tikam langit dengan pedang Gaja Dompak. Sebelum hembuskan nafas terakhir. Atas kehendak Mulajadi Nabolon. Demi daulat Tano Batak
Kau Patuan Bosar Ompu Pulo Batu. Gelar Raja Sisingamangaraja XII. Raja Batak terakhir.
Kau Pahlawan Bangsa!"
Poltak meneriakkan baris terakhir puisinya seraya menunjuk ke arah selatan, ke kiblat Bakkara.
Setelah itu, dia membungkuk menghormat dewan juri. Diiringi tepuk-tangan dan tempik-sorak kekaguman.
Tapi reaksi juri terbelah. Dua orang, Frater Ambrosius dan Pak Nahum, berdiri tepuk tangan. Seorang lagi, Pak Rapolo, tetap duduk sambil mencibir.
Alamat bakal ada masalah. Dan memang begitulah.
"Ini karya plagiat. Mustahil anak kelas enam esde bisa bikin puisi sebagus ini," kata Pak Rapolo saat rapat juri untuk penentuan juara.
"Poltak tak boleh jadi juara," desisnya dalam hati dengan sorot mata ular.
Pak Rapolo menyimpan dendam kesumat pada Poltak. Tahun lalu dia dipermalukan anak itu di kelas lima SD Hutabolon. Poltak bisa menjawab semua pertanyaannya. Tapi dia tak bisa menjawab satu, hanya satu, pertanyaan Poltak: "Mengapa batang pohon karet di perkebunan condong ke arah utara?"
Sementara Fater Ambrosius dan Pak Nahum telah satu kata. Puisi Poltak sangat impresif, orisional, dan menggugah. Poltaklah juara pertama.
"Pak Rapolo, kalau puisi Poltak plagiat, lalu puisi siapa yang dia jiplak?" tanya Frater Ambrosius.
"Anu ... ah, Felix Tani," jawab Pak Rapolo. Nama Felix Tani muncul begitu saja di benaknya. Entah dari mana datangnya.
"Felix Tani? Siapa dia? Saya tidak pernah tahu ada penyair Felix Tani." Frater Ambrisius mengerinyitkan dahi. Dia minta penjelasan dari Pak Rapolo.
"Saya juga tak pernah tahu ada penyair Felix Tani. Orang Spanyol?" Pak Nahum juga minta penegasan.
Pak Rapolo gelagapan. Dia sendiri tak pernah tahu siapa Felix Tani. Dia tadi bicara sembarang.
"Begini saja. Kita tanyai Poltak. Bagaimana cara dia bikin puisi itu." Pak Rapolo memberi usul, bukannya menjawab pertanyaan.
"Baik, kalau begitu," Frater Ambrosius setuju.
Poltak segera dipanggil untuk menghadap dewan juri.
"Nak, puisimu bagus sekali. Kau membaca puisi siapa saja waktu menyusunnya?" tanya Frater Ambrosius sambil tersenyum.
"Matilah kau, Poltak. Plagiator kau." Pak Rapolo menyumpahi, puas, dalam hati.
"Aku hanya membaca buku puisi Chairil Anwar. Kerikil Tajam dan Yang Terempas dan Yang Putus. Terutama puisi berjudul 'Aku'," jawab Poltak jujur.
"Ada lagi, Nak?" selidik Guru Nahum.
"Tidak ada. Tapi seorang Ulu Punguan Parmalim pernah bercerita padaku tentang perjuangan Sisingamangaraja Keduabelas melawan penjajah Belanda."
"Nah, kurasa dia menjiplak puisi Chairil Anwar," bisik Pak Rapolo pada Frater Ambrosius.
"Chairil Anwar menulis puisi 'Dipobegoro'. Bukan 'Sisingamangaraja Keduabelas'," sanggah Frater Ambrosius, menatap tajam Pak Rapolo. "Ada dendam apa di kepala orang ini," pikirnya.
"Sudah, Nak,"kata Frater Ambrosius, "kau boleh kembali ke tempatmu lagi. Mauliate, da?"
"Nauli." Poltak membungkuk hormat, lalu berbalik melangkah ke arah teman-temannya.
Dewan juri kembali melanjutkan rapat penentuan juara-juara Lomba Menulis dan Membaca Puisi. Tanpa perdebatan.
Matahari bersinar penuh di langit biru cerah. Riak-riak kecil di bentang permukaan Danau Toba kerlap-kerlip bagai hamparan padang permata. Berta tersenyum manis pada Poltak, sang juara di hatinya. (Bersambung)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI