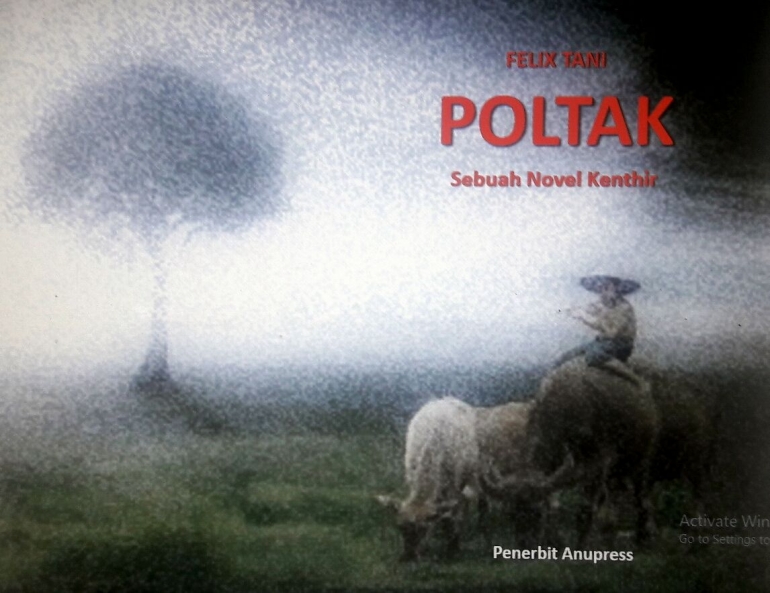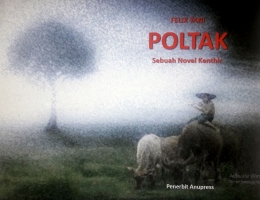Tak seorangpun tahu, Poltak diam-diam sudah menenggak tuak na tonggi tadi. Tanpa sadar tuak na tonggi itu hanya istilah. Sebenarnya tuak itu sudah diberi raru sehingga beralkohol. Poltak tidak sadar dirinya kini sedang mabuk tuak.
Dibimbing oleh kakeknya, akhirnya Poltak berhasil juga menyulangkan makanan dan meminumkan tuak kepada kakek-nenek buyutnya.
Semua hadirin lega, puas, dan bahagia. Semua beranggapan bahwa leluhur telah hadir di tengah mereka.
Acara manulangi dan makan bersama usai sudah. Sambungannya, sesuai janji, kakek-nenek buyut Poltak membagikan warisan untuk anak-anaknya. Sawah, rumah dan pusaka keluarga.
Keputusan orangtua tentang warisan itu mutlak. Tidak seorangpun boleh mendebatnya. Keadilannya tak boleh diragukan. Hula-hula dan boru menjadi saksinya.
Poltak tidak tertarik dengan urusan pembagian warisan itu. Dia ingin turun ke halaman, mencari udara segar. Di dalam rumah terasa sumpek baginya.
Dia lalu bangkit, terhuyung, melangkah ke arah jendela yang terbuka.
"Oi, Poltak! Mau kemana kau!" Kakek nomor empat, Ama Rotua, berteriak.
"Hah. Apa. Mau terbang ke luar," sahut Poltak datar, tanpa ekspresi, sambil mendekati bibir jendela. Memang dia merasa tubuhnya seakan terbang melayang.
"Oi, Parandum! Tangkap Si Poltak itu," Ama Rugun, kakek bungsu, berteriak, khawatir. Seketika suasana menjadi heboh. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H