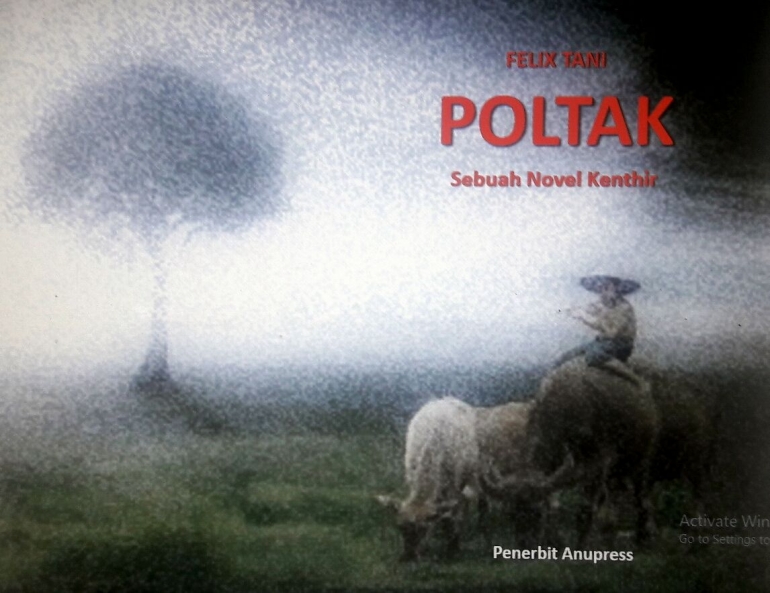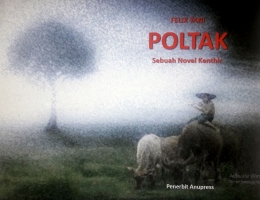Setelah mendapatkan sepotong kecil leher babi bakar dari Ama Rotua, ompungnya, Poltak beranjak pergi. Memang itu saja yang diinginkannya. Bukan kaki babi bakar, upah membersihkan jeroan babi. Itu hak anak-anak kampung Hutabolon.
Di dapur, para perempuan sedang sibuk menyiapkan nasi, air minum, dan peralatan makan.
"Itu apa, namboru?" Poltak mengamati Riama yang menuang cairan putih susu dari jerigen kecil ke dalam ceret aluminium.
"Tuak na tonggi. Untuk manulangi nanti," jawab Riama, singkat.
"Tuak na tonggi?" Poltak membathin. "Pasti nikmat itu. Manis," pikirnya.
Tuak na tonggi, tuak yang manis. Bahan baku gula aren itu aslinya memang manis. Dia menjadi beralkohol kalau kulit kayu raru direndam di dalamnya.
Poltak tak kuasa menahan hasrat. Ketika Riama beranjak sejenak, secepat kilat diacmengangkat ceret dan, "Glek glek glek," menenggak tuak langsung dari paruh ceret.
Aneh. Poltak tidak merasakan manis di lidahnya. Sebaliknya justru agak pahit. Tapi segar.
Ketika Riama kembali, Poltak tak bertanya soal rasa pahit tuak na tonggi itu. Takut ketahuan congok mencuri tuak. Bisa kena marah. Soalnya, itu tuak khusus untuk kakek-nenek buyutnya.
"Oi, Poltak. Ke sini kau. Kita mau manulangi sekarang," bapak Si Poltak memanggil dari ruang tengah.
Poltak bangkit melangkah. Dia merasa semakin aneh. Badannya terasakan enteng. Seakan bisa terbang. Tapi langkahnya limbung.