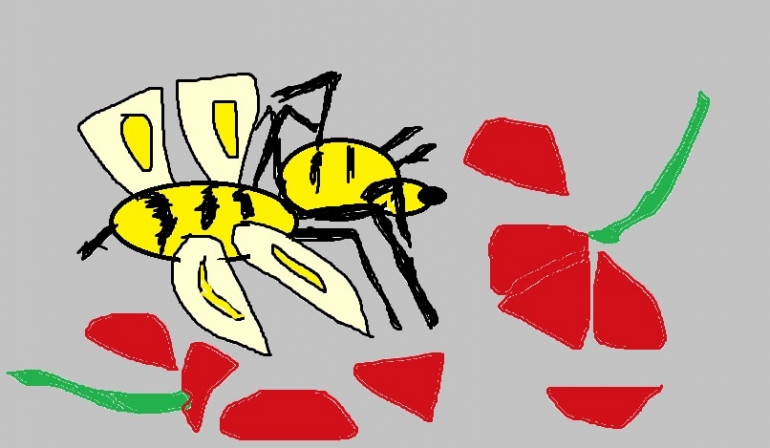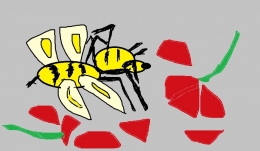Alif mengikuti Pak Nanang ke sebuah kamar di bagian belakang. Mereka melewati taman belakang. Belasan kereta bayi dan berapa pengasuh. Alif menitikan air mata, tangisan tertawa dan celoteh bercampur menjadi satu.
“Mereka tadinya seperti bayi itu?”
“Betul anakku, betul anakku. Kami sudah menampung lebih dari tiga puluh bayi sejak yayasan ini berdiri. Ini baru di Bandung, dari Jakarta sudah merengek minta mengirim ada 20-an lagi, bayi-bayi yang dibuang, dari Tangerang, Bogor, baru Jawa Barat anakku sudah ratusan dalam lima tahun,”
“ Apa tempat ini bisa menampung, kalau jumlahnya semakin banyak?”
Pak Nanang tidak menjawab. “Entahlah.”
Alif basah matanya. Pelan-pelan ia memasuki sebuah kamar. “Kok saya jadi cengeng? Anak laki menjadi cengeng?”
“Itu tandanya kau punya hati,”
“Ada orangtua yang ingin punya anak tetapi tidak diberi. Ini dikasih kok dibuang? ”Alif bertanya dengan lugu.
Mereka terus berjalan.
“Seandainya ada satu negeri yang menerima anak-anak seperti ini dan tidak ada orang di negeri itu yang memandang seorang bayi yang dilahirkan patut disesali. Karena itu dosa orangtua mereka dan bukan dosa bayi.”
Nanang Sumarna terdiam. Dia merasa kalimat terakhir Alif terlontar dari hati. “Suatu negeri yang belum pernah ada tapi akan ada.”