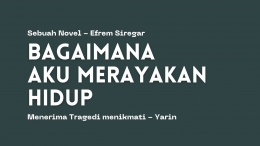Jakarta, 27 Februari 2023
Sepanjang hidup, manusia bertanya pada diri mereka sendiri satu pertanyaan abadi: bagaimana cara menikmati hidup? Bila perut menyusut lapar, orang akan menelan makanan. Saat mulut kering merintih kehausan, air akan menyembuhkannya.
Namun, hidup memiliki cahaya menyala dan lentera penerang di dalam kegelapan daripada sekadar rutinitas menyelamatkan tubuh lewat asupan makanan dan minuman.
Di sisi lain, tampaknya tidak begitu penting, selalu bersembunyi, tetapi di saat itu juga kehidupan kembali hadir dalam imajinas masa lalu ketika orang-orang merindukan sesuatu yang lebih indah.
Pertanyaan tentang cara menikmati hidup memiliki kekuatan yang ajaib, yang mampu merangsang pikiran untuk mencari dan memperhatikan apa-apa di sekitar tanpa batas.
Dalam kisah yang aku tuliskan ini, setidaknya akan ada sebagian hal yang akan ditangkap.
Cara paling sederhana menjalani kehidupan adalah dengan berimajinasi. Kita berada dalam realitas yang tidak dapat diganggu-gugat sebagai ketetapan, tetapi di bagian lain, kita menggunakan akal untuk berimajinasi demi menjauh dari realita yang buruk.
Sekarang usiaku menginjak 30 tahun. Sebuah angka yang membuat aku mengetuk lembar demi lembar perkara hidup.
Satu kepastian bahwa aku meninggalkan masa muda selamanya. Dalam arti, aku kehilangan alasan agar orang lain mau memaklumi segala tindakanku.
Aku memasuki usia dewasa dan harus bertanggung jawab atas segala perbuatan, menjalani semua dengan kehati-hatian bahwa aturan sosial dan hukum harus dipatuhi.
Meski demikian dalam beberapa konteks, persepsi masa muda dan masa tua berbeda dari pandangan umum. Seorang walikota berusia 40 tahun dapat dianggap sebagai pemimpin muda.
Di sisi lain, Anda bisa menyaksikan bagaimana organisasi pemuda ternyata menghimpun orang-orang berusia 50 tahun ke atas. Orang lain mungkin menerima kenyataan tersebut, tetapi izinkan aku untuk menertawakannya.
Menjadi dewasa adalah masa-masa yang menghadirkan cakrawala dalam keadaan yang sulit diukur.
Apakah kebahagiaan dan sukacita itu datang atau harus diraih? Apakah aku harus menolak kutukan dan segala ancamannya, atau justru menerimanya sebagai bagian hidupku?
Aku memahami bahwa segalanya menjadi buruk dan suram. Tinggal di dalam kemiskinan, bahkan aku tidak memiliki tabungan di dalam rekening bank. Ini adalah bagian yang harus aku terima, menikmati kehidupanku selagi aku memang bisa.
Konsekuensi ini kemudian membawa aku sering melamunkan hal-hal indah dan menyenangkan.
Dan seperti kebanyakan orang, aku memikirkan masa muda, di mana aku bebas tertawa atas nestapa orang lain, mengutuk dan menghujat orang lain selagi aku memegang apa yang kuyakini benar.
Orang dewasa dan orang muda adalah dua kata sifat yang berbeda. Bukan hanya mencakup referensi usia, tetapi bagaimana mentalitas orang melihat dunia secara berbeda.
Kejadian ini pernah aku alami, tepatnya 11 tahun silam. Saat itu, aku merasa memulai kehidupan baru sebagai calon mahasiswa.
Ada rasa bangga. Setelah aku membicarakan rencana kepergianku kepada Linda, keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk berbicara kepada orangtuaku.
Bapak adalah orang pertama yang kuberitahu tentang diterimanya aku sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya.
Meski aku sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk memberikan ruang pembicaraan, tetapi Bapak seperti telah menunggu untuk langsung mengetahui pengumumannya dariku.
"Brawijaya? Di mana itu?" Bapak membuka pertanyaan.
"Di Malang, Pak," jawabku sambi mendorong pintu tertutup setibanya di rumah.
"Kok jauh kali, kenapa nggak ambil USU atau Unimed?"
"Cuma ini yang aku diterima. Mau di tempat lain, belum rejeki."
Semua terucap begitu saja di antara kami. Lagi-lagi, apa yang aku cemaskan ternyata berakhir dengan ketidakdugaan. Pembicaraan berlangsung teramat cair, seperti obrolan sehari-hari tanpa memiliki tujuan.
Akan tetapi, dari sini, perlahan-lahan Bapak menunjukan gelagat berubah dari keyakinan luar biasa menjadi sebuah keraguan. Aku bisa melihat sesuatu yang menempatkan penolakan pada rencana yang sudah seharusnya terjadi.
"Baguslah, berarti semakin mantap jalanmu ke depan. Di jurusan apa?"
"Sastra Prancis."
"Ah, kok lain pilihanmu. Mau jadi apa nanti di Sastra Prancis, kau"
"Pasti ada aja jalan, Pak."
Bapak menggelengkan kepalanya. Tidak ada jawaban lagi yang kunjung terdengar.
Aku meninggalkan Bapak sendirian di ruang tamu. Aku tahu bahwa dia tidak puas dengan apa yang baru saja kukatakan, tetapi memang tidak ada gunanya membahasnya lebih lanjut.
Masa mudaku adalah masa yang penuh dengan kepercayaan diri, keegoisan, dan sikap memberontak.
Kehidupan di Medan sangat membosankan. Aku dan sebagian orang menghabiskan pikiran untuk dapat selamat dari gangguan geng motor yang kejam, premanisme dan segala bentuk kekerasan yang selalu dipandang sebagai citra kota ini.
Tapi aku tahu watak-watak keras ini bukanlah ciri khas yang membudaya. Tergantung bagaimana orang mempersepsikan kekerasan.
Di satu sisi, menjalani hidup berarti menyadari pentingnya kerja keras yang akan membantu orang sukses dan bahagia.
Sebenarnya, aku tidak mau mengumbar kalimat motivasi yang menurutku sendiri adalah bentuk kebohongan yang menghibur.
Kalimat semacam itu menyembunyikan fakta bahwa sikap keras cenderung muncul sebagai makna negatif di masyarakat karena timbulnya ekspresi ketidakpastian, keputusasaan, dan kecemasan.
Dan aku nyaris putus asa memikirkan jeratan kemiskinan yang sangat siap memeluk orang-orang.
Orang mungkin menyalahkanku sebab mendasarkan nilai dari titik negatif. Tetapi, realita sosial yang sangat anggun memperlihatkannya di hadapan kita. Kemiskinan menghalangi segala kemajuan dan cita-cita, tetapi kita sanggup mencintainya.
Bapak mengajarkan kami sejak belia supaya mau mengorbankan kesenangan. Ada sesuatu yang lebih besar di depan kami, yang harus kami perjuangkan hari ini.
Tentu saja, pengorbanan yang diajarkan Bapak merupakan sebuah kepedulian. Sekalipun hasil akhirnya tetap sebuah ketidakpastian, tetapi niat baik harus terus berkumandang.
Aku pergi tidur dengan pikiran-pikiran ini, menghabiskan sisa sore itu dengan mengunci diri di kamar. Baunya sangat lembab dan membuatku harus mencium kotoran ayam yang mengepung di mana-mana.
Di sekitar kamarku, sinar matahari enggan menembus kaca jendela karena tertutup awan pekat.
Hujan akan turun, di saat Bapak masih memikirkan tentang rencana perkuliahanku. Malam ini, dia ingin membicarakannya lagi dengan pesan yang sangat serius.
"Ari, Bapak sebenarnya nggak keberatan kalau kau harus merantau. Tapi, coba pikirkan lebih matang, apa jurusanmu laku di dunia kerja?" kata Bapak.
"Soal kerja, nggak mungkin lah kampus berani buka jurusan kalau memang lulusannya nganggur."
"Benar yang kau bilang. Tapi, cobalah dulu ambil di fakultas hukum atau ekonomi."
"Aku udah lolos jalur undangan. Ini kan jawabannya pasti. Kalau harus ujian masuk lagi... Aku mau yang pasti-pasti aja. Tamat sekolah, kuliah."
"Kalau itu jawabanmu, berarti terserah samamu lah. Nggak laku samaku keras kepala," ucap Bapak dengan nada ketus.
Aku mengabaikan kemarahan Bapak yang meledak redam untuk menunjukkan ekspresi kekecewaannya secara tidak langsung.
Dia mencoba menelan kemarahannya karena harapannya bahwa aku memilih di fakultas hukum atau ekonomi tidak akan tercapai.
Pikiranku sudah bulat. Seperti yang telah kusebutkan sebelumnya, aku sangat percaya diri, bahkan, lebih tinggi dari keputusan yang ditimbang matang. Ketika aku mengatakan pergi merantau, maka pada detik aku mengatakannya, aku harus melaksanakannya segera mungkin dengan bertekad kuat.
"Aku nggak akan bayar kuliahmu, kalau kau mau melanjutkan, silakan. Tapi seperserpun nggak akan keluar dari Bapak."
Aku berdiri tegak di bawah bunyi kegelapan yang hening. Ucapan Bapak memberikankuu dorong kuat agar pergi menjauh.
Kekecewaan yang bertakar kecil, bibirku tertahan rapat menahan amarah. Aku tidak lagi memikirkan apapun selain aku harus meninggalkan kota ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H