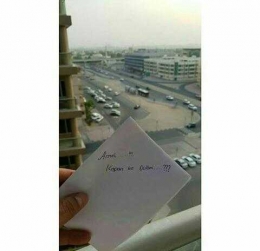Dulu aku menyusu di payudara ibumu. Begitu kehendak takdir. Kita tumbuh dari air susu yang sama. Padahal, aku tidak pernah memohon kepada Tuhan agar ibumu menjadi ibu susuku. Aku juga tidak pernah berdoa agar kita menjadi saudara sesusuan. Kita menangis dan tertawa bersama. Kita bahagia dan terluka bersama.
Entah bagaimana mulanya, diam-diam cinta menyusup ke dalam dada kita. Kala itu, usia kita menjelang remaja. Tiga belas tahun. Lehermu sudah berjakun, dadaku mulai tumbuh susu.
Tiap berjauhan denganmu, serasa ada yang kurang dalam diriku. Tiap kauabaikan pesan pendekku, dadaku serasa dihantam palu. Tiap kuprotes kepadamu, kamu malah mencebik. Meledek. Seakan-akan perasaanku bukan sesuatu yang penting bagimu.
Aku masih ingat hari ketika pertama kali kutegur kamu karena seharian aku tidak menemukanmu.
"Kenapa kaumatikan ponselmu?"
Kamu cengengesan. "Lagi ujian!"
"Bisa kaubalas saat istirahat, kan?"
"Takut konsentrasiku buyar."
"Jadi selama ini aku hanya mengganggumu?"
Kamu menggeleng. "Aku suka bibirmu kalau sedang merengut."
"Jangan mengalihkan pembicaraan!"
"Aku suka suaramu kalau sedang merajuk."
"Kampret!" Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Kamu tidak kangen?"
"Kangen, kok."
"Kamu tidak sayang kepadaku?"
Beberapa jenak kamu habiskan untuk menatap mataku. Tidak menjawab pertanyaanku, tetapi terus menatapku. Aku ingin mendesakmu dengan sebuah pertanyaan lagi, namun aku tahu kamu paling tidak suka didesak-desak. Maka kubiarkan hatiku didesak-desak oleh rasa kesal. Sungguh-sungguh kesal karena tidak mendengar pernyataan sayang darimu.
Dulu aku menyusu di payudara ibumu. Begitu kuasa takdir. Takdir pula yang sekarang menyeret kita ke dalam satu bilik cinta. Menyekap kita dalam bilik itu sehingga kita tidak melihat ada cinta selain di pelukan kita. Lalu sepat masa depan memukul-mukul jantung kita.
Menjelang usia lima belas tahun, kamu belum mengatakan apa pun tentang perasaanmu kepadaku. Aku juga tidak ingin menyatakan perasaanku kepadamu. Kamu mulai berani mengecup keningku setiap aku pamit untuk pulang ke rumahku, aku mulai berani menumbuhkan harapan di dadaku bahwa kamu juga menyukaiku.
Bukan suka, melainkan cinta.
Aku masih ingat adegan saat pertama kali kaukecup keningku. Saat itu, kita hanya berdua di rumahmu. Sore yang hujan dan ibumu belum pulang dari kantornya. Kamu baru saja bercerita tentang seorang gadis di sekolahmu yang jatuh cinta kepadamu.
Tiba-tiba aku merasa ditikam kenyataan dan berasa sia-sia berada di sini, di rumahmu, di sisimu, dan kukira aku telah membuang-buang waktuku demi mendengarkan cerita menyedihkan dari bibirmu. Aku kesal. Sakit hati. Aku ingin mengumpat, memaki, menjerit, melolong, atau sekadar melarang kamu berdekatan dengan gadis yang mencintaimu itu, tetapi lidahku kelu.
"Aku tidak mencintainya," katamu sambil memegang daguku.
Aku mendongak dan menatap matamu. "Apa peduliku!"
"Benar, aku tidak bohong."
"Aku tahu."
"Kamu cemburu."
Aku mendelik. "Sok tahu!"
Kamu tertawa. Lepas sekali. Seakan-akan tanpa beban. Entah mengapa aku suka derai tawamu. Aku lega. Lega sekali. Rambut ikalmu yang selalu kuledek dan kuhina mendadak sangat indah di mataku. Entah mengapa aku ingin sekali merebahkan kepalaku ke dada bidangmu. Aku senang. Senang sekali. Hidung mancungmu yang selalu kuejek dan kucerca seketika amat sedap kupandang.
"Aku jatuh cinta."
Tiga kata itu membuatku terperangah. "Kepada cewek di sekolahmu itu?"
Kamu hanya menggeleng.
"Ada cewek lain?"
Kamu mengangguk.
"Siapa?"
Kamu menatapku. Lembut sekali. Bibirmu mendarat di keningku. "Kamu!"
Kita akhirnya mengaku saling cinta, tetapi perasaan cinta itu kita sembunyikan rapat-rapat. Tidak seorang pun kita biarkan membaca dan mengetahui perasaan kita. Baik ibumu ataupun ibuku. Baik ayahmu ataupun ayahku.
Tetap begitu hingga usia kita memasuki tahun kedua puluh. Tubuhmu makin berisi, tubuhku makin semampai. Rambutmu tetap ikal, rambutku mayang terurai. Matamu setajam mata elang jantan, mataku setenang mata singa betina.
Hingga tiba satu hari ketika kamu berhenti mengecup keningku. Kulihat kamu berusaha menahan diri untuk tidak menggenggam jemariku. Kamu juga mulai menarik diri acapkali kupeluk dari belakang. Kamu tidak berkata apa-apa, tetapi matamu terlalu banyak bicara.
"Ada apa?"
Kamu hanya menggeleng.
"Kamu menderita karena aku?"
Kamu menggeleng lagi.
"Kamu sudah tidak mencintaiku?"
Kamu menatapku. Lembut sekali. Tetapi bibirmu tidak mendarat di keningku. Matamu digenangi air. Lalu kamu menoleh seakan-akan menyembunyikan tangis dariku. Padahal aku tahu kamu sedang menyimpan sesuatu. Aku tahu kamu sedang merahasiakan sesuatu.
"Katakan sekarang," cecarku tanpa ampun.
Kamu menghela napas. "Karena dalam darah kita mengalir susu yang sama maka haram bagi kita hidup bersama dalam satu rasa. Kita cuma titik embun di daun yang bergulir jatuh ke tanah tanpa jejak basah."
"Maksudmu?"
"Cinta kita cinta terlarang!"
"Mestinya agama tidak memenjara dua hati yang saling mencinta."
"Tabu bagi kita mengisap tebu pelaminan."
Dulu aku menyusu di payudara ibumu. Begitu garis takdir. Pada mata ibumu kamu larikan perih nasib, pada matamu aku menyembunyikan pedih cinta. Ada duka membayang di matamu, ada luka mengembang di mataku. Luka yang mencucup air mata di pipiku, duka yang mencecap getir di sudut bibirmu.
Kemudian tibalah hari yang paling ingin kulupakan sekaligus paling sulit kulakukan. Kamu mengajakku duduk di beranda rumahmu. Kamu membisu selama beberapa menit, sedangkan aku menunggu saja. Kamu ingin aku tetap di sampingmu. Aku tahu itu dari caramu menatapku.
Suaramu sangat pelan ketika kamu bertanya. "Masih ingat Dubai?"
"Kota yang ingin kita datangi bersama."
"Aku akan ke sana."
"Kamu?"
Kamu hanya mengangguk.
"Sendirian?"
Kamu mengangguk lagi.
"Tanpa aku?"
Kamu menatapku. Lembut sekali. Tiba-tiba bibirmu mendarat di keningku. Tidak ada yang bisa kulakukan selain memejam. Sensasi dingin merayap dari pori-pori keningku ke sekujur tubuhku. Ini bukan kecupanmu yang kukenal. Ini semacam kecupan penghabisan. Ini sejenis kecupan yang tidak diinginkan.
Dengan mata basah aku bertanya, "Kamu mau ke Dubai?"
Kamu hanya mengangguk.
"Ke Burj Khalifa?"
Kamu mengangguk lagi.
"Mengunjungi bangunan yang kita sempat bayangkan akan menyeruput teh di lantai seratus enam puluh atau berdoa pada ketinggian enam ribu meter biar Tuhan lebih mendengar permintaan kita?"
"Aku harus pergi, Alzena Mehrin!"
Aku terpana. Tidak pernah kausebut namaku selengkap itu kecuali kamu sedang marah atau terluka. "Kamu tidak boleh ke mana-mana, Denish Farshad!"
"Aku tidak bisa membohongi diriku. Aku ingin menikahimu, tetapi itu mustahil terjadi."
"Kita bisa tetap bersama tanpa harus menikah."
Kamu menggeleng-geleng.
"Tidak ada alasan. Kamu tidak boleh pergi."

Dulu aku menyusu di payudara ibumu. Begitu alir takdir. Orang-orang menyangka kamu ke kota megapolitan, yang kerap kita bincangkan, demi meraup rezeki. Andai kamu tahu, ada yang berderak di dadaku.
Aku tidak tahu bagaimana bisa kamu memilih pergi, menjauh, menjauhiku, menjauh sejauh-jauhnya, hanya gara-gara ngilu sendu. Kamu sakiti hatimu sendiri. Kamu lukai hatiku. Mana mampu kita membendung banjir rindu. Pohon cinta di dada kita tumbuh rimbun dan rindang.
Aku sedih membayangkan kamu berangkat sendiri. Kupalingkan dukaku dari matamu sesaat sebelum pesawat membawamu pergi. Pukul dua dini hari kamu tergugu di pelukan ibumu, pukul dua dinihari aku tersedu di pelukanmu. Aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Aku tidak tahu kapan kamu kembali untuk mengecup keningku.
Kamu menatapku. Lembut sekali. Tetapi kamu tidak mengecup keningku. "Jaga kesehatan!"
Aku hanya mengangguk.
"Rajin-rajin jenguk Ibu, Dik."
Aku mengangguk lagi.
"Aku tidak akan menikah. Seumur hidupku. Sebab secara batin aku telah menikahimu."
Aku tercenung. Tidak ada yang mampu kulakukan selain tergugu di dadamu. Aku tahu kamu juga menangis. Aku tahu itu karena setitik air hangat dari matamu terjatuh ke lenganku. Tetapi aku tahu kamu tidak akan mengubah keputusan untuk pergi, menjauh, menjauh dariku, menjauh sejauh-jauhnya. Kamu kepala batu. Jika sudah A akan selalu A walau apa pun yang terjadi.
Hingga tumpah semua keluhku. "Aku mencoba untuk memahami alasan kepergianmu, tetapi aku tetap tidak mengerti mengapa kamu harus pergi. Aku merasa tersiksa karena mengerti bahwa sebenarnya kamu juga tersiksa. Aku ingin meminta agar kaubatalkan kepergianmu, tetapi kamu orang yang selalu merasa benar dan tidak ada yang perlu dipikirkan ulang. Aku ingin membencimu, tetapi cintaku sangat kuat menahan gelegak benci itu!"
"Kamu akan baik-baik saja," katamu sambil mengelus rambutku.
"Kalimat paling bodoh yang pernah kudengar darimu, Kak."
"Kamu perempuan tangguh, Dik!"
"Dengan cinta yang tanggung?"
Tetapi pertanyaanku menggantung di udara. Kamu berbalik, memunggungiku, dan tidak menoleh sedikit pun. Barangkali aku akan tetap di Bandara Soekarno-Hatta, berdiri mematung, berharap kamu berbalik dan tiba-tiba ke luar memanggilku, tetapi ibumu menggamit lenganku dan mengajakku pulang.
Dulu aku menyusu di payudara ibumu. Begitu getir takdir. Aku tahu betapa nyeri rasanya berusaha lari dari luka. Kamu pergi karena ingin menjauhi nestapa. Aku tahu itu. Dua tahun berlalu, kamu tetap hidup sendiri. Aku juga masih sendiri. Tiga tahun berlalu, kamu belum menikah. Aku juga belum menikah.
Kamu setia pada janji tidak akan menikah dengan perempuan mana pun, aku bertahan mencari lelaki yang sepenyayang dirimu. Pada tahun keempat, kabar darimu tinggal satu-satu. Kularikan deritaku pada pelukan banyak lelaki, tetapi kenangan tentangmu sangat lekat dalam ingatan. Pada tahun kelima, aku dan ibumu benar-benar kehilangan kamu.
Sekadar kamu tahu, aku berhenti mendatangi rumahmu sejak tahun keenam kepergianmu. Aku tidak ingin lukaku kambuh. Memasuki rumahmu seperti memasuki masa lalu. Lagi pula, aku tidak ingin luka Ibu kita kumat. Ibu selalu menangis setiap melihatku. Kepergianmu meninggalkan luka bagi dua perempuan yang kaucintai dan sangat mencintaimu.
Dulu aku menyusu di payudara ibumu. Begitu kuasa takdir. Lalu kamu menyusu di payudaraku. Begitu kuasa cinta.
Amel Widya
Catatan: Cerpen ini dikembangkan dari puisi Narasi Luka Hati (Kumpulan Puisi Beranda Berahi).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H