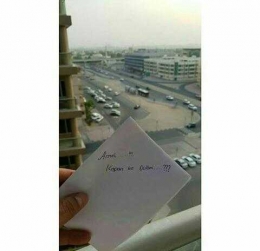Tetapi pertanyaanku menggantung di udara. Kamu berbalik, memunggungiku, dan tidak menoleh sedikit pun. Barangkali aku akan tetap di Bandara Soekarno-Hatta, berdiri mematung, berharap kamu berbalik dan tiba-tiba ke luar memanggilku, tetapi ibumu menggamit lenganku dan mengajakku pulang.
Dulu aku menyusu di payudara ibumu. Begitu getir takdir. Aku tahu betapa nyeri rasanya berusaha lari dari luka. Kamu pergi karena ingin menjauhi nestapa. Aku tahu itu. Dua tahun berlalu, kamu tetap hidup sendiri. Aku juga masih sendiri. Tiga tahun berlalu, kamu belum menikah. Aku juga belum menikah.
Kamu setia pada janji tidak akan menikah dengan perempuan mana pun, aku bertahan mencari lelaki yang sepenyayang dirimu. Pada tahun keempat, kabar darimu tinggal satu-satu. Kularikan deritaku pada pelukan banyak lelaki, tetapi kenangan tentangmu sangat lekat dalam ingatan. Pada tahun kelima, aku dan ibumu benar-benar kehilangan kamu.
Sekadar kamu tahu, aku berhenti mendatangi rumahmu sejak tahun keenam kepergianmu. Aku tidak ingin lukaku kambuh. Memasuki rumahmu seperti memasuki masa lalu. Lagi pula, aku tidak ingin luka Ibu kita kumat. Ibu selalu menangis setiap melihatku. Kepergianmu meninggalkan luka bagi dua perempuan yang kaucintai dan sangat mencintaimu.
Dulu aku menyusu di payudara ibumu. Begitu kuasa takdir. Lalu kamu menyusu di payudaraku. Begitu kuasa cinta.
Amel Widya
Catatan: Cerpen ini dikembangkan dari puisi Narasi Luka Hati (Kumpulan Puisi Beranda Berahi).
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H