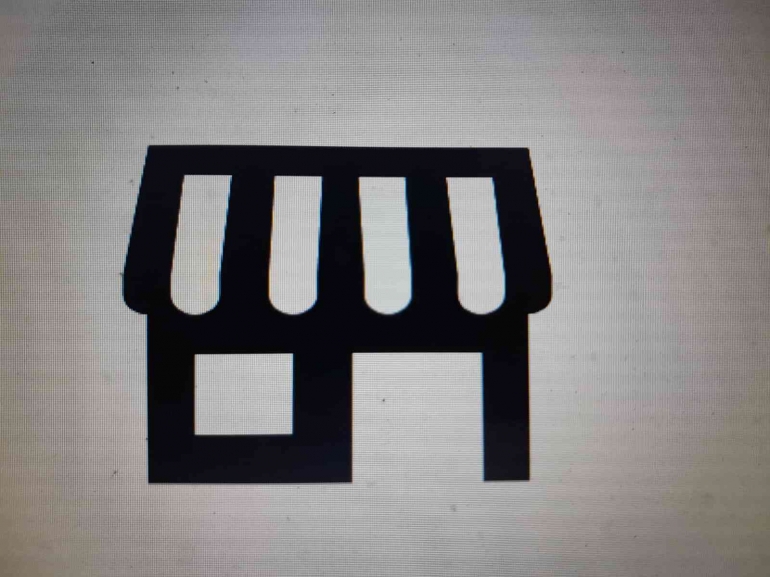Percobaan Jahat Menjelang Senja
Warung kecil yang kami kelola selalu ramai pada jam-jam tertentu. Sejak buka pukul sepuluh pagi, pembeli sudah berdatangan. Tepatnya, mampir atau singgah saat melakukan perjalanan. Mayoritas pembeli di warung kami adalah orang yang sedang lewat baik mengendarai motor maupun mobil.
Posisi warung yang strategis memudahkan pembeli untuk singgah sebentar. Mereka tidak perlu repot memutar jalan atau masuk gang untuk menuju warung kami. Mereka cukup menepikan kendaraannya, memarkir, singgah sebentar, beli minuman yang kami jual, lalu bisa segera pergi.
"Pakai nangka atau tidak, Pak?" tanyaku pada pembeli yang baru saja turun dari sepeda motor.
"Dua,ya, pakai nangka!" tutur pria itu sambil memandangku dengan sorot mata nakal.
Hal itu sudah biasa aku alami. Sebagai seorang wanita yang berjualan di warung pinggir jalan, aku harus jaga diri. Para pembeli, khususnya laki-laki, sering menggoda atau sekadar melotot ke arahku. Kerudung yang aku kenakan tidak membuat mereka malu atau sungkan menatap wajahku. Padahal aku sudah berusaha tampil apa adanya. Tidak memakai lipstik, tidak memakai bedak, atau gincu.
Jilbab yang aku kenakan juga jilbab yang 'syar'i', bukan sekadar kain penutup rambut. Cara bicaraku dalam melayani pembeli juga dengan suara yang standar, tidak dibuat-buat layaknya seorang pelayan di kafe-kafe kota besar yang pernah aku tonton di televisi. Intinya, aku tidak kemayu. Tidak genit. Tidak centil. Aku tampil lugu.
"Kalau sore tutup jam berapa?" tanya lelaki itu sambil melihat arloji di tangannya.
"Tidak tentu, Pak. Kalau dagangan sudah habis, ya, kami tutup. Kalau belum habis, kami buka di sini sampai pukul lima sore," jawabku lugas.
"O ... berarti nanti saya sekembali dari seberang bisa mampir ke sini lagi," tuturnya dengan wajah ceria.
"Semoga belum habis," tuturku pendek sambil menyerahkan dua porsi es dawet ayu kepada lelaki itu.
Selembar uang sepuluh ribuan ia serahkan. Aku menerima uang itu sambil mengucapkan terima kasih. Lelaki itu segera menuju sepeda motor yang ia parkir tak jauh dari warung kami.
Tempat berjualan kami tidak jauh dari pintu gerbang menuju pelabuhan kapal feri. Tak jauh dari pelabuhan itu, ada pelabuhan kapal kayu dan pelabuhan speedboat. Ibuku menyewa petak warung cukup strategis.
"Makan siang datang!" suara adikku terdengar.
Ia memarkir sepeda motor agak jauh sedikit dari warung. Itu dilakukan agar tidak menghalangi pembeli yang mampir ke warung kami. Sebuah rantang berisi makanan ia tenteng dengan langkah lebar-lebar. Terik sinar mentari membuatnya tidak mau berlama-lama di tempat terbuka.
"Lauknya apa, Lis?" tanyaku sambil melirik rantang tiga susun yang ditaruhnya di atas lincak, bangku panjang terbuat dari anyaman bambu.
Lincak itu berada di dalam. Ada gorden warna merah sebagai tirai. Dengan begitu, ada pemisah antara tempat berjualan dengan lincak. Ibuku sering duduk di sana pada hari-hari tertentu, pada saat ia ingin menemani kami berjualan.
Ketika kami masih kecil, ibulah yang berjualan dawet ayu di tempat itu. Seiring dengan perjalanan usia, ibu tidak kuat lagi berlama-lama berada di warung. Atas inisiatif Lisa, kami memutuskan untuk berjualan berdua. Tepatnya bergantian.
Pagi hari Lisa harus pergi ke sekolah hingga pukul dua siang. Aku yang jaga warung mulai pukul sepuluh pagi. Ibuku di rumah mempersiapkan dagangan dawet ayu tersebut. Kami hanya hidup bertiga sejak sembilan tahun yang lalu. Ayah kami meninggal karena kecelakaan. Tepatnya, ayah menjadi korban tabrak lari.
Waktu itu, senja hari. Ketika ayah sedang dalam perjalanan dari warung ke rumah, tiba-tiba ada sepeda motor yang ngebut menyalipnya. Kendaraan ayah tersenggol. Spontan ayah terjatuh. Sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi melindas tubuh ayah yang masih terkapar di tengah jalan.
Baik pengemudi motor maupun pengemudi truk tidak menghentikan kendaraannya. Seolah-olah mereka baru saja menabrak benda yang tidak berharga. Mengetahui kejadian itu, ibuku jatuh sakit sampai seminggu lamanya.
Untung aku dan Lisa segera menyadari. Kami tidak boleh terlalu lama bersedih. Kami harus mencari nafkah untuk menyambung hidup. Ibuku juga mulai bangkit. Dengan kemampuan meracik dawet ayu, kami terus berjualan.
Lisa termasuk gadis yang sabar. Ia tidak malu ikut membantu berjualan. Teman-teman di sekolahnya banyak yang menjadi pelanggan tetap di warung kami. Bahkan, guru-guru dan staf karyawan di sekolahnya sering mampir ke warung kami.
Setiap pulang sekolah, Lisa segera membawakan makan siang buatku. Ibu yang memasak di rumah. Dengan pembagian tugas seperti itu, kami selalu merasa saling membutuhkan.
===
"Kakak sedang melamun, ya?" ucap gadis itu.
Dengan cekatan, kulihat Lisa ambil cangkir besar untuk membuat dawet sendiri. Setiap hari selalu begitu.
"Haus betul, Kak, hari ini. Tadi pulang sekolah saya tidak sempat minum di rumah. Habis makan langsung disuruh Ibu ke sini. Takut kakakku yang cantik ini kelaparan," tutur Lisa sambil melirik ke arahku.
"Gombal," ucapku seraya membuka tutup rantang paling atas. Aroma lauk ikan goreng menyeruak. Hidungku benar-benar merasakan kenikmatan. Rasa lapar bertambah kuat. Dengan terburu-buru aku angkat rangtang pertama. Sayur berkuah terlihat menggoda pada rantang yang kedua. Selanjutnya, saya angkat rantang kedua untuk menemukan nasi yang berada pada rantang ketiga.
"Tadi ada lagi laki-laki mata keranjang," tuturku sambil menuangkan sayur pada rantang berisi nasi.
Lisa menatapku agak lama. Cangkir besar berisi es dawet yang dipegangnya ia letakkan di atas kursi. Sementara aku mulai memasukkan nasi ke dalam mulut setelah membaca doa dalam hati.
Adikku sangat marah bila ada laki-laki yang mau kurang ajar kepada diriku. Beberapa kali Lisa membentak-bentak lelaki yang berusaha mau berbuat jahil kepadaku. Awalnya hanya berbicara agak jorok, kemudian berusaha menyentuh tanganku.
Lisa langsung ambil sapu di sudut warung dan mengangkat tinggi-tinggi serta berseru.
"Awas! Jangan sentuh kakakku!" ucap adikku waktu itu.
Lelaki yang akan berbuat usil akhirnya mengurungkan niatnya. Apalagi Lisa berteriak dengan lantang. Para pejalan kaki atau pengendara banyak yang menoleh waktu itu. Lelaki itu pun pergi setelah melemparkan uang seharga minuman es dawet ayu satu porsi.
"Sudah, minum dulu dawetmu!" ucapku setelah mengunyah dan menelan suapan pertama.
Perlahan Lisa meraih cangkirnya. Ujung sedotan plastik segera ditempelkan di bibirnya. Perlahan ia sedot es dawet itu sambil memejamkan mata. Aku tahu betul, Lisa sangat menyukai dawet buatan Ibu. Meskipun setiap hari meminum dawet itu, Lisa tidak pernah merasa bosan.
"Tadi Ibu cerita, stok gula merah tinggal sedikit," tutur Lisa pendek setelah berhenti menyedot es dawet.
"Aku habiskan makanku dulu. Nanti aku yang belanja!"
Lisa mengangguk. Ia paling suka berada di warung melayani pembeli. Dengan gaya bicara yang cerdas, pembeli yang semula hanya ingin membeli satu porsi es dawet ayu, bisa berubah pikiran untuk membeli dua atau tiga porsi untuk dibawa pulang.
Sebelum berangkat belanja gula merah, aku lihat dulu keadaan cuaca. Langit terlihat mendung pekat. Awan hitam menggumpal di sebelah barat. Meskipun begitu udara terasa panas. Dalam hati aku berdoa, semoga masih ada pembeli yang datang.
Pada saat aku keluar dari warung kami, kulihat pedagang di kiri dan kanan kami mulai tutup. Mereka biasa begitu. Jika cuaca mau hujan, mereka segera menutup warungnya. Sebelah kiri adalah pedagang gado-gado. Sebelah kanan penjual sayur segar.
"Kakak tidak lama, khan, beli gula merahnya?" pertanyaan Lisa meluncur.
Aku tersenyum sambil berjalan menuju sepeda motor yang tadi diparkir Lisa. Aku menoleh sebentar ke warung, seolah ada sesuatu yang tertinggal. Kuraba tas tangan untuk memastikan uang untuk belanja sudah terbawa.
Belum sepuluh menit aku meninggalkan Lisa sendirian di warung, perasaanku tidak enak. Ada sesuatu yang entah apa, aku tidak paham. Aku belum sampai di kios tempat jual gula merah, sepeda motor aku hentikan. Ada bisikan lembut yang menyuruhku segera kembali ke warung.
Dengan gerakan reflek, sepeda motor aku jalankan lagi, langsung berbalik arah. Jalanan terlihat makin ramai. Menjelang senja biasa seperti itu. Kulihat antrean mobil untuk naik kapal feri agak panjang. Motor kuparkir agak jauh dari warung kami.
Betapa kagetnya aku. Ada dua lelaki bertato duduk di sebelah kiri dan kanan warungku. Masing-masing memegang HP di tangan. Namun, gerak-geriknya penuh kewaspadaan. Seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga. Angkringan es dawet sudah ditutup sembarangan dengan kain. Aku yakin bukan Lisa yang menutup angkringan seperti itu. Lisa sangat rapi kalau menutupi angkringan.
Aku tidak melihat Lisa berada di luar dekat angkringan. Pikiranku berkecamuk. Di mana Lisa? Mungkinkah Lisa sudah pulang? Atau ada temannya yang menjemput untuk mengerjakan PR? Tak sabar aku segera berjalan menuju warung. Dengan suara lantang, aku bertanya kepada dua lelaki bertato itu.
"Mana, Lisa, adikku?"
Kedatanganku mengagetkan kedua lelaki bertato itu. Mereka berdiri dan berusaha menangkap lenganku. Namun, aku segera menghindar sambil berteriak.
"Tolong ... tolong ... tolong!"
Beberapa orang yang sedang lewat dan para pengemudi mobil yang kendaraannya terparkir segera mendatangiku. Mereka pasti ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dari dalam warung, aku melihat gorden tersibak. Seorang lelaki lain keluar langsung loncat ke arah belakang.
Ketiga lelaki itu, semuanya dapat meloloskan diri dari kepungan massa. Aku segera berlari menuju lincak di dalam warung. Betapa kagetnya aku. Di atas lincak, mulut Lisa ditutup dengan lakban hitam. Kedua tangannya diikat di belakang.
Orang-orang yang ikut masuk segera memberikan pertolongan. Pelan-pelan lakban yang menutupi mulut Lisa dibuka. Tali yang mengikat kedua tangan Lisa juga dilepas. Beberapa orang yang berkerumun banyak yang bergumam, mengungkapkan rasa kasihan, mengumpat kepada para pelaku, dan komentar lain yang berseliweran di telingaku.
Lisa segera aku peluk erat-erat untuk menunjukkan perlindungan. Pakaiannya masih lengkap. Tidak ada bagian tubuhnya yang luka. Dengan sesenggukan Lisa meluapkan perasaan sedihnya. Aku pun ikut menangis.
Aparat polisi yang datang tak lama kemudian, menanyai orang-orang yang berkerumun. Mereka bercerita dengan versi masing-masing. Pak ketua RT yang sempat kulihat segera kupanggil. Aku beri tahu motor kami yang kuparkir. Kunci motor masih menggantung di sana. Aku minta segera diantarkan pulang.
"Baik, mbak. Ada mobil saya tak jauh dari sini. Biar motor mbak Lusi dibawakan pulang anak saya," tutur Pak RT dengan bijak.
Sebelum meninggalkan warung, Pak RT mengingatkan barang-barang apa saja yang akan dibawa pulang. Aku hanya menunjuk rantang dan laci tempat menyimpan uang. Dengan cekatan Pak RT mengambil rantang.
"Isi laci diambil sendiri, ya." ucap Pak RT.
Aku buka laci, uang hasil penjualan es dawet masih ada di sana. Lisa masih menggelayut di pundakku. Ketakutannya belum hilang. Air matanya masih mengalir. Orang-orang yang berkerumun masih menonton kami. Mereka sibuk bercerita.
Pak RT minta jalan untuk lewat. Aparat polisi yang tadi menanyai orang-orang diajak Pak RT ikut mobilnya. Senja makin kelam. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Rasa dukaku tak dapat kuungkapkan dengan kata-kata.
Penajam, 18 Maret 2018
(diedit 22 April 2024)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI