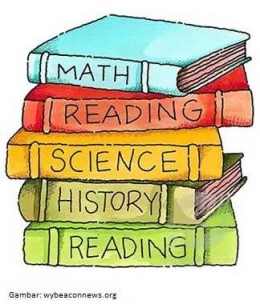***
Saat seleksi tahap 1 yang lalu, seleksi jalur non akademik, walau tahu bahwa si bungsu tidak punya peluang untuk bisa diterima melalui jalur non-akademik tersebut, aku dan suamiku jalan- jalan ke beberapa SMA di kota kami.
Putra kami itu bukan anak yang bisa daftar masuk melalui seleksi tahap 1 untuk jalur prestasi non-akademik, orang tuanya bukan guru, serta tidak termasuk anak berkebutuhan khusus.
Kalau mau lewat jalur surat miskin ya kok rasanya kami tidak miskin, juga rumah kami tidak mepet dekat sekolah.
Sementara, hal- hal tersebutlah yang bisa membuat anak didaftarkan melalui saringan tahap pertama tersbut.
Jadi ya sudahlah, dia akan mesti daftar lewat jalur yang masih memperhitungkan capaian akademik, yang terdiri dari dua komponen utama: jarak rumah ke sekolah, dan nilai ujian nasional.
Nah itu, walau sadar bahwa si bungsu hanya akan bisa mendafar di tahap kedua, saat pendaftaran tahap satu yang lalu, kami datang ke beberapa SMA di kota kami, untuk melihat- lihat situasi. Sebab walau ini anak bungsu, anak ketiga, kami tak punya pengalaman mendaftarkan anak dengan cara seperti ini. Dua kakaknya dulu, masuk SMA Negeri melalui testing.
Salah satu SMA yang kami datangi adalah SMA dimana kakak- kakaknya dulu bersekolah.
Dan di SMA itu, SMA Negeri yang konon paling top di kota kami, somehow kami menangkap aura kefrustrasian.
Saat kami mengobrol dengan guru- guru disana, kegemasan bahwa 'entah siapa dan seperti apa murid yang diterima di sekolah ini nanti' tertangkap jelas. Kalimatnya tentu tidak eksplisit seperti itu. Tapi dari gesture dan kalimat implisit, kekhawatiran dan kegemasan itu jelas tampak.
Bisa dibayangkan. SMA itu, SMA dimana biasanya hanya murid- murid dengan nilai rata- rata ujian nasional SMP di atas 90-lah yang akan diterima. Jadi profil muridnya selama ini sudah tampak jelas. Murid- murid disitu adalah anak- anak yang dikaruniai otak cerdas, dan/ atau rajin belajar.