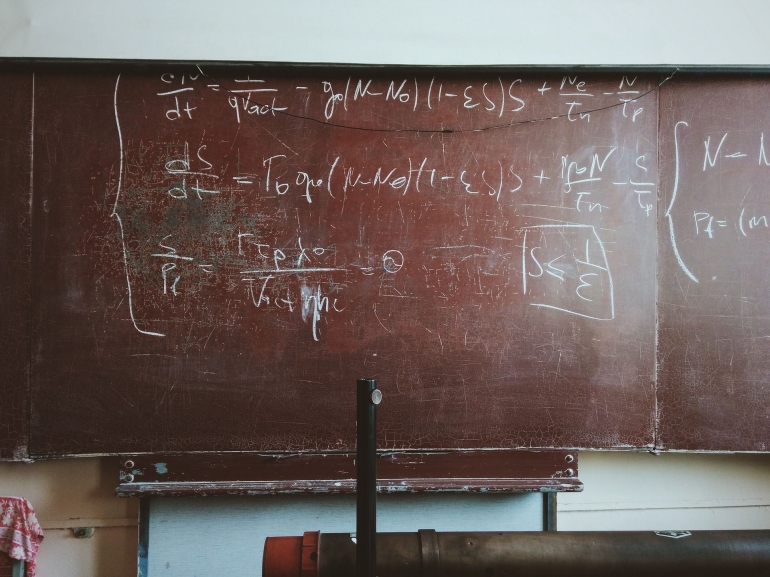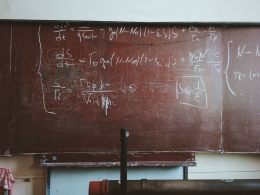Ada satu masalah fundamental yang sedari dulu saya benci tentang sekolah. Adalah jalannya pembelajaran di ruang kelas yang lebih mirip seperti penjara, bahkan lebih buruk.
Di kelas, saya mendapatkan tumpukan tugas dan tuntutan hafalan, belum lagi serangkaian ujian yang dipatok nilai minimumnya. Jika saya gagal dalam satu mata pelajaran, maka nilai keseluruhan saya akan terganggu hingga pada akhirnya menghambat kelulusan.
Dalam banyak kesempatan, saya tidak dibiarkan bertanya dan berpendapat. Bahkan ketika saya berhasil mengajukan pertanyaan, kadang-kadang, pertanyaan itu harus dijawab oleh saya sendiri dengan mantra, "Nah, itulah PR hari ini: mencari jawaban atas pertanyaan itu."
Dari waktu ke waktu, seiring meningkatnya jenjang saya, saya semakin bisa merasakan betapa mengungkungnya ruangan kelas bagi pemikiran kreatif. Ini bukan hanya soal pelajar, tapi juga guru.
Skenarionya begini: tidak semua pelajar kritis bisa terwadahi oleh guru, pun tidak semua guru kritis bisa dipahami oleh muridnya. Acapkali guru tidak membiarkan muridnya berpikir kritis karena dirundung oleh gengsi, takut kekalahan, atau tidak mampu mengimbangi.
Demikian pula pelajar yang biasanya punya kesenjangan pengetahuan yang teramat jauh dengan gurunya, sehingga guru mereka tidak bisa mengembangkan pengetahuannya di dalam kelas. Dengan sentuhan ironi: (semi) penjara itu kita sebut sebagai tempat belajar.
Lebih ironisnya, di dunia ini terdapat banyak penulis atau pemimpin besar yang mengembangkan ide-idenya di balik jeruji besi: Bapak Presiden Soekarno, Nelson Mandela, Adolf Hitler, Tan Malaka, Martin Luther King Jr., dan banyak lagi.
Ini bukan soal kedewasaan atau kecerdasan, apa yang lebih penting adalah soal kebebasan. Di penjara, orang masih punya kebebasan untuk berkreativitas. Sedangkan di ruang kelas, tempat yang seharusnya menjadi tanah inspirasi, kenyataannya tidak.
Masalah yang lebih besar muncul ke permukaan. Ketika ruang kelas terlalu mengungkung kebebasan dan kreativitas pelajar, mereka menjadi benci terhadap ilmu pengetahuan dan ujung-ujungnya sekolah hanya sebagai pembunuhan waktu yang sia-sia.
Jika satu generasi bangsa benci terhadap ilmu, maka di situlah titik kehancuran negara mulai terlihat.
Paradigma sekolah dari masa klasik hingga sekarang hampir tidak ada bedanya, bahwa sukses itu adalah mereka yang menjadi PNS, dokter, dan pilot. Pada akhirnya, bakat masing-masing individu mati karena tertekan oleh tuntutan tersebut.
Akibatnya terlihat jelas sekarang: generasi muda kita mencari pelarian dengan bermain media sosial. Mengapa? Karena di sana mereka bebas dan eksis, seakan-akan hanya di sanalah mereka diakui sebagai manusia yang independen.
Masalahnya menjadi semakin kompleks ketika realitas menghantam kita bahwa pembelajaran daring belum juga usai. Suasana kelas menjadi semakin pasif, seperti acara pidato satu arah di mana audiensi hanya mendengarkan dan memerhatikan, itu pun tidak menjamin mereka paham.
Jalannya pembelajaran semakin lesu. Apalagi ketika koneksi internet sedang gangguan, bawaannya sudah malas duluan untuk belajar. Oh, itu saya.
Tapi titik bencananya adalah, sekadar transfer ilmu saja tidaklah cukup. Ruang kelas adalah tempat yang sepatutnya menjadi sumber inspirasi. Kenyataannya ... coba kira-kira sendiri.
Mungkin kita hanya belum beradaptasi. Ya, mungkin. Tetapi kualitas pendidikan kita sudah tertinggal amat jauh dari kualitas pendidikan di negara-negara maju. Dan di sisi lain, pandemi seolah-olah menampar kita untuk tetap melaksanakan pembelajaran daring.
Itu tidak apa-apa. Harus tidak apa-apa. Jika pembelajaran daring terus menghambat kita untuk menggali ilmu pengetahuan, pendidikan kita akan semakin hancur seperti perekonomian sekarang ini.
Ruang kelas impian
Pembelajaran telah dimulai kembali. Ketika saya memerhatikan saudara perempuan saya yang sedang mengikuti pembelajaran daring, terbetik sebuah ide bahwa saya ingin memproyeksikan ruang kelas impian versi saya. Dan di sinilah saya sekarang.
Dengan begitu, saya menempatkan diri sebagai seorang idealis. Saya tidak akan (lagi) menggambarkan apa yang benar-benar terjadi di ruang kelas (realisme), melainkan saya akan menggambarkan apa yang "seharusnya" terjadi di ruang kelas (idealisme).
Parameter saya terbatas pada suasana pembelajaran di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Jadi, inilah proyeksi ruang kelas ideal yang saya pikir bisa menghidupkan pendidikan kita.
Pembelajaran berlangsung dua arah
Komunikasi dua arah adalah fondasi pembelajaran yang sedari dulu saya idam-idamkan. Mungkin terkesan sepele bahwa Anda mengira selama ini memang sudah terjadi komunikasi dua arah: guru mempersilakan murid untuk berbicara.
Kenyataannya, tidak sesederhana itu.
Apa yang terjadi selama ini di ruang kelas adalah komunikasi satu arah. Saya tahu betapa membingungkannya istilah "komunikasi satu arah" di mana secara definitif nyaris berseberangan. Tapi itulah yang terjadi.
Selama ini, penegakan posisi terlalu kaku. Maksud saya, guru harus selalu menjadi guru dan murid harus selalu menjadi murid. Pada akhirnya, gurulah yang kemudian banyak berbicara, sedangkan murid-muridnya terkesan pasif dan sekadar menganggukkan kepala.
Memang tidak keliru bahwa guru adalah guru, dan murid adalah murid. Tapi dalam beberapa kesempatan, guru bisa menjadi murid dan murid bisa menjadi guru.
Bahkan ketika seorang guru geografi mengajarkan mata pelajarannya, bukan berarti beliau tanpa celah.
Pada titik tertentu, muridlah yang ternyata mampu menutupi celah tersebut. Tapi jika keadaannya adalah komunikasi satu arah, guru akan menentang kritik muridnya dan bersiteguh bahwa dialah yang menjadi guru di kelas.
Tidak begitu!
Kalau keadaannya terus-menerus demikian, pelajar akan selamanya menjadi objek dari pembualan guru dan berakibat pada matinya kreativitas mereka. Ketika murid diperlakukan seperti robot, maka begitu pula dia akan berkembang.
Komunikasi dua arah menuntut murid dan guru bersifat aktif. Apalagi dalam pembelajaran daring di mana murid bisa leluasa mematikan mikrofon dan kamera, guru menjadi "kesepian" seperti berhadapan dengan robot-robot yang habis daya.
Syarat terbangunnya komunikasi dua arah adalah kesediaan guru dan murid untuk berpikiran terbuka. Tidak hanya dari guru ke murid, tapi juga dari murid ke guru.
Ketika salah satunya enggan demikian, maka pembelajaran akan selamanya pasif. Tidak akan ada buah inspirasi dan tidak akan ada efektivitas pembelajaran.
Barangkali tidaklah aneh bagi murid, karena memang sudah menjadi tugas mereka untuk menerima pembelajaran. Tetapi murid terbaik adalah murid yang bisa mengungguli gurunya secara terhormat. Ini perlu diperhatikan oleh pelajar agar tidak sekadar menerima saja.
Dan guru pun seyogyanya tidak repetitif, dalam artian tidak seperti batu asah. Apa yang salah dari batu asah? Ia terus menajamkan pisau-pisau, tetapi dirinya sendiri begitu tumpul.
Kasus di negeri kita, pengajar matematika akan merasa puas dengan pengetahuannya di bidang matematika dan berhenti menajamkan pengetahuan di ranah lain. Ujung-ujungnya, ketika ada muridnya yang bertanya tentang kaitan matematika dan fisika ... alamak sudah!
Padahal ilmu itu sendiri saling terikat satu sama lain.
Ini penting untuk menghidupkan suasana kelas agar tidak seperti khotbah Jumat. Akibat dari komunikasi satu arah adalah, pelajar kita tidak cukup berani untuk berpikir sendiri. Andaikan mereka punya pendapat yang berbeda dengan gurunya, mereka menyerah pada ketakutannya.
Bahwa beliau adalah guru saya. Bahwa beliau lebih banyak tahu daripada saya. Bahwa di sini, saya hanya sebagai murid. Bahwa pada akhirnya, saya terbantahkan.
Jadi tidaklah heran kalau pelajar kita (termasuk di level perguruan tinggi) masih banyak yang tidak berdaya saat harus presentasi. Isi makalah mereka sepenuhnya plagiarisme dari internet. Dan kalaupun mereka tahu banyak hal, pengetahuan mereka adalah "pengetahuan menurut".
Menurut Soerjono Soekanto, menurut Adam Smith, menurut David Ricardo, menurut Keynes, menurut ... semuanya didahului "menurut". Dan hebatnya, kita takjub dengan orang yang berkata seperti itu. Sungguh!
Ketika orang tidak bisa berpikir sendiri, orang hanya bisa mengutip.
Tidaklah keliru jika kita ingin mengutip apalagi memperdalam pemikiran orang lain, tapi pada saat yang tepat, kita harus punya pemikiran sendiri agar kita tidak bergantung pada pemahaman orang lain.
Padat diskusi
Tidaklah berguna kalau komunikasi dua arah berlangsung, tetapi bobot pembicaraannya dipenuhi omong kosong. Memang gurauan itu diperlukan, tetapi tidak boleh melebihi bobot pembelajaran itu sendiri.
Padat diskusi berarti guru dan murid saling bertukar pikiran tentang sebuah isu yang diangkat. Di sekolah menengah maupun perguruan tinggi, suasana semacam itu sudah amat terkikis karena beberapa alasan.
Justru suasana demikian malah saya temukan di warung-warung dekat rumah atau di perkumpulan komunitas. Ini semakin membingungkan terkait posisi sekolah sebagai tempat pencerahan.
Perbedaan mendasar antara diskusi dan debat terletak pada status kedua belah pihak. Dalam diskusi, pihak oposisi adalah kawan. Sedangkan dalam debat, pihak oposisi adalah lawan.
Diskusi melahirkan perbedaan pendapat untuk mencapai satu kesimpulan. Tetapi dalam debat, perbedaan pendapat adalah patokan nilai untuk menentukan siapa yang menjadi pemenangnya.
Dengan berdiskusi, kita bukan hanya mengetahui pendapat orang lain tentang ide kita, tapi juga pendapat kita tentang ide mereka. Kedua belah pihak saling bereaksi. Dan kunci terpentingnya, "mereka menyanggah, maka aku bertambah baik".
Tentu ruang kelas adalah tempat berdiskusi. Karena untuk ruang berdebat, kita punya tempat yang jauh lebih luas untuk itu: kompleks parlemen. Di sana kita bisa berdebat secara leluasa seperti anggota dewan. (Bahkan banyak kursi untuk dilemparkan ke lawan Anda).
Mengutamakan kedalaman dan bukannya keluasan
Siapa yang akan lebih mengetahui keindahan samudra: penyelam atau nelayan? Jawabannya jelas penyelam, karena mereka tahu apa yang ada di kedalaman samudra, sedangkan nelayan hanya sekadar tahu bahwa laut begitu ganas dan di situlah mereka bergantung.
Mungkin nelayan lebih banyak melihat keluasan laut, tetapi penyelam, meskipun hanya satu titik samudra yang diselaminya, mereka mengalami masa-masa yang indah dengan keajaiban dunia bawah laut.
Itulah gambaran saya tentang betapa pentingnya kedalaman pengetahuan daripada sekadar mengetahui banyak hal dan berhenti di permukaannya saja.
Paradigma kebanyakan orang percaya bahwa keluasan pengetahuan seseorang menggambarkan betapa geniusnya dia. Tapi apalah arti keluasan jika pengetahuan dia tidak cukup mendalam. Dalam istilah lokal: kagok! Tanggung! Setengah-setengah!
Lebih baik berdiskusi satu isu dan menggalinya hingga ke akar daripada berdiskusi banyak hal tetapi serba di permukaan.
Permasalahan ini mengantarkan kita pada dilematik antara spesialis dan multi-talenta. Tentu yang lebih baik adalah kedua-duanya atau yang umum disebut polimatik. Ilmuwan di zaman klasik banyak yang menjadi seorang polimatik.
Tidaklah mudah untuk menjadi seorang "multi-spesialis". Itu seperti sebuah mimpi di malam yang hangat. Tapi apa yang saya maksudkan adalah, jadilah spesialis terlebih dahulu, dan jika menyisakan banyak waktu, beralihlah ke bidang lain.
Ini menjadi seperti paradoks: spesialis tapi di banyak bidang. Tidak apa-apa, sebab kehidupan kita tidak bisa dijalani dengan hanya satu bidang pengetahuan. Jika diibaratkan permainan, selesaikan satu tahap dulu untuk bisa melanjutkan permainannya.
Saling mengapresiasi
Kota Wina, Austria, sempat menjadi pusat perkembangan musik klasik dunia dengan komponis legendanya, Mozart dan Beethoven. Bahkan Bapak Psikoanalisis, Sigmund Freud, juga besar di sana. Apa yang membuat kota Wina saat itu dipenuhi orang-orang genius?
Adalah keterbukaan penduduk kota Wina untuk menerima berbagai macam karya dan mengapresiasinya. Tak heran, Mozart dan Beethoven serta yang lainnya maju pesat di sana. Mereka punya seisi kota yang bersorak untuk mereka.
Bukan hanya bersorak, penduduk kota Wina juga menyemangati para genius, mendorong mereka agar semakin baik, agar mereka memberikan kontribusi pada dunia dengan lebih intens.
Begitu pun di dalam kelas. Apresiasi menjadi hal terpenting untuk membangun motivasi pelajar dalam bersifat aktif dan berinteraksi. Selama ini, mereka takut bahwa kesalahan mereka akan dicaci, kemudian menciptakan trauma berkepanjangan.
Tidak ada kilauan piala dalam ruangan kelas seperti yang terjadi di arena perlombaan. Tidak ada kerlap-kerlip lembaran uang untuk memotivasi para siswa. Satu-satunya yang paling sederhana dan sangat mungkin untuk menjadi sarana penyemangat, adalah saling mengapresiasi.
Bukan berarti setiap murid yang mengajukan pendapat harus diberi tepuk tangan, tapi berilah penghormatan atas setiap pendapatnya ketika pihak lain menanggapi.
Katakanlah Jono memaparkan pendapatnya tentang isu pemanasan global. Saya sebagai penanggap mesti memberikan penghormatan dengan pertama-tama mengatakan kelebihan argumennya sebelum saya berkomentar atau mengkritik.
Juga peranan pengajar amatlah fundamental dalam hal ini. Sangat tidak mudah untuk membangun suasana semacam itu. Pelajar sering termakan oleh gengsi dan ego, maka jalan alternatif akan sangat bergantung pada peranan pengajar.
Saya pernah menuliskan artikel di sini tentang pentingnya memerhatikan pujian sebelum melayangkannya.
Tidak ada yang lebih manis dibandingkan tepuk tangan sepenuh hati dari audiensi yang mengerti. Sungguh!
Pertimbangan relevansi
Masalah yang sedari dulu belum terselesaikan adalah, tidak semua materi kurikulum relevan terhadap pelajar itu sendiri maupun kehidupan sehari-hari. Di sinilah kecerdikan pengajar diuji: apakah mereka tetap memaksakan apa adanya kurikulum atau "memodifikasinya".
Pembelajaran yang humanis tidak selayaknya memaksakan semua materi untuk ditelan murid. Maksudnya, pandangan humanisme memandang bahwa setiap orang itu otentik dan unik. Mereka yang berbakat di basket belum tentu bisa mencerap pelajaran kimia.
Pengajaran mesti disesuaikan dengan tingkat kemampuan pelajar karena setiap individu punya ketimpangan pemahaman. Kalau tidak ingin seperti ini, maka pelajar harus mandiri dalam belajar. Tetapi menjadikan mereka mandiri tidaklah mudah.
Selama ini selalu terjadi pertarungan antara kurikulum dan waktu. Dan ini menjadi tantangan bersama antara pengajar dan pelajar. Sebab belajar itu seperti naik tangga: langkah demi langkah.
Jadi ketika memulai sebuah pembelajaran, mungkin ada beberapa pelajar yang pemahamannya belum sampai ke sana.
Katakanlah sekarang pembahasan elastisitas harga. Akan dipelajari tentang apa itu elastisitas, bagaimana aturannya dan bagaimana rumusnya serta kurvanya. Saya yakin bahwa di antara semua murid ada yang belum memahami apa itu kurva atau pemikirannya belum bisa sampai ke sana.
Itulah kelemahannya: pendidikan kita terlalu memukul rata dengan asumsi semua punya kemampuan yang sama. Tidak, setiap pelajar punya kesenjangan pengetahuan sebelum pengajar memulai suatu materi.
Jadi kalau pelajar yang tertinggal itu tidak diantarkan dulu ke tingkat yang sama dengan mereka yang sudah paham, maka pembelajaran tersebut selamanya tidak manusiawi. Artinya, materi pembelajaran pun perlu dibuat relevan terlebih dahulu dengan kemampuan murid.
Guru matematika saya ketika SMP mempraktikkan metode unik. Beliau memerhatikan kemampuan setiap murid sehingga pembelajaran yang beliau berikan dapat disesuaikan dengan masing-masing individu. Maksud saya dalam artian harfiah.
Pembelajaran menjadi seperti berlevel. Si A ada di level 3 dan si B baru di level 1. Seiring waktu, si B berkembang dan naik level ke level berikutnya. Memang terjadi kesenjangan, tapi di akhir semester, semua murid mencapai garis akhir yang sama.
Apalagi tidak semua materi relevan dengan tujuan pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ini menjadi hambatan karena melahirkan asumsi di kepala murid bahwa pembelajaran yang dimaksud tidaklah penting, maka tidak perlu dipahami.
Tantangannya adalah, memilah materi yang relevan dari tuntutan kurikulum, atau menjadikan semua materi bersifat relevan dengan murid dan kehidupan sehari-hari.
Seperti yang selalu dikatakan matematikawan, "Semuanya bisa dihitung. Jika tidak bisa, buatlah agar bisa dihitung."
Mampu menempatkan diri
Mereka yang berpengetahuan mesti berani bersuara. Mereka yang tidak tahu mesti banyak diam. Tidak bisa dibalik.
Persamaan dari keduanya adalah, semua orang harus punya pertanyaan yang bagus. Semua itu dilakukan dengan penuh rendah hati dan kesadaran, semata-mata demi kebenaran itu sendiri.
"Saya tidak pernah membiarkan sekolah untuk mengganggu pembelajaran saya." (Mark Twain)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H