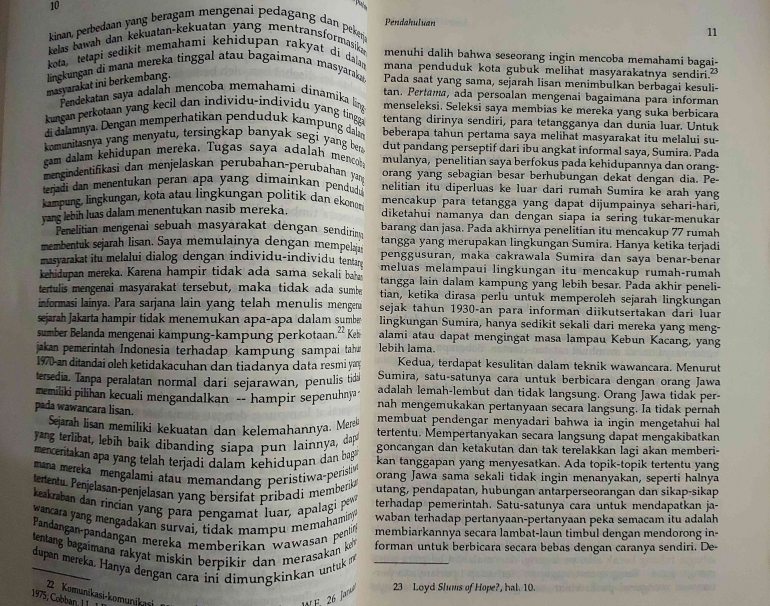Sekali lagi, saya tak akan membabar apa itu konstruktivisme dan teori kritis. Njlimet bikin puyeng itu.
Intinya, menurut dua paradigma riset itu realitas sosial adalah hasil bentukan sosial. Entah itu hasil bentukan bersama, inter-subyektivitas (paradigma konstruktivisme), atau bentukan sepihak subyek yang berkuasa (teori kritis).
Karena itu, mustahil ada realitas sosial obyektif sebagaimana dipikirkan oleh kaum positivis empirik dari sains natural.
Penelitian sosial adalah proses inter-subyektivitas, interaksi komunikatif antara subyek peneliti dan subyek tineliti.
Karena itu mustahil untuk mensterilkan riset sosial dari faktor subyektivitas. Kata Max Weber, untuk menjadi obyektif, kita harus menafsir subyektivitas tineliti. Implikasinya, karena sifatnya tafsir, faktor subyektivitas kita sebagai periset ikut berperan juga.
Bingung? Intinya begini.
Riset sosial dengan paradigma konstruktivisme -- khususnya riset-riset kualitatif partisipatif sosiologi, antropologi, dan etnologi -- mengasumsikan realitas sosial (yang diklaim) obyektif itu tak eksis di luar sana.
Realitas sosial obyektif, dengan demikian, adalah hasil inter-subyektivitas, atau resultan dari interaksi komunikatif antara subyek peneliti dan subyek tineliti.
Biar terang, saya beri contoh.
Di desa Kandangan, Bawen Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1990 saya berbincang dengan seorang lelaki buruh tani. Dia bercerita harus meninggalkan kerja buruh bangunan di Semarang untuk ikut panen padi di sawah Pak Bekel (Kepala Dusun). Padahal upah buruh bangunan lebih besar dibanding upah panen padi.
Menurut pandangan obyektifku, pilihan buruh tani itu bekerja panen di sawah Pak Bekel tak rasional secara ekonomi. Tapi menurutnya, dia harus mengambil pekerjaan itu. Jika tidak, dia akan kehilangan pekerjaan-pekerjaan lain sepanjang tahun dari Pak Bekel. Karena dianggap tak setia.