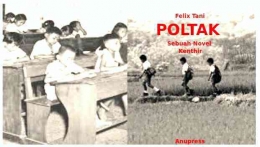Samisara Purasa, Sipahaonom. Hari keempatbelas bulan September dalam parhalaan, penanggalan Batak. Esoknya Tula, hari kelimabelas, saat purnama menerangi malam.
Samisara Purasa itu hari raja. Hari baik untuk menghelat pesta besar, pesta muda-mudi, dan mengantar anak ke rumah kakek-neneknya.
September belum basah. Curah hujan masih rendah. Sesekali hujan lebat. Beberapa kali gerimis. Lebih sering hari cerah.
Seperti malam itu. Malam Samisara Purasa, ketika rembulan nyaris purnama menyinari Tanah Batak. Tak terkecuali Sosorbinanga, kampung Ama Rumiris, ayah Berta -- pariban Poltak.
Poltak dan neneknya sedang berkunjung ke situ. Ada urusan adat lingkup kerabat besar nenek Poltak.
Kerabat besar hendak membangun batu na pir, makam semen, untuk leluhur mereka di Hutabayu, Tanah Jawa. Ompu Sotaronggal, itu nama leluhur mereka. Kakek dari Ompu Soaduon -- ayah Ama Rumiris, nenek Poltak, dan Amani Purbatua yang tinggal di Hutabayu.
Untuk biaya pembangunan, kerabat besar⅕ Ompu Sotaronggal bersepakat melakukan toktok ripe, iuran per rumahtangga.
"Paraman Ama Rumiris. Aku tak perlulah ikut rapat keluarga di Hutabayu, ya." -- paraman, sebutan dari perempuan untuk putra saudara laki-lakinya.
Nenek Poltak tahu diri. Dia berstatus boru, pihak penerima istri bagi bapak dan kakeknya. Rapat pembangunan makam di Hutabayu itu adalah urusan namardongan sabutuha, semua anak dan cucu laki Ompu Sotaronggal yang sudah berkeluarga.
"Bah, nauli, Namboru," jawab Ama Rumiris. Namboru adalah status sekaligus panggilan untuk saudara perempuan ayah. Suaminya, amangboru.
"Aku titiplah toktok ripe dari kami, keluarga Ompu Poltak. Sampaikanlah dengan baik kepada keluarga di sana."
Nenek Poltak menyampaikan sejumlah uang kepada Ama Riris.
"Nauli. Kusampaikan pun nanti. Mauliate godang, Namboru."
"Nauli. Horaslah amang di perjalanan besok. Horas pula semua kerabat di sana."
Setelah itu, pembicaraan berlanjut ke rencana Ama Rumiris sekeluarga pindah ke Pangururan, Samosir. Katanya, mereka diminta menjaga mertua Ama Rumiris yang sdah sakit-sakitan di sana.
Lulu beralih ke isu-isu keseharian. Tentang hasil panen padi, kopi, kerbau, ternak babi, harga gulamo-- ikan asin di Tigaraja, obat rematik, dan seribu tetek-bengek lain.
Semua itu tak menarik bagi Berta dan Poltak. Bukan urusan mereka hari ini.
Terang bulan di luar rumah jauh lebih menarik. Bahkan terlalu menarik. Setidaknya untuk Berta dan Poltak.
"Berta. Ayo lihat bulan," ajak Poltak.
"Eh, Berta, pergi sana temani paribanmu," sambar Nai Rumiris, sebelum Berta sempat menjawab.
Berta dan Poltak menjadi dua ekor laron. Mereka setengah berlari ke pintu depan rumah. Lalu turun ke halaman.
Berdua berdiri di tengah halaman. Memandang ke langit timur. Terpukau menatap bulatan terang rembulan Samisara Purasa yang nyaris tula, purnama.
Berdua adalah laron. Terpikat oleh sihir cahaya emas rembulan.
Dari sebelah timur, terhalang oleh porlak, kabun campuran, terdengar riuh teriakan anak-anak. Mungkin sedang main galasin, atau petak umpet, di bawah terang bulan.
"Mungkin ada Alogo dan Tiur." Poltak membatin. Tapi dia tak berminat pergi ke sana.
Begitupun Berta.
Berduaan lebih indah. "Kita duduk di situ saja, Poltak," ajak Berta sambil nenunjuk bangku kayu di sisi barat halaman.
Poltak menurut duduk disamping Berta. Seperti raja laron menurut pada ratunya. Pasangan paling setia.
"Poltak, bila kau menikah kelak, jadilah seperti ratu dan raja laron. Setia sampai mati."
Begitu nasihat kakek Poltak pada suatu malam. Dulu, dulu sekali. Ketika laron buyar dari sarangnya dan berjatuhan di halaman rumah.
"Jangan seperti belalang sembah," lanjut kakeknya.
"Kenapa rupanya belalang sembah, Ompung," tanya Poltak heran.
"Bahaya. Belalang sembah betina makan jantannya. Mau kau begitu?" bisik kakek Poltak sambil melirik nenek Poltak yang pura-pura tuli.
"Bah. Tak maulah, Ompung." Poltak bergidik.
"Poltak." Suara Berta membuyarkan lamunan Poltak.
"Kenapa, pariban."
"Betulkah bulan itu tempat pertemuan dua pasang mata?"
Hal itu ditanyakan Berta, sebab tahun depan dia pasti berpisah dengan Poltak. Poltak akan pergi ke Siantar, melanjut ke seminari, sekolah calon pastor.
Berta sendiri dan keluarga akan pindah ke Pangururan. Dia dan Poltak akan terpisah jauh oleh gunung dan danau.
Berta teringat pula satu larik lagu Batak lama. "Bulan i, bulan i, pardomuan ni simalolong." Bulan itu, bulan itu, tempat mata bertemu pandang.
Mata orang-orang saling merindu.
"Bukan dua pasang mata saja, Berta. Tapi jutaan."
Berta melotot pada Poltak. Bukan itu jawaban yang didambanya.
"Aduh, sakit, Berta." Sebuah cubitan pedas baru saja didaratkan Berta di pinggang Poltak. Itu hukuman atas salah jawab.
"Kamu jahat," sembur Berta, cemberut.
Poltak menatap wajah cemberut itu. Tetap cantik, indah. Seperti bulan sabit terbalik, cekung ke bawah.
"Kamu rembulan Samisara Purasa," balas Poltak, sembarang bicara.
Tapi itu terdengar seperti rayuan di telinga Berta. Rayuan dari pujaan hati. Yang bikin tahi kerbau tampak macam kue tart.
Perlahan senyum Berta mekar lagi. Lalu tawa, bersambut tawa. Riang-ria di bawah sorot rembulan September.
Terdengar alunan suara merdu lelaki diiring petikan gitar dari dalam rumah.
"Itu tulang bernyanyi?"
Berta mengangguk.
"Di rondang ni bulan i,
di topi tao i,
marsolu do ahu disi.
Di na lao mulak ahu,
mulak tu solukki,
hujalang ma ibotongki.
Tung mansai lambok do begeon disi,
di na nidokmu tu ahu.
Sai unang lupa ho,
ito di janjimi, sai unang be maose i.
Di rondang ni bulan i,
di topi tao i, marsolu do ahu disi.
Di na lao mulak ahu,
mulak tu solukki,
hujalang ma ibotongki."
["Di bawah terang bulan,
di tepi danau itu,
kukayuh biduk di situ.
Saat aku mau pulang,
kembali ke bidukku,
kujabat erat kekasihku.
Sungguh lembut kudengar suaramu,
saat kau berkata padaku.
Jangan pernah kau lupa, janjimu kekasih, jangan pernah kau ingkari.
Di bawah terang bulan,
di tepi danau itu,
kukayuh biduk di situ.
Saat aku mau pulang,
kembali ke bidukku,
kujabat erat kekasihku."]
"Ah, buah kecapi jatuh tidak jauh dari pohonnya ," pikir Poltak. Dia tahu sekarang dari mana datangnya suara merdu Berta.
"Itu lagu kenangan among dan inong," kata Berta, sedikit lirih.
"Ceritakanlah."
"Dulu, waktu among masih perjaka. Dia merantau ke Pangururan. Berkenalan dengan seorang gadis, inong, di Sitanggangbau. Kampung di utara Pangururan. Di mulut terusan Tano Ponggol."
Berta mengambil jeda. Poltak diam. Menunggu lanjutan kisah. Bulan masih setia di atas mereka.
"Tiap malam bulan purnama, among naik biduk melintasi Tano Ponggol, dari selatan ke rumah inong di utara. Pulangnya, kembali naik biduk. Begitu selama tujuh purnama. Setelah itu inong dan among menikah."
"Haa ..., Berta, itu macam dongeng putri dan pangeran."
"Kau tak percaya?"
"Percaya, boru ni rajaku."
"Begitu cerita inong padaku."
Poltak termenung. "Ada rupanya kejadian seperti lagu Di Rondang Ni Bulan I," pikirnya.
"Parbogasan nauli," puji Poltak dalam hati. Dia takjub akan parbogasan, kisah pacaran tulang dan nantulangnya itu.
"Eh, Poltak. Lagi pikir apa kau."
Poltak tersentak.
"Benarkah itu, Berta? Kalian akan pindah ke Pangururan?"
"Kata among dan inong, begitulah."
Poltak menghela nafas, pelan. "Jadi kita akan terpisah jauh, Berta?" bisiknya dalam hati.
"Ah, kita akan berpisah, Poltak." Berta membatin, seakan menjawab.
Keduanya saling pandang. Tanpa kata-kata. Hanya ada derik jangkrik malam. Seperti mengabarkan perih yanng sama di dua hati.
Ada yang tak dapat disembunyikan Poltak dan Berta di bawah sinar rembulan. Rasa rindu yang datang sebelum perpisahan tiba.
"Aku ingin kau memelukku, Poltak," pinta Berta dalam hati. Dia mengharap sebuah kenangan dari paribannya itu.
Sebuah pelukan adalah obat. Penawar rindu yang datang mendera sebelum waktunya.
"Ah, Berta. Inginku, memelukmu. Tapi kutakut dosa, pariban," bisik Poltak dalam hati, seakan tahu pikiran Berta.
Poltak meyakinkan diri sendiri. Suara hatinya mengingatkan, "Poltak, kau mau jadi pastor. Tak bolehlah memeluk pariban. Kalian masih kecil pula. Dosalah itu."
"Ei. Berta! Poltak! Di mana kalian! Sudah larut malam."
Teriakan ibu Berta memecah dinding hening di antara Poltak dan Berta.
"Aku harus pulang, Berta."
Rembulan sudah tinggi. Saatnya dua hati dipisah tirai malam. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H