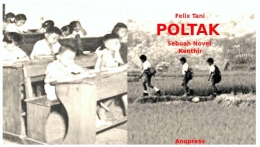"Kalau pariban wajib dinikahi, berarti kau akan punya banyak istri. Kan banyak tulangmu. Banyak pula paribanmu."
Poltak mendapat jawaban panjang lebar dari neneknya. Hanya untuk satu pertanyaan pendek yang diajukannya. Apakah pariban harus dinikahi? Takpaham dia maksud neneknya soal banyak istri itu. "Maksudnya apa?" pikirnya.
"Suka hatimu pada Berta, ya. Bah, tak usahlah kau pikirkan itu. Kau baru kelas satu SD. Belum waktunya bicara soal nikah. Pikirkan saja pelajaranmu sajalah. Agar kau naik ke kelas dua."
"Bagaimana pula cara ompungku bisa menduga isi pikiranku," batin Poltak takjub. Dia tidak pernah paham. Seorang nenek sejati kenal pahompu hasian, cucu kesayangan, luar dalam seperti dia mengenal dirinya sendiri.
Itu pembicaraan Poltak dan neneknya minggu lalu. Sepulang dari rumah Ama Rumiris, ayah Berta, paribannya di Sosorbinanga.
Pembicaraan itu terngiang kembali di kepala Poltak pagi ini di dalam kelas. Dipicu tawa lepas Berta. Dia bersukaria saat diberitahu Guru Barita dia naik ke kelas dua.
Hari ini, di penghujung Desember 1968, adalah hari pembagian rapor di SD Hutabolon. Sekaligus pengumuman kenaikan kelas bagi murid kelas satu sampai lima. Untuk kelas enam, pengumuman lulus SD.
"Poltak! Maju! Kau naik kelas. Nilaimu pemuncak. Bagus. Pertahankan." Guru Barita memanggil Poltak ke depan kelas.
Prestasi Poltak sebagai pemuncak kelas diumumkan Guru Barita. Ditambah satu kata pujian, lalu satu kata penyemangat. Itu saja. Irit, tanpa piagam, apalagi piala. Belum zamannya.
"Hebat kali kau, Poltak!"
Ah, itu ucapan kagum Berta. Pujian langsung tak terduga. Poltak melirik ke arah Berta. Senyum anak perempuan itu sedang merekah delima.
"Oi, enak kalilah dipuji pariban itu," celetuk Alogo, disambut tawa anak-anak kelas satu lainnya.
"Makanya kau punya paribanlah!"
Tembakan pengunci mulut dari Poltak untuk Alogo. Entah karena belum lahir, entah karena takada, atau mungkin taktahu, Alogo pernah mengaku tak punya pariban.
Pembagian rapor sekaligus pengumuman kenaikan kelas adalah perjodohan berita gembira dan berita sedih. Berita gembira untuk murid yang naik kelas. Berita sedih untuk murid yang tinggal kelas.
Berita sedihnya, Dolok dan Togu, dua murid kelas satu, menangis sesenggukan di bangku masing-masing. Mereka berdua dinyatakan tinggal kelas.
"Hajablah aku nanti dihajar amongku. Pakai batahi " Itulah hal yang paling menakutkan bagi Dolok. Lecutan batahi, pecut rotan spesial untuk kerbau, tepat di betisnya. Bayangan pecutan itu, akibat tinggal kelas, menghantuinya. Sehingga dia menangis sesenggukan.
"Bah, kau kan bukan kerbau, Dolok." Jonder mulai menyalakan kompor. Tapi segera padam karena dipelototi Poltak.
Togu lain pula masalahnya. Dia menangis karena takut tarhirim, sakit sebab keinginan badan tak kesampaian.
Kata Togu, ibunya sudah berjanji, kalau dia naik kelas maka boleh ikut ke onan Tigaraja-Parapat untuk membeli sepatu spartakus yang sangat diidamkannya. Togu takut tarhirim, lidah kakinya jadi bengkak karena gagal bersepatu.
"Tak perlu takut kau, Togu. Tahun depan, setelah pakansi, sepatu spartakusku boleh kau pakai."
Poltak membujuk Togu. Dia memang tak pernah lagi mengenakan sepatu spartakusnya. Sepatu itu lebih pintar melukai ketimbang menjaga keamanan kakinya.
Seketika tangis Togu berhenti. Matanya, walau banjir air mata, memancarkan sinar bahagia. Sepatu spartakus terbayang di depan mata. Tahun depan.
Anak kecil memang tak terduga. Bukan tinggal kelas yang membuat mereka bersedih hati. Melainkan rasa sakit yang akan dialami akibat tinggal kelas. Itulah yang membuat mereka menangis.
Sebenarnya di SD Hutabolon naik ke kelas dua atau tinggal di kelas satu tak ada bedanya secara spasial. Kelas satu dan kelas dua masih tetap duduk di bangku yang yang sama di bagian depan gedung gereja HKBP Hutabolon. Mereka juga tetap diajar oleh guru yang sama, Guru Barita.
Bedanya hanya soal waktu sekolah dan materi pelajaran. Kelas satu masuk pukul 07.00 - 10.00 WIB. Kelas dua pukul 10.00 - 13.00 WIB. Lalu, materi pelajaran setingkat lebih tinggi untuk kelas dua.
Di antara delapanbelas murid yang naik kelas,sudah pasti tersebut nama a sekawan Binsar dan Bistok. Bertiga dengan Poltak, mereka kini sama-sama kelas dua SD. Itu sesuai dengan Perjanjian Hariara Hapuloan. Mereka akan senantiasa setia kawan, kompak, dalam untung dan malang. Beruntung naik kelas bukanlah kemalangan.
"Bah, bakalan tiga tahun aku duduk di bangku yang sama," keluh Binsar. Bistok manggut-manggut mengiyakan. Mereka berdua senasib.
"Aku rasa di bangku itu sudah ada cetakan pantat kalian," celetuk Poltak.
"Hah! Cetakan pantat Bistok paling lebar," Binsar menyambar umpan.
Tiga sekawan itu tertawa geli terpingkal-pingkal. Mereka sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dengan rapor naik kelas di tangan. Langkah kaki mereka enteng seringan kembang ilalang tertiup angin di padang.
"Selama pakansi kita mengumpul buah makadamia saja. Lumayan dijual ke Kehutanan. Uangnya bisa buat tambahan beli baju Natal dan Tahun Baru." Poltak menawarkan ide kerja liburan.
Pegawai Kehutanan memang sedang sibuk membeli buah makadamia tua lewat seorang makelar dari Kampung Sorpea. Anak-anak Sorpea dan Panatapan tinggal mengumpulkan buah jatuhan dari sabuk hijau pohon makadamia di sepanjang sisi barat jalan raya Trans-Sumatera.
Kehutanan akan membibitkan buah makadamia itu. Setelah cukup besar, bibit akan ditanam membentuk sabuk hijau anti-api, pelindung hutan pinus, entah di mana. Disebut anti-api karena lantai hutan makadamia itu basah dan bersih dari semak dan rumput, sehingga tidak bisa dilewati api.
"Setuju!" Binsar dan Bistok menjawab bersamaan.
"Uangnya bisa untuk beli limun juga. Biar pandai seperti Poltak." Binsar menambahkan.
"Limun pangkal pandai," timpal Bistok.
Tiga sekawan itu tertawa geli. Mereka baru saja sukses mengubah pepatah "rajin pangkal pandai" menjadi "limun pangkal pandai." Adakah seorang pujangga di negeri ini yang lebih kreatif dari mereka? (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H