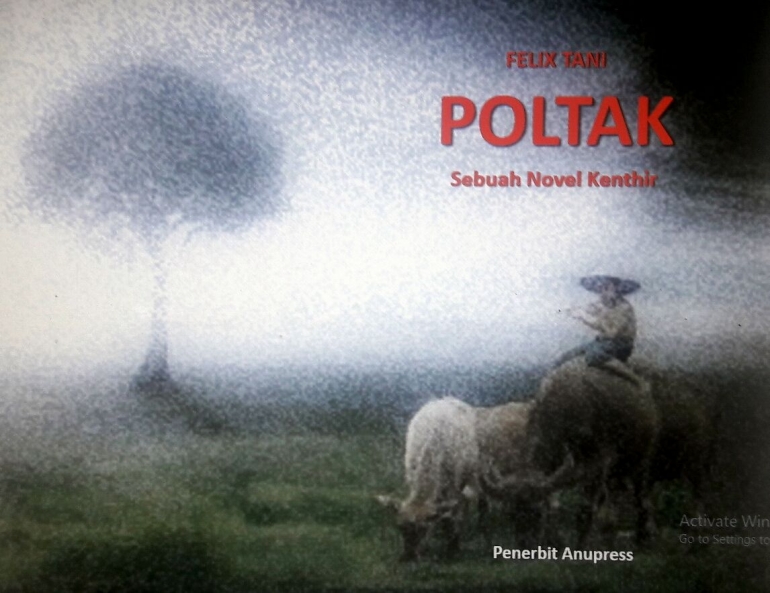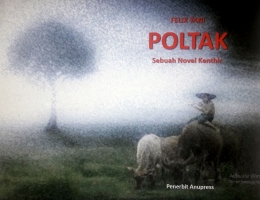"Oi! Bangun kau, Poltak! Pagi buta mimpi!" Poltak terlonjak duduk dari baringnya. Dia merasa tubuhnya diguncang-guncang. "Mengganggu orang tidur saja kau!" Neneknya merepet.
Poltak spontan merogoh saku bajunya. Uangnya masih ada. Dicabut dan dihitungnya, masih genap enam rupiah. Utuh. Masih tetap kaya raya.
"Bah, mimpi rupanya aku, Ompung," gumamnya. Lega hatinya.
"Uang saja di kepalamu. Sampai mimpi buruk macam itu. Sini uangnya. Ompung simpan."
Neneknya tak perlu persetujuan. Uang enam rupiah langsung disambarnya dari genggaman Poltak. Lalu diselipkan ke balik kutangnya. Aman. Poltak pasrah.
Poltak tak tertarik lagi meneruskan tidurnya. Perlahan dia bangkit berdiri. Lalu beranjak ke dapur, berdiang di depan perapian.
Cahaya fajar semburat di timur. Di luar sudah terang tanah. Kesibukan persiapan pesta telah mulai.
Terdengar seekor babi mengiak panjang. Nyaring di udara pagi. Lalu tiba-tiba senyap. Seutas tali nyawa telah putus.
"Poltak, bantu namboru membawa kopi ke penjagalan," Namboru Riama, putri sulung kakek nomor dua, Ama Riama minta tolong, sambil menunjuk pada ceret berisi kopi panas. Riama sendiri membawa cangkir-cangkir dan talam berisi lampet, kue putu khas Batak.
Penjagalan, di kebun belakang rumah, sudah sibuk. Kelompok kerabat boru, pihak penerima isteri untuk buyut Poltak, sudah lengkap di sana. Mereka menjalankan peran adatnya sebagai parhobas, pelayan pesta adat untuk hula-hula.
Kakek Poltak nomor empat, Ama Rotua dan nomor enam, Ama Rugun si bungsu hadir juga di situ. Keduanya ikut bantu-bantu memotong dan mencincang daging babi.