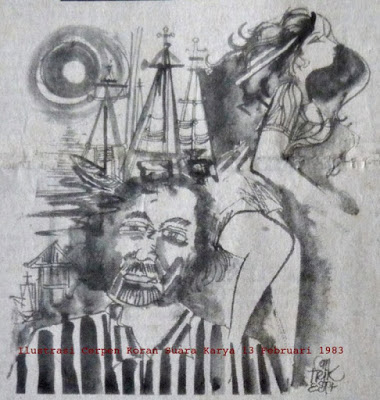RAKIT-RAKIT dan jung termangu di pantai. Arus yang biasanya deras seakan enggan menghanyutkan diri. Di kejauhan, di pelabuhan, tinggal beberapa tiang layar mengacung sepinya sendiri. Kapal-kapal yang menyauh di dermaga, setia menerima angin yang lela. Kehidupan yang biasanya penuh peluh, sekarang seperti ingin bermimpi.
Mimpi?
Lelaki itu menyeruput minuman yang masih tersisa. Penjaga warung itu menawarkan lagi, kalau-kalau ia masih hendak menambah. Tetapi lelaki itu menggelengkan kepala. “Aku hanya ingin menanyakan apakah Mariyah masih suka mampir ke sini.”
“Beberapa kali setelah itu. Setelah kalian berpisah karena engkau berpaling kepada Rosa.”
Wanita penjaga warung menatap lurus ke wajah lelaki itu. Di kejauhan tirai gerimis memutih membuat kota jadi kelabu. Ke arah luasan sungai, gerimis telah berubah menjadi hujan yang menyirami jung-jung dan tongkang yang berlayar dengan lela.
“Memang keparat. Lelaki keparat,” terdengar suara lelaki itu seperti menumpah. “Kawan yang suka menggunting dalam lipatan. Mariyah dan Rosa jadi korban!”
Wanita penjaga warung itu mengemasi beberapa gelas dan piring di atas meja warung. Tangannya yang cekatan menandakan bahwa ia memang orang warungan sejak muda. Lalu terdengar suaranya tertuju kepada lelaki itu. “Kupikir mungkin salahmu sendiri. Terlalu percaya kepada kawan. Adakah orang yang tidak berdosa di muka bumi ini?”
Soalnya bukan salah atau dosa atau suatu kesucian. Tetapi kepercayaan. Manusia harus memulai sesuatu dari saling percaya.
“Itulah masalahnya. Mariyah sakit hati karena engkau mengambil Rosa. Sedang….”
“Sedang Rosa akhirnya dimangsa Rachmat juga!”
“Itu karena Rosa tak yakin engkau akan kembali. Ia telah menanti tiga tahun lamanya. Bahkan sempat menjadi guru di desa….”
“Tetapi ia sudah tahu. Kuliah untuk sampai sarjana, paling kurang lima tahun lamanya.”
“Lima tahun tak lama, kata Rosa. Tetapi menurut kabar dari Rachmat, engkau telah menyunting gadis Jawa. Nah, kau tahu sendiri. Dia bukan dipaksa Rachmat, tetapi menyerahkan diri untuk….”
Lelaki itu mengertakkan gerahamnya. Ia ingat Rachmat. Kawan karibnya di sekolah. Rachmat tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena ia lebih mementingkan uang. Ia ikut sindikat penyelundup. Ia jadi kaya raya, dan itu membuat ia dengan mudah menggaet wanita.
“Itu namanya terjerat bujuk rayu. Bukan Rosa yang menyerahkan diri, tetapi Rachmat yang menjerat!”
“Karena Rosa merasa dipanasi Mariyah, Rosa hendak merebut Rachmat dari Mariyah.”
Lelaki itu meneguk sisa terakhir di dasar gelasnya. Ia ingat Mariyah, gadis yang sederhana. Ia mula-mula sekali tertarik dengan Mariyah. Tetapi lama-kelamaan, Rachmat mengatakan kepadanya kalau Mariyah sebenarnya lebih cocok untuk Rachmat. Karena mersa sebagai teman akrabnya, lelaki muda itu bersedia, asal saja ia mendapatkan gantinya. Ia memang mendapatkan Rosa.
“Tetapi Rosa telah bersumpah untuk bersatu denganku. Bahkan hingga surat-suratnya yang terakhir. Masih kusimpan di Yogya.”
“Itulah salahmu, Yahya. Kau tak pernah pulang. Gadis siapa yang tahan menanti tak menentu semacam itu?”
“Saat aku kembali kala riset skripsi, Rosa telah tiada. Yang menyakitkan, ia, kata saudaranya, dibuang ke kampung pedalaman; sekalian mengajar di sana. Karena sudah berbadan dua. Rachmat tak mau bertanggung jawab, karena ia sudah punya istri.”
“Rosa kena penyakit kuning. Bayinya mati, dan ia sendiri.”
Lelaki itu sekali lagi menggertakkan gerahamnya. Hatinya panas. Darah seakan mendidih ke ubun-ubunnya. Begitu melangsa saat ia ingat sumpah setia kekasihnya. Begitu buruknya perangai Rachmat.
“Jadi Rachmat tak mau mengobatinya?”
“Rachmat sudah berlayar ke Sulawesi.”
“Ke Sulawesi?”
“Ia pulang ke Enrekang. Ke kampung halamannya, bersama istrinya yang orang sini.”
“maksudmu, ia punya istri lain?”
“Kudengar ada yang di Tarakan, ada pula yang di Toli-Toli.”
Lelaki muda itu menarik napas dalam-dalam. Gerimis yang membentuk tirai putih tadi seakan memisah diri dari hujan deras yang melanda bagian sungai ke arah hilir. Ke bagian hulu tirai hujan makin menebal, sehingga membentuk bayangan kelabu yang mengelam.
“Kupikir soal itu telah berlalu,” terdengar suara wanita itu lagi. “Kau sebagai sarjana harus memikirkan masa depan yang lebih berguna bagi nusa dan bangsa.”
Ada sesuatu yang tersekat di kerongkongan lelaki muda itu.
Seakan ia menyusuri masa silamnya beberapa tahun yang lalu. Lama sudah berbagai kejadian merambang di depan matanya saat ia masih di sini, di kota kelahirannya ini. Lelaki sebayanya hampir semuanya pergi meninggalkan kampung halaman. Ada yang masih sekolah, ada pula yang sudah bekerja dan berkeluarga di tempat-tempat yang jauh. Hanya sejumlah teman wanita yang masih berada di kampung, dan kebanyakan dari mereka juga telah berkeluarga.
Lalu tentang Ramlah?”
“Ramlah? Kau belum tahu kabar Ramlah?”
“Ceritakan. Aku sungguh tak tahu lagi….”
“Hampir seburuk Mariyah. Mariyah harus menggugurkan kandungannya karena Rachmat, dan kemudian mendendam kepada lelaki. Ia tenggelam dalam lumpur bunga raya. Sedang Ramlah, karena tergoda harta. Mungkin juga karena ketaktahuan. Ia menikah dengan pekerja kayu dari luar negeri. Kawin kontrak. Setahun yang lalu suaminya pulang, dan Romlah kadung ditinggali dua anak yang masih kecil. Kasihan, tak ada yang ditinggalkan, sehingga Ramlah hampir-hampir terlantar.”
“Begitu buruknya,” lelaki muda itu seakan menyesali. “Semua yang kukenal mengalami nasib sial”
“Pun Titi sudah pergi.”
“Maksudmu? Titi juga mati?”
“Kapal yang ditumpanginya diamuk badai. Tenggelam….”
Lelaki itu memandang jauh kedepan. Tirai hujan makin kedap. Tak ada cahaya matahari seperti senja kala biasa.
“Aku pernah bercita-cita membuat jembatan penyeberangan di atas sungai kita ini. Kuingat, kawan kita dahulu. Wahid, Abdul Wahid. Tentu ia sudah insinyur sekarang,” suara lelaki itu memecah kediam-diaman yang memanjang. “Dahulu Wahid amat antusias mendengar cita-citaku itu.”
“Jadi kau belum tahu?”
“Wahid juga kena bencana?”
“Ia kerobohan tambang batu bara. Tiga hari lamanya baru mayatnya dapat diangkat.”
“Lalu Jamhari?”
“Jamhari jadi sopir taksi. Taksinya mencebur ke kali. Rupanya pintu taksi itu terkunci. Ketika diangkat, Jamhari sudah jadi mayat!”
“Huh!” lelaki itu mengeluh dan seperti muak, “Ceritamu hari ini begitu buruknya. Semuanya petaka.”
“Tetapi kau yang memintanya, Yahya. Aku kangen sebenarnya. Aku kangen bisangobrol denganmu. Sejak SD kita pisah, engkau terus sekolah, aku hanya hanya lulus SD. Tetapi aku selalu ingat kau.
Sekarang kau sarjana. Mana istrimu orang Jawa itu?”
Lelaki muda itu seperti memandang dalam kegelapan. Tiga gadis yang pernah menambat hatinya telah mengalami nasib tragis. Juga gadis keempat, gadis Jawa yang dicintainya harus pula berpisah karena suatu kecelakaan. Bus yang ditumpangi gadis itu—saat kembali dari KKN di Wonosobo—terbalik dan masuk jurang. Tak tertolong, Sri Murtini harus kembali ke alam baka. Kini, di sini, di kota kelahirannya, ia mendengar sejumlah cerita tragis yang mengiris hati.
“Sekarang kau telah pulang, Yahya. Kau memang sekalian pulang ini?” suara si wanita terdengar lagi. “Sayang kalau semuanya menumpuk di kota seperti Yogya atau Jakarta.”
“Aku barusan wisuda. Aku ingin masuk ke pedalaman. Ingin mendirikan sekolah di daerah yang sukar dijangkau angkutan. Hanya, aku masih harus meminta izin di sini. Apakah pemerintah setempat setuju?”
“Aku malu, Yahya. Aku orang warung, kau ajak bercakap begitu tinggi…”
Lelaki itu menatap wajah gadis itu, masih juga jelita, seperti dahulu. Sayang ia tak punya kesempatan sekolah. Lalu terdengar suara lelaki itu. “Aku hanya meminta keterangan darimu. Sekarang aku senang. Banyak yang kudapat darimu….”
Yahya meminta diri dan kemudian melangkah mencari oplet yang bisa ditumpanginya ke arah hulu, ke rumah orang tuanya. Saat mengayunkan kaki, ia teringat ke waktu lalu. Sebelum berangkat memasuki kapal untuk pergi ke Jawa, ia mampir terlebih dahulu di warung Maimunah. Ia sempat minum dan ngobrol. Waktu itu gerimis sedang turun, dan matahari Januari tak menampakkan cahayanya. Biasanya pelangi melengkung kalau ada gerimis mencecahkan kaki kakinya yang runcing ke sungai. Tetapi saat itu, seperti juga saat ini, pelangi itu tak ada. Yang ada hanya tirai putih yang kedap, seperti rimba yang gelap. Adakah ia menggambarkan kehidupan yang penuh tantangan ini? Kehidupan yang diarungi dengan penuh peluh ini?
Yahya tertawa dalam hati. Semua yang disayang dan dicintai pergi. Jika Maimunah yang dicintainya., Apakah gadis itu juga harus menjadi korban? Maimunah belum dua enam, seperti hal dirinya sendiri. Lelaki muda itu membayangkan, ia, insinyur, istrinya lulusan SD, orang warungan lagi. Bukankah itu seperti bumi dengan langit? Tetapi, sebenarnya ia sangat mengenal Maimunah dibandingkan gadis lain. Kalau Maimunah mencintainya, apalagi arti perbedaan itu? Maimunah bisa memasak, menjahit dan membantu pekerjaan sosial, sementara ia mengajar dan terus membangun desa.
Tetapi, bisakah itu?
Lelaki itu tersentak ketika ia turun dari oplet. Ternyata Maimunah sudah ada di depan rumahnya. “Kak,” kata wanita itu. “Ini Kak Yahya yang baru pulang dari Yogya. Kenalkan, Kak Muis, suami Maimunah.”
Matahari akhir Januari tak muncul dari balik tirai gerimis yang turun makin deras. Angin santer dan waktu melompat seperti nadi.
Udara gemetar.
Di arah jauh terdengar suara guruh…
Jakarta, 17 Januari 1983.
Rujukan:
[1] Disalin dari karya Korrie Layun Rampan (terpublikasikan di situs id.klipingsastra.com sekaligus guna mengenang beliau yang telah wafat pada hari kemarin -- Kamis, 19 November 2015)
[2] Pernah tersiar di surat kabar "Suara Karya" pada Minggu 13 Februari 1983
***
Bagi Anda yang gemar dengan bacaan sastra, baik yang berujud cerita pendek, cerita bersambung, puisi ataupun sajak, sila menuju situs dokumentasi id.klipingsastra.com ini. Salam.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H