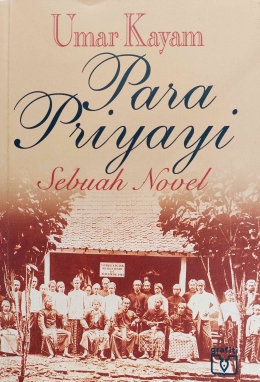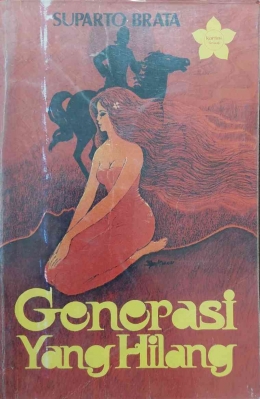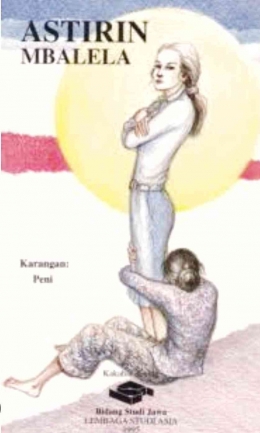Nama Suparto Brata tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan sastra Jawa modern karena karya-karyanya menunjukkan kualitas yang baik dan dari tangan pengarang inilah sastra Jawa modern mengenal genre cerita detektif. Suparto Brata memiliki kemampuan menulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
Suparto Brata, Priyayi, dan Wong Cilik
Suparto Brata, mantan pegawai Kantor Telegrap PTT (1952---1960), karyawan Perusahaan Dagang Negara Djaya Bhakti (1960---1967), wartawan freelance (1968---1988), pegawai negeri Pemda II Kotamadya Surabaya (1971---1988); mempunyai banyak kegiatan. Ia menulis berita, feature, ulasan, artikel dan cerita fiksi sejak tahun 1951; dimuat dalam majalah Siasat, Mimbar Indonesia, Kisah, Seni, Buku Kita, Sastra, Aneka, Vista, Sarinah, Kartini, Putri Indonesia, dan lain-lain.
Sedangkan harian/surat kabar yang memuat karya-karyanya antara lain Surabaya Post, Pikiran Rakyat, Trompet Masyarakat, Jawa Pos, Sinar Harapan, Indonesia Raya, Kompas, dan Republika.
Menulis fiksi dalam bahasa Jawa sejak tahun 1958 dan dimuat majalah Panjebar Semangat, Mekar Sari, Jaya Baya, Djaka Lodhang, Jawa Anyar, dan Dharma Nyata.
Suparto Brata dalam menulis karya sastra sering mengganti nama menjadi Peni, Eling Jatmiko, dan M. Sholeh. Nama-nama tersebut mengacu kepada kebudayaan Jawa dan Islam. Nama samaran Suparto Brata memiliki makna positif. Kata peni mempunyai arti 'anggun' dan 'indah'. Kata djatmika mempunyai makna 'selalu sopan santun'. Dengan demikian, nama Eling Jatmiko mengandung pengertian selalu ingat dengan sopan santun (bermoral). Sedangkan pengertian sholeh dalam agama Islam dikaitkan dengan ketaatan seseorang menjalankan ibadah.
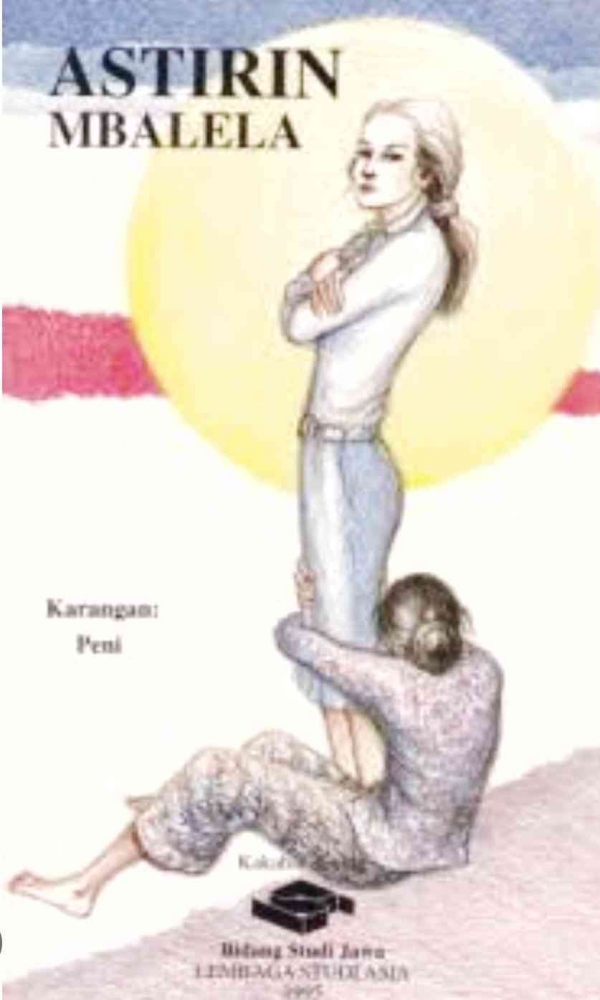
Penggantian nama merupakan hal biasa dalam sistem kepengarangan sastra Jawa.
Sapardi Djoko Damono (1998) bahkan menyatakan bahwa penggunaan (beberapa) nama samaran merupakan salah satu kebiasaan dalam sistem pengarang Indonesia sejak awal perkembangannya. Dalam dunia sastra Indonesia, Hamka pernah menyebut dirinya Aboe Zaky, Armijn Pane dengan Anom Lengghana, dan A. Rifai dengan UsEffNas.
Beberapa tulisan Suparto Brata berupa hasil riset dalam bentuk buku adalah Master Plan Surabaya 2000 (bersama Ir. Johan Silas, 1976); Sejarah Pers Jawa Timur (bersama Mochtar, 1987); dan Sejarah Panglima-panglima Brawijaya (1945-990) (diprakarsai oleh LIPI Jakarta dan Kodam Brawijaya, 1988).
Cerita fiksi Suparto Brata yang layak diperhitungkan antara lain "Tak Ada Nasi Lain" (1958), diterbitkan bersambung dalam Kompas, 1990. Novel Kaum Republik, awalnya merupakan naskah pemenang pertama sayembara cerita bersambung Panjebar Semangat, 1959, diterbitkan dalam bentuk buku oleh CV Ariyati, 1965, dengan judul Lara Lapane Kaum Republik.
Novel Sanja Sangu Trebela (dengan nama samaran Peni), ide ceritanya berangkat dari naskah drama Die Besuch der Alten Dame karya Friedrich Duerrenmatt, dimuat bersambung dalam Panjebar Semangat, 1965. Dibukukan CV Ariyati Surabaya, 1967, dicetak ulang Yayasan Penerbitan Djojobojo Surabaya, 1996.
Novel Sisa-Sisa Kemarin merupakan pemenang Harapan I sayembara menulis novel Dewan Kesenian Jakarta, 1974. Buku Jatuh Bangun Bersama Sastra Jawa (1980), merupakan pemenang Harapan I Naskah Bacaan Mahasiswa yang diadakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
Novel Kunanti di Selat Bali merupakan pemenang I Penulisan Novel Majalah Putri Indonesia, 1981 (kemudian diterbitkan Kartini Grup), dan disadur/diterbitkan dalam bahasa Cina oleh Prof. Ju San Yuan, 1989. Karya "Terjebak di Monitor" (1991), keluar sebagai pemenang Harapan II Sayembara Menulis Novel majalah Kartini, 1991. Cerita "Kremil" (1994); dimuat bersambung dalam Kompas, 1996.
Cerita "Solo Gelap Gulita", diindonesiakan dari "Solo Lelimengan" (1965); dimuat bersambung dalam Republika (1995) dengan judul "Buku Harian Seorang Perwira". Cerita "Saksi Mata" (1995), dimuat bersambung dalam Kompas, 1997---1998, dan diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, 2002.
Dari sisi kuantitas dan kualitas karya, sudah sepantasnya jika nama Suparto Brata tercatat dalam buku Five Thousand Personalities of the World (Sixth Edition, 1998) terbitan The American Biographical Institute, Inc., North California, USA.
Nama Suparto Brata mengacu kepada wilayah kebudayaan Jawa, apalagi jika Suparto Brata tidak enggan menuliskan gelar "Raden" di depan namanya. Hal ini bukanlah sesuatu yang berlebihan karena ia memang merupakan keturunan trah njeron benteng. Ayahnya, Raden Suratman Bratatanaya, dan ibunya, Raden Ajeng Jembawati, keduanya berasal dari Surakarta---diduga merupakan kerabat Kraton Mangkunegaran.
Suparta Brata menikahi gadis keturunan darah biru dengan gelar kebangsawanan "Raden Rara" Ariyati. Sebagai orang Jawa tulen, dalam menuliskan tanggal lahir pun Suparto Brata tidak lupa menyertakan weton-nya, yaitu Sabtu Legi, 27 Februari 1932 atau 19 Syawal 1862 Je.
Meskipun tergolong kaum bangsawan (priyayi), Suparto Brata tidak banyak mengedepankan persoalan-persoalan kepriyayian dalam karya-karyanya, hal ini berbeda dengan Umar Kayam---seorang priyayi ("Raden Mas" dari Kraton Surakarta) yang memandang sekitarnya dari sudut priyayi sehingga tokoh-tokoh yang diciptakannya, mulai dari "Chief Sitting Bull" sampai "Drs. Citraksa dan Drs. Citraksi", dimainkan dan dilihat dari sudut priyayi.


Di lain pihak, tokoh Suryapraba ditampilkan sebagai wakil sosok masyarakat tradisional, mengagungkan derajat kebangsawanan. Relasi oposisi kedua tokoh tersebut melahirkan beragam konflik, menciptakan berbagai tragedi.
Genduk Darmirin merupakan tokoh kontroversial dengan pengingkarannya terhadap pandangan orang Jawa (pinggiran) yang menganggap dunia priyayi sebagai bentuk puncak apa yang menjadi angan-angan mereka. Seorang perempuan dikatakan beruntung atau berhasil hidupnya jika mampu bergaul dekat dengan bangsawan (priyayi) dan melahirkan bayi keturunan mereka:: derajat kebangsawanan merupakan jaminan hidup, kekayaan, dan kekuasaan.
Penolakan terhadap derajat kebangsawanan secara semiotik mengisyaratkan bahwa Genduk Darmirin merupakan sosok wanita Jawa yang kritis terhadap kepincangan-kepincangan sosial, tidak begitu saja tunduk (nrima) sebagai seorang gadis Jawa yang diikat kuat oleh tradisi.
Lewat novel ini Suparto Brata menyatakan bahwa dunia kebangsawanan hanya mendewa-dewakan tata cara feodal; sikap dan tata cara yang seharusnya sudah lama dikuburkan. Dengan ketegasan sikap itu, maka jarang sekali (bahkan mungkin tidak ada) karya Suparta Brata lainnya (terutama yang bermediakan bahasa Jawa) mengungkap masalah kepriyayian; apalagi kehendak membela dunia kepriyayian.
Suparto Brata lebih fasih bercerita mengenai nasib wong cilik: bagaimana Saiman membunuh seorang wanita demi anaknya, Giya, yang kelaparan ("Slendang Bang-Bangan"), kesengsaraan Markam melayani Pak Tawangalun ("Wong Gedhe"), tragis dramatisnya cinta Dulmawi (tukang arloji Pasar Keputran) kepada Ijah ("Trem"), dan juru ketik yang terpaksa menjadi perampok untuk membahagiakan keluarga ("Rampog").
Kepiawaian Suparto Brata menampilkan sosok wong cilik berkorelasi dengan kehidupan keluarga yang cukup menderita: ibunya pernah menjadi pembantu rumah tangga, buruh batik, dan pengasuh anak. Suparto Brata berkumpul dengan ayahnya di Surabaya hanya sekitar enam bulan karena kedua orang tuanya kemudian berpisah, Suparto Brata dibawa ibunya menetap di Solo, sekitar empat tahun, kemudian pindah ke Sragen.
Banyak kejadian di Sragen yang membekas diingatan Suparto Brata. Menjelang tidur malam, ibunya sering mendongengkan cerita-cerita rakyat "Ande-Ande Lumut", "Jaka Tarub", "Endang Rara Tompe", dan sebagainya. Setelah masuk sekolah dan dapat membaca huruf Jawa, setiap berangkat tidur, ibunya selalu membacakan cerita "Menak" (macapat yang ditembangkan). Ketika duduk di kelas tiga SD, meskipun Suparto Brata belum lancar membaca huruf latin, tetapi ia sering meminjam buku di perpustakaan sekolah, dan orang lain diminta membacakan---sementara ia mendengarkan.
Menjelang Jepang masuk, ibunya melamar menjadi pembantu di kediaman Mr. Wongsonegoro, Bupati Sragen. Suparto dan ibunya kemudian tinggal di rumah keluarga Mr. Wongsonegoro. Ia mulai membaca buku (dari perpustakaan sekolah) Cinta yang Membawa Maut, Siti Nurbaya, Kalau Tak Untung, Percobaan Setia, Tiga Orang Panglima Perang, dan sebagainya. Selain senang membaca, Suparto Brata gemar menonton film spionase.
Tahun 1945---1947, bersama ibunya, Suparto Brata mengungsi ke Probolinggo ke tempat kakak satu-satunya, Suwondo (teknisi radio, pegawai perusahaan listrik dan gas). Suparto Brata masuk SMP di Probolinggo, dengan tetap melanjutkan kegemarannya membaca buku dari perpustakaan sekolah bersama sahabatnya Rubai Kacasungkana. Mereka selalu mendiskusikan buku yang mereka baca, antara lain Don Kisot, Sepanjang Jalan Raya, Anjing Setan, dan Graaf de Monte Christo.
Di sekolah, Suparto Brata termasuk anak pandai dalam ilmu pasti. Suwondo, kakaknya, selalu menekankan bahwa bidang teknik merupakan simbol kemajuan zaman dan teknisi adalah orang yang maju, hidup di garda depan. Meskipun Suparto Brata anak pandai, tetapi lama-kelamaan timbul kegelisahan terhadap bidang teknik dan mulai mencari alternatif. Lambat laun ia merasa bahwa sastra tidak kalah pentingnya dalam kehidupan.
Di Probolinggo hanya sekitar dua tahun, Suparto Brata kemudian pindah ke Surabaya bersama ibunya. Ia meneruskan sekolah di SMP Tempelstraat (Kepanjen), lulus tahun 1950. Ia dan ibunya kemudian pindah ke Solo dan mondok di rumah keluarga di Kemlayan, Keprabon. Waktu itu SMA St. Joseph dibuka, Suparto Brata masuk sebagai murid permulaan. Ia rajin datang ke perpustakaan rakyat di alun-alun, membaca majalah Siasat, Seni, Pedoman, Zenith, dan buku-buku Pramoedya Ananta Toer, serta mencoba mengirimkan cerita ke Mimbar Indonesia.
Karena keuangan tidak memungkinkan (ibunya bekerja sebagai buruh batik dan menjadi pengasuh anak), maka ia kemudian ke Surabaya naik sepeda mencari pekerjaan. Mula-mula bekerja di laboratorium rumah sakit kelamin (Jalan Dr. Sutomo), tetapi tidak kerasan.
Suparto Brata kemudian ikut kursus operator teleprinter PTT (1953), dan bekerja sebagai operator teleprinter kantor telegrap, Jalan Njagal, Surabaya. Kakaknya sepulang dari Belanda ditempatkan di Surabaya. Ibunya kemudian ditarik ke Surabaya dan mereka kemudian tinggal dalam satu atap (menyewa rumah di Keputran Kejambon). Suparto Brata kemudian meneruskan sekolah yang sempat terhenti, pagi sekolah dan siangnya bekerja. Waktu sekolah di SMAK St. Louis Surabaya, Suparto Brata mulai mengirim karangan ke Siasat, Mimbar Indonesia, dan lain-lain.
Tahun 1955, kakaknya dipindahkan ke Bandung dan ibunya sering berada di Bandung. Suparto Brata bertemu dengan Rubai, sahabatnya di Probolinggo--bekerja di Pabrik Semen Gresik sebagai penerjemah. Keduanya kemudian menempati rumah kontrakan di Rangkah 5/23B, karena RA Jembawati (ibunda Suparto Brata) memastikan menetap di Bandung. Tinggal bersama Rubai, Suparto Brata merasakan kebahagiaan tersendiri karena mereka mempunyai kesamaan hobi membaca dan berdiskusi.
Tahun 1956, Suparto Brata berhasil menyelesaikan sekolah. Rubai bekerja sebagai wartawan Surabaya Post dan karena pandai berbahasa Inggris, Suparto Brata belajar bahasa Inggris kepada Rubai.
Sementara itu terjadi pengusiran orang-orang Belanda dari Indonesia. Buku-buku milik Belanda--banyak buku bahasa Inggris yang diterbitkan untuk tentara sekutu ditinggal pergi pemiliknya--melimpah di loakan. Buku tersebut dijual sangat murah. Suparto Brata memborong buku-buku terbitan Pinguin bersampul hijau (crime and mistery).
Berkat buku tersebut, Suparto menjadi lancar membaca dan mulai mengenal Agatha Christie, Georges Simenon, Dorothy L. Seyer, dan masih banyak lagi. Untuk mengikuti perkembangan sastra Indonesia, Suparto berlangganan mingguan Siasat dan Mimbar Indonesia.

Tahun 1958 Suparto Brata mengikuti sayembara yang diadakan Panjebar Semangat. Karangannya berjudul "Kaum Republik" mendapat juara pertama. Sejak itu Suparto Brata berkenalan dengan redaksi Panjebar Semangat, yaitu Cuk Amiwarso, Subekti, Satim Kadaryono, dan lainnya.
Di samping itu, ia mulai berkenalan dengan para seniman/sastrawan Surabaya yang berada di sekitar Percetakan Nasional Surabaya (gedung tempat Panjebar Semangat berkantor). Pergaulan Suparto Brata dengan cerita Jawa kian kental, mengingatkannya pada bacaan terbitan Balai Pustaka, misalnya Ni Wungkuk ing Bendhagrowong, Ngulandara, Tarzan Kethek Putih, Ayu ingkang Siyal, Badan Sepata, dan sebagainya.
Menulis dalam bahasa Jawa bagi Suparto Brata merupakan kepuasan tersendiri karena saat itu tiras majalah berbahasa Jawa cukup tinggi, melebihi tiras majalah berbahasa Indonesia. Dengan demikian, jumlah orang yang membaca karangannya juga cukup banyak dan Suparto Brata mendapat berbagai tanggapan dari pembaca.
Hal ini menumbuhkan kebahagiaan tersendiri, ia semakin mantap sebagai penulis sastra Jawa. Dalam mengarang cerita, Suparto Brata sangat teliti. Semua konsep ditulis dengan tangan, kemudian baru diketik. Baginya, ini merupakan hal penting, utamanya kalau menulis cerita detektif. Dengan cara itu, hal-hal yang menjadi pemecahan persoalan, dapat disisipkan pada cerita yang di depan. Naskah dapat lebih matang sehingga sewaktu diketik tidak terdapat banyak kesalahan.
Cara menulis cerita dengan model ditulis tangan dijalaninya sampai tahun 1988, saat ia pensiun dari pegawai Kotamadya.
Untuk meningkatkan penghasilan, tahun 1960 Suparto Brata pindah kerja ke Perusahaan Dagang Negara Djaya Bhakti sebagai operator teleprinter. Di samping gajinya besar, pekerjaan di kantor dapat diselesaikan dalam waktu cepat; dengan demikian waktu luangnya dapat dipergunakan untuk mengarang. Di tempat kerjanya ini, Suparto bertemu Rara Aryanti, yang kemudian dinikahinya.
Tahun 1967, PN Djaya Bhakti mengadakan perampingan pegawai. Suparto ikut mengajukan permohonan berhenti. Waktu itu pergaulannya dengan Basuki Rachmat kian akrab. Dari Basuki Rachmat, Suparto Brata banyak belajar mengenai keterampilan menjadi wartawan (memotret, membuat berita, mengarang, dan bermain drama). Suparto Brata kemudian menjadi wartawan lepas, bersama Basuki Rachmat mengelola majalah Jaya Baya dan Gapura.
Tahun 1971, Suparto menjadi pegawai negeri (sebagai Humas) di kantor Pemda Surabaya. Penghasilan pokok dan penghasilan tambahan yang didapatkan dari menulis artikel dan cerita membuat ia dan keluarganya mampu hidup layak, mempunyai rumah bagus dan dapat membiayai pendidikan anak-anak.
Keempat anaknya, yaitu Tatit Merapi Brata, Teratai Ayuningtyas, Neo Semeru Brata, dan Tenno Singgalang Brata, semuanya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dan menjadi sarjana, hidup mandiri.
Tahun 1988 Suparto Brata pensiun dari pegawai negeri. Ia bekerja keras karena dari keempat anaknya baru satu yang lulus dari perguruan tinggi, itu pun masih menganggur, ditambah rumahnya di Rungkut Asri III/12 masih harus dicicil, jumlah cicilannya persis sama dengan uang pensiun. Keterampilannya sebagai pengarang dan wartawan benar-benar membantu Suparto Brata mengatasi kesulitan keuangan.
Akhir tahun 1989 ia diajak Aswendo Atmowiloto mengelola majalah Praba di Yogyakarta (bekerja di Yogya untuk mempersiapkan penerbitan Praba selama satu tahun lebih, namun akhirnya harus menyerah karena terbentur pada SIUP).

Embrio cerita detektif dalam sastra Jawa berupa cerita alap-alapan yang terdapat dalam cerita pewayangan, antara lain cerita Alap-alapan Siti Sundari, Alap-alapan Rukmini, Alap-alapan Banowati, dan Alap-alapan Surtikanti.
Kata alap-alapan berasal dari kata alap yang memiliki arti '(meng-) ambil'. Dalam konteks pembicaraan ini, cerita alap-alapan berarti cerita yang mengisahkan penculikan (pengambilan) seorang puteri untuk diperistri.
Cerita alap-alapan disebut sebagai prototipe cerita detektif Jawa karena di dalamnya terdapat unsur penjahat (penculik), sasaran kejahatan/penculikan (perempuan), tokoh pelacak, dan cerita penculikan itu sendiri yang dominan dan menentukan perkembangan cerita. Pasca cerita alap-alapan, hadir karya Jasawidagda, Jarot (Balai Pustaka, 1931), berkisah mengenai penangkapan penjual candu gelap --menceritakan penyamaran tokoh Jarot sebagai mata-mata.
Kemudian terbit Ni Wungkuk ing Bendha Growong, menceritakan keberhasilan Ni Wungkuk mengungkap rahasia kejahatan. Selain itu, hadir pula cerita Tri Jaka Mulya, Kembang Kapas, dan Gambar Mbabar Wewadi yang kesemuanya memperkuat hadirnya prototipe cerita detektif dalam sastra Jawa.
Kedekatan Suparto Brata dengan dunia cerita detektif melewati proses panjang. Sampai pada suatu ketika, ia berkeyakinan bahwa roman detektif berbahasa Jawa belum pernah ada sebelum ia mengarang serial detektif Handaka. Baginya---dalam bacaan berbahasa Jawa---yang ada hanyalah roman kejahatan; yaitu roman yang bercerita tentang tindak kejahatan.
Pernyataan tersebut mendapat kritisi dari beberapa pengamat sastra Jawa karena pada tahun 1956 dan 1957 telah terbit cerita bersambung "Warisan Macan Kumbang" (Soekandar S.G., Jaya Baya, 18 Maret---3 Juni 1956) dan "Lulus ing Pendadaran" (Soekandar S.G., Jaya Baya, 7 April---9 Juni 1957), menampilkan bentuk cerita detektif.
Ditinjau dari segi waktu, Soekandar S.G. telah menulis terlebih dahulu dibandingkan Suparto Brata. Apalagi antara "Warisan Macan Kumbang" dan "Pethite Nyai Blorong" (Suparto Brata, 1965) terdapat persamaan teknik pemecahan misteri. Persamaan teknik ini mengundang kesangsian terhadap pernyataan Suparto Brata. Bahkan, sebelumnya telah hadir karya-karya yang mengandung episode tindak kejahatan dan pelacakan, terlihat dalam Sukaca (Sastradiardja, 1923) dan Mungsuh Mungging Cangklakan (Asmawinangun, 1926).
Di sisi lain, Suparto Brata menjelaskan bahwa roman kejahatan berbahasa Jawa biasanya dipukul rata, disamakan dengan roman detektif Tri Jaka Mulya, Kepala Kecu, Kembang Kapas, Gambar Mbabar Wewadi---kisah dan teknik penelusuran kejahatan dan bagaimana tindak kejahatannya bisa terbongkar umumnya terselesaikan dengan "gampang-gampangan", bukan merupakan hasil penalaran atau pemikiran/penyelidikan, melainkan hanya merupakan peristiwa "kebetulan".
Titik-titik kejahatan, "kebetulan" ditemukan oleh pelaku utama. Bila judul bukunya saja Gambar Babar Wewadi ('Lukisan Membuka Rahasia'); tentunya pembaca sudah dapat menebak bahwa misteri kejahatan akan terkuak oleh sebuah lukisan!
Suparto Brata mendefinisikan cerita detektif sebagai cerita tentang kejahatan yang berkisar dan lebih mengupayakan bagaimana melacak serta membuka tabir rahasia kejahatan.
Detect (bahasa Inggris) berarti mengetahui, menggeledah, menelusur, dan menjumpai. Detektif adalah sersi (searcher), juru geledah, juru sidik. Detector berarti alat untuk menemukan rahasia. Dengan demikian, roman detektif sejati berarti cerita atau kisah yang mengupayakan hal-hal penyidikan atau menelusur teknik untuk menemukan penjahat.
Dalam bacaan berbahasa Jawa (sebelum Suparto Brata menulis roman detektif), yang ada hanyalah roman kejahatan, yaitu roman yang bercerita tentang tindak kejahatan. Roman yang bercerita tentang tindak kejahatan yang menjadi sumber penulisan roman detektif Suparto Brata cukup banyak.
Sejak duduk di kelas empat sekolah Angka Loro, Suparto Brata---yang lebih lancar membaca huruf Jawa (hanacaraka) dari pada huruf latin (gedrik)---mulai membaca roman kejahatan berbahasa Jawa, salah seorang pelakunya bernama Kyai X. Meskipun tokoh tersebut bukan polisi, namun secara misterius berhasil menggagalkan kejahatan.
Selain itu, Suparto Brata membaca novel Ni Wungkuk ing Bendhagrowong (Jasawidagda, 1938), Topeng Mas, dan Kacu Sandi. Ni Wungkuk ing Bendhagrowong bercerita mengenai seorang wanita tua (Ni Wungkuk) penderita kusta---dijauhi oleh masyarakat-- yang berhasil menggagalkan tindak kejahatan.
Novel Topeng Mas terdiri dari tiga jilid, menggunakan huruf Jawa dengan ragam ngoko, bercerita tentang tiga orang prajurit dari kerajaan Turki, yaitu Hasanbei, Suranbei, dan Sardibei, maju dalam peperangan dan berhasil menundukan lawan-lawan mereka karena mendapat "petunjuk" dari seseorang yang wajahnya tertutup topeng berwarna kuning emas.
Pada akhir cerita, Sardibei terkena kutuk karena setelah berhasil merampas harta beserta puteri kerajaan, ia tidak lagi "memperhatikan" topeng mas. Cerita Topeng Mas disisipi kejadian-kejadian mencekam sekaligus mengejutkan: putri keraton yang baik hati mendapat fitnah sehingga dikubur hidup-hidup; suatu ketika putri yang baik hati itu keluar dari kubur menuntut balas.
Setelah kemerdekaan, Suparto Brata membaca beberapa buku roman kejahatan, antara lain Gerombolan Gagak Mataram dan Gerombolan Mliwis Putih. Buku-buku tersebut, menurut Suparto Brata, memiliki model cerita jauh dari kisah-kisah detektif, apalagi jika dibandingkan dengan cerita Kyai X. Hal itu terjadi karena Gerombolan Gagak Mataram dan Gerombolan Mliwis Putih lebih mengetengahkan cerita bagaimana cara memberantas kejahatan dari pada menggunakan penalaran memecahkan misteri kejahatan.
Cerita detektif yang dihasilkan Suparto Brata dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu cerita detektif seri Handaka dan cerita di luar seri Handaka. Beberapa cerita detektif seri Handaka adalah: (1) Tanpa Tlacak (semula merupakan cerita bersambung dalam majalah Panjebar Semangat, 1959, diterbitkan dalam bentuk buku oleh CV Pustaka Sari, Surabaya, 1962); (2) Emprit Ambuntut Bedhug (dimuat secara bersambung dalam Panjebar Semangat, 1960, diterbitkan oleh Penerbit Djaja Baja, 1965); (3) Tretes Tintrim (dimuat bersambung dalam Jaya Baya, 1965, diterbitkan dalam bentuk buku oleh Penerbit Lawu, Solo, 1967); (4) Jaring Kalamangga (dimuat bersambung dalam majalah Jaya Baya, 1965); dan (5) Garuda Putih (dimuat bersambung dalam Panjebar Semangat, 1974).
Di luar novel seri Handaka, hadir novel Pethite Nyai Blorong, "Candikala" (Suparto Brata menggunakan nama samaran Andanawarih), Ngalacak Ilange Sedulur Ipe (dengan nama samaran Peni), Sala Lelimengan, dan beberapa cerkak/cerpen yang termuat dalam antologi Trem (Pustaka Pelajar, 2000).

Unsur "pelacakan" terdapat dalam cerkak "Trem", menceritakan bagaimana keinginan Dulmawi (tukang arloji di Pasar Keputran) berkenalan dengan seorang perempuan yang selalu satu trem dengan dia. Cerkak "Trem" memperlihatkan kedekatan pengarang dengan wilayah geografis dan sosial. Suparto Brata mengetahui secara detail wilayah Surabaya dan mampu menggunakan dengan luwes dialek Jawatimuran dalam cerkak tersebut.
Pemanfaatan suspense (dengan menyembunyikan siapa sesungguhnya Ijah) merupakan salah satu ciri cerita detektif yang memberikan informasi sedikit demi sedikit agar menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap penyelesaian cerita.
Hal yang sama ditemui dalam cerkak "Nglari Nakagawa"; pengarang tidak memberitahukan kepada pembaca siapa sesungguhnya Repi --perempuan yang disinyalir berkaitan dengan kepergian Nakagawa; siapa sesungguhnya orang kurang waras yang selalu berada di atas jembatan desa sehingga mengetahui siapa saja yang keluar masuk desa. Hilangnya Nakagawa merupakan misteri, membuat cerita menjadi mencekam. Pengaruh cerita detektif terasa kuat dengan adanya pelacakan yang dilakukan Merto terhadap kepergian Nakagawa.
Cerkak lain yang menarik dan mendatangkan polemik adalah "Rampog". Cerkak ini menjadi perbincangan dalam diskusi bulanan Nyemak Crita Cekak yang diadakan oleh Sanggar Triwida tahun 1981. Diskusi bulanan Nyemak Crita Cekak selalu membicarakan cerita-cerita pendek yang dianggap menarik dan dimuat dalam majalah Jaya Baya atau Panjebar Semangat. "Rampog" dijadikan pilihan karena di samping ceritanya bagus; pengarangnya pun dinilai cukup terkenal.
"Rampog" bercerita mengenai juru ketik (wong cilik) bernama Somad yang jujur dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia harus menghidupi seorang isteri dan empat orang anak. Ditambah lagi kewajiban memikirkan uang sekolah, gizi anak-anak, dsb. Meskipun ia mempunyai pekerjaan sampingan sebagai agen majalah dan koran, menerima jasa pengurusan SIM serta STNK, semua itu tidak cukup menutupi keperluan sehari-hari.
Karena terdesak keadaan dan "bisikan" untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya ia mengambil jalan pintas: merampok! Pekerjaan ini melahirkan perang batin karena ia dikenal sebagai orang jujur.
Secara makro, "Rampog" merupakan perwujudan kritik sosial pengarang terhadap berbagai peristiwa/kenyataan yang terjadi dalam masyarakat: tergerusnya nasib wong cilik dalam hiruk-pikuk pembangunan, buruknya dunia pendidikan di Indonesia, ancaman kemajuan teknologi (karena kebodohan bangsa Indonesia), dan kurang efektifnya kerja polisi dalam mewujudkan keamanan bagi masyarakat luas.
Cerkak dengan teknik sorot balik ini berhasil membawa pembacanya "berlarian" dari satu permasalahan ke permasalahan lain secara dinamis sehingga cerkak ini tidak sekedar hadir sebagai potret dunia hitam---putih. Setidaknya pembaca bisa memperdebatkan siapa sesungguhnya yang mengajak Somad merampok: apakah orang lain (perampok profesional), bayangan dirinya sendiri, atau hati nuraninya (?).
Somad disudutkan oleh kebutuhan, tidak hanya terbatas pada kebutuhan hidup keluarga tetapi juga karena harus mengundurkan pagar akibat terkena pelebaran jalan. Tidak mengundurkan pagar berarti "melawan" penguasa, jika mengundurkan pagar tidak punya biaya; hutang pun tidak mungkin lagi. Pikiran Somad menjadi buntu, kalut, putus asa, sehingga ia berniat bunuh diri dari atas jembatan. Pada saat kritis itulah "ilham" atau "bisikan"datang.
Dalam keselurahan cerita, Somad berada di dua dunia: dunia nyata (kesadaran) dan dunia tak nyata (ketaksadaran). Dunia ketaksadaran memunculkan "kejanggalan-kejanggalan" yang seharusnya tidak perlu dipersoalkan ketika pembaca menyadari bahwa dunia "Rampog" adalah dunia fiksi dengan berbagai kemungkinan, bukan kepastian.
Dalam dunia ketaksadaran bisa saja Somad yang juru ketik tiba-tiba menjelma menjadi perampok, mampu menggunakan senjata api dengan tangan kiri (meskipun ia tidak pernah belajar cara menggunakan senjata api), mengikuti kata hati menjadi perampok, menyebar uang hasil rampokan tanpa rasa bersalah. Relasi Somad dengan dunia orang-orang kantor adalah relasi realita, sedangkan relasi Somad dengan dunia rampok adalah relasi irasional. (Herry Mardianto)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H