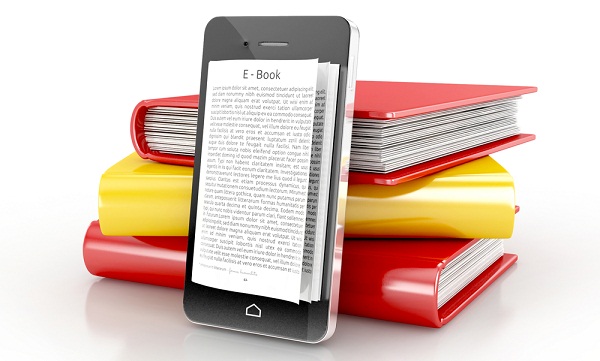"Bagi seorang yang hidup dalam pikiran yang mesti disebarkan, baik dengan pena maupun dengan mulut, perlulah pustaka yang cukup." -- Tan Malaka dalam Madilog.
Dari komunitas stand-up comedy saya pernah belajar ini: bahwa setiap orang punya selera humor masing-masing, terlepas bagaimana mereka membuat atau menerima sesuatu yang kerap dianggap lucu dan menggelitik. Dan entah mengapa, bagi saya, Tan Malaka punya selera humor yang sangat baik --setidaknya elegan di mata saya. Sudah tentu alasannya adalah dalam beberapa hari terakhir ini , saya sendiri tidak tahu terkena angin apa, membaca Madilog.
Tidak. Tidak dalam versi cetak, namun digital di sebuah situs. Sepertinya sekarang biasa-biasa saja membaca Madilog di sembarang tempat. Saya malah pernah lihat seorang dengan khidmat membaca itu di kereta. Dengan kaki diangkat satu dan bersender di bahu bangku. Terlihat Nnkmat lha.
Jelas berbeda dengan masa-masa orde baru. Karena saya pernah dapat cerita ini: masa di mana mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan, selalu ada pemeriksaan oleh aparat. Bagi yang tertangkap tangan masih terlibat dalam bentuk apapun itu, baik gerakan atau sekadar kenal dengan para Komunis --termasuk pembaca buku-buku kiri, termasuk Madilog-- akan ditangkap. Tanpa terlebih dulu diadili di pengadilan. Tas sudah pasti dikeluarkan isinya. Jaket atau almamater mesti dilepas. Makanya untuk mengakali itu, ada yang sampai menempeli buku itu di badan dengan menggunakan solatip. Aman. Setidaknya saat itu keberuntungan masih berpihak padanya.
Dari membaca Madilog itulah akhirnya saya temukan sisi humoris dari Tan Malaka. Baru masuk Pendahuluan saja, Tan Malaka sudah mendelegasikan kerangka pikirnya pada pembaca. Seperti yang kalian tahu, Madilog banyak ditulis saat Tan Malaka dalam pelariannya dari Indonesia. Kita dibawa oleh Tan Malaka dari satu tempat ke tempat lain dengan ketegangannya masing-masing. Rusia, Vietnam, Hongkong sampai Singapura. Sampai pada satu ketika, Tan Malaka mesti pergi ke suatu tempat untuk pelariannya, tapi tanpa membawa banyak buku. Pada saat itu Tan Malaka seakan jadi malu sendiri. Maka dalam pendahuluan Madilog yang Tan Malaka tulis adalah:
"Bagi seorang yang hidup dalam pikiran yang mesti disebarkan, baik dengan pena maupun dengan mulut, perlulah pustaka yang cukup."
Ada kegetiran. Ada keresahan yang Tan Malaka rasakan. Lebih-lebih saat ia tahu apa yang dilakukan Bung Hatta atau Leon Trotsky selama di tempat pembuangan. Trotsky ke Alma Aja; sedangkan Bung Harta ke hampir tiap pembuangannya di mana pun. Karena mereka berdua itu selalu membawa buku berpeti-peti. Tan Malaka tahu. Tan Malaka juga sadar sikap kedua pemimpin itu. Tan Malaka menyesali tidak bisa berbuat seperti mereka. Dan selalu gagal mencoba seperti begitu.
Membayangkan itu, saya tergelitik sendiri. Bahwa seorang Tan Malaka pun bisa iri kepada oranglain. Iri dengan cara yang dingin. Sebab ia sendiri mengakuinya.
Andai pada masa itu teknologi sudah berkembang seperti sekarang, mungkin dalam pelariannya Tan Malaka tetap bisa membawa berpeti-peti buku, namun dalam format digital. Hanya yang jadi persoalan kemudian adalah seberapa besar memori yang ia punya?
***
Satu-satunya musuh bagi orang yang berkarya adalah pembajak. Mereka, si pembajak itu, seakan tidak bisa dimusnahkan. Hilang satu, tumbuh seribu. Malah ada satu frasa seperti ini: di mana ada karya, di situ pula tersedia bajakannya. Yang selalu jadi persoalan dan tantangan adalah bagaimana menyakapi pembajakan ini?
Jika pernah membaca laporan panjang Dea Anugerah yang berjudul "Berkebun di Tengkulak Penulis", kita akan disajikan hal menarik. Bahwa di negara Peru, tahun 2009 tepatnya, pernah ada razia besar-besaran yang dilakukan sebuah Konsorsium Penerbit dan Kepolisian setempat. Buku-buku bajakan disita dari pembajak sebanyak 90 ribu eksemplar jumlahnya. Jika dihitung, dalam harga buku bajakan itu, senilai 348 ribu dolar Amerika Serikat. Angka yang amat fantastis bagaimanapun.
Namun yang kemudian jadi kendala adalah barang sitaan itu hanya memenuhi gudang di pengadilan. Sampai tiga bulan lamanya, jika ingatan saya tidak berkhianat mengingat. Tidak ada tindak untuk itu, jadi pengadilan belum berhak membakar atau memcacah buku-buku itu menjadi bubur kertas sekalipun. Malah diusulkan untuk disumbangkan ke sebuah program pemerintah Peru yang bergerak dibidang pendidikan.
Entah bagaimana caranya, semacam ada permainan antara pembajak dan pengadilan, buku-buku sitaan itu kembali ke rak-rak tepat di mana semula buku itu disita!
Kini pembajakan buku, saya kira, menjadi salah satu "lahan basah" sebenarnya. Ketika pemerintah kadung tidak bisa mengatur harga buku, di sana "pemain buku ilegal" senang. Negara India, yang mayoritas skala ekonominya sedikit di bawah Indonesia saja pemerintahnya masih peduli terhadap sirkulasi harga buku. Jika dibandingkan dengan kita, satu berbanding lima. Harga satu buku di Indonesia, setara dengan lima buku di India. Mahal. Lebih tepatnya, harga satu buku di sini sama halnya dengan segelas kopi di gerai-gerai warung kopi asing.
Mesti ada upaya untuk mencegahnya. Atau, paling tidak merendahkan angka pembajakan itu. Menggalakan buku digital, misalnya?
***
Semasa kuliah, ada satu tempat favorit saya jika tidak punya uang: toko buku. Karena tidak punya uang, sudah bisa dipastikan saya ke sana tidak untuk membeli. Sekadar datang, pilih-pilih buku, baca yang tidak tertutup plastik, dan mencatat harga buku yang sekiranya ingin saya beli.
Tatkala sedang melihat buku dan mencatat harga di bagian belakang buku, seorang petugas pernah menghampiri. Ia bertanya, "cuma nyatet harga saja, mas? Tidak beli?"
Diam dan membalasnya dengan senyum terburuk yang saya punya. Itu saja yang saya bisa. Malu, sudah tentu; tapi masa menyalahkan keadaan. Bisa baca beberapa sinopsis dan buku yang terbuka dengan cuma-cuma, buat saya itu jauh lebih dari cukup.
Ini sering. Ketika saya sudah mengumpulkan uang, buku yang saya ingin beli, sudah tidak dijual di toko buku jaringan besar itu. Internet adalah dunia gelap yang saya takut datangi. Entah bagaimana regulasi buku di toko buku dengan jaringan terbesar itu bekerja. Yang jelas, dalam waktu dua atau tiga bulan, buku itu raib dari rak buku mereka.
Akal-akalan saya ketika itu hanya mencari bedah bukunya. Jika diadakan di Bogor, pasti saya datangi. Jika di luar Bogor, saya masih pertimbangkan. Sebab kadang malah buku itu saya dapat cuma-cuma a.k.a gratis.
Dan kalau bukan tugas kuliah, barangkali saya tidak tahu kalau buku yang dicetak juga tersedia bentuk digitalnya. Saat itulah saya rajin ke warnet untuk mengunduhnya secara gila.
***
Kalau dihitung-hitung, tahun ini adalah tahun ke-4 saya bersama teman-teman di perpustakaan Teras Baca secara rutin membuat buku digital setiap tahunnya. Saat ini baru mampu satu buku saja memang. Tapi namanya juga usaha, ada yang progresnya cepat, lambat dan di situ-situ saja. Saya termasuk yang terakhir tentunya.
Konsisten itu mudah, yang sulit adalah menjaganya. Semangat mengkonsep buku itu tidak segampang merancang masa depan bersama pasangan yang pada akhirnya berakhir menjadi angan-angan. Apalagi jalur yang saya dan teman-teman di perpustakaan Teras Baca adalah buku digital. Selain karena tidak punya biaya produksi buku cetak, kami sadar, buku yang kami hasilkan belum layak untuk dicetak. Paling tidak karya kami tidak ingin sekadar menyia-nyiakan pohon yang dipotong demi satu eksemplar buku. Bumi ini masih butuh paru-paru.
Itu saya bagikan secara gratis. Cukup unduh, lalu bisa langsung dibaca. Namun hanya tahun ini saja saya coba mengubah cara pemasarannya. Buku digital kami "sebenarnya gratis", sebab tidak ada transaksi jual-beli untuk bisa memilikinya. Namun, saya tengah mencoba melibatkan perantara lain, pihak ketiga, pay with tweet, namanya. Jadi setiap orang yang ingin membaca buku digital buatan perpustakaan teras baca cukup membayarnya dengan sebuah cuitan. Lumayan dan efektif hasilnya saya kira.
Pada bulan Maret - April 2016, Pew Reserch Center di Amerika Serikat membuat riset untuk Digital Book Year 2016. Mereka meneliti tentang tingkat pola jenis pembaca. Didapat hanya sekitar 6% yang benar-benar membaca buku digital (red: buku digital di sana juga termasuk audio book). Selebihnya, 28% membaca buku cetak dan digital, 38% hanya membaca buku cetak saja. Dan 26% membaca non-buku (red: koran, majalah, dan lain sebagainya)
Tanpa melihat berapa jumlah korespondensi, 6 porsen saya kira angka yang cukup besar. Di Indonesia, barangkali, buku digital hanya alternatif belaka. Tapi bila suatu saat nanti susah lahir industri buku digital, harapan saya, juga teman-teman di perpustakaan teras baca adalah kami masih konsiten dan ikut dalam ombak industri buku digital tersebut. Semoga. Intinya, konsiten dulu saja.
***
Ada kalanya saya tidak ingin bawa buku ke mana-mana. Selain karena cuaca hijan dan takut bukunya basah lalu rusak, maksudnya tangan ini pun ingin digunakan untuk menggandeng tangan seseorang. Tapi apa daya, jika sedang di kereta, (tangan) saya hanya dipakai untuk membaca lewat layar gawai. Menjadi sendiri ketika kereta tak pernah sepi.
Mengaktifkan paket data pada gawai selama perjalanan, sama artinya melibatkan diri pada jejaring sosial yang ada di gawai itu sendiri. Bukan tidak ingin terlibat di sana, namun semua ada waktu dan tempatnya masing-masing. Pada saati itulah saya hanya ingin membaca. Buku-buku digital terlebih dulu saya unduh, yang kemudian saya baca selama perjalanan.
Bukan beruntung, sih, tapi kemajuan teknologi yang mau-tidak-mau hadir saat saya membutuhkannya. Awalnya saya menggunakan aplikasi-aplikasi baca yang ada. Namun, apa boleh dipunya, gawai milik saya minim kapasitasnya. Satu aplikasi ditambah beberapa buku digital, memori gawai kadung penuh. Beberapa aplikasi sudah dihapus, masih saja penuh. Akan selalu ada yang dikorbankan dari sesuatu yang kita inginkan bagaimanapun.
Tapi hampir satu bulan ini saya belangganan premium di SCOOP. Harganya relatif murah: 89ribu. Cukup unduh aplikasinya, saya bisa unduh ribuan buku yang saya inginkan. Baiklah, itu berlebihan. Sebab saya hanya mengunduh 70 buku. Lumayan. Buku-buku yang awalnya sekadar sanggup saya pandangi jika melintas toko buku jaringan besar, kini dengan mudah saya baca.
Oiya, tidak hanya itu. Bila berlangganan premium, setiap akun yang digunakan bisa digunakan oleh lima orang. Jadi, yha seperti membuat semacam perpustakaan digital yang bisa diakses oleh teman atau keluarga. Lumayan. Namun sayang, jika sudah tenggat waktu, buku-buku yang sudah diunduh tidak lagi bisa dibaca. Ada dua pengecualian untuk itu: lanjut berlangganan atau beli secara reguler.
Saat di mana semua bergerak dengan gegas, saya kira membaca buku digital adalah koentji di era kiwari.
Perpustakaan Teras Baca, 8 Desember 2016
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H