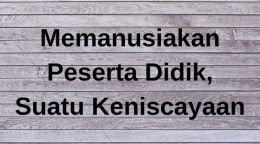Seperti yang saya sudah ulas di artikel dengan judul 21 Tahun Perenungan, Mengabdi sebagai Guru di Tengah Keterbatasan, saya terpaksa blusukan untuk bertemu orangtua murid, menanyakan kenapa putra-putri mereka tidak masuk sekolah alias bolos, kenapa tidak membuat PR, dan kenapa orangtua tidak datang ke sekolah, padahal ada surat panggilan dari saya.
Dari sekian banyak blusukan yang saya lakukan, 3 pengalaman ini tak terlupakan di benak saya.
Selain saya merasa, bahwa ini menyentuh sisi kemanusiaan, juga karena sebagai guru, tidak bisa menghakimi anak itu malas semata karena dari sisi sang anak. Mungkin ada faktor yang melatarbelakangi, seperti faktor ekonomi keluarga, latar belakang anak tinggal dengan kakek atau nenek, atau masalah lainnya.
1. Vanessa, bukan nama sebenarnya
Saya lupa tanggal, bulan, dan tahun terjadinya.
Yang saya ingat adalah murid saya ini berada di kelas lima saat itu.
Yang menjadi masalah waktu itu adalah anak ini sering tidak membuat PR, padahal saya hanya memberi lima nomor soal, untuk waktu seminggu.
Pertimbangan, karena pasti mereka, para murid sudah mendapat banyak PR dari guru kelas mereka, baik itu PR Matematika, IPS, IPA, dan lain sebagainya (momen ini terjadi di saat masih menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)).
Itu pun, biasanya saya memberi 5 nomor soal Pilihan Ganda (PG) atau Isian, sehingga tidak membebani peserta didik.
Dengan waktu seminggu, tingkat kesukaran soal yang standar, serta teman sekolah yang bisa membantu, sebenarnya tidak ada alasan bagi siapa pun untuk tidak mengerjakan PR.
Saya juga tidak menghukum peserta didik kalau tidak membuat PR, karena menurut saya, buang-buang waktu memarahi murid. Yang rajin jadi tersisihkan.
Saya menggunakan Buku Bimbingan dan Konseling seperti saran pengawas, menulis nama sang anak, dan pelanggaran apa yang dilakukan, lalu meminta sang anak membubuhkan tanda tangan atau menuliskan nama di buku itu.
Misalnya, Vanessa; pelanggaran : baru sekali tidak membuat PR; alasan : lupa mengerjakan.
Setelah itu, saya menasihati supaya rajin mengerjakan PR.
Nah, Vanessa ini sudah tiga kali tidak membuat PR, dan juga tiga kali bolos, di jam pelajaran saya. Saya pun sudah melayangkan surat, ke wali murid, karena ternyata Vanessa tinggal bersama paman, adik ayahnya.
Saya pun mengirimkan surat panggilan lewat Santi, teman sekelas Vanessa, yang rumahnya dekat dengan rumah Vanessa.
Karena paman Vanessa tidak datang esok paginya, saya meminta tolong sepupu Vanessa yang kebetulan sekelas dengan Vanessa, Intan (bukan nama sebenarnya), untuk mengantarkan saya bertemu dengan ayahnya yang juga paman Vanessa, yang menampung Vanessa di rumahnya.
Saya mengantarkan Intan pulang, dan kalau pun tidak bertemu dengan paman Vanessa, bertemu bibinya pun tidak masalah, pikir saya.
Untungnya, ayah dan ibu Intan atau dalam hal ini, paman dan bibi Vanessa, mereka berdua ada di rumah.
Saya cukup terkejut melihat kondisi rumah dari orangtua Intan ini.
Rumah terbuat dari kayu, atap seng tanpa plafon (bisa dipastikan luar biasa panasnya di saat tengah dan siang hari, di waktu terik matahari), dan waktu saya duduk di alas terpal yang terhampar di lantai, saya merasa, permukaan lantai tidak rata. Saat saya meraba terpal dan berusaha meluruskan, saya baru sadar, kalau di bawah terpal itu adalah tanah. Permukaan tanah!
"Maaf, Pak, saya tidak bisa datang ke sekolah pagi ini, karena saya bekerja," Pak Tejo, sebut saja begitu, meminta maaf terlebih dahulu, sebelum saya bertanya, seakan tahu kalau saya akan menanyakan itu.
"Kalau istri bapak?" tanya saya langsung.
"Istri saya ngurus anak saya yang bayi, Pak."
"Oke. Begini, Pak. Keponakan bapak dan ibu sudah tiga kali tidak membuat PR dan bolos juga sudah tiga kali di saat jam pelajaran saya."
"Iya. Nessa memang sering sakit, Pak. Kalau tentang PR, kami tidak tahu kalau dia tidak membuat PR," jawab Bu Ani, bukan nama sebenarnya.
"Yah, saya minta tolong pada bapak dan ibu, untuk memperhatikan pendidikan keponakan Anda, dan juga Intan, anak Anda. Sayang, kalau tidak naik ke kelas enam, dikarenakan malas belajar dan sering membolos," cuma itu yang saya katakan dan saya pun mengakhiri.
2. Rudi, bukan nama sebenarnya
Kebetulan, saya mempunyai salah satu murid lagi, bernama Rudi, sebut saja begitu, yang rumahnya di atas bukit, setelah rumah Vanessa. Jadi setelah dari rumah Vanessa, saya beranjak ke rumah Rudi.
Rudi juga mempunyai masalah yang sama dengan Vanessa.
Tidak membuat PR lebih dari tiga kali, sering tidak masuk sekolah pas jam pelajaran saya, dan orangtua tidak datang menghadap saya walau sudah menerima surat panggilan.
Apesnya, waktu itu lagi musim hujan, jadi jalan menuju bukit sangat licin, karena jalan berupa tanah lempung yang becek.
Tapi keadaan tersebut tak menyurutkan saya untuk datang ke rumah orangtua Rudi.
Kondisi rumah?
Kalau menurut saya, lebih memprihatinkan daripada rumah Vanessa.
Kayu rumah yang sudah lapuk, kondisi di dalam rumah yang gelap dan pengap, dan kondisi rumah itu adalah rumah panggung. Itu pun menumpang di tanah milik orang lain. Mereka minta ijin untuk membangun rumah dan menetap di situ. Pemilik tanah mengijinkan.
"Saya minta maaf, Pak, kondisi rumah kami tidak memadai," sang ibu memohon maaf.
"Tidak apa, Bu," jawab saya pendek, merasa tidak enak, karena baik ayah maupun ibu Rudi terkesan malu, sebab saya, guru anaknya, datang ke rumah mereka.
Saya pun mengutarakan kenapa saya datang, "Anak ibu dan bapak sudah tiga kali tidak membuat PR, dan juga sudah tiga kali tidak masuk sekolah pas pelajaran saya."
"Iya, Pak, dia juga sudah bilang ke kami. Kami tidak sanggup membelikan buku pelajaran. Suami saya cuma kuli bangunan. Upah tak seberapa. Saya cuma ibu rumah tangga. Masih mengurus bayi, adik Rudi. Tidak bisa bekerja di luar rumah," jawab sang ibu.
"Tapi kan ibu dan bapak bertetangga dengan Intan dan Vanessa. Rudi bisa pinjam buku Intan."
"Kami malu kalau pinjam terus menerus. Tergantung pada orang lain."
Saya terdiam. Biarpun mereka miskin, mereka tidak mau tergantung pada orang lain. Tidak mau dikasihani. Harga diri mereka tercederai karena itu.
"Begini saja, Bu," setelah lama hening, saya membuka suara, "Saya akan berikan fotokopi buku pelajaran ke Rudi besok pagi, supaya Rudi bisa belajar. Buku pelajaran bahasa Inggris saja. Saya fotokopi, karena buku-bukunya sudah ditarik semua sama penerbit."
"Berapa harganya, Pak?" tanya sang ibu.
"Bapak dan ibu tidak perlu membayar. Gratis. Saya ikhlas memberikan. Supaya Rudi bisa belajar, tidak tergantung pada orang lain."
"Terima kasih banyak, Pak," jawab ibu dan bapak Rudi bergantian. Sampai keluar rumah pun, mereka berdua tak henti mengucapkan terima kasih.
3. Hadi, bukan nama sebenarnya
Di hari yang berbeda, saya mengunjungi rumah orangtua Hadi.
Masalah Hadi juga sama dengan Vanessa dan Rudi.
Tiga kali tidak membuat PR dan tiga kali juga bolos waktu jam pelajaran saya.
Saya sudah menitipkan surat panggilan ke orangtua Hadi lewat teman Hadi, Joko, sebut saja begitu, karena berdasarkan pengalaman, kalau saya memberikan pada anak yang bersangkutan, pasti surat tak akan sampai ke orangtua.
"Berikan ke orangtua Hadi langsung. Jangan kasih ke Hadinya," pesan saya pada Joko, yang rumahnya dekat dengan Hadi.
"Ya, Pak," jawab Joko.
Saya menyebutkan di surat itu, supaya orangtua Hadi bisa datang pada hari Senin. Dua hari kemudian.
Ternyata, hari Senin, orangtua Hadi tidak datang pada jam 9 pagi, seperti yang tertera di surat.
Saya pun bertanya pada Joko, "Ko, waktu hari Sabtu, kamu kasih surat itu ke siapa?"
"Ke Hadi, Pak. Soalnya, ayah sama ibunya tidak ada di rumah. Kakaknya juga tidak ada di rumah. Kerja," jawab Joko.
Ya, pantas aja gak datang. Kemungkinan surat itu dibuang sama Hadi, begitu dugaan saya.
"Bisa bapak minta tolong antarkan ke rumah Hadi setelah pulang sekolah?" tanya saya pada Joko lagi.
"Bisa, Pak."
Saya pun melangkah ke rumah Hadi setelah selesai mengajar, sekitar jam satu.
"Itu, Pak, rumahnya," Joko menunjuk rumah panggung di depan, berwarna hijau, terbuat dari kayu, dengan atap seng, dan rumput yang tinggi di sekelilingnya.
"Assalamualaikum," saya memberi salam. Pintu depan terbuka.
"Wa'alaikumussalam," suara perempuan menjawab dari dalam.
"Permisi, Bu. Apa benar ini rumah Hadi?" tanya saya.
"Benar, Pak. Bapak siapa ya?" Perempuan tua itu memandang saya dengan curiga.
"Perkenalkan, Bu. Saya Anton, guru bahasa Inggris Hadi di SD."
"Oh ya, Pak. Ada apa ya, Pak?" Seketika raut wajah perempuan itu berubah. Kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya.
"Maaf, Bu. Bisa kita bicarakan di dalam saja?" Saya berkata sambil tersenyum.
"Oh, bisa, bisa, Pak. Maaf. Silakan, Pak," Perempuan tua itu terbata-bata, mempersilahkan saya masuk.
Ruang tamu tidak ada furnitur apa-apa. Kosong. Hanya ambal dengan warna biru memudar yang menutupi lantai kayu.
Tidak ada kursi satu pun. Satu meja pun juga tidak ada.
"Begini, Bu," saya langsung membuka pembicaraan, "Ibu dan bapak ada dapat surat dari saya?"
"Surat apa, Pak?" tanya ibu itu heran.
"Surat yang menyatakan bahwa saya ingin bertemu bapak dan ibu pagi ini jam 9 di sekolah. Saya meminta tolong Joko," Saya menunjuk ke Joko yang ada di sebelah kiri saya, "untuk memberikan surat itu langsung ke orangtua Hadi. Ibu ibunya Hadi kan?"
"Iya, Pak, saya ibunya Hadi. Tapi kami tidak dapat surat itu."
"Kata Joko, dia berikan surat itu pada Hadi, karena waktu dia datang ke sini; bapak, ibu, dan kakak laki-laki Hadi sedang tidak ada di rumah."
"Siang hari ya, Ko?" tanya ibunya Hadi.
"Iya, Tante," jawab Joko singkat.
"Memang, Pak, kami semua tidak ada di rumah dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, karena suami saya kerja di bangunan, saya jualan sayur di pasar, dan kakak laki-lakinya juga kuli bangunan," kata sang ibu, pandangan beralih pada saya kembali.
"Kata Joko, dia menyerahkan surat itu pada Hadi. Apakah Hadi tidak memberikan surat itu pada bapak dan ibu?"
"Tidak, Pak," sang ibu berkata, lalu kemudian pandangan beralih ke Hadi.
"Saya curiga, anak ibu membuang surat itu. Saya sudah mempunyai banyak pengalaman, kalau diberikan pada anak yang bersangkutan, pasti surat tidak akan sampai ke orangtua."
"Bener, Le? Kamu buang surat dari Pak Guru?" tanya sang ibu pada anak laki-lakinya, Hadi.
Hadi cuma menunduk. Sekilas, terlihat air mata menitik dari pelupuk.
"Assalamualaikum," tiba-tiba ada salam dari luar, seorang pria, dengan rambut yang sudah banyak beruban, masuk. Saya berasumsi, bapak ini adalah ayah Hadi. Setelah itu, diikuti dengan seorang lelaki muda. Saya perkirakan, umurnya baru 20-an lebih. "Pasti kakak laki-laki yang disebutkan Joko dan ibunya Hadi," pikir saya.
"Wa'alaikumussalam," kami serentak membalas salam tersebut.
"Pak, ini guru Hadi di sekolah," ibunya Hadi memperkenalkan saya pada suaminya.
"Oya, Pak. Ada apa, Pak? Hadi nakal?" tanya ayah Hadi, sembari duduk bersila di ambal, di dekat pintu.
"Ah, kenakalan anak-anak biasa, Pak. Sudah tiga kali tidak membuat PR dan sudah tiga kali pula tidak masuk sekolah pas jam pelajaran saya di kelasnya," Saya menjawab dengan tersenyum.
"Bikin malu aja, Pak. Tidak buat PR, bolos, sekarang surat dari Pak Guru malah sengaja dibuang," kata sang ibu, sedikit terisak.
"Bener begitu, Le? Tole, tole, kok bisa begitu kamu. Itu surat panggilan untuk bapak dan ibu, kamu buang kemana?"
"Hadi robek dulu, Pak. Lalu Hadi buang ke tempat sampah," Hadi tetap tak berani menengadahkan wajahnya. Air mata semakin deras mengucur.
"Ibu jadi malu, Le," ibunya Hadi menitikkan air mata.
Saya jadi tak enak melihat, "Jadi, begini saja, Bapak dan Ibu," Saya langsung menengahi, "Saya pikir sudah cukup sampai di sini saja. Saya harapkan bapak dan ibu untuk lebih memperhatikan pendidikan putra Anda berdua di rumah, karena kami, sebagai guru, tidak bisa memantau perkembangan peserta didik selepas dari sekolah. Kami mohon kerjasamanya. Demi masa depan Hadi.
"Untuk buku," saya mengeluarkan buku pelajaran bahasa Inggris dari tas saya, "Saya akan fotokopikan untuk Hadi. Buku-bukunya sudah diambil sama penerbit, jadi terpaksa saya berikan fotokopinya saja. Besok pagi saya berikan, supaya putra Anda bisa belajar, tidak tergantung pada orang lain."
"Terima kasih banyak, Pak," Ayah dan Ibu Hadi mengucapkan bersamaan.
"Saya mohon pamit, bapak dan ibu, karena saya ada pekerjaan lain sesudah ini. Mohon maaf, kalau sudah mengganggu. Terima kasih atas waktunya," saya beringsut, bangkit, bersalaman dengan ayah dan ibunya Hadi, kakak laki-laki Hadi, dan Hadi.
Ibunya Hadi menemani saya sampai depan pagar. Saya tidak tahu kalau beliau membawa sebuah plastik hitam di tangan. Waktu sudah di depan pagar, ibu itu memberikan plastik hitam itu pada saya, "Ini, Pak, sekedarnya buat bapak."
"Apa ini, Bu?" tanya saya, heran.
"Cuma gula merah, Pak. Mohon diterima."
Saya tertegun. Pemberian yang sederhana, dari sepasang suami istri yang dalam keadaan kekurangan, tapi ikhlas memberi, walau pemberiannya mungkin tak berharga secara materi, tapi bernilai tinggi dari sisi kerendahan hati.
"Mohon maaf, Bu. Saya tidak bisa menerima. Kami, para guru, dilarang untuk menerima segala bentuk pemberian dari para orangtua murid. Lebih baik, buat keluarga ibu saja. Terima kasih banyak, Bu."
Ibu itu pun tersenyum, dan saya pun berlalu.
Memanusiakan Peserta Didik, bukan sekedar data di atas kertas
Memanusiakan - v. menjadikan (menganggap, memperlakukan) sebagai manusia (sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima)
Semoga dengan melihat tiga pengalaman saya di atas, bisa memberikan manfaat, bukan saja bagi para guru, namun juga para orangtua, bahwa peserta didik, murid, bukan obyek, tapi subyek, mempersiapkan mereka sebagai pelaku, penemu, pemimpin, kelak di kemudian hari.
Saya merasa perlu untuk blusukan, karena kebanyakan para guru hanya menganggap kenakalan atau kemalasan peserta didik, karena kesalahan peserta didik semata.
Itu anggapan yang keliru.
Mereka, kebanyakan para guru, tidak melihat langsung kondisi keluarga dari peserta didik.
Dari 3 pengalaman di atas, kebanyakan yang menyebabkan malas atau sering bolos sekolah karena faktor ekonomi keluarga yang berada dalam tingkat menengah ke bawah.
Sebenarnya, masih banyak faktor lain, semisal perceraian orangtua, KDRT, orangtua sudah meninggal, dan lain sebagainya.
Kiranya, para guru lebih proaktif, terjun langsung, menjalin tali silaturahmi dengan orangtua atau wali peserta didik, karena itu lebih penting daripada hanya berlandaskan angka-angka, data-data yang ada di ruang kelas.
"Memanusiakan peserta didik, bukan slogan, bukan propaganda, tapi suatu keniscayaan."
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H