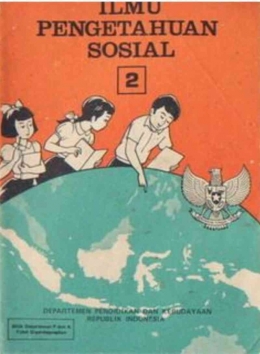Memiliki benda-benda produk industri kota seperti yang banyak ditampilkan di TVRI merupakan salah satu cara mereka untuk merasakan diri menjadi modern sekaligus meningkatkan prestige di tengah-tengah masyarakat. Saya masih ingat ketika salah satu teman sebaya dari keluarga berada dibelikan sepeda BMX begitu bangga ketika saya dan kawan- kawan mengerumuninya di sekolah.
Keberhasilan Revolusi Hijau ternyata menyebabkan hilangnya beberapa tradisi dalam sistem pertanian desa. Penggunaan bibit hibrida hasil rekayasa genetik para pakar pertanian menghilangkan bibit lokal seperti Rojolele, Pandanwangi, dan Kruwing yang tahan hama sangat cocok untuk sawah tadah hujan.
Beroperasinya waduk mengubah pola tanam 1 + 2 (padi 1 kali-palawija 2 kali) menjadi 2 + 1 (padi 2 kali-palawija 1 kali) atau 3 + 0 (padi 3 kali nir palawija). Ritual-ritual pertanian seperti selamatan menjelang tandur musim tanam atau selamatan miwiti musim panen ketika hendak panen mulai hilang.
Pemberian sesajen menjelang panen ke sawah sebagai bentuk rasa syukur warga desa kepada Tuhan melalui Dewi Sri juga mulai lenyap dari tradisi pertanian. Dalam konteks ritual, tampak ada titik temu antara ajaran agama dan pembangunan. Para guru ngaji selalu mengatakan kalau membuat sesajen itu bagian dari musyrik.
Sementara, percepatan pembangunan pertanian tidak membutuhkan semua ritual itu karena yang dibutuhkan hanyalah pupuk, irigasi, dan pestisida.
Kehadiran mesin perontok padi dan huller juga ikut mengubah sistem panen dan pengolahan hasil panen di desa kami beserta tradisi yang menyertai.
Sebelum ada mesin itu, panen dilakukan dengan sistem bawon. Para buruh tani perempuan memotong padi dengan ani-ani (pemotong padi tradisional dengan sebilah pisau kecil yang dipasang di rangka kayu) dan setelah selesai akan mendapatkan imbalan beberapa ikat padi. Selama masa panen, para buruh perempuan bisa mengumpulkan padi untuk menyambung kehidupan mereka sekaligus sebagai sarana ketahanan ekonomi mereka.
Sebelum ada huller, ibu-ibu menumbuk padi di lesung dan lumpang untuk bisa mendapatkan beras dari bulir-bulir padi yang sudah kering. Waktu menumbuk padi menjadi arena kultural bertemunya ibu-ibu sambil membicarakan permasalahan hidup sehari-hari, termasuk ngrasani (bergosip) warga yang ketahuan selingkuh.
Masyarakat desa mulai menyekolahkan anak-anak mereka, paling tidak, sampai tingkat SD bagi keluarga miskin, tingkat SMP/SMA bagi keluarga menengah, dan perguruan tinggi bagi keluarga berada.
Sampai awal 90-an di dusun saya terhitung hanya ada 5 orang yang menempuh kuliah, 4 orang di perguruan tinggi swasta dan 1 orang di perguruan tinggi negeri, yakni anak Kepala Dusun (Senden). Karena merasa bangga dengan prestasi putranya yang diterima di Universitas Jember, Pak Senden membuat tasyakuran
Sebagian besar anak- anak di dusun saya hanya bersekolah sampai tingkat SMP/SMA pada akhir 80-an sampai dengan awal 90-an. Menyekolahkan anak adalah sebuah harapan dan doa agar kelak generasi penerus keluarga bisa baca- tulis dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, agar nasibnya tidak sama dengan orang tua yang hanya berprofesi sebagai petani.