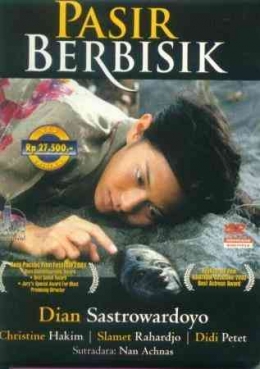Ketiga, genre horor, ceritanya berasal dari cerita-cerita mistis dan gaib yang berkembang dalam masyarakat, dengan artis terkenalnya Suzzana. Keempat, genre lain, seperti komedi, film ekspedisi, musikal, dan anak-anak.
Genre sentimentil berkembang pesat dan populersangat di tengah- tengah masyarakat. Dalam genre ini, film-film Indonesia banyak diwarnai dengan ‘keluarga metropolis’ dan kehidupan remaja dengan kehidupan glamor dan modern ibukota dan bisa dianggap menawarkan nilai-nilai budaya nasional dalam bingkai modernitas.
Taufik Ismail (dikutip Heider, 1991: 7), menjelaskan bahwa dari 27 finalis FFI 1977, 85,1 % menggunakan latar kota dan 14,9 % dengan latar desa. Sebanyak 92,6 % berkaitan dengan kehidupan kelas menengah kota dan 7,4 % mengetengahkan kehidupan orang desa.
Sejumlah 18,5 % menampilkan mobil Mercedes atau Volvo dan 70,3 % menampilkan paling tidak satu keluarga dengan hanya satu anak dan 29, 7 % keluarga dengan lebih dari satu anak, serta 52,1 % film berlatar kota menampilkan kehidupan nightclub.
Data tersebut menunjukkan betapa kehidupan dan keberbudayaan yang diusung sebagai landasan etis perfilman Indonesia, mengalami paradoks yang cenderung mengusung nilai-nilai kehidupan kota sebagai satu kesadaran kultur yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia, termasuk yang tinggal di pedesaan.
Tentu saja ini sejalan dengan semangat pertumbuhan ekonomi yang dibayangkan oleh rejim dengan pusatnya perkotaan, sekaligus untuk menutupi kontradiksi dan ketimpangan yang dirasakan oleh rakyat kecil sehingga mereka sebagai kelas subordinat tetap harus dimanjakan dengan narasi filmis utopia yang seolah-olah memperlihatkan artikulasi terhadap kepentingan mereka.
Akibatnya hegemoni akan terus berlangsung dan film dengan genre sentimentil berhasil membungkam potensi resisten mereka karena dalam banyak film yang melakukan misrepresentasi terkait ketidakadilan dan ketimpangan sosial.
Meskipun ada beberapa film yang mengkritisi gaya hidup kota dengan menampilkan konflik-konflik keluarga dan urban, toh semua tidak pernah memberikan perspektif kritis bagaimana menyelesaikan problem dan cenderung terus merepresentasikan kultur kota.
Beberapa film yang berusaha kritis dan dianggap melawan tema-tema glamornya kehidupan kota, ternyata tidak bisa melepaskan diri dari bingkai kultur yang "serba tentram dan tidak menimbulkan gejolak," sebagaimana yang digariskan Orba.

Salah satu film yang memotret persoalan kemiskinan dan kehidupan kota adalah Pengemis dan Tukang Becak (1979) yang disutradari Wim Umboh. Kristanto (2004: 79-81) menyebut film itu, bersama-sama dengan November 1828, berhasil memberikan warna dan tema lain dalam jagat film Indonesia yang banyak dipenuhi warna glamor, seksualitas, dan sadisme.