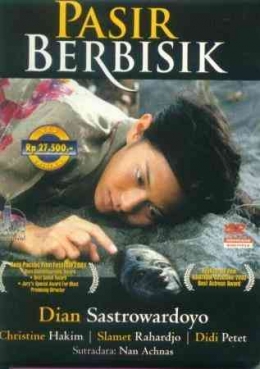Bahkan dengan tegas Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada saat itu, Jero Wacik, menyatakan bahwa Indonesia masih membutuhkan keberadaan LSF karena budaya masyarakat yang sangat beragam dan tingkat pendidikannya masih rendah sehingga LSF masih perlu dipertahankan hingga beberapa puluh tahun ke depan.
Wacana yang dilontarkan oleh si menteri ternyata mendapat gayung bersambut dari PARFI (Persatuan Artis Film Indonesia) dan juga PARSI (Persatuan Artis Sinetron Indonesia) (Arsuka, 2008).
Bahkan, salah satu kritikus film ada yang dengan terang-terangan membela LSF dengan argumen tentang standar moralitas masyarakat yang masih dalam masa transisional dan kebingungan harus berperilaku dan bersikap seperti apa.
Indarto (2007), dengan cukup meyakinkan mengajukan argumen yang cukup logis, meskipun tetap sepihak. Menurutnya, pembubaran LSF, tidaklah relevan. Ia mengajukan pertanyaan kritis: Benarkah keberadaan LSF selama ini menghambat tumbuhnya film-film Indonesia yang bermutu baik? Apakah sensor film sudah membuat film Indonesia yang tadinya bermutu baik menjadi tidak bermutu?
Menurutnya tidak. Film bagus setelah disensor tetap bagus, dan film jelek tetap saja jelek. Di banyak negara, bahkan sensor yang jauh lebih keras dan represif tetap bisa melahirkan film-film bermutu baik. Kalau yang mau dibela ialah kebebasan berekspresi, mengganti LSF dengan lembaga klasifikasi bisa menimbulkan komplikasi baru.
Masih menurut Indarto, persoalan sesungguhnya adalah standar moral masyarakat kita, yang pasti bakal tercermin sebagai standar moral LSF atau lembaga klasifikasi baru tersebut. Apabila hal itu oleh para pekerja film muda yang lebih modern dan “Barat” dianggap terlalu konservatif, inkonsisten, dan membingungkan, ya begitulah wajah masyarakat Indonesia.
Lucunya lagi, adalah pernyataan sang menteri tentang rendahnya pendidikan masyarakat yang menjadikan film harus disensor. Bagaimana bisa seorang pejabat berusaha mencemooh pendidikan warganya sendiri, sementara dia dan kolega-koleganya tidak juga berbuat kebaikan bagi pendidikan di negeri ini.
Usulan MFI untuk membubarkan LSF dan diganti dengan Lembaga Klasifikasi Film, sebenarnya menjadi kekuatan ideologis yang akan membebaskan para sineas Indonesia dari kekangan kuasa, karena selama ini terlalu banyak pemotongan yang dilakukan LSF atas nama budaya dan moralitas yang tentu saja bisa mengurangi esensi dan pesan ideologis yang hendak disampaikan melalui narasi film.
Wardhana (2008) berpendapat bahwa kendati ragam sensor dipakai dasar pemenggalan adegan, terkesan kuat bahwa yang disensor LSF adalah yang berkait dengan moral. Itu sebabnya, wacana yang dimunculkan adalah bahwa pembubaran lembaga sensor sama artinya dengan membiarkan moral jadi terkacaukan.
Padahal karya sinema bukan semata-mata ekspresi seni. Karya sinema merupakan tawaran ide, bahkan ideologi. Maka, memenggal suatu adegan ataupun memangkas judul, atau apapun sebagaimana yang dilakukan LSF selama ini, sama maknanya dengan memenggal atau menghalang-halangi keutuhan sebuah ide atau ideologi.
Jadinya, LSF merupakan kepanjangan tangan negara atau penguasa atau kelompok tertentu untuk menindas kemungkinan beragamnya ide, ideologi, pendapat, wacana, dan tata nilai.