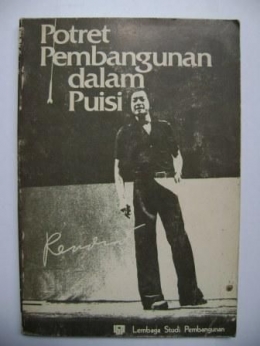AWAL(-AN)
Adalah sebuah kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 10 tahun terakhir peminat skripsi dengan objek puisi di Jurusan Sastra Inggris semakin sedikit, bisa dihitung dengan jari tangan. Indikasi apakah ini? Apakah menelaah puisi terlalu sulit bagi mahasiswa? Apakah keterbukaan model komunikasi media sosial menjadikan para mahasiswa semakin tidak terbiasa dengan ekspresi puisi?
Ataukah, semakin ke sini semakin sedikit mahasiswa yang menenggelamkan diri dalam samudra kata mahaluas dari sebuah puisi? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu saja bersemayam dalam pikiran saya selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, saya sudah meminta ke salah satu dosen pengampu matakuliah Poetry di Prodi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember (UNEJ) untuk memformulasi model pembelajaran yang asyik. Hasilnya tetap saja, peminat objek puisi untuk skripsi tidak beranjak dari beberapa jari.
Meskipun demikian, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa karena yang dibutuhkan memang bukan menyalahkan, tetapi melakukan refleksi kritis untuk mereformulasi pemahaman tentang kerja-kerja teoretis dan analitis yang bisa dipahami oleh para mahasiswa dan peminat puisi.
Maka, ketika mendapatkan undangan untuk menjadi pemateri dalam Workshop Puisi (diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Kampus Fakultas Ilmu Budaya, UNEJ, 29 April 2018) dengan senang hati saya menerimanya. Paling tidak, saya bisa menawarkan pemikiran tentang bagaimana kita bisa menikmati puisi sebagai bagian dari kajian ilmiah yang menuntut adanya standar-standar tertentu. Tentu saja, tawaran saya bukanlah sesuatu yang bersifat final dan masih bisa didiskusikan.
Tentu saja, setiap orang berhak untuk menemukan patokan-patokan dalam memahami sebuah puisi. Adakalanya, tidak membutuhkan teori ndakik-ndakik, katanya. Tapi, apakah benar tidak mempedulikan teori berarti bebas dari teori? Kita perlu menengok-kembali peringatan Belsey (1990: 4) ketika dia membincang soal pentingnya teori dalam melakukan kritik sastra.
Menurutnya, tidak ada "praktik [analisis, pen] tanpa teori, meskipun banyak dari teori tersebut yang ditekan sedemikian rupa, tidak diformulasikan atau dipersepsikan sebagai "yang jelas". Apa yang kita lakukan ketika membaca, meskipun tampak 'natural', tetaplah mengandaikan keseluruhan wacana teoretis tentang bahasa dan maknanya, tentang hubungan antara makna dan jagat, dan, akhirnya tentang diri orang-orang dan tempat mereka di dunia, meski tak terucap."
Meskipun kita seperti tidak menggunakan teori, pada dasarnya, kita tetap menggunakannya ketika membaca sebuah puisi atau karya-karya sastra yang lain. Apalagi, dalam membaca dan menganalisis sebuah puisi, kita tidak boleh berhenti pada makna tekstual, tetapi harus membawanya ke ruang kontekstual, bernama "jagat" yang sangat kompleks di mana permasalahan dan kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dimainkan.
Mengapa kita harus "susah-susah" melakukan pembacaan demikian? Bagi saya, pembacaan terhadap karya sastra merupakan 'tugas ideologis'. Seorang peneliti tidak hanya terikat dengan unsur-unsur intrinsik sebuah puisi, seperti diksi, metafor, simbol, dan relasi di antara semuanya. Lebih dari itu, mereka juga sebisa mungkin mengungkapkan makna dan wacana yang dikonstruksi dalam struktur tekstual tersebut serta kepentingan yang menjadikan teks itu ada.
Atas pertimbangan itulah, melalui tulisan ini, saya akan menawarkan formula pengkajian teks puisi berbasis disiplin akademis sastra, sebagaimana juga dilakukan oleh para peneliti sastra dalam lingkup internasional. Namun, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, ada baiknya, pertama-tama kita pahami terlebih dahulu bagaimana kita harus memaknai dan memosisikan puisi sebagai sebuah karya.
MENEMPATKAN PUISI PADA TEMPATNYA: TEKS, WACANA & KONSTRUKSI IDEOLOGIS
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan puisi? Sangat mungkin banyak jawaban yang bisa diajukan. Namun, marilah sejenak mendiskusikan pendapat William Wordsworth yang mengatakan bahwa puisi "yang harus ditulis dalam bahasa yang sebenarnya dari umat manusia merupakan luapan spontan perasaan: ia mengambil asal-muasalnya dari emosi yang dikumpulkan-kembali dalam ketenangan" (https://www.poetryfoundation.org/poets/william-wordsworth).
Menarik kiranya untuk memahami apa yang dimaksudkan Wordsworth dalam definisi sederhana tersebut. "Bahasa sebenarnya dari umat manusia" adalah ekspresi kebahasaan yang tidak mengikuti aturan-aturan mekanistik ala soneta yang sangat ketat dengan per-rima-an seperti a-a-b-b.
Bahasa yang mengalir seperti dalam bahasa keseharian, tanpa harus dibebani rumus-rumus sastrawi yang mengasingkannya. Dengan kata lain, bahasa puisi bukanlah bahasa yang harus "berbunga-bunga", penuh dengan kata dan kalimat pepuji. Apa yang diungkapkan berasal dari membuncahnya perasaan sehingga bisa menjadi ekspresi yang membawa keluar kompleksitas aspek inner.
Masing-masing penyair memiliki kemampuan kreatif untuk mengeluarkan aspek emosional dari dalam dirinya. Aspek emosional inilah yang harus diolah secara kreatif dengan ketenangan dan kontemplasi sehingga ketika keluar dalam bentuk puisi bisa memberikan impresi kepada pembaca.
Apakah aspek emosional ini semata-mata berurusan dengan wilayah inner? Tentu tidak. Emosi semua orang, termasuk di dalamnya penyair, novelis, cerpenis, seniman, koreografer, serta manusia-manusia biasa, bukanlah entitas merdeka yang semata-mata berkaitan dengan hasrat, kesedihan, kemarahan, dan harapan.
Beragam peristiwa dalam kehidupan personal maupun komunal yang berlangsung dari ruang keluarga, pasar, lampu lalu-lintas, sekolah, kampus, kantin, dan tempat-tempat lainnya akan direkam, baik dalam moda sedih, gembira, ataupun galau. Seseorang juga bisa memberikan respon emotif dari apa-apa yang ia baca, tonton, ataupun dengarkan.
Semua tumpukan itulah yang bisa dipanggil-kembali dalam proses kreatif penciptaan puisi. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, bait demi bait, dengan demikian, merupakan hasil rekonstruksi kreatif melalui perspektif partikular dari tumpukan peristiwa yang dibaluri kekuatan emosional.
Maka, ketika ia sudah menjadi teks, puisi bukan lagi luapan perasaan, tetapi lebih dari itu, merupakan produk dari kecerdasan kreatif dan kritis penyair dalam memaksimalkan tumpukan peristiwa dan permasalahan dalam wilayah batinnya. Konsekuensi dari kerangka berpikir tersebut adalah bahwa ekspresi kebahasaan apapun yang diungkapkan seorang penyair membawa makna-makna denotatif yang berasal dari logika relasional antarunsur pembentuknya.
Namun, ia tidak berhenti pada makna tersebut, tetapi juga memroduksi wacana (discourse), sebuah ranah penggunaan bahasa dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menghadirkan topik tertentu yang tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dalam masyarakat (Foucault, 2013: 162-163).
Dalam pemahaman demikian, teks puisi merupakan produk semiotik sekaligus diskursif. Dikatakan produk semiotik karena unsur-unsur internal, khususnya ekspresi kebahasaan, di dalamnya merupakan rangkaian tanda (relasi penanda-petanda) yang menyatu dalam struktur relasional sehingga akan menghasilkan makna-makna denotatif dan makna-makna simbolis partikular.
Ekspresi kebahasaan dalam teks puisi merupakan luapan proses mimetik yang berpusat pada aspek emosional dan kecerdasan kreatif dalam membingkainya. Tentu saja, bahasa yang digunakan memiliki kualitas dan gaya yang berbeda, termasuk dalam penggunaan metafor, simbol, dan lain-lain, meskipun tetap terikat dengan hubungan kontekstual dengan kode-kode kultural dalam masyarakat.
Sebagai produk diskursif, makna-makna yang sudah ada tersebut berhubungan dengan topik-topik partikular, menunjukkan subjek siapa yang sedang diposisikan dalam teks, hal-hal apa yang dihadirkan dan tidak dihadirkan, apa yang layak digambarkan dan tidak layak, dan bagaimana otoritas kuasa dihadirkan dalam permainan tekstual yang menghasilkan wacana serta terhubung dengan wacana-wacana di luar teks tersebut.
Kehadiran wacana di dalam teks puisi, tentu, bukan sekedar menjadi pilihan individual penyair, tetapi juga berjalin-kelindan dengan sesuatu yang bersifat publik. Bagaimanapun juga, penyair hidup di tengah-tengah galaksi wacana yang mempengaruhi subjektivitasnya sebagai manusia kreatif dan menggunakan bahasa publik pula sebagai alat ekspresi tersebut.
Dalam kondisi demikian, puisi bukan hanya menjadi formasi diskursif dari konstruksi wacana atau pengetahuan tertentu yang berkembang dalam masyarakat. Lebih dari itu, puisi yang sudah dipublikasikan adalah 'milik publik'. Wimsatt & Beardsley (dikutip dalam Besley, 1990: 16) mengatakan puisi bukan lagi milik penyair semenjak kelahirannya karena ia beranjak menuju "dunia", melampaui segala kekuatan yang dimaksudkan untuknya atau yang hendak mengendalikannya.
Puisi menjadi milik publik karena ia menubuh dalam bahasa (sebuah kepemilikan istimewa dari publik) dan juga bercerita tentang manusia, masyarakat, dan kompleksitas permasalahannya. Pengarang memang masih berhak menyematkan namanya di halaman sampul sebagai penanda kehadirannya.
Namun, ia tidak bisa lagi mengarahkan dan mengendalikan tafsir ataupun eksplorasi wacana yang ada di dalamnya karya-karyanya oleh para peneliti. Ia cukup menghadirkan puisi dan biarkan keragaman makna dan wacana menjadi tugas pembaca dan peneliti untuk mengungkap.
Kemenyatuan puisi dengan sesuatu yang bernama publik, baik terkait permasalahan, wacana maupun bahasa ungkap yang digunakan, menjadikannya tidak bisa dipisahkan dari persoalan ideologi. Dalam kerangka Marxian, ideologi dipahami sebagai keyakinan, perspektif, atau pemikiran tertentu yang menjadi penuntun laku individu-individu dalam meng-ada di sebuh masyarakat. Mengikuti sudut pandang deterministik, ideologi menjadi sistem keyakinan yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan eksploitatif sebuah kelas dominan terhadap kelas-kelas subordinat; "ide kelas penguasa adalah ide untuk menguasai".
Marx and Engel (2006: 9) menegaskan bahwa ide kelas penguasa akan selalu diarahkan menjadi ide yang menguasai karena mereka memiliki alat dan kemampuan produksi mental melalui pengetahuan, filsafat, moral, wacana, dan lain-lain yang bisa disebarluaskan ke tengah-tengah massa yang tidak memiliki kecukupan alat dan kemampuan produksi.
Ideologi, kemudian, sangat ditentukan oleh struktur-basis dalam sebuah masyarakat di mana kelas pemodal atau kelas penguasalah yang mengendalikan. Ide yang menguasai merupakan ekspresi ideal dari relasi-relasi material yang selalu menguntungkan dominasi kelas penguasa.
Tentu saja, sudut pandang tersebut perlu dielaborasi lagi dalam kaitannya dengan pengkajian puisi atau karya-karya sastra lainnya, khususnya terkait bagaimana cara ideologi beroperasi dalam karya sastrawi. Mengapa? Pemaknaan ideologi tersebut berangkat dari kesadaran praksis, sementara, karya puisi adalah produk kebahasaan yang sudah mengalami proses mimesis, mediasi, dan diskursif, sehingga untuk membacanya kita perlu memiliki kerangka baru terkait ideologi secara dinamis.
Ideologi bukanlah sesuatu yang bersifat dogmatis dan menggurui berupa jargon atau kampanye yang terang benderan di dalam sebuah karya. Sebagai sebuah kerangka berpikir atau cara pandang terkait sesuatu,
ideologi dituliskan dalam wacana-wacana spesifik, ranah penggunaan bahasa, cara tertentu untuk berbicara (dan menulis serta berpikir). Sebuah wacana melibatkan asumsi-asumsi terbagi tertentu yang muncul dalam formulasi yang mengkarakterisasinya. Wacana tentang kehendak bersama, misalnya, jelas berbeda dengan wacana fisika modern, sehingga beberapa formulasi dari satu wacana bisa berkonflik dengan formulasi wacana lain.
Ideologi dituliskan dalam wacana dalam makna bahwa ia secara literer ditulis atau diomongkan di dalamnya; ia bukanlah elemen terpisah yang eksis secara independen dalam beberapa ranah bebas-mengambang dari ide-ide dan sesudah itu menubuh dalam kata-kata, melaikan sebuah cara berpikir, berbicara, dan mengalami. (Besley, 1991: 5)
Sesederhana atau se-njlimet apapun diksi, se-kompleks apapun metafor yang diambil, se-panjang apapun baitnya, puisi tetaplah tuturan dalam bentuk tulis yang digunakan seorang penyair untuk merangkai ideologi yang tidak lagi tampak sebagai sebuah keyakinan bersama.
Ideologi hadir secara wajar dalam wacana-wacana spesifik yang dikonstruksi melalui makna dan topik tertentu dari kata, kalimat, dan bait dalam sebuah puisi. Sebuah puisi Romantik yang membawa energi misterius alam dengan kata-kata yang mengalir, bukan berarti hanya bicara keindahan diksional semesta tanpa menghadirkan ideologi.
Tentu saja, kita tidak harus buru-buru mengatakan bahwa puisi si A ber-ideologi kapitalisme atau sosialisme hanya dengan membaca biografinya. Pengarang bukan lagi menjadi faktor utama untuk membongkar konstruksi ideologi dalam wacana-wacana puitik. Bahkan, ketika dalam sosiologi sastra Goldman, analisis pengarang hanya dilekatkan kepada posisi kelasnya. Itu pun pertama-tama yang dianalisis adalah struktur signifikan yang memroduksi makna-makna dalam keseluruhan karya dan kondisi zaman (Faruk, 2010).
Mengikuti pemikiran Foucault (1984: 107), nama pengarang mewujudkan pemunculan rangkaian diskursif tertentu dan mengindikasikan status wacana tersebut dalam sebuah masyarakat dan budaya. Gugusan teks puitik yang dibuat seorang penyair dalam karya-karyanya mengkonstruksi wacana-wacana ideologis yang selalu terhubung dengan kondisi historis masyarakat dan budaya tempatnya berkarya.
Maka, membaca dan menelaah puisi tidak bisa menghentikan kita hanya kepada proses semiosis di dalam gugusan kata, kalimat, dan bait. Puisi adalah produk ideologis yang membangun skema dan cara berpikir subjek masyarakat pada sebuah zaman. Sebagaimana diyakini oleh para pemikir New Historicism, karya sastra selalu menjadi bagian dari kondisi kultural, politik, sosial, dan ekonomi yang lebih luas, sehingga ia terlibat secara langsung dalam sejarah (Bertens, 2001: 177).
Puisi menjadi konstruksi verbal-yang-terikat-waktu-dan-tempat yang selalu berada dalam ranah politis. Tentu saja, "politis" di sini tidak selalu harus dimaknai dengan kekuasaan praksis, tetapi kepentingan-kepentingan dan penyebarluasan ideologi pada waktu dan masyarakat tertentu.
Karya sastra menjadi kekayaan tekstual dan diskursif yang bersama-sama karya tekstual lain bisa digunakan untuk mengkonstruksi sekaligus melacak kekuatan ideologis atau kepentingan politik pada masa tertentu. Karya sastra tidak semata-mata merefleksikan relasi kekuasaan, namun secara aktif berpartisipasi dalam konsolidasi dan/atau konstruksi wacana dan ideologi. Ia berfungsi sebagai instrumen dalam konstruksi identitas, tidak hanya pada level individual tetapi juga pada level kelompok atau bahkan negara.
Apa yang harus diingat adalah kemungkinan terkait bagaimana wacana ideologis diposisikan dalam karya puisi. Dalam sebuah negara di mana banyak kekuatan ekonomi, politik, dan kultural saling berkontestasi untuk meng-ada dalam tatanan dan struktur sosial, ragam kepentingan kuasa dan ideologis juga tidak mungkin menjadi tunggal.
Artinya, dalam praktik kehidupan sehari-hari dan dalam karya representasional, termasuk sastra di dalamnya, tidak mungkin kita hanya menjumpai satu ideologi. Meskipun demikian, di antara ideologi dan kelompok atau kelas sosial yang ada bisa saling melintasi dan saling bertemu ketika ada aspek-aspek yang bisa didialogkan dan dikonstruksi untuk mewujudkan kepentingan bersama.
Ideologi patriarki, misalnya, bisa bertemu kapitalisme dalam pembagian kerja berbasis jenis kelamin di mana kaum perempuan menempati posisi kedua dengan upah yang lebih rendah ketimbang laki-laki. Dalam kesempatan tertentu, nilai-nilai agama tertentu bisa di-cumbu-kan secara manis dengan akumulasi modal perusahaan besar melalui tayangan iklan di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri atau hari-hari besar agama lain.
Kecuali di negara-negara dengan watak otoriter, ideologi yang digerakkan oleh aparat negara melalui konstitusi juga tidak selamanya bisa steril dari pengaruh ideologi-ideologi lain. Dalam konteks Indonesia, misalnya, aparat negara bolehlah mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mengikat semua warga negara. Namun, dalam praktik kehidupan ekonomi, kita melihat betapa neoliberalisme yang berazaskan pasar bebas semakin menguat di era pasca Reformasi.
Dengan penggambaran di atas, penyair sebagai subjek yang menulis sekaligus anggota dari kelas atau kelompok tertentu di dalam masyarakat atau negara bisa memainkan prinsip inkorporasi dan artikulasi terhadap permasalahan yang sesuai dengan kecenderungan ideologisnya sebagai tahapan menuju hegemoni.
Mengikuti pemikiran hegemoni Gramsci, proses kultural menjadi elemen penting dalam keberlangsungan kuasa (Gramsci, 2006; Boggs, 1994; Williams, 2006; Hall, 1997). Bukan semata-mata faktor struktur basis yang berkaitan dengan kapasitas modal dan alat produksi yang menentukan struktur supra seperti budaya, filsafat, agama, dan pendidikan.
Bahwa dalam proses produksi itu sendiri terdapat kompleksitas sehingga sebuah kelas penguasa bisa menggerakkan kekuasaan berbasis moral, intelektual, dan kultural: hegemoni. Untuk menghasilkan karya kultural yang bisa digemari dan bisa mempengaruhi kelas-kelas subordinat lain, para kreator mutlak harus melakukan inkorporasi terhadap potensi budaya yang ada, termasuk permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, dan politik.
Mereka bisa mengambil budaya residual/tradisional dan budaya emergent, yang baru berkembang, sebagai basis penciptaan. Meskipun demikian, mereka akan menerapkan prinsip artikulasi, menyeleksi secara ketat potensi dan permasalahan yang bisa dihadirkan dalam karya, sehingga akan menghasilkan karya baru yang ditandai dengan percampuran ragam nilai dan wacana, meskipun ditujukan untuk mendukung kepentingan kelas penguasa.
Kemampuan para kreator untuk menghasilkan karya yang bisa menyelami struktur perasaan masyarakat bisa mempengaruhi terbentuknya konsensus politik tanpa harus melibatkan kekerasan, sehingga mereka bisa menerima kekuasaan hegemonik sebagai sebuah kewajaran.
Dalam keranga pikir di atas, penyair, misalnya, bisa mempuisikan ketimpangan antara si miskin dan si kaya dari sudut pandang kapitalis, sosialis, ataupun komunis sesuai dengan keterlibatan ideologisnya. Ketika penyair memilih untuk menghadirkan diksi-diksi yang berpihak kepada kepentingan kelompok dominan, meskipun ia juga mengartikulasikan kepentingan kelompok-kelompok lain demi memenuhi konstruksi yang menunjukkan keutamaan kelompok pertama.
Penyair juga sangat mungkin membangun wacana yang menyampaikan resistensi terhadap ideologi atau kepentingan kelompok dominan karena diposisikan merugikan rakyat kebanyakan. Selain itu, wacana yang dikonstruksi seorang penyair juga bisa menjadi negosiasi di mana ia sebenarnya bisa menerima keberadaan ideologi atau kepentingan kuasa partikular, tetapi dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan orientasi ideal yang ia yakini.
Ini bukan berarti kita harus menelanjangi otobiografi penyair. Kita butuh membaca teks dan konteks serta wacana ideologis apa yang dituliskan seorang penyair dalam karyanya. Lacakan biografis hanya digunakan untuk melihat posisi kelas dia di tengah-tengah masyarakat. Posisi kelas ini akan mempengaruhi produksi-produksi wacana dan kepentingan di dalam puisi.
MEMAHAMI PUISI: SEKEDAR CONTOH
Untuk lebih memahami kerangka konseptual di atas, marilah kita menganalisis sebuah puisi yang ditulis W.S Rendra dari buku Potret Pembangunan dalam Puisi (1993), "Sajak Matahari". Tidak seperti puisi-puisi lain dalam buku tersebut yang menggunakan diksi transparan untuk mengkritisi ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di era Orde Baru, "Sajak Matahari" menghadirkan diksi yang relatif kompleks, meskipun Rendra masih menghadirkan kata atau ekspresi yang menjadi kata kunci untuk memahami kritiknya.
Sajak Matahari
Matahari bangkit dari sanubariku.
Menyentuh permukaan samodra raya.
Matahari keluar dari mulutku,
menjadi pelangi di cakrawala.
Wajahmu keluar dari jidatku,
wahai kamu, wanita miskin!
Kakimu terbenam di dalam lumpur.
Kamu harapkan beras seperempat gantang,
dan di tengah sawah tuan tanah menanammu!
Satu juta lelaki gundul
keluar dari hutan belantara,
tubuh mereka terbalut lumpur
dan kepala mereka berkilatan
memantulkan cahaya matahari.
Mata mereka menyala
tubuh mereka menjadi bara
dan mereka membakar dunia.
Matahari adalah cakra jingga
yang dilepas tangan Sang Krishna.
Ia menjadi rahmat dan kutukanmu,
ya, umat manusia!
Matahari menjadi kata yang cukup dominan; "motor struktural" yang cukup determinan dalam hal melahirkan kata dan bait secara menyeluruh serta makna di dalam puisi ini. Matahari dalam konsepsi kehidupan masyarakat Indonesia adalah sesuatu yang bersifat "mutlak".
Artinya, seluruh wilayah Republik dan semestanya mendapatkan anugerah melimpah berupa sinar matahari; dari pagi hingga senja, dari ujung timur hingga ujung barat, dari permukaan tanah, lautan, hingga langit. Tidak mengherankan, dalam bait pertama, semacam pengantar atau pengenalan terhadap sebuah subjek bernama matahari, kita bisa menjumpai beberapa istilah seperti "sanubariku", "samodra raya", "mulutku", "pelangi", dan "cakrawala".
Matahari adalah subjek yang bisa berada dan bangkit dalam lubuk sanubari, sesuatu yang bersifat mendalam, agung, atau menjelang pagi hari. Perjalannya akan menyapa dan menyentuh lautan luas atau samodra di bumi Indonesia, memberikan kehangatan kepada air laut dalam segala makhluk yang ada di dalamnya yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
Panas menganga yang diberikan matahari juga bisa menjadi keindahan visual ketika bercumbu dengan air langit, pelangi. Wacana ke-matahari-an yang mampu menghadirkan kehidupan dan keindahan menjadi konstruksi yang distrukturasikan dalam bait pertama puisi ini.
Pertanyaan berikutnya, siapa "-ku" dalam puisi ini? Karena ia membincang subjek matahari, kita bisa membacanya sebagai entitas "semesta Indonesia". Bisa jadi muncul tafsir lain yang lebih konotatif, seperti penguasa yang sangat kuat yang bisa mempengaruhi dan menggerakkan kehidupan di Indonesia.
Saya memilih "bumi Indonesia" karena ini berkaitan dengan bait berikutnya yang memainkan paradoksisasi dengan kondisi ideal keberadaan matahari. "-Ku" dalam bait kedua adalah "-Ku" yang berkontrakdiksi dengan "-Ku" dalam bait pertama, meskipun sama-sama "semestra Indonesia".
Menjadi paradoks karena cerita kehidupan dan keindahan harus menjumpai realitas "wanita miskin" yang keluar dari "jidat" semesta Indonesia, yang terbakar sinar matahari. Wanita ini adalah buruh tani yang kakinya harus terbenam di lumpur sawah hanya demi mengharapkan imbalan seperempat gantang beras.
Wanita itu adalah representasi buruh tani miskin yang banyak terdapat di Indonesia para era Orde Baru. Mereka adalah kaum miskin yang harus memberikan tenaga fisiknya demi menyambung hidup, bekerja keras, sampai merelakan "tuan tanah" menanam mereka, mempekerjakan buruh tani perempuan di tanah berlumpur.
Saya masih ingat saat para buruh perempuan, termasuk ibu dan budhe, nandur, menanam bibit padi, di sawah yang selesai dibajak. Kemiskinan ekonomi menjadikan banyak perempuan harus bekerja di sawah sebagai buruh tani karena mereka kebanyakan tidak memiliki kecukupan lahan.
"Tuan tanah" secara denotatif bisa dibaca sebagai para pemilik lahan sawah, sebuah istilah yang cukup populer di era Sukarno, terutama di kalangan komunis. Tuan tanah adalah salah satu musuh utama kaum proletar dalam kelompok "tujuh setan desa". Tentu saja, yang dimusuhi adalah tuan tanah yang jahat.
Istilah "tujuh setan desa" berasal dari laporan penelitian yang disusun PKI di bawah kepemimpinan D.N. Aidit. Penelitian partisipatoris di lapangan yang menggunakan tiga metode (bekerja bersama, makan bersama, tidur bersama) berlangsung pada tahun 1964 dan Aidit memimpin langsung penelitian yang melibatkan 40 kader PKI terpilih itu.
Dari penelitian tersebut didapatkan identifikasi tentang musuh kaum proletar yang harus diwaspadai dan dilawan yang kemudian disebut "tujuh setan desa". Mereka adalah: tuan tanah jahat, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat (pegawai negeri yang korup), tengkulak jahat, bandit desa dan penguasa jahat yang membela kepentingan kaum pengisap desa (https://historia.id/modern/articles/cerita-di-balik-tujuh-setan-desa-vXWwm).
Rendra sengaja menggunakan "idiom residual" dari era 60-an untuk menegaskan bahwa di zaman pembangunan ini masih banyak pihak, baik individual, swasta, maupun negara, yang berperilaku seperti tuan tanah, sebuah kontradiksi. Banyak tuan tanah-tuan tanah jahat yang masih menancapkan kuku-kukunya untuk mengeskploitasi bumi pertiwi yang semestinya bisa dinikmati oleh warga negara.

Bait berikutnya tidak kalah mengerikan; satu juta lelaki gundul keluar dari hutan dengan tubuh terbalut lumpur. Tentu saja, kita bisa memberikan beberapa tafsir tentang lelaki gundul. Bisa jadi rambut kepala mereka terbakar atau sengaja disuruh plontos oleh para tuan yang mempekerjakan mereka. Atau, mungkin ada yang menafsirnya sebagai tentara yang baru selesai pendidikan.
Yang pasti mereka selesai melakukan pekerjaan berat di tengah hutan yang menjadikan mereka penuh lumpur serta terpapar sinar matahari. Saking panasnya, mata mereka seperti menyala dan tubuh mereka siap membakar apa saja yang dijumpai di jalan. Ungkapan tersebut merupakan bentuk penyangatan yang menekankan kondisi yang cukup mengenaskan.
Kalau kita lacak lagi, sejak era kolonial banyak kaum kuli yang dipekerjakan oleh pekebun Belanda untuk membuka dan menggarap lahan. Mereka harus menjadi buruh di tanah Nusantara. Tradisi kuli tersebut masih berlanjut hingga era pasca kemerdekaan. Bahkan, di era Orde Baru ketika pembangunanisme dikampanyekan secara massif, ketika janji kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir orang dan elit di lingkaran kekuasaan. Para wanita dan lelaki miskin tetap harus menjadi subjek yang menderita dari praktik eksploitasi bumi dan manusia.
Bagi saya, melalui "Sajak Matahari" dan puisi-puisi lainnya dalam Potret Pembangunan dalam Puisi merupakan usaha Rendra sebagai sastrawan dan intelektual untuk menawarkan kritik terhadap kebrengsekan dan ketidakadilan yang dilahirkan rezim Orde Baru. Konstruksi wacana-wacana ketidakadilan beraroma paradoks dari idealisasi dan pembenaran yang dikonstruksi rezim negara merupakan pilihan ideologis yang diambil Rendra untuk disebarluaskan kepada para pembacanya.
Konstruksi diskursif ini memberikan alternatif cara pandang dan pola pikir terhadap kampanye pembangunan yang banyak diamini intelektual pada zaman Orde Baru. Paling tidak, konstruksi tersebut menjadi tandingan dari kebenaran ideologis yang dikonstruksi rezim negara melalui bermacam produk representasionalnya.
Eksploitasi paradoks pembangunan, dengan demikian, menjadi pilihan dan kepentingan ideologis Rendra untuk menyebarluaskan wacana resistensi melalui pendalaman dan pemunculan kesengsaraan manusia Indonesia. Populeritas puisi-puisi Rendra di kalangan mahasiswa dan dosen pada era 90-an hingga saat ini menegaskan bahwa ada energi perlawanan yang disampaikan melalui puisi bisa menggerakkan kesadaran kritis mereka.
SIMPULAN
Dari Rendra kita bisa belajar bahwa menghadirkan wacana-wacana kritis tidak hanya bisa dilakukan melalui pertunjukan drama, karya prosaik, ataupun demonstrasi. Karya-karya puisi yang kelahirannya sangat personal, senyatanya, bisa menghadirkan bangunan tekstual-kontekstual yang membawa wacana-wacana resistensi terhadap dominasi dan eksploitasi.
Energi perlawanan inilah yang semestinya bisa dinyatakan oleh para penyair muda di tengah-tengah praktik ketidakadilan ekonomi, eksploitasi tambang, dan perusakan hutan yang seringkali melibatkan pemodal besar dan aparat negara. Permasalahan sehari-hari yang kita jumpai dalam kehidupan sosial juga bisa 'diperas' secara kreatif dan kritis dalam bentuk puisi.
Itulah mengapa, pengkaji juga sudah semestinya membangun kesadaran kritis bahwa puisi bukanlah sekedar susunan kata-kata indah penuh majas dan metafor. Memosisikan puisi sebagai teks, wacana, dan konstruksi ideologis merupakan pilihan konseptual yang bisa berdampak kepada metodologi untuk membongkar kompleksitas proses ideologis dituliskan.
Pembacaan puisi sebagai struktur tekstual bermakna merupakan pintu masuk untuk membincang gugusan wacana sebagai topik atau konsep yang dihadirkan oleh penyair. Konstruksi diskursif tersebut merupakan sebuah ruang untuk menghadirkan kepentingan dan posisi ideologis dari penyair dan karyanya di tengah-tengah permasalahan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.
Pembacaan semiotik-diskursif-ideologis itulah yang akan mengantarkan kajian puisi tidak berhenti kepada makna deskriptif-puitik, tetapi kepada konstruksi dan kepentingan yang lebih bersifat politis dan ideologis.
DAFTAR BACAAN
Bertens, Hans. 2001. Literary Theory The Basics. London: Routledge.
Besley, Cathrine. 1991. Critical Practice. London: Routledge.
Boggs, Carl. 1984. "The Theory of Ideological Hegemony". Dalam The Two Revolutions: Gramsci and the Dilemmas of Western Marxism. Boston: South End Press.
Faruk, HT. 2010. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
Foucault, Michel. 2013. Archaeology of Knowledge. London: Routledge.
Foucault, Michel. 1984. "The Author". Dalam Paul Rainbow (ed). Foucault Reader. New York: Panthean Books.
Gramsci, Antonio. 2006. "History of the Subaltern"; "The Concept of Ideology"; Cultural Themes: Ideological Material". Dalam Meenakshi G. Durham & Douglas M. Kellner (eds). Media and Cultural Studies Keyworks. Victoria: Blackwell Publishing.
Hall, Stuart.1997. "Gramsci's relevance for the study of race and ethnicity". Dalam David Morley & Kuan-Hsing Chen (eds). Stuart Hall, Critical Dialogue in Cultural Studies. London: Routledge.
Marx, Karl & F. Engels. 2006. "The Ruling Class and the Ruling Ideas". Dalam Meenakshi G. Durham & Douglas M. Kellner (eds). Media and Cultural Studies Keyworks. Victoria: Blackwell Publishing.
Rendra, W.S. 1993. Potret Pembangunan dalam Puisi. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
Williams, Raymond. 2006. "Base and Superstructure in Marxist Theory". Dalam Meenakshi G. Durham & Douglas M. Kellner (eds). Media and Cultural Studies Keyworks. Victoria: Blackwell Publishing.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H