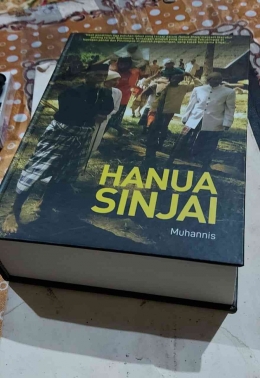Malam bersama Drs. Muhannis di pelosok selatan Pulau Sulawesi, tepatnya di Desa Ara Kecamatan Bontobahari, Bulukumba barangkali malam yang membawa banyak penyesalan.
Sesal bukan karena waktu yang terbuang percuma, bukan karena person yang saya temui itu tidak menarik dan juga bukan karena materi perbincangan yang tidak bermanfaat.
Sama sekali bukan!
Sesal yang timbul justru karena terbatasnya waktu yang tersedia, tidak cukupnya kesempatan untuk berbincang dalam dan tidak memadainya persiapan untuk menangkap pesan berharga.
Dan sesal terhadap bagaimana cara kita, atau sebagian dari kita, memandang sejarah beserta segala pernik-perniknya.
Drs. Muhannis, seorang pensiunan ASN, tepatnya Guru Bahasa Jerman memberi cermin bening untuk menggambarkan seperti apa negeri ini menghargai dirinya sendiri.
Istilah Negeri dalam konteks ini bukan sebatas pengertian administrasi atau wilayah melainkan mencakup juga suasana yang melingkupi bentang alam, rentang masa beserta segenap tingkah penghuni di atasnya.
Negeri yang saya maksud di sini lebih kepada sebentuk kesepahaman atau kesadaran, meski mungkin diam-diam, bahwa dalam rentang masa tertentu, pada bentang wilayah dengan batasan luas tertentu terdapat komunitas yang mendiaminya dan memberinya isi dan makna.
Dalam dimensi horizontal seturut masa mengalir, isi dan makna itu sebut saja sebagai sejarah sedangkan dalam dimensi vertikal, yang juga berwarna sejalan waktu, sebut saja isi dan makna itu sebagai kebudayaan.
Budayawan dan pendidik low profile itu di penghujung Ramadhan 1443 H tahun ini menghamparkan sebuah buku yang baru terbit, HANUA SINJAI, kepada khalayak yang mengaku gemar membaca.
Hanya seorang penggemar sejatilah yang akan tertarik dengan buku setebal hampir 700 halaman, tanpa gambar atau ilustrasi berwarna dan juga tanpa text box berisi kutipan yang menarik mata sebagaimana buku-buku motivasi diri yang membanjiri pasaran.

Ratusan halaman tersebut bersumber dari catatan puluhan tahun yang dihimpun dengan kecintaan, kesabaran, kejujuran dan terkadang diselingi titik air mata.
Hamparan catatan dan dokumentasi yang merekam kejadian penting, pertautan silsilah yang rumit dan tersampaikan kepada generasi hari ini melalui jalan yang juga berliku.
Tentang HANUA SINJAI sendiri, terus terang saya sendiri pun baru membaca sampai bab awal yang menjelaskan tentang toponimi Sinjai.
Tapi bahkan ketika baru sampai pada bab ini pun, kekaguman muncul mengikuti baris demi baris penjelasan tentang asal-usul nama tersebut.
Bukan seperti penjelasan yang umum kita jumpai yang lebih banyak menggunakan pembuka "konon", asal-usul nama SINJAI diuraikan bersandar pada naskah-naskah kuno maupun dokumentasi kolonial sehingga kita mendapat penjelasan komprehensif yang rasanya sulit untuk dibantah.
Sebenarnya bagian yang menyita pemikiran adalah di Kata Pengantar.
Alih-alih hanya berisi ungkapan terima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung penerbitan buku tersebut, bagian ini juga merekam suka-duka, pahit-getir dan ragam pernik yang mengiringi perjalanan mengumpulkan informasi, menguji validitas sumber sejarah dan menyusun rangkaian yang runut dari ragam sumber yang ada.
Di tahap ini lah pergulatan intelektualitas berbenturan dan terkadang berkelindan dengan nafsu kekuasaan dan sentimen primordial.

Mengambil analogi tentang praktik konservasi bangunan tua warisan sejarah, Edward Hobson (2004) dalam Conservation and Planning, Changing Values and Practices menyebutkan bahwa konservasi hanya satu cara dalam berurusan dengan struktur bersejarah.
Konservasi sebagian besarnya berhubungan dengan sikap budaya generasi hari ini dalam menentukan bangunan tua tertentu yang harus dilindungi.
Bahkan konservasi suatu warisan sejarah pada dasarnya merupakan bentuk negosiasi antar generasi untuk melakukan transisi dari masa lalu ke masa depan dan karenanya merupakan refleksi dari sikap budaya terhadap masa lalu.
Negosiasi antar generasi inilah yang tertangkap samar-samar dalam Kata Pengantar buku HANUA SINJAI. Negosiasi untuk memperkuat citra seorang tokoh dan meredupkan peran tokoh lain yang diusung oleh pihak yang merasa mewarisi satu cabang silsilah.
Sebagian lontara yang juga jadi salah satu sumber primer dalam penulisan HANUA SINJAU ini berisi tentang silsilah yang tentu isinya menyajikan perspektif, latar dan kebutuhan penulisannya.
Perspektif menjaga kemurnian garis darah dan karena akan berkorelasi dengan hak turun-temurun dalam pewarisan kekuasaan adalah satu variabel dalam penulisan sejarah lokal ketika hak-hak kekuasaan tradisional meredup seturut diterimanya demokrasi sebagai salah satu prinsip dalam pengelolaan komunitas bernama negara dan daerah.
Siapa bisa membendung atau menghilangkan romantisme masa lalu dari keturunan tersisa hari dan juga para pendaku keturunan?
Romantisme itu muncul atau diam-diam menyusup ketika sejarah suatu komunitas ditulis hari ini. Romantisme bisa mewarnai alasan apologetik saat tafsiran hari ini tidak sejalan dengan kondisi ideal yang tercitrakan dari tatanan masa lalu.
Romantisme juga bisa muncul ketika ada interes teleologis bahwa penyusunan uraian hari ini akan membawa dampak menguntungkan hari ini dan masa depan. Entah dalam bentuk manfaat ekonomi maupun manfaat politis.
Tak percaya?
Cobalah perhatikan saat kontestasi politik lokal, bukankah banyak yang menggali dan berupaya menyambungkan garis keturunannnya dengan silsilah dari penguasa atau tokoh penting dari masa lalu?
Praktik semacam ini tentu dengan harapan mendapatkan legitimasi sosial dan kultur bahwa yang bersangkutan memiliki DNA dan karenanya pantas untuk menjadi pemimpin hari ini. Dalam bahasa ringkasnya adalah yang bersangkutan bukanlah orang biasa-biasa saja.
Tidak boleh dinafikan juga dalam setiap kegiatan selalu akan ada pihak yang berperspektif oportunis mencari keuntungan ekonomi sesaat.
Sikap budaya hari ini itulah yang mengiringi perjalanan penulisan HANUA SINJAI ini dalam menyusun untaian data dan fakta. Jangan lupa juga bahwa pemilik naskah kuno sering membungkus kepemilikan naskahnya dalam ragam kepentingan.
Ketika kepemilikan dimaknai sebagai kepemilikan makna pesan sampai hari ini, maka yang muncul adalah proteksi terhadap kelompok lain yang potensial mengganggu kemapanan pemegang naskah.
Ketika kepemilikan berkelindan dengan keinginan menguasai manfaat di masa depan maka proteksi muncul dalam bentuk pencarian peminat dengan tawaran tertinggi, baik berbentuk materi maupun pemanfaatan symbol hari ini dan seterusnya.
Tentu tidak sepenuhnya salah sikap protektif semacam itu.
Karena menulis sejarah hari ini, sebagaimana praktik konservasi sebagaimana disitir dalam buku Hobson di atas, merupakan negosiasi antara memori masa lalu, penafsiran hari ini dan ekspektasi di masa depan yang semuanya berlangsung dalam lini masa yang sambung-menyambung.
Tempatkan para pihak yang berkepentingan, atau merasa berkepentingan, dalam pusaran itu maka kita akan memperoleh gambaran aktor dan struktur sosial yang ada sebagaimana dialektika yang digambarkan oleh Karl Marx ketika berbicara materialism historis.
Penulis yakin kondisi semacam itu bukan hanya berlaku di Sinjai melainkan terjadi hampir di semua daerah di negeri tercinta ini.
Keinginan untuk memperteguh eksistensi kesejarahan lokal ditunggangi oleh ragam kepentingan merupakan kondisi yang hanya akan bisa disaring oleh literasi sejarah yang memadai.
Sayangnya di banyak daerah tuntutan akademis untuk mendapatkan sumber sejarah yang memadai sering masih menjadi impian.
SINJAI beruntung memiliki sumber sejarah yang cukup melimpah dari lingkungan budaya dan masyarakat yang menghargai aktifitas pencatatan.
SINJAI juga beruntung disinggahi oleh seorang Guru Penggerak yang mampu mengubah tumpukan dokumen kuno menjadi permata yang bernilai.
Melalui buku HANUA SINJAI, Sinjai juga beruntung mampu menampilkan eksistensinya di tengah dominasi kisah Gowa dan Bone yang hari ini banyak dikonsumsi oleh kaum milenial.
Membaca HANUA SINJAI kita akan mendapatkan sandingan dengan bukunya Christian Pelras, MANUSIA BUGIS, yang sering menjadi rujukan peneliti-peneliti mutakhir.
Bukan untuk saling menegasikan tapi saling memperkuat. Kalau MANUSIA BUGIS berbicara tentang Bugis secara umum dari kacamata cendekiawan Barat, maka HANUA SINJAI bercerita lebih mendetail, sehingga mengambil setting lokasi yang lebih sempit, dari kacamata cendekiawan lokal yang selama 30 tahun menghirup udara setempat.
Bayangkan kalau semua daerah di Nusantara memiliki dokumen serupa, dan sumber sejarah dan standar historiografi yang setara, maka kita akan memperoleh gambaran lengkap betapa antar suku di Nusantara memiliki pertautan yang kuat di masa lalu. Pertautan itulah yang sesungguhnya menjadi warisan utama dari masa lalu ke masa modern sehingga NKRI yang kita banggakan hari ini dapat mewujud.
Sebagian mungkin akan mengatakan bahwa sejarah lokal tidak sepenuhnya bisa dijadikan sandaran karena banyaknya kepentingan primordial yang menggelayuti dalam penggalian dan pengungkapannya dibanding sejarah nasional yang sudah mapan.
Tapi bukankah sejarah yang disebut sejarah nasional pun isinya sebenarnya tentang kejadian dan tokoh lokal yang dengan teknik historiografi tertentu dapat menjadi memiliki dampak yang melintasi batas kelokalannya?
Dapat saja dikatakan bahwa sejarah nasional merupakan akumulasi dari sekian banyak sejarah local atau sebaliknya sejarah lokal merupakan gambaran lebih detail dari sejarah nasional.
Bias tafsir atau cacat data pendukung merupakan hal yang biasa dalam penulisan sejarah lokal tapi bisa dibincangkan secara akademis, dan karenanya semakin banyak yang menulis sejarah lokal dengan memperkaya sumber primer yang diacu ibarat sumbangan kepingan-kepingan yang nantinya akan menghasilkan gambaran yang utuh.
Karenanya kita butuh lebih banyak sosok seperti Drs. Muhannis. Kita butuh lebih banyak lagi buku sejarah lokal untuk meneguhkan ikatan keberagaman negeri tercinta ini.
Salam literasi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H