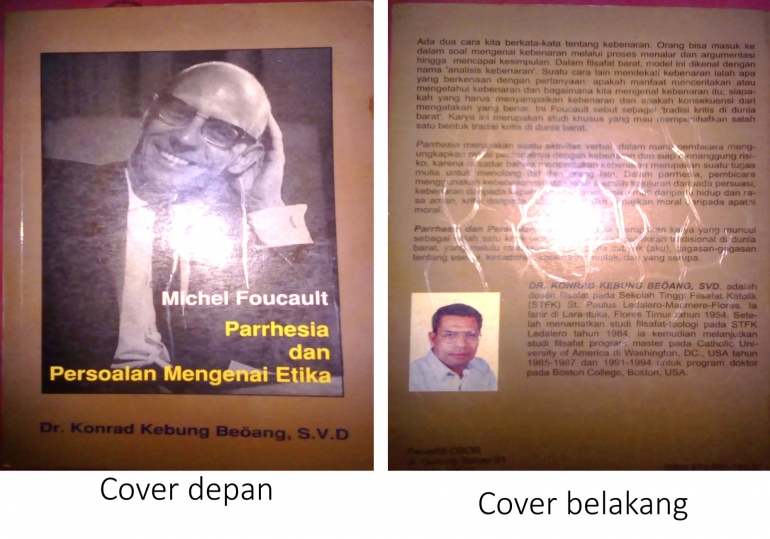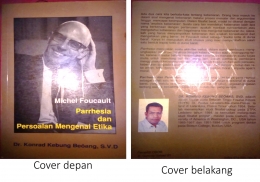Pernakah saudara-saudari warga Kompasiana mendengar kata "parrhesia"? Atau setidak-tidaknya pernah membaca tentang kata ini? Saya sendiri begitu yakin bahwa warga Kompasiana, tahu dan lebih dari itu memahami secara benar tentang kata "parrhesia".
Tulisan mini ini sebagai buah refleksi saya atas hasil baca selama libur karena pencegahan pandemi Covid-19, dari buku Michel Foucault Parrhesia dan Persoalan Mengenai Etika, karya Dr. Konrad Kebung Beang, SVD yang dicetak pada bulan September 1997 yang lalu, di percetakan Obor, Jakarta.
Dari hasil membaca buku ini, saya mencoba mengaitkannya dengan demokrasi Indonesia yang selama ini secara publik kita alami.
Parrhesia: etimologi dan pemahaman Foucault
Parrhesia secara etimologi dari bahasa Yunani, yaitu kata "pan" dan kata "rhesia" atau "rhema". Kata "pan" artinya semua dan kata rhesia atau rhema artinya ekspresi, apa yang dikatakan, pidato atau perkataan. Disamping itu, juga berarti ucapan, omongan, ujaran, dan berbicara.
Dari arti kata secara etimologi tadi, ada hal esensi yang kita temukan dari parrhesia yaitu ketrampilan berbicara, kehalusan, keterbukaan, keterusterangan, dan kebebasan dalam berbicara. Dari etimologi kata parrhesia, rupanya ditemukan juga dalam berbagai bentuk: ada bentuk nominal, verbal, dan subyektif.
Dari berbagai bentuk ini parrhesia, Michel Foucault (1926-1984), seorang pemikir asal Prancis yang terkenal di abad 20, tergerak hatinya untuk mendalami apa sebenarnya parrhesia itu. Setelah melakukan studi yang mendalam, Foucault mengatakan bahwa parrhesia itu adalah "bebas berbicara" tetapi dalam kaitannya dengan kebenaran.
Dan jika parrhesia hanya asal berbicara maka si pembicara dapat diketahui sejauh mana seseorang itu ber-etika atau tidak. Kalau parrhesia itu dalam arti bebas berbicara namun benar maka inilah tugas dan kebajikkan dari si pembicara.
Dari pemahaman Foucault ini, parrhesia memiliki makna yang mendalam yaitu bahwa kebebasan berbicara itu, tidak asal omong, tetapi berkorelasi dengan kebenaran. Dan karena itu, parrhesia sebenarnya aktivitas seseorang mengungkapkan segala sesuatu yang ada didalam pikirannya. Dalam mengungkapkan itu, muncul unsur-unsur seperti kemerdekaan, kebebasan, penuh keyakinan, dan polos.
Foucault lebih tegas mengungkapkan bahwa berbahasalah yang menjadi gambaran atas kebebasan, kemerdekaan, penuh keyakinan, dan polos. Memang benar bahwa jika dalam berbahasa terdapat banyak polesan, banyak hiasan, maka tidak lebih dari asal omong. Atau lebih krennya, asal bunyi. Tong kosong nyaring bunyinya.
Parrhesia dan kebenaran
Parrhesia dalam hubungan erat dengan kebenaran, inilah problematika pemikiran Foucault. Banyak berbicara, namun tidak ada isinya adalah berbahaya. Bumerang! Berbicara sedikit tetapi bernas isinya, adalah konfigurasi dari kecerdasan berpikir dan kedewasaan berbicara. Tidak asal omong. Jika berbicara bebas tetapi kebenaran dalam isi pembicaraan, nihil merupakan petaka besar. Maka bebas berbicara bisa saja, tetapi harus yang benar.
Sampai disini, pertanyaan yang bisa kita ajukan ialah apa itu kebenaran dan kebebasan? Siapa saja yang boleh dikatakan bebas berbicara benar? Bagaimana kebebasan berbicara yang benar?
Pertanyaan-pertanyaan ini dihadirkan disini dengan maksud mendorong siapapun juga untuk merefleksikan. Sehingga dalam forum apapun dan dalam bentuk apapun, kebebasan berbicara tetap ada namun kebebasan berbicara itu harus menampilkan kebenaran. Sehingga tidak dibilang hoax atau palsu.
Dalam studi Foucault tentang kebenaran, ia menemukan bahwa topik tentang kebenaran telah dibahas sejak masa pra-Sokrates. Masa pra-Sokrates, memandang kebenaran sebagai "Being" atau sesuatu yang bersifat ilahi.
Di zaman Sokrates, kebenaran adalah sesuatu yang harus diperlihatkan dalam hidup yang baik, yang benar dalam pikiran diwujudkan dalam kehidupan etis.
Sementara Plato melihat kebenaran sebagai sesuatu yang berada dalam lingkup Forma yang terlepas dari dunia indrawi. Turunan dari ide kebaikan dalam dunia intelektual melalui illuminasi menjadi visibel sehingga dapat diketahui. Lebih lanjut kata Plato, kebenaran adalah obyek dan syarat pertama pengetahuan.
Aristoteles memahami kebenaran melalui ide mengenai physis yang adalah Being. Kebenaran ialah suatu perjumpaan antara subyek yang mengetahui dan obyek yang diketahui. Apa yang dipahami Aristoteles tentang kebanaran dilanjutkan oleh Heraklitos. Dengan mendasarkan pada kata-kata "Cogito ergo sum", Descartes mengakui bahwa kebenaran yang paling mendasar ialah "Aku" sendiri.
Merefleksi lanjutan dari Descartes, Hegel kemudian menyimpulkan bahwa kebenaran itu segala-galanya, yang utuh dan absolut yang selalu sadar dan hadir dalam dirinya dan diperlihatkan dalam perjalanan epok sejarah. Dan kebenaran dalam pemikiran M. Heidegger dikatakan suatu keterbukaan Being (aletheia), yang didasarkan pada keterbukaan Dasein terhadap cahaya Being.
Dari pembicaraan tentang kebenaran, Foucault malahan sedikit pun tidak menyentuh soal kebenaran ini. Foucault malahan berbicara bahwa omong tentang kebenaran yang menurutnya suatu problematika, sebenarnya bukan soal kebenaran itu. Tetapi bagaimana cara kita berbicara seputar kebenaran.
Makanya Foucault menyebut kira-kira ada dua cara omong soal kebenaran, yaitu pertama, bahwa kita harus masuk dalam problematikan kebanaran. Ketika sudah masuk maka yang dipakai ialah menalar dan mengajukan argumentasi hingga mencapai keputusan atau kesimpulan. Cara kedua ialah dengan analisis kebenaran itu sendiri.
Terhadap hal ini, Foucault menegaskan, "menyangkut bagian yang berkenan dengan cara menentukan entah suatu pernyataan itu besar, kita memiliki akar-akar tradisi besar dalam filsafat barat yang lebih suka saya sebut "analisis kebenaran." Dari omong tentang kebenaran, lebih lanjut Foucault menegaskan, bahwa didalam parrhesia kita mau mengetahui tentang kebenaran atau menceritakan tentang kebenaran.
Demokrasi Indonesia tentang hak bersuara: macam apa itu?
Demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Didalamnya diatur secara implisit mengenai hak bersuara, berkumpul, dan lain-lain, baik secara pribadi maupun secara komunal
Makanya demokrasi kita memang khas kita sehingga disebut sebagai Demokrasi Pancasila. Elemen-elemen penting dan dasariah yang membentuk kepribadian bangsa dan negara kita inilah yang menguatkan sikap dasar mengenai hak-hak demokrasi kita. Salah satunya ialah musyawarah-mufakat.
Demokrasi Indonesia dalam hubungannya dengan hak bersuara ialah musyawarah untuk mencapai mufakat. Sejajar dengan apa yang disebut Foucault, mengenai kebenaran dalam parrhesia yaitu menalar dan berargumentasi lalu mengambil keputusan atau kesimpulan. Bahwa dalam musyawarah, dialog terjadi.
Setiap orang diberi ruang dan waktu untuk bebas berbicara. Setiap orang tidak hanya bebas berbicara, bahkan dibuka ruang untuk berdebat, dan dalam perdebatan itu pertarungan argementasi terlaksana dengan alot.
Satu hal yang menarik dalam sikap berdebat dengan argumentasi yang kuat ialah bahwa masih tetap mempertahankan sopan satu, saling menghargai, dan saling menerima satu sama lain. Bukan musuh, bukan penjahat. Tetapi saudara dalam pencarian bebas berbicara untuk mencapai kebenaran.
Selain sikap berdebat tadi, juga dalam musyawarah itu pun diberi kesempatan untuk menalar atas pokok-pokok pembicaraan serentak berargumentasi.
Dalam ranah inilah, kebenaran yang ada dalam dialog, diperdengarkan. Disinilah, kebenaran berargumen dan kritis terhadap argumen menjadi dasar dalam suatu keputusan. Ukurannya apa? Ukurannya ialah daya nalar dan argumentatif, bukan kekuatan berbicara dan asal berargumen. Menalar berarti mendalami, menyelami pokok-pokok pembicaraan dan menyangganya dengan argumen yang tidak hanya benar tetapi tepat.
Bukan duduk dan bermimpi lalu berdiri mengetuk permukaan mic dan berteriak, saya tidak setuju! Atau tidak setuju lalu diungkapkan dengan cara melempar-lempar sesuatu atau marah-marah.
Unsur subyektif begitu kelihatan. Panggung musyawarah menjadi panggung pasar atau teater belaka. Musyawarah menjadi sandiwara. Ini yang tidak sesuai dengan makna terdalam parrhesia dan konteks demokrasi ala Indonesia.
Kita sangat beruntung bahwa rumusan, musyawarah sampai mufakat itu dibuka ruang atas voting. Voting, diandaikan menalar benar dan argumentatif sama kuat.
Bukan karena berbicara asal bunyi dan karena itu suara terbanyak. Dalam musyawarah mencapai mufakat daya menalar itu memiliki kekuatan karena berangkat dari "pengetahuan subyektif" yang kredibel dan diteguhkan dengan argumentatif ilmiah kritis. Maka tidak salah, semangat musyawarah mufakat diawal-awal bangsa dan negara ini berdiri sangat merdeka, bebas dan otonom.
Parrhesia yang telah lama dikembangkan di masa Euripides (Yunani), hingga 17 Agustus 1945, entah sadar atau tidak benar-benar dijalankan oleh para pendiri dan pejuang bangsa dan negara ini.
Bebas berbicara tetapi dengan isi yang benar, menggambarkan kredibilitas seseorang. Panggung publik menjadi yang dipakai untuk mendapat informasi yang benar, akurat, dan benas isi, jarang dijumpa.
Sopan santun dalam berbicara terkadang menjadi ragu. Sinar-sinar cahaya kebenaran pudar. Makna parrhesia, hampir redup. Karena didalam bebas berbicara, hiasan kata penuh jamak muatan. Esensi pembicaraan dangkal digali dan bahkan lemah dalam argumentatif.
Demokrasi Indonesia, rupanya memiliki warna dasar parrhesia. Masyarakat kita telah menghidupkannya. Pendiri dan pejuang bangsa dan negara ini pun telah menggalinya dari masyarakat kita. Rumusan demokrasi Pancasila yang didalamnya musyawarah mufakat, secara sadar atau tidak didalamnya juga termaktup makna parrhesia, yaitu bebas berbicara diberi ruang dan waktu, penuh dengan murni menalar, argumentatif yang ilmiah dan dilatari tata kramah, adat istiadat, dan kesantunan sebagai bingkai demokrasi Indonesia. ***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H