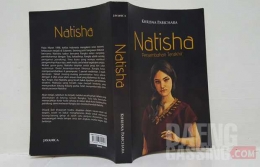Benjamin Franklin pernah berpetuah. Jika ingin dikenang sejarah maka menulislah. Atau, lakukan sesuatu yang layak ditulis. Akan tetapi, bagaimana saya tahu apa itu sejarah dan bagaimana menyejarah jika saya tidak membaca?
Saya selalu terpesona setiap membaca cerita-cerita gubahan Kuntowijoyo, terutama mengenai filsafat yang dikaitkan dengan hal-hal remeh dalam hidup sehari-hari. Perkara-perkara ringan jadi tumpuan filsafat yang berat dan, tanpa terasa, saya terseret arus kata dan makna.
Saya selalu terkesima setiap membaca novel-novel Jostein Gaarder, terutama tentang filsafat yang dibaurkan dengan lika-liku cinta biasa. Hal-hal ringan bercampur aduk dengan hal-hal dalam dan, tanpa terasa, saya dihanyutkan gelombang imajinasi.
Saya selalu terpana setiap membaca tulisan-tulisan Karen Armstong soal teks-teks suci yang dipadukan dengan endapan pemikiran mendalam. Sisik-melik agama yang berat dan dalam ditaja dengan ringan dan mengalir hingga, tanpa terasa, saya ditelan ombak pencerahan.
Dari bacaan-bacaan itu, juga bacaan lain dengan sajian senada, otak saya dididihkan oleh gagasan-gagasan tentang menyajikan esai bahasa Indonesia secara menyenangkan. Bahasa Indonesia, dunia yang saya minati dan saya cintai, ternyata bisa disajikan dengan ringan tanpa kehilangan makna.
Soal kelak akan menyejarah atau tidak, biarlah waktu yang berbicara. Bagi saya, cukuplah menulis saja. Tentu saja saya tetap berharap setiap yang saya tulis meninggalkan kesan dan faedah bagi pembaca. Kalaupun belum, saya tidak risau lantaran saya memang masih dalam proses belajar.
Adalah Pramoedya Ananta Toer yang menggelitik benak saya. Menulis itu bekerja bagi keabadian. Namun, bagaimana saya tahu akan menulis bagi keabadian kalau saya tidak membaca?
Salah seorang guru yang saya kagumi dalam dunia tulis-menulis adalah Bambang Trim. Beliau yang pertama kali menyuntikkan semangat ke dalam tubuh saya agar tidak ragu membukukan ide-ide sepele di benak saya.
Mula-mula saya temui beliau lewat buku-buku tentang cara mudah menulis buku. Saya mamah buku-buku karangan beliau. Saya pendam dalam-dalam di dasar kalbu. Kemudian, bersama setumpuk tulisan, saya temui beliau di Bandung. Dari situ bermula kelahiran buku-buku saya.
Salah seorang guru yang saya takzimi dalam dunia karang-mengarang adalah Hernowo Hasyim. Beliau yang paling getol menggedor-gedor saya untuk tidak berhenti menulis. Beliau pula yang melihat potensi saya dalam mengudar dunia potensi otak dengan bahasa yang ringan.
Saya temui beliau lewat buku-buku mengenai ikat-mengikat makna. Lalu, bersama setumpuk tulisan tentang neurologi, saya sambangi beliau di Bandung. Beliau tunjukkan apa yang kurang dan perlihatkan sisi yang lebih dari tulisan saya.
Pram, Bambang, dan Hernowo telah mengayakan batin saya. Kekayaaan itu tidak akan saya temukan seandainya saya tidak membaca. Beliau bertiga telah merangsang gairah saya untuk tidak berhenti pada sebatas membaca, tetapi terus menopang hidup dengan menulis.

Jika itu sudah terjadi, otomatis menulis akan menopang hidup saya. Kalaupun belum secara saksama menopang biaya hidup keluarga saya, itu perkara nasib. Penulis di negeri ini memang bernasib unik. Selain pajak 15% atas royalti yang hanya 10%, masih ada permintaan buku gratis dari orang-orang dekat atau orang-orang yang merasa dekat.
Sederhananya begini. Jika sebuah buku yang dikarang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dijual seharga Rp100.000,00 maka penulis berhak atas royalti Rp10.000,00 per buku. Apabila terjual 1000 buku, berarti penulis menerima royalti sebesar Rp10.000.000,00.
Kemudian, negara menarik pajak sebesar 15% atau Rp1.500.000,00. Jadi penghasilan penulis sebesar Rp8.500.000,00 dalam rentang enam bulan. Apabila dibagi per bulan menjadi Rp1.416.666,00. Bayangkan apabila si penulis hanya menulis alias tidak punya pekerjaan lain. Bayangkan jika si penulis punya tiga orang anak yang butuh uang jajan, biaya sekolah, ongkos kesehatan, dan biaya makan sehari-hari.
Bayangkan jika 15 teman meminta buku gratis. Berarti buku seharga Rp1.500.000,00 harus ditanggung sendiri oleh penulis. Berarti satu bulan royalti bablas. Berarti satu bulan anak-istri si penulis terpaksa gigit jari dan menahan lapar.
Tidak. Negara dengan tarikan pajak sebegitu besar, dan tidak mengakui penulis sebagai salah satu profesi di kartu pengenal kependudukan, sebenarnya tidak salah. Teman-teman penulis yang suka minta buku gratis juga tidak salah. Penulis yang salah. Lah, siapa suruh menjadi penulis.
Sekalipun demikian, penulis tidak akan berhenti menulis. Getir hidup tidak akan mematahkan semangat berbagi. Pahit nasib tidak akan mengendurkan hasrat berbagi. Setidaknya dalam satu tulisan selalu ada ilmu yang dimanfaatkan. Syahdan, itu jenis pahala yang abadi. Tidak terputus.
Itulah enaknya jadi penulis.
Siradjuddin Bantang, maestro kesenian tradisional Makassar, merapal lima kata. Menulis itu merekam perjalanan hidup. Namun, bagaimana kita tahu akan tulisan yang mampu merekam perjalanan hidup apabila saya tidak membaca?
Umur saya niscaya tidak akan sepanjang usia Nabi Adam, Nabi Idris, atau Nabi Nuh. Bahkan mungkin tidak sepanjang usia kakek saya, Punda Manrawa, yang mencapai 130-an. Di situlah pentingnya menyejarahkan diri lewat tulisan.
Paling tidak, saya meninggalkan jejak tatkala saya sudah tiada. Kerabat saya tidak akan bingung jika ada yang menanyakan perihal siapa saya atau apa yang pernah saya lakukan. Jawabannya ringkas. Khrisna penulis dan salah satu karya, sekadar menyebut contoh, adalah novel Sepatu Dahlan.
Kalau mau jawaban lebih panjang juga bisa. Tinggal menyatakan bahwa Khrisna peduli pada kisah-kisah berlatar Bugis-Makassar. Lihat saja dalam Natisha, Gadis Pakarena, atau Barichalla. Beres. Selesai. Dengan begitu, amanat Pram mengenai bekerja bagi keabadian sudah saya kerjakan.

Bagaimana saya tahu itu? Karena saya membaca. Namun, bagaimana saya akan menulis perkara yang sama jika saya tidak banyak membaca?
Padahal, sebagaimana disitir maestro Sinrilik, Siradjuddin Bantang, menulis adalah merekam perjalanan hidup. Apakah yang saya baca sepanjang perjalanan batin saya? Apakah tiap-tiap yang saya baca itu, terutama yang memacu kegelisahan, sudah saya tulis?
Masih ada pertanyaan lain. Adakah momen-momen krusial yang dilewatkan oleh mata saya? Adakah yang tidak terlewati sudah saya tuangkan ke dalam tulisan? Sungguh, orang-orang yang hidup setelah saya pasti akan menggunakan tulisan sebagai jembatan untuk mengetahui kondisi saat ini, seperti saya menggunakan tulisan untuk tamasya ke masa lalu.
Namun, bagaimana saya tahu akan informasi apa yang penting bagi generasi setelah saya jikalau saya tidak banyak membaca?
Kakek saya, Punda Manrawa, adalah penghafal bositimurung (roman dalam sastra lisan Makassar). Beliau dapat menghafal isi bositimurung hingga titik dan komanya. Kakek saya yang lain, Silang Magga, penulis kittak parakara (kitab berisi tamsil-tamsil kehidupan dalam bahasa Makassar). Beliau mahir menulis dalam aksara Makassar atau aksara Arab berbahasa Makassar. Namun, bagaimana saya akan mewarisi kebiasaan mereka jika saya tidak membaca?
Semasa kecil hingga dewasa, hampir setiap waktu saya memegang buku. Saksi-saksi masih hidup hingga sekarang. Bakaring, kakak sulung saya, masih bugar. Ram Prapanca, guru saya semasa SMA, masih sehat sentosa. Amel, perempuan yang saya cintai karena cinta kepada-Nya, masih segar bugar dan penuh pesona.
Namun, makin banyak yang saya baca berasa makin banyak pula yang tidak saya ketahui. Berasa makin sedikit yang saya tahu. Persis setitik air di samudra.
Demikian getol saya membaca, sampai-sampai apa yang saya baca sering saya angankan menjadi kenyataan. Cerita cinta, luka-luka, pujian, dan hinaan yang dialami para tokoh yang saya baca kisahnya seolah merupakan kisah saya sendiri.
Kadang saya merasa melompat ke tahun 1660-an dan menjadi Sultan Hasanuddin pada satu ketika dan menjelma Arung Palakka pada ketika yang lain. Kadang saya merasa tercebur ke masa-masa perih Datu Museng dan melihat Maipa Deapati tergugu menunggu takdir.
Kadang saya merasa bagai Sawerigading yang dilarang menikahi We Tenriabeng dan ditolak lamarannya oleh We Cu Dai. Kadang saya mengira diri saya adalah I Maddi Daeng Rimakka yang dituduh mencuri kuda milik Karaeng Bontotangnga.
Saya juga pernah merasa bahwa sayalah Romeo yang tersungkur di sisi Juliet. Atau Sangkuriang yang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Atau Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi dalam semalam bagi Rara Jonggrang. Atau menjelma tokoh sebijak Krishna sekaligus setegar Zeus.
Padahal saya bukan siapa-siapa. Karena membaca, saya sering berangan-angan atau beringin-ingin menjadi seperti tokoh dalam cerita yang berperang, berselisih, menderita luka dan hina, menerima pujian serta penghargaan, dan menikmati hidup tanpa nestapa.
Namun, bagaimana saya akan menulis dengan baik jika saya tidak membaca? Itu saya. Bagaimana dengan kalian? Hidup amatlah singkat. Hanya menulis yang dapat membuat umur kita lebih panjang, malahan dapat jauh melampaui usia kita. Namun bagaimana kita bisa menulis dengan baik jika kita tidak membaca?
Menulis sejatinya upaya merawat nyali dalam menjalani hidup yang tidak sempit dan berani menjelajahi dunia berbeda. Namun, bagaimana kita tahu akan hidup yang luas dan terinspirasi untuk menjelajahi dunia berbeda jika kita tidak membaca?
Aktivitas membaca bukan sekadar mengenali suku-suku kata, mengeja kata demi kata, atau mengintimi rangkaian kalimat-kalimat, melainkan memberi asupan gizi bagi otak sebagaimana kita membutuhkan gizi untuk membentuk otot.
Hanya dengan membaca maka kita berpotensi menulis dengan baik. Hanya itu.
Pada akhirnya, hidup adalah rangkaian pengalaman batin yang akan berguna jika kita jadikan cermin. Begitu petuah Kuntowijoyo. Namun, bagaimana kita tahu pengalaman mana yang dapat dijadikan cermin jika kita tidak membaca?
Kandangrindu, 2018
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H