Maka, kubiar diriku seperti seekor ikan kecil di lautan. Menikmati ketenangan ceruk-ceruk keheningan di kedalaman, agar tak mengusik terjangan gelombang pasang dan riak ombak di permukaan. Aku memilih tenggelam. Namun, tidak diam.
Kedua. Berbatas Melompati Batas
Dalam berbagai kesempatan, aku kerapkali menyebut diriku "orang hutan". Curup tempat kelahiran, sekaligus tempat berdiam dan menambang rezeki, kugambarkan seperti "hutan". Secara kata maupun makna.
Terkadang, hutan menjadi petilasan sepi menguak sunyi. Mencumbui embun, menyiangi cahaya mentari, menyaksikan kesahduan senja dalam pergantian hari. Atau merimbunkan bisikan kerinduan di butiran hujan yang berjatuhan.
Dan, mengubahnya menjadi senjata rekaan dengan peluru bersayap kata-kata.
Namun, tak pula mampu kubantah. Hutan memiliki titik batas dari keliaran negeri antah berantah. Perkelahian tak perlu serta ritual berjibaku dengan gulir waktu, menjadi alasan klise deretan berita dan barisan cerita.
Mungkin, alam memiliki caranya sendiri, agar orang-orang, termasuk aku tak perlu melampui batas.
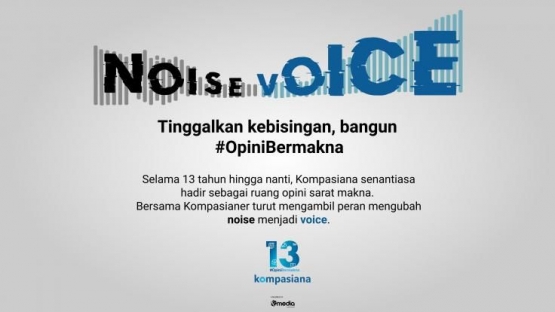
Ketiga. Mengikat Tanpa Ikatan
Nyaris tiga tahun berlalu, aku merasakan ada ikatan di Kompasiana. Tentu saja bukan, tentang tulisanku yang tak seberapa, dan pasti kalah jauh dari legenda hidup di Kompasiana. Baik Secara kuantitas maupun kualitas.
Sebut saja Mamanda Tjiptadinata Effendi, Pak Katedra Radjawen, Mas Hendro Santoso, Suhu Susy Haryawan, Uda Irwan Rinaldi Tanjung, Prof Felix Tani, Pak Rustian Ansori, Mbak Suprihati, hingga Mbak Lilik Fatimah Azzahra. Aih, barisan nama ini akan semakin memanjang.












