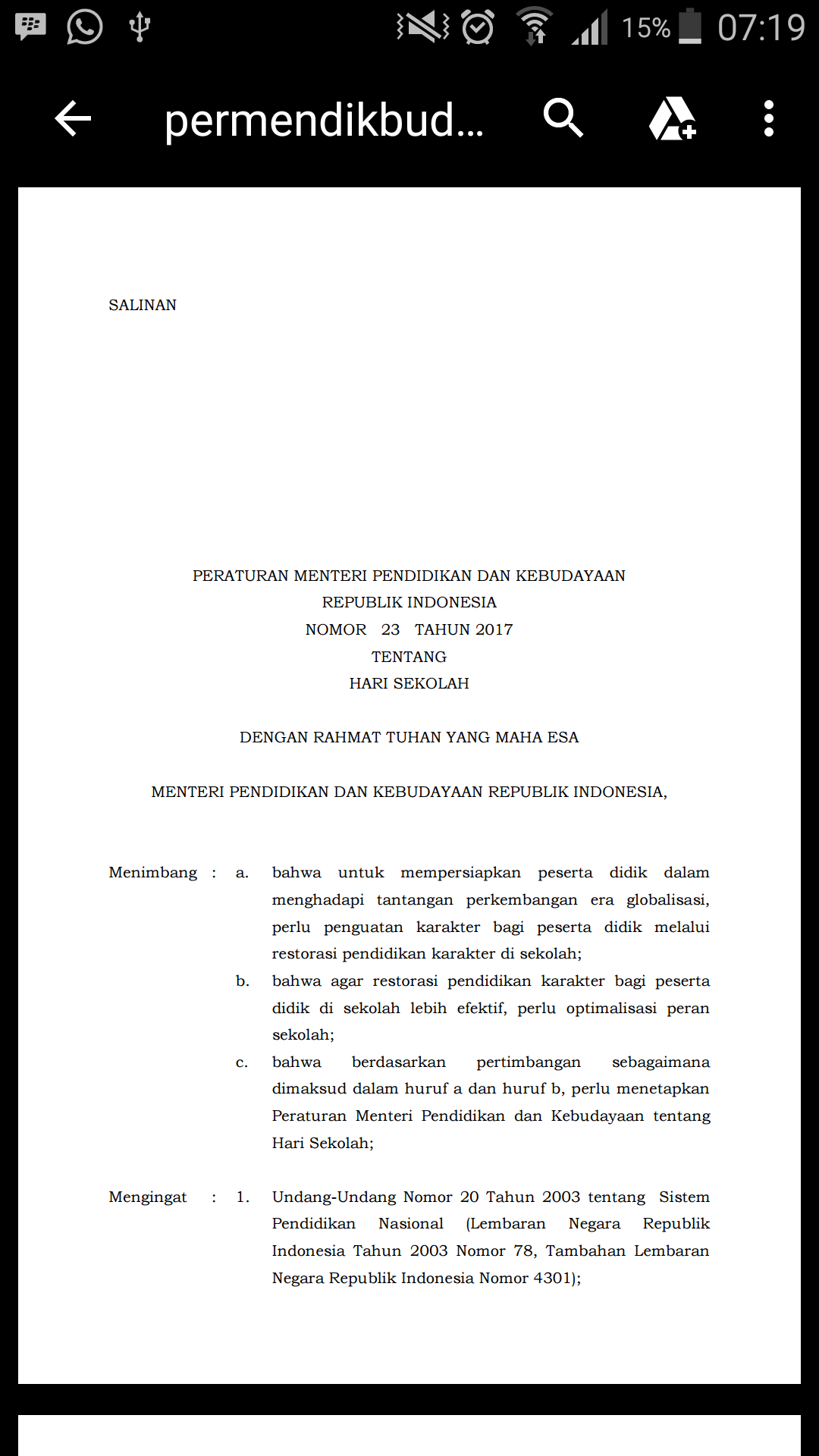Kebijakan kontreversial Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Medikbud) yang sedang hangat dibicarakan di seantero negeri adalah tentang Lima Hari Sekolah (LHS). Kebijakan ini lahir dengan diimplementasikannya Permendikbud No. 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Di sebut kontroversial karena banyak pelaku pendidikan yang kurang setuju dengan kebijakan ini, walaupu kebanyakan aktor pendidikan wait and see terhadap implementasi permendikbud ini.
Yang paling getol menyuarakan penolakan adalah aktivis Nahdlatul Ulama, para pelaku Madrasah Diniah (MD) baik MDA atau DTA, Taman Pendidikan Qur’an, Sekolah dalam naungan pesantren dan para pemerhati pendidikan. Salah satu guru besar Pendidikan mengatakan kepada kami dalam group WA para ahli kurikulum, “Tampaknya kebijakan kita; ngomong duluan setelah itu mikir”.
Seorang kawan yang protagonis dan guru Besar keislaman UIN Jakarta dalam postingan di FB mengatakan kurang lebih “kaji dulu permendikbud No. 23 baru bisa ngomong, atau mengkritiknya.” Dalam konteks ini saya sangat setuju sehingga saya harus mereview ulang tulisan-tulisan awal tentang “Produktivitas Full Day School” pada dua bulan yang lalu, atau tulisan tiga hari yang lalu tentang “Pertempuran Sengit di Medan Full Day School”.
Walaupun tulisan-tulisan itu adalah analisa yang lahir dari wacana sebelum lahirnya Permen 23 itu (saat awal Mendikbud diangakat jadi menteri), namun saya tegaskan bahwa sepertinya nilai kritis di dalamnya masih relevan dan bersenyawa dengan kebijakan permendikbud ini. Ada pun persamaan dan perbedaan antar analisis itu dengan teks permendikbud, maka dengan tulisan ini saya mencoba menguraikannya. Walaupun saya tidak menganalisis perkalimat, karena terlalu berjibun, saya akan ambil prinsipnya saja. Tidak ada tendensi apa-apa tentang kebijakan ini, paling tidak saya bisa berargumentasi dalam melihat “pertempuran’ protagonis dan antagonis dalam menghadapi fenomena ini.
Terakhir, saya mendapatkan informasi viral melalui group WA bahwa pokok pertemuan Dirjen Dikdasmen dengan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag di ruang Rapat Dirjen Dikdasmen Lt. 5 Gd. E pada tanggal 12 Juni 2017 menyimpulkan bahwa tidak ada yang perlu diresahkan tentang Pendidikan Islam yang “gulung tikar” dan justru menjadi sebaliknya, MD akan booming dan menjadi program nasional karena pada dasarnya Full Day School (FDS) adalah penguatan karakter siswa di sekolah. Masalah teknis akan dibicarakan melalui konsolidasi pihak terkait.
Kasus di atas, dari anatgonis, protagonis dan diskusi yang akrab dan hangat antar lembaga yang memiliki kepentingan pendidikan di negeri ini telah mencerminkan kepada kita betapa hebatnya dampak permendikbud No 23 tahun 2017. Semua tokoh dari PBNU, MUI, Para pemerhati pendidikan, Kemendikbud dan Kemenag begitu riuh membicarakan ini di berbagai kesempatan terutama dunia pemberitaan. Di group medsos yang saya ikuti pun begitu banyak yang menumpahkan perasaan dan ke(tidak)berpihakan mereka atas permen ini.
Permendikbud ini saya bagi bahasannya menjadi tiga bagian; bagian tentang relasi guru dan hari sekolah (pasal 3 dan 4), bagian kegiatan-kegiatan hari sekolah (pasal 5), dan bagian penetapan kebijakan dan implementasi hari sekolah (pasal 8). Permendikbud ini sangat sederhana dan tidak rumit untuk ditafsirkan sehingga maknanya jelas dan tidak anti kritik. Di dalamnya juga tidak ada satu kata pun menyinggung kata “FDS” sehingga FDS bisa jadi akronim sederhana untuk mengganti LHS (lima hari sekolah dengan 8 jam perhari, 40 jam sepekan). Saya kira tidak salah kita mengganti LHS dengan FDS asal ada konsensus kita bersama.
Pertama, pasal yang menjadi pokok alasan dalam penerbitan permendikbud ini adalah tentang beban kerja Guru. Guru yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tunduk pada UU No. 5 tahun 2014 dimana mereka memiliki beban kerja selama 40 Jam perpekan. 40 jam inilah yang menjadi alasan utama jumlah hari sekolah di lima harikan dengan penambahan jam setiap harinya menjadi 8 jam dari 5 – 7 jam sebelumnya.
Sebagaimana kebijakan awal bahwa kewajiban mengajar guru adalah 24 jam pelajaran (JPL) sepekan. Jadi dalam lima hari guru bisa mengajar 24 jam, sesisanya mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, mengukur, dan mengevaluasi siswanya. Melalui paradigma lama guru, 24 jam ditafsirkan mentransfer ilmu, sehingga terminologi “mengajar” lebih pas. Ada 16 jam untuk kegiatan lainnya.
Faktanya, setiap guru ASN yang mengajar di sebuah sekolah tidak full berangkat ke sekolah selama enam hari dalam sepekan. Dengan jumlah guru yang banyak di sekolah, semua memilki jadwal yang tidak tumpang tindih. Mereka bisa datang ke sekolah selama 4 hari untuk mengajar dan satu hari untuk piket. Atau mereka tiga hari mengajar dan dua hari untuk melaksanakan tugas guru lainnya. Untuk mayoritas guru, sepertinya 5 hari waktu ke sekolah sudah ada sejak 24 JPL itu diimplementasikan (ingat, guru sebagai pegarai fungsional, bukan struktural).
Jadi, permendikbud ini adalah legalisasi atas tradisi mayoritas guru mata pelajaran (GMP) di sekolah, dan ini tentu saja berbeda dengan guru kelas (GK) di SD yang harus masuk 6 hari setiap minggu dengan tidak ada kewajiban 24 JPL tadi. Untuk kasus GMP, saya kira tidak ada yang perlu dikwatirkan karna memang sudah tradisinya begitu, namun ada masalah di GK. Mereka akan dipaksa untuk memepercepat perkembangan kognisi siswa. Kita tahu, semakin lama di sekolah, maka semakin bosan siswa-siswa SD kita. Ini akan menjadi masalah yang sangat serius.
Ketika LHS ini menjadi 5 hari dan GMP berbarengan masuk sekolah, maka sekolah akan sesak dengan guru. Bila saja sarana kantor guru memadai dan fasilitas gurunya sangat menunjang, bisa jadi ini merupakan perubahan besar-besaran tentang performance guru di sekolah. Mereka akan banyak berdiskusi di sela-sela mengajar dan mereka pun akan saling berinteraksi memperbaiki kualitas masing-masing. Namun bila sebaliknya, maka akan ada waktu yang kontra produktif bagi guru. Bila saja paradigma lama terus dilakukan, maka guru akan finger print ke sekolah sebagai kehadiran dan kemudian meninggalkan sekolah karena tidak ada jadwal mengajar. Mereka bisa melupakan fungsi gurunya (yang beberapa kali ditekankan dalam permendikbud ini) yakni membimbing, mengarahkan, melatih, mengukur dan mengevaluasi.
Menurut saya, bila permendikbud ini diawali dengan landasan dasar jam kerja ASN, maka ini tidak adil. 40 jam kerja ASN dipaksakan untuk melakukan perubahan sistem yang sudah tertata rapih adalah hal yang kurang dewasa, toh mereka sudah melakukan 40 jam di sekolah pada sistem yang berjalan. Sekolah itu tentang siswa bukan tentang guru. dimensi siswa harus dominan dalam landasan merubah sistemnya, bukan karena gurunya. Bila siswa itu beragam dari berbagai sudut semisal kota-desa, dasar-menengah, akademik-kejuruan, kebutuhan-bakat, maka tidak akan bisa dipukul rata dalam memandangnya. Kita bisa memukul rata jam kerja guru, namun kita tak bisa memukul rata siswa. Jadi sekolah itu milik siapa? Guru atau siswa?
Kedua, kegiatan belajar siswa dalam LHS. Disebutkan bahwa 8 jam ala FDS dan 40 jam sepekan akan dilaksanakan intra kurikuler, kokurikuler dan ekstra kurikuler. Intra dan kokurikuler sangat erat hubungannya dengan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah, bedanya dalam model pembelajarannya saja antara pembelajaran tatap muka dan penguatan tatap muka, sedangkan ekstra kurikuler dapat beraneka ragam kegiatan, baik karya ilmiah, krida, olah bakat/minat dan keagamaan.
Dalam konteks pendidikan menengah di SMA ataupun SMK, tiga kegiatan ini sudah dilaksanakan sebelum pemendikbud ini lahir. Karena pendidikan menengah ini sudah hampir putus dengan MD, maka melalui program “pengembangan diri” di sekolah, saat sepulang kegiatan intra dan kokurikuler, ekstra kurikuler dilakukan secara terstruktur di sekolah. Jadi tidak ada yang baru dalam konteks pendidikan menengah.
Mungkin ini menjadi asing bagi pendidikan dasar (SD dan SMP). Biasanya mereka pulang antara jam 12 (SD kelas atas) dan jam 13 (SMP) mereka melanjutkan kegiatan di lingkungannya. yang paling banyak dilakukan di masyarakat pedalaman dan kota-kota kecil di Indonesia adalah masuk ke MD. Mungkin hal ini kasuistik di kota besar macam Jakarta, ada yang masih memegang teguh MD ada juga yang telah menggantinya dengan bimbel atau les dengan gurunya atau lembaga lain. Ini sangat bervariatif.
Mungkin inilah pangkal dari masalah permendikbud ini yang banyak dikritik berbagai kalangan terutama aktivis pendidikan Islam. SD dan SMP sebagai input MD di take over oleh sekolah, dimana hanya menyediakan opsi keagamaan berbagi dengan kegiatan lainnya semacam krida, karya ilmiah, dan olah bakat/minat. Awalanya 6 hari mereka dididik dengan agama yang 100% untuk mengolah jiwa keagamaan mereka dan tentu saja penguatan identitas keagamaan mereka, hari ini “disingkirkan” secara terstruktur oleh sekolah dengan kegiatan lainnya. Bila saja kita adil dalam permendikbud itu, maka dalam ekstra kurikuler itu 25% karya ilmiah, 25% krida, 25% olah bakat/minat dan 25% keagamaan. Jadi MD kehilangan 75% haknya untuk mendidik. Itu kalau adil.
Bila saja MD dipanggil ke sekolah, maka kemanakan eksistensi MD sebagai lemabaga pendidikan yang mandiri? Bila saja pihak siswa yang datang ke MD, maka dimana transportasinya dan ada tidak anggarannya? Kalau ada atau ditangguhkan, berapa lama waktu yang dibuang untuk ke MD dan pulang ke rumah dari jarak ke sekolah. Ini sangat membutuhkan pemikiran panjang dan kontra produktif. Untuk ulasan yang mendalam bisa dilihat di tulisan lalu “Peperangan Sengit di Medan FDS”
Penguatan karakter yang menjadi pondasi kegiatan intra-ko-dan ekstra kurikuler yang dipromosikan dalam permendikbud ini adalah sesuatu yang sudah ada. Relijius, nasionalis, integritas gotong royong, dan kerja keras yang diprioritaskan oleh Mendikbud (walau tidak disuratkan dalam permennya) adalah sesuatu yang baik dan harus dibagi-bagi kegiatannya. Bisa jadi karakter nasionalis, integritas dan kerja keras dititipkan di sekolah dan karkater relijius-gotong royong dititipkan di MD (untuk kasus Islam). Yang terpenting ada kolaborasi antar lembaga yang serius. Bila alasan utamanya untuk menghindari terorisme, apakah Mendikbud sekerdil itu menuduh MD yang 7000an dan 7juta santrinya?
Ketiga, pelaksanaan LHS diimplementasikan pada tahun akademik 2017/2018. Permendikbud ini dilahirkan dari lembaga dengan logo “Tut Wuri Handayani” ini pada Juni 2017. Bulan ini sangat berdekatan dengan Juli 2017 sebagai awal tahun ajaran 2017/2018. Bila pengetahuan SD kita sama, hitungan harinya tidak sampai kepada 100 hari. Apakah ini rasional? Atau kalau saya boleh berprasangka, ada apa di balik semua kebijakan ini? Apakah benar mau membunuh lembaga pendidikan di luar persekolahan? Saya tidak menemukan jawaban dengan logika yang sehat.
Jawaban sementara dalam permendikbud itu adalah permen ini dilaksanakan bagi sekolah yang siap dan secara bertahap akan dilaksanakan secara nasional dan integratif. Saya melihat kegagalan kurikulum 2013 (K-13) yang didesain tahun 2012 selama kurang lebih 6 bulan persiapan dan dipaksa diimplementasikan di Juli 2013 di sekolah project pilot bisa menjadi contoh pas. Tarik ulur K-13 dalam kesiapannya belum juga selesai pada tahun ini. Sudah 4 tahun kita tarik ulur K-13, dan sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Apakah kebijakan ini (LHS) juga akan sama nasibnya dengan K-13. Kalau iya, kita benar-benar masuk jurang yang sama.
Dengan menggunakan terminologi bagi sekolah yang siap, maka saya menerka ini untuk menutupi ketidak mampuan negara dalam mengimplementasikan idenya secara menyeluruh. Tidak ada keadilah nasional bila terminologi ini disampaikan dalam sakralitas permendikbud yang cakupannya nasional. Seharusnya, project pilot sekolah dengan segala kematangan sistemnya harus diuji publikan dahulu, agar sistem LHS ini tidak konfrontatif.
Bila saya bisa berkomentar, ini bukan permen tapi panduan untuk sekolah yang ingin membuat model FDS. Model ini sudah banyak lahir sebelum LHS ini di permen-kan. Ada FDS yang begitu banyak di perkotaan, ada sekolah “plus” di manajemen sekolah berbasis pesantren, ada sekolah Islam Terpadu (IT) pada sekolah yang meyakini atas nilai-nilai Islam dalam persekolahannya. Ada juga sekolah internasional yang menganggap bahwa sekolah harus memilki nilai-nilai globalisasi yang baik. Mereka adalah FDS yang disebutkan dalam permen itu. Jadi, menurut saya, permendikbud no 23 tahun 2017 ini harus diganti judulnya bukan LHS tapi menjadi Model FDS. Isinya tentu saja harus ada juklak juknis bagaimana FDS yang beragam itu distandarkan sehingga Indonesia memiliki kekhasan FDS secara nasional. Wallahu a’lam.
Bumisyafikri, 15/06/17
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H