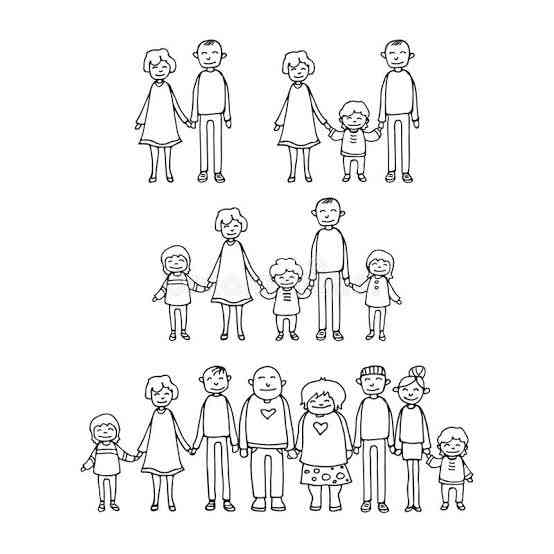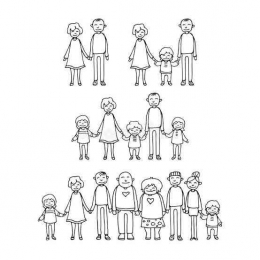Belakangan ini, banyak muncul pembahasan soal childfree di Indonesia, lengkap dengan pro-kontranya. Banyak yang sudah memperdebatkan ini, dan kalau terlalu diikuti bisa seperti labirin, tidak tahu dimana titik akhirnya.
Jujur saja, kalau dilihat lagi, bahasan soal childfree di Indonesia sebenarnya berada dalam satu irisan, antara budaya dan logika rasional khas era kekinian.
Soal budaya, pengaruhnya didominasi oleh paradigma klasik soal aspek reproduksi dalam satu pernikahan. Seperti diketahui, salah satu tujuan dasar pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, guna menyambung garis keturunan.
Di negara-negara monarki, keberlanjutan garis keturunan raja selalu jadi perhatian. Ambil contoh, sampai tahun 2005, rakyat Jepang sempat ketar-ketir ketika Kerajaan Jepang masih belum punya generasi penerus tahta.
Kecemasan itu sendiri lalu berubah jadi kegembiraan dan optimisme, ketika Pangeran Hisahito lahir tahun 2006.
Dalam lingkup lebih kecil, kita juga banyak menemui pejuang garis dua, yang rela mengorbankan biaya, waktu, sampai perasaan, demi dikaruniai anak. Jadi, bisa dimaklumi juga kalau pandangan childfree terasa seperti satu penghinaan buat usaha mereka.
Tapi, kalau salah satu faktor dasar pada pandangan childfree dicermati secara mendalam, sebenarnya ini bisa jadi medium evaluasi sebelum mantap menikah dan berkeluarga (dalam hal ini punya anak).
Seperti diketahui, salah satu pertimbangan dasar bagi mereka yang memilih childfree adalah berkenaan dengan biaya besar dalam membesarkan anak.
Dengan besaran biaya yang semakin besar di berbagai aspek, bisa terbayang seberapa besar biaya dalam merawat dan membesarkan anak, lengkap dengan beragam biaya tak terduga yang jumlahnya seabrek.
Mulai dari sejak masih berada dalam kandungan, lahir, sekolah, kuliah, sampai akhirnya bisa mandiri. Ini sebuah rentang waktu yang tidak sebentar.
Itu baru biaya, belum termasuk beragam potensi masalah lain seperti kesehatan fisik dan mental yang sudah pasti sangat melelahkan, kadang juga butuh biaya ekstra.
Sampai di sini, bisa dipahami mengapa childfree bisa jadi satu pilihan sikap yang diambil. Bukan hanya pada mereka yang menikah, tapi juga pada mereka yang memutuskan tidak menikah.
Sebagai satu pilihan sikap, sebenarnya ini bukan satu kesalahan, karena memang jadi bagian dari keseimbangan: ada orang yang memang ingin punya anak, ada yang tidak.
Kalau menikah tapi memilih sepakat untuk tidak ingin punya anak pun, sebenarnya tidak salah. Apalagi, kalau pernikahan tersebut sudah sah secara hukum legal dan agama. Toh, mereka sudah jujur soal ketidaksiapan punya anak.
Satu lagi, keputusan childfree karena memang tidak ingin punya anak seharusnya juga bisa jadi pembelajaran mental, khususnya buat mereka yang ingin punya anak.
Selain siap secara finansial, kesiapan secara mental seharusnya juga jadi satu perhatian penting saat memutuskan ingin punya anak.
Kesiapan mental ini penting, karena akan berpengaruh pada baik-buruknya perilaku si anak. Orang tua yang siap mental untuk punya anak tidak akan memandang anak sebagai trofi berjalan atau investasi, tapi sebagai sebuah tanggung jawab.
Lebih baik punya anak sedikit tapi dibiayai dan dididik seperti seharusnya oleh orang tua yang siap luar-dalam, daripada banyak anak tapi tak terurus. Anak bukan semata soal jumlah, tapi soal seberapa berkualitas dia sebagai seorang manusia.
Jadi, kalau siap menikah tapi tidak siap mental punya anak, jangan salahkan siapapun kecuali pasangan itu sendiri, karena ketidaksiapan mereka justru bisa jadi awal munculnya generasi "rusak" yang bisa jadi akan semakin ambyar di masa depan.
Sudah ada banyak anak tidak bersalah ditelantarkan bahkan jadi korban hanya karena orangtuanya (ternyata) tidak siap mental dan biaya untuk punya anak. Mau sampai kapan?
Keputusan dan pandangan soal childfree baru menjadi satu kesalahan, jika itu dipaksakan menjadi satu kebenaran. Masyarakat yang majemuk jelas akan menolak satu pembenaran sepihak, apalagi kalau ada dikotomi baik-buruk, benar-salah atau semacamnya.
Ada keberagaman perspektif yang membuat urusan punya anak atau tidak bukan untuk diperdebatkan atau diumbar sembarangan. Ini seharusnya privasi, bukan untuk konsumsi umum, kecuali kalau tujuan utamanya hanya untuk pamer.
Pada akhirnya, mau childfree atau tidak, semua kembali ke pribadi masing-masing, karena beda orang beda perspektif. Perspektif sendiri ada bukan untuk diseragamkan, tapi untuk menciptakan satu keseimbangan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H