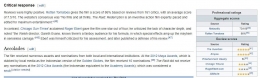Salah satu profesi dalam dunia kepenulisan yang pernah saya masuki adalah menjadi kritikus film. Itu terjadi pada periode tahun 2006 hingga 2009 lalu.
Kala itu, redaktur rubrik entertainment di edisi Minggu koran Suara Merdeka di Semarang, yaitu Budi Maryono, menugasi saya untuk menulis artikel tentang film Indonesia dengan format berupa ulasan kritis, bukan semata berita dan rangkuman data dan fakta seperti artikel-artikel saya lainnya di sana.
Saya pun kemudian sengaja nonton film untuk menuliskan resensinya. Beberapa film yang pernah saya ulas waktu itu adalah Sembilan Naga yang disutradarai Rudi Soedjarwo, Cewe Matrepolis (Effi Zen), Heart (Hanny R. Saputra), dan juga Denias: Senandung di Atas Awan (John De Rantau). Koleksi resensi-resensi tersebut bisa Anda inceng di sini.
Dengan segala kekurangannya, ulasan-ulasan itu memang hanya bisa menempatkan saya sebagai kritikus film amatir. Satu, kala itu saya menulis bukan sebagai anggota jajaran editor Suara Merdeka. Dan dua, saya tak punya background pendidikan soal sinematografi, apalagi pernah kerja di film dalam posisi kreatif.
Saya melakukan amatan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saja soal film, bukan dengan basis berbagai teori sinema yang ndakik-ndakik (tinggi dan kompleks).
Para sineas besar pasti tak akan menganggap penting tulisan-tulisan itu andai membacanya. Meski demikian, ketika itu saya berharap ulasan-ulasan tersebut mengawali satu gerakan kepenulisan yang saat itu nyaris mati di Indonesia, yaitu kritik film.
Di bidang ini, kita punya Leila S. Chudori, yang sudah lama menulis ulasan film di majalah Tempo. Dan kala itu juga muncul laman kritik film Sinema Indonesia (amatir juga) yang menuliskan kritik-kritik terhadap film nasional dengan bahasa yang lucu dan kreatif.
Sayang harapan tinggal harapan. Tak terlihat kemunculan era baru penulisan kritik film sama sekali hingga saya pensiun tahun 2009. Situasi masih sama seperti sebelumnya, di mana urusan kritik film hanya sesekali disebut di penganugerahan Piala Citra, dan satu-satunya tokoh yang dihormati dan didengar di ranah ini masihlah hanya Bu Leila.
Laman Sinema Indonesia pun kemudian berhenti berproduksi. Entah karena para kontributornya kemudian menikah dan kerja kantoran, atau mereka tak tahan berdebat dengan para sineas yang pernah mereka kritik.
Dan hingga hari ini pada akhir 2019, tak ada pergerakan baru apa-apa di bidang penulisan kritik film Tanah Air. Hanya ada tambahan beberapa movie addicts yang menuliskan ulasan kritis mereka di internet. Itu pun masih jauh dari istilah sebuah resensi.
Kadang justru malah berupa testimoni. Padahal yang diperlukan adalah sebuah "jaringan" pengamatan, sehingga baik publik maupun sineas dan pemangku kepentingan komersial dunia perfilman bisa melihatnya dengan ukuran yang sama.
Di dunia perfilman luar negeri---setidaknya pada tingkat Hollywood---kritik film sebagai sebuah sistem sudah berjalan dengan baik. Ada tiga pilar utama kritik film yang mengemuka, dan oleh karenanya kemudian digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kualitas film, baik sebagai komoditas industri maupun "artefak" seni budaya adiluhung. Mereka adalah IMDb (Internet Movie Database), Rotten Tomatoes, dan Metacritic.
Ketiganya menyarikan kritik-kritik film dengan cara yang kurang lebih sama, yaitu mengumpulkan artikel-artikel kritik dari banyak sumber berbeda dan mengambil skor rata-rata. Tulisan yang resmi diakui adalah kritik film dari media-media massa mainstream (awalnya surat kabar harian), seperti The Washington Post, LA Times, Chicago Sun-Times, atau The New York Times.
Tiap media memiliki satu atau beberapa kolumnis expert yang khusus menulis kritik film, seperti Leila untuk Tempo. Beberapa nama yang paling tersohor adalah Roger Ebert (1942-2013) dan Richard Roeper dari Chicago Sun-Times, Claudia Puig (USA Today), Mick LaSalle (San Francisco Chronicles), dan juga James Berardinelli (Reelviews).
Umumnya mereka menulis ulasan setelah diundang menghadiri pemutaran khusus (special screening) yang diperuntukkan bagi kalangan media. Ini biasanya dilakukan beberapa hari sebelum jadwal pemutaran resmi (premiere) film bersangkutan.
Tiap ulasan biasanya memberikan rating skor berupa bintang, antara nol hingga empat atau lima bintang. IMDb, Rotten Tomatoes, dan Metacritic kemudian menghitung dan menampilkan angka rata-rata dari semua kritik film resmi yang masuk ke data mereka. Hasilnya adalah berupa skor atau persentase kritik positif.
Ada berapa persen dari keseluruhan kritik tersebut yang memberikan ulasan positif (disebut thumbs up), dan berapa persen yang sebaliknya (thumbs down).
Film dengan perhitungan rata-rata di atas 75% dianggap sebagai berkualitas. Yang berada di kisaran 40% hingga 70% disebut dengan istilah mixed review alias sedang-sedang saja (karena persentasi kritik positif dengan yang negatif imbang). Sedang angka rata-rata di bawah 40% masuk kategori film jelek. Kita dapat melihat ringkasan angka persentasi ini pada halaman Wikipedia tiap judul film di segmen Reception (atau Release).

Meski secara umum The Raid mendapat rating tinggi terkait ulasan kritis, Ebert justru tak menyukainya dan hanya menghadiahkan satu dari maksimal empat bintang. Ia mendapat kritik atas kritiknya tersebut, dan kemudian harus menerbitkan artikel klarifikasi untuk menjelaskan latar belakang ulasannya.
Kita sebagai penonton pun kemudian sedikit banyak teredukasi soal apresiasi film, setidaknya dilihat dari pengamatan para kritikus film berlatarbelakang jurnalisme (karena ada juga dari background akademik, yang kerap kali dianggap "lebih pantas didengarkan" oleh para sineas).
Dan kita jadi tahu bahwa film sejenis Independence Day dan Godzilla (keduanya karya sutradara Roland Emmerich) atau seri Bad Boys (Michael Bay) jebul dianggap amat jelek, meski populer dan merajai box office.
Sistem itulah yang belum berjalan baik---bahkan belum eksis---di Indonesia. Special screening untuk media massa memang ada, tapi output-nya mayoritas berupa testimoni.
Mungkin karena para jurnalis tak enak hati, karena menaruh respek terlalu besar pada para sineas. Dan bukan sekali dua saya mendengar selentingan bahwa para jurnalis berhenti menulis kritik karena tak tahan didebat (bahkan dimarahi) para sineas!
Padahal kritik penting karena merupakan "pilar demokrasi" dunia seni. Bagaimanapun formatnya, apakah berasal dari warga awam (pembaca/penonton), jurnalis, atau tokoh akademik, kritik membuat para seniman tak bisa berkreasi semaunya.
Ada kontrol, ada pengawasan, untuk kemudian kita harus hati-hati dan njelimet dalam bekerja sehingga terus bisa meningkatkan kualitas. Sebagai novelis, itu benar-benar saya rasakan berdasar sistem kritik buku yang sudah berjalan, baik di Goodreads maupun di kalangan blogger buku.
Di film, kita di Indonesia tak punya orientasi soal pencapaian kualitas tanpa adanya ukuran semacam yang didapat film-film Hollywood melalui lembaga-lembaga pengukur tersebut.
Kita hanya tahu ada film-film (yang dikategorikan) bagus setelah FFI atau Indonesia Movie Awards mengumumkan judul-judul pemenang. Namun di luar itu, kita tak pernah tahu apakah Bumi Manusia, Gundala, atau Menculik Miyabi sesungguhnya bagus atau jelek.
Yang ada hanyalah deretan opini subjektif yang sebagian besar berisi, itu tadi, testimoni.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H