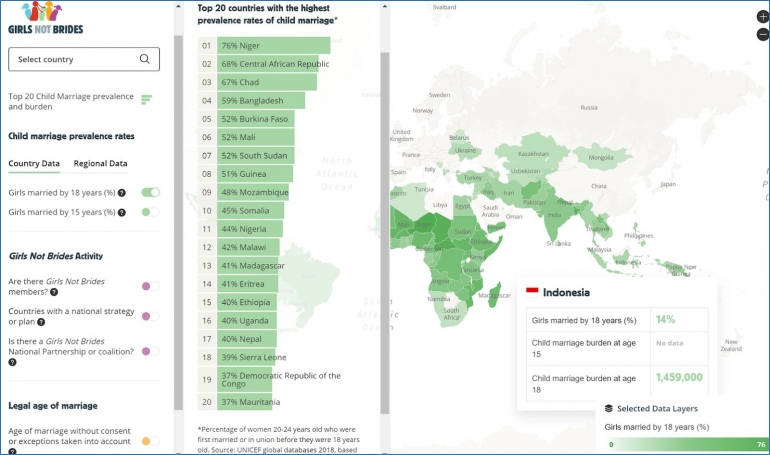Kelima, Insecurity (krisis): para orangtua mempercayai bahwa menikahkan anak-anak mereka yang berusia dibawah 18 tahun dianggap menjadi jalan bagi jaminan finansial. Hal ini semakin parah dalam kondisi konflik dan perang, terutama di wilayah pengungsian. Dengan demikian negara-negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia dianggap sebagai negara rapuh, karena mereka mempertaruhkan masalah ekonomi negaranya pada kualitas sumber daya manusia yang rendah.
Praktek perkawinan anak selain melanggar hak-hak anak yang dilindungi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, juga rentan menimbulkan berbagai kerugian pada anak. Dalam Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Perkawinan, terdapat 4 hal besar hasil kajian dan penelitian atas dampak perkawinan anak di Indonesia, yaitu:
Satu, Pelanggaran atas Hak Pendidikan: Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan dijamin oleh UUD 1945 pasal 28C ayat (1) di mana setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika anak-anak melakukan perkawinan, maka mereka akan putus sekolah, khususnya perempuan yang mengalami kehamilan. Hidup mereka akan semakin sulit karena rendahnya pendidikan akan berperangaruh pada pekerjaan yang berupah rendah, dan mereka pun terjerat kemiskinan dan bisa menjadi korban perdagangan orang (human trafficking)
Dua, Eksploitasi Anak: keluarga miskin cenderung memaksa anak untuk menikah saat usia sekolah dengan alasan mengurangi beban ekonomi keluarga. Padahal, hal ini justru menjerat si anak memasuki siklus baru kemiskinan keluarga dan lebih jauh terjerat dalam kekerasan dalam rumah tangga dan masalah lain.
Tiga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami anak-anak yang menjalani praktek perkawinan anak, khususnya perempuan. KDRT yang dimaksud mulai dari kekerasan verbal, fisik, ekonomi dan seksual. Tingginya jumlah pekerja migran perempuan karena masalah ekonomi keluarga menunjukkan bahwa perkawinan anak membuat anak memasuki siklus ekonomi rentan.
Padahal, dengan menjadi pekerja migran mereka bisa menjadi korban perdagangan orang dengan modus memberi pekerjaan, termasuk dijual untuk industri seks.
Empat, Terganggunya Keadaan Kesehatan Perempuan: praktek perkawinan anak membawa konsekuensi kesehatan pada tubuh anak, khususnya perempuan. Kurangnya pemahaman soal sistem reproduksi dan seksualitas tak jarang membuat pasangan kawin anak terjerat masalah kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan kesehatan mental sang perempuan, hingga kematian ibu dan bayi.
Karena praktek perkawinan anak ini sesungguhnya melanggar hak-hak anak yang dilindungi hukum nasional dan internasional, maka upaya pencegahan pun dilakukan dengan berlapis. Di level nasional misalnya kita telah menyaksikan sendiri bagaimana upaya banyak pihak akhirnya berhasil membuat DPR RI meevisi UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjadi UU Perkawinan No. 16 tahun 2019.
Revisi kebijakan ini tidak hanya menyoal batasan usia perkawinan lho, melainkan ada sejumlah hal lain, yaitu:
- Usia perkawinan: dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi lelaki. Maka pada UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 diubah menjadi batas usia perkawinan bagi perempuan dan lelaki adalah 19 tahun. Perubahan ini didasarkan atas pengaduan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi.
- Syarat sahnya perkawinan: hal ini berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan dengan beda agama, serta penganut kepercayaan.
- Anak anak diluar kawin: hal ini berkaitan dengan status anak yang lahir diluar pernikahan, bayi tabung hingga sewa rahim (surrogate mother).
- Status kepala keluarga: jika selama ini status kepala keluarga merupakan lelaki, maka berbagai pihak mengajukan keberatan, sebab di lapangan justru banyak perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.
- Poligami: UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang sah dan diakui negara merupakan monogami, meski memperbolehkan praktek poligami. Hal ini menjadikan kebijakan ini bias, sebab di lapangan banyak lelaki yang menekan istrinya untuk menyetujui poligami yang dilakuannya melalui pengadilan.

Maka diperlukan kembali sosialisasi sebagai proses membangun kesadaran, misalnya bahwa salah satu syarat untuk menikah itu kesiapan organ reproduksi seperti untuk melakukan hubungan seksual, khususnya bagi perempuan yang mengalami hamil dan melahirkan. Terlebih, diperlukan upaya berlapis agar orangtua, anak dan pemimpin suatu masyarakat memahami dampah buruk perkawinan anak, sebab mereka merupakan pihak yang terdekat dengan kehidupan anak.