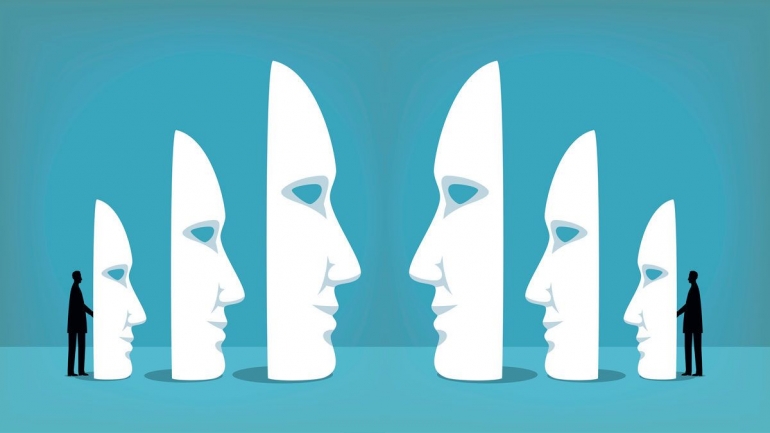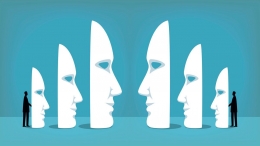George Orwell mengatakan "In time of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act", bahwa di zaman penipuan universal, mengatakan sebuah kebenaran akan menjadi tindakan revolusioner. Ungkapan ini terasa benar, post-truth (pasca-kebenaran) yang sedang menjangkiti manusia post-modern, hidup dalam bayang yang dianggap benar namun sebanarnya itu adalah sebuah kebohongan.
Produk baru yang lahir dari rahim post-modern saat ini yaitu post-truth society atau masyarakat pasca-kebenaran. Post-truth bukanlah gejala positif dari modernisme, melainkan sebuah fenomena accindental, wabah sosial yang telah menjangkiti semua elemen masyarakat.
Wabah sosial ini, sebelumnya tak pernah terdeteksi oleh para teoretikus. Sebaliknya, post-modern didesain untuk menatap masa depan baik bagi umat manusia; keadilan, kesejahteraan, kemajuan dan gairah hermoni masyarakat.
Sosiolog klasik, Auguste Comte sebelumnya, telah meramalkan tahap sejarah intelektual umat manusia yang kemudian dikenal dengan hukum tiga tahap, tahap ke-tiga disebut sebagai akhir dari intelektual kehidupan manusia. Intinya, sejarah manusia secara evolutif akan melalui tiga tahap yaitu teologis, metafisik dan positivistik.
Menurutnya, masa teologis dan metafisik adalah periode di mana nuansa perilaku dan pemikiran manusia masih terikat dengan norma, sistem kepercayaan, cara pandang masyarakat yang terbatas.
Sementara tahap ketiga yaitu positivistik, ditandai dengan perubahan total pada semua aspek kehidupan masyarakat, terjadi dinamisasi pola berfikir yang maju dan progresif. Cara pandang positivisme ini disinyalir menjadi landasan berfikir rasional, pasti dan terukur.
Hingga hari ini, segala capaian modernisme dalam teknologi nyatanya tak dapat melakukan penyelarasan dalam sosial terutama keadilan dan masalah kemanusiaan.
Jika teknologi berguna mempermudah akses manusia, maka sebaliknya teknologi pun menyimpan daya destruksi. Jadi, modernisme berhasil menciptakan manusia positivistik, namun gagal melahirkan produk yang peka terhadap sosial, yang ada adalah memanfaatkan atau dimanfaatkan, dalam istilah Machiavelli yaitu binatang politik yang haus kekuasaan.
Postmodern ingin bebas dari tuduhan itu. Postmodern menawarkan solusi atas kegagalan modernisme dalam menciptakan keadilan dan prinsip kemanusiaan lainnya.
Prinsipnya, postmodern (postmo) adalah perpaduan antara inovasi dan keramahan lingkungan, teknologi dan kesejahteraan, rasionalitas dan norma.
Akan tetapi, ditengah proses itu, proyeksi ini berjalan di luar dugaan, postmo terjangkit wabah yang menghambat implementasi dari terwujudnya positivisme intelektual manusia. Meski, tanda watak rasional itu dominan, tetapi tidak diikuti kemampuan untuk mendeteksi kebenaran.
Dengan demikian, pertanyaan dasarnya adalah jika kita menyadari post-truth adalah wabah sosial, lalu apa solusi untuk mencegah watak post-truth ini? solusinya ada ditangan kekuasaan. Bila kekuasaan mampu membentuk daya pikir ilmiah atau tradisi intelektual dan masyarakat memiliki kesadaran (awareness) untuk mengidentifikasi kebenaran, maka kebohongan, karakter dari pasca-kebenaran tidak akan terjadi.
Masalahnya, kekuasaan telah memanfaatkan post-truth untuk mengendalikan pikiran publik, mendesain agar nampak kekuasaan hadir dengan kebenaran tunggal sehingga kadang ia muncul dengan watak otoriter; pengendali kebenaran, membolak-balikkan fakta atau bahkan berita palsu pun dimanfaatkan hanya kepentingan kekuasan. Watak otoriter kuasa ini melahirkan opsi ketiga setelah kekuasaan dan media yaitu masyarakat. Kekuasaan mengendalikan media, masyarakat memilih jalan lain untuk menciptakan kebenaran.
Jadi, hadirnya post-truth karena kekuasaan gagal membuka keran kebebasan informasi sehingga masyarakat memilih yang sebenarnya palsu (hoax) tetapi dianggap benar untuk melawan otoritarianisme kuasa. Post-truth adalah kegagalan kuasa mentransmisikan kebenaran pada publik, sehingga publik lebih memilih berita fiktif sebagai alat perlawanan.
Contoh sederhana, ketika presiden pada awal pemerintahannya (2014) meyakinkan publik bahwa ekonomi Indonesia akan meroket, kurs-rupiah akan mengalami penguatan, namun faktanya, empat tahun berkuasa, ekonomi Indonesia tak sanggup melawan terjangan kondisi global, meleset dari rencana. Namun, kuasa tetap mengklaim berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan narasi versi kekuasaan.
Post-Truth dan Kekuasaan
Menurut James Ball dalam bukunya "Post-Truth; How Bullshit Conquered The World" menjelaskan, wabah Post-Truth terjadi karena dua fenomena politik yaitu retorika politik presiden Donald Trump dan Brexit, upaya Inggris Raya keluar dari Uni Eropa.
Pertama, memang bukan hal baru dalam kontestasi presiden bahwa retorika hanya komuditas politik. Tetapi pada tahun 2016, Donald Trump membawa warna baru dalam kluster retorikanya terutama tentang sebuah fakta yang tidak masuk akal, tuduhan yang tak dapat dibuktikan sekaligus kontroversial.
Contoh sederhana, kebijakan pajak Donald Trump, ia mengklaim pemotongan pajak dapat membantu mendorong pertumbuhan AS hingga mencapai 5 hingga 6% per tahun; angka di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi domestik selama tiga puluh tahun terakhir.
Kedua, Referendum Britania Raya pada 23 Juni 2016, ketika perusahaan dan politisi Inggris selama berbulan-bulan berupaya mewujudkan referendum yang menegaskan bahwa Inggris akan keluar dari Uni Eropa.
Pada pagi hari, ketika Inggris akan meninggalkan Eropa, mata uang Poundsterling jatuh 10 % terhadap dollar, menyentuh level terendah dalam 31 tahun. Beberapa jam setelahnya, David Cameron telah mempersiapkan upacara pelepasan Inggris dari ikatan 43 tahun Uni Eropa.
Referendum itu sebagai tanggapan atas perpecahan selama beberapa dekade di antara para pendukung mengenai keanggotaan Uni-Eropa. Namun, hingga detik ini upaya referendum itu belum menemukan titik terang.
Di balik agenda itu, untuk memuluskan langkah Inggris keluar dari Uni Eropa, beberapa politisi menyebar berita bohong (hoax). Seperti tentang klaim Inggris membayar 350 juta poundsterling setiap minggu ke Uni Eropa, propaganda tersebut berhasil membujuk warga Inggris untuk memilih keluar Uni-Eropa. Jumlah nominal itu kemudian setelah dikonfirmasi adalah kesalahan data yang disajikan tim kampanye.
Dengan demikian, jika kita menyadari post-truth adalah era kebohongan, lalu siapa yang memproduksi itu?
Menurut James Bill, ada empat produsen kebohongan. Pertama, kebohongan itu diproduksi oleh para politisi dan kekuasaan. Kepercayaan kita pada para politisi sangat rendah, skandal politik, dan korupsi terjadi hampir semua elemen pemerintah, baru-baru ini politikus Romahurmuzy terjerat kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.
Siapa yang tak kenal politisi ini, sosok yang mewakili elemen nasionalis-religius, membius publik dengan retorikanya, merasa paling suci kini menjadi maling negara.
Kedua, yaitu media lama (old media) atau media arus utama. Media tradisonal memainkan peran penting dalam membentuk pandangan publik.
Seringkali, media arus utama menyebarkan berita bohong melalui propaganda ekonomi dan politik meskipun tetap mengklaim bekerja secara objektif.
Ketiga, hadirnya media baru. Media baru memanfaatkan kemudahan akses. Melalui koneksi internet, kita bisa kapan saja, mengakses ragam informasi aktual.
Namun, pada prosesnya, media baru ini tidak menggunakan etika jurnalisme. Media baru ini bagi saya adalah produksi hoax (berita bohong) paling besar.
Keempat adalah Fake news, bersumber dari media sosial yang secara rutin memproduksi berita-berita bohong, berita tentang tujuh kontainer yang berisi surat suara yang telah tercoblos, kasus Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu adalah contoh konkret dari berita bohong (hoax).
Jika, kekuasaan dan media sebagai tulang punggung negara dan demokrasi telah kehilangan kredibilitas dan subjektvitasnya, maka yang terjadi adalah masyarakat akhirnya hanya mempercayai media yang ia yakini tanpa memandang kredibilitas, objektivitas berita yang disajikan.
Maka, untuk mencegah maraknya kebohongan yang merupakan ciri dasar dari post-truth, maka perlu sinergitas semua pihak.
Media harus kembali pada titah awal, menyampaikan kebenaran, tanpa tendensi pada kekuasaan. masyarakat pun dituntut untuk mulai cerdas, memilah sumber berita atau media yang tidak kredibel, tidak mudah terpancing dengan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Post-truth adalah era, di mana kebenaran itu disembunyikan, maka gunakan rasionalitas dan pengetahuan untuk menemukan kebenaran.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H