"Karya-karya sastra sering dengan lihai memanggil kisah masa lalu, menghadirkannya sebagai cermin bagi peristiwa-peristiwa hari ini."
-- Tilaria Padika, "Arok Dedes Pramoedya: Perang Proksi dan Problem Kebhinnekaan"
Semalam saya menonton film. Menarik sekali. Fahrenheit 451 judulnya, adalah film yang baru saja dirilis 12 Mei 2018 oleh HBO. Meski begitu, novel berjudul serupa yang diadaptasi ke film ini sudah terbit sejak 1953. Novelis Amerika Roy Bradbury penulisnya.
Fahrenheit 451 adalah novel distopia, memang--dari filmnya--tak sekelam 1948 milik Orwell. Melalui novel ini, Bradbury mengkritik politik Amerika Serikat di era itu sekaligus mengingatkan akan kemungkinan masa depan yang dihadapi jika kondisi itu terus dibiarkan.
Karena belum membaca versi novelnya, dan tidak tahu apakah versi film adalah adaptasi menyeluruh terhadap novel, saya tulis artikel ini berlandaskan film dengan menambahkan informasi tentang novel itu dari review sejumlah orang.
Film Fahrenheit 451 menceritakan masa depan masyarakat yang anti-buku. Unit Pemadam Kebakaran (Damkar) berubah fungsi menjadi satuan aksi sweeping dan pembakaran buku-buku. Orang-orang yang memiliki buku dihukum dihapus identitasnya dan karena itu tidak bisa hidup normal dalam masyarakat yang sangat terkoneksi dengan teknologi.
Ingatan publik akan masa lalu dihapus. Tak ada jejak tertulis dan digital. Anggota Damkar tidak akan percaya jika dikatakan dahulu tugas unit mereka adalah memadamkan kebakaran, bukan menyulut api pada buku-buku.
Dalam masyarakat masa depan itu, satu-satunya bacaan dan sumber informasi adalah kecerdasan buatan bernama "Nine".
Kita dapat membayangkan Nine sebagai Google yang tanpa pesaing. Tidak ada media daring selain Nine. Seluruh informasi dimasukkan ke dalam Nine, tetapi bukan isi buku-buku bacaan.
Informasi ditulis dan disampaikan oleh algoritma komputer super cerdas. Tak adalagi penulis, jurnalis, bahkan tidak ada media sosial seperti facebook atau twitter. Partisipasi publik dalam jaringan komunikasi daring hanyalah memberi emoticon smile dan like pada berita real time yang disampaikan Nine.
Nine menyampaikan kabar dalam format visual. Orang-orang tidak dapat memilih berita apa yang hendak dipirsa. Arus informasi masuk satu arah, dari Nine kepada publik tanpa bisa difilter.
Nine menyerap informasi melalui kejadian dan percapakan yang direkamnya di tempat publik dan privat. Bahkan di kamar mandi pun ada kamera dan perekam suara cerdas yang dapat berkomunikasi dengan kita.
Dalam film Fahrenheit 451, ketidaktatoran Nine dan negara (dengan unit Damkar sebagai instrumen koersif utama) tidak lahir dari kudeta mesin terhadap manusia seperti film-film distopia lain atau oleh berkuasanya orang gila serupa Hitler atau diktator seperti Soeharto.
Nine muncul karena dikehendaki publik. Dikisahkan ---melalui dialog--- masyarakat Amerika Serikat memilih menyerahkan kebebasannya kepada Nine setelah mengalami pahitnya dampak Perang Sipil. Perang Sipil itu dipicu oleh perdebatan dan pertikaian di tengah masyarakat.
Pengetahuan menjadi kambing hitam. Publik meyakini bahwa perang disebabkan orang-orang berpengetahuan. Orang-orang yang bepengetahuan akan memiliki mimpi-mimpi, ideal-ideal. Ketika tiap-tiap orang memperjuangkan idealismenya, benturan gagasan dan konflik dalam tindakan akan terjadi. Ujungnya perang sipil!
Perang membuat orang tidak bahagia. Tentu saja. Karena itu pengetahuan menjadi musuh bersama. Buku sebagai sumber pengetahuan harus dilenyapkan. Orang-orang yang membaca, yang berpikir, yang memimpikan masa depan bersama yang lebih baik adalah para penjahat.
Demi kebahagiaan, orang-orang merelakan kebebasannya ke tangan kediktatoran teknologi. Mereka menciptakan diktator bagi diri sendiri.
Latar belakang novel Fahrenheit 451
Menurut Om Ben Travers, kritikus TV yang menulis untuk Indiewire.com, ada banyak perubahan besar dalam isi film Fahrenheit 451 tetapi tanpa mengubah tema.
Perubahan itu dibuat agar film lebih kontekstual dengan kondisi 2018. Contohnya, di dalam film yang dibakar bukan hanya buku tetapi juga hard disk komputer. Kehadiran Nine, sistem jaringan sekaligus media daring tunggal yang mengontrol segala tampaknya juga baru ditambahkan di dalam versi film.
Saya menduga begitu sebab Om Ramin Bahrani, sutradara dan screen writer-nya katakan, "Really what [we're] getting into is consolidated internet and internet controlled not by a handful of companies but by one, right? Say if Google or Facebook joined forces and there was not much of anything else left, then they could control and censor anything. And suddenly physical things have a different power."
Perubahan lain adalah karakter utama perempuan, Clarisse (diperankan penari Algeria yang keren, Sofia Boutella) yang dalam novel adalah anak perempuan kecil, pada versi film berubah menjadi gadis muda yang saling cinta dengan Montag (Michael B. Jordan) karakter utama yang kemudian tewas (bahkan ending-nya pun berbau distopia). Tampaknya Clarisse-Montag juga sudah begituan. Simak saja sendiri nanti.
Sayangnya Om Ben Travers tidak menulis apappun tentang latar belakang sosial-ekonomi-politik yang melahirkan novel ini atau yang dikritik novel ini.
Saya kemudian menemukan soal itu dalam rekaman wawancara radio Om Roy Bradbury pada 1956 dalam situs oldradioprograms.us.
Rupanya Novel Fahrenheid 451 lahir sebagai kritik atas Mc Carthyism di Amerika di masa yang sama.
Mc Carthyism adalah ideologi dan praktik teror domestik pemerintahan Amerika Serikat kepada warga negara sendiri pada 1947-1956. Disebut dengan nama tokoh utamanya, Senator Mc Carthy.
Pada periode 1947-1959 kehidupan sosial-politik di Amerika Serikat penuh ketakutan oleh tindak represif pemerintah dan karena itu dikenal sebagai Second Red Scare. Era ini ditandai oleh masifnya pembungkaman terhadap kebebasan sipil dengan dalih untuk menghidari pengaruh Komunis di Amerika Serikat.
Di masa itu, para PNS, guru dan dosen, aktivis serikat buruh serta pekerja seni dan media di-litsus. Mereka yang dituduh berideologi komunis dikeluarkan dari pekerjaan. Naskah-naskah karya penulis yang dicurigai komunis dilarang difilmkan. Banyak di antara mereka dipenjara tanpa pengadilan yang fair.
Saya pernah menulis tentang masa ini ketika meresensi film Trumbo, salah satu film yang mengisahkan Hollywood Ten, yaitu 10 penulis naskah yang masuk daftar hitam Pemerintahan Truman (Senator Mc Carthy sebagai panglima dari perang khayalannya). Saya lupa pernah dimuat di mana artikel itu. Tidak terlacak lagi jejak digitalnya.
Novel Fahrenheit 451 adalah kritik Roy Bradbury terhadap masa itu, yaitu ketika publik Amerika Serikat membenarkan tindakan pemerintah, merelakan kebebasan mereka dalam berpikir dan berkebudayaan demi hal abstrak yang disebut kebahagiaan. Orang-orang percaya kebahagiaan bisa tercipta jika individu-individu tidak berpikir, tidak membaca, tidak bercita-cita. Terima saja kebenaran tunggal yang disediakan negara bagimu.
Indonesia dalam ketakutan-ketakutan
Sebagai film ---juga novel tentunya--- Fahrenheit 451 sangat kontekstual untuk kehidupan Indonesia. Pelarangan buku-buku kritis sejak Orde Baru hingga kini masih terjadi. Bedanya jika dulu garda depannya adalah Kejagung dan aparatus militer, kini aksi-aksi sweeping dan pembakaran buku dilakukan oleh milisi sipil bekas binaan tentara (ratih/PAM Swakarsa) seperti FPI.
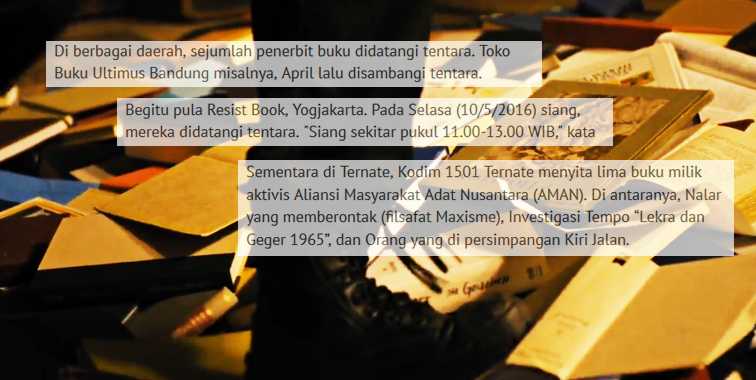
Baca artikel terkait perang melawan terorisme: Sertifikasi Penceramah dan Penalaran Compang-camping Politisi
Oleh ketakutan terhadap teror dan kebencian yang diproduksi kelompok-kelompok puritan fundamentalis, publik berkecenderungan menyerahkan kekebasannya. Dalam percakapan daring tampak jelas semangat untuk mendukung represi terhadap kebebasan berpendapat.
Kian mencemaskan jika melihat besarnya dukungan publik terhadap RUU Anti-Terorisme yang memuat pasal Guantanamo yang memberikan hak kepada aparatus koersif untuk bisa menahan terduga teroris selama 6 bulan tanpa pengadilan.
Orang-orang yang hidup selama masa Orde Baru seharusnya tahu persis bagaimana aparat koersif bertindak sewenang-wenang, dimobilisasi institusi politik (pemerintah) untuk memukul musuh-musuhnya. Kita baru saja memperingati 20 tahun kebebasan dari masa itu, dengan realita lapangan praktik-praktik peninggalan dua dekade lalu masih diterapkan.
Kini, oleh ketakutan-ketakutan akan terorisme, kita cendrung bereaksi membabi-buta, lupa jika pemberian wewenang berlebihan kepada aparatus koersif negara justru berpotensi menjerumuskan kita ke bentuk lain terorisme: official terrorism, teror yang dilakukan negara.
Kita pernah mengalaminya. Tiga puluh dua tahun lamanya!
Menyikapi kondisi Indonesia kini memang tidak mudah, Om-Tante. Kita sering berhadapan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang seolah-olah simalakama (Baca: "Sertifikasi Penceramah dan Penalaran Compang-camping Politisi"). Jangan mudah menyerah untuk mencari jalan terbaik. Untuk mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Ya, Om-Tante. Semoga perlawanan terhadap teror dan aksi-aksi kebencian kaum puritan fundamentalis tidak menjerumuskan kita untuk mengarah kembali ke masa itu. Melek literasi mungkin salah satu kunci untuk mencegahnya.
***
Tilaria Padika
22052018
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H








