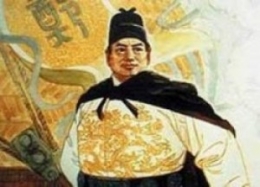[caption id="attachment_96955" align="alignleft" width="490" caption="http://dandry.wordpress.com/category/uncategorized/"][/caption]
Sampuraga dan Malin Kundang
Kalau disebutkan nama Sampuraga, apa yang pertama terlintas di pikiran kita? Anak durhaka, bukan? Tapi Sampuraga dari Sumatera Utara bukanlah satu-satunya anak durhaka dalam folklore kepunyaan Indonesia. Ada Malin Kundang dari Sumatera Barat yang jauh lebih terkenal. Juga ada Amat Rhang Mayang dari Aceh yang belum dikenal publik. Last but not least, masih ada juga Sampuraga dari Kalimantan Tengah. Loh kok Sampuraga lagi?
Sampuraga yang kita kenal adalah si anak miskin dari Padang Bolak yang merantau ke negeri Mandailing dan akhirnya menjadi orang kaya, dan saat menyelenggarakan pesta pernikahannya ia dikutuk sang ibu karena kedurhakaannya. Kolam Sampuraga, yang menjadi obyek wisata Pemerintah Mandailing Natal dipercayai sebagai bukti kutukan itu. Setidaknya itulah yang menjadi inti cerita tentang Sampuraga versi Mandailing yang dapat kita baca dari situs berikut: http://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/asal-mula-kolam-sampuraga-di-mandailing-natal/
Sampuraga versi lainnya dikisahkan sebagai folktale pada banyak keluarga suku Dayak Tomun di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Seperti halnya kisah Sampuraga dari Sumatera Utara dan cerita Amat Rhang Mayang dari Aceh, suku Dayak Tomun menganggap cerita Sampuraga sebagai cerita yang benar-benar terjadi di Kalimantan Tengah. Jika kita lihat dari segi bentuk, struktur cerita, dan persepsi yang terkandung di dalamnya, kisah Sampuraga dari Kalimantan Tengah lebih mirip dengan kisah Malin Kundang ketimbang Sampuraga dari Sumatera Utara.
Malin Kundang dan Sampuraga versi Dayak Tomun sama-sama menyebutkan tentang kapal dan tokoh utamanya yang dikutuk ibunya menjadi batu. Kapal Malin Kundang menjadi batu di Pantai Air Manis, Teluk Bayur di Kota Padang. Demikian pula kapal Sampuraga yang menjelma bukit berbentuk kapal 2 kilometer dari tepian sungai Belantikan di desa Karang Besi, Kabupaten Lamandau. Lalu kenapa nama tokohnya sama dengan tokoh anak durhaka dari Sumatera Utara? Suatu kebetulan atau telah terjadi salah persepsi saat ceritanya diwariskan? Lalu siapa penutur aslinya? Bagaimana seharusnya folktale itu diceritakan?
(Karena cerita Sampuraga versi Dayak Tomun bercampur aduk dengan Malin Kundang, saya jadi teringat dengan naskah Puti Bungsu (Wanita Terakhir) karya Wisran Hadi. Beliau menggabungkan tiga mitos dalam narasi berbeda: Malin Kundang, Malin Deman dan Sangkuriang dalam satu ruang teks cerita baru: Puti Bungsu. Jangan-jangan Wisran sendiri yang meramu cerita Sampuraga tersebut? Hehehe...)
Cerita rakyat adalah salah satu bagian dari folklore. Pada umumnya, cerita rakyat hanya berbentuk cerita lisan yang diceritakan secara turun temurun. Indonesia- yang terdiri dari berbagai suku bangsa - sangat kaya dengan cerita rakyat, peribahasa, pantun, mitologi, legenda, mau pun dongeng. Cerita-cerita tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat pendukungnya masing-masing. Dilihat dari beragam cerita rakyat yang tersebar di berbagai daerah, tampak adanya kesamaan bentuk penceritaan antara cerita rakyat daerah yang satu dengan daerah lain. Perbedaannya hanya terletak pada versi dan warna lokal daerah masing-masing.
Saat menulis cerita Sampuraga di Wikipedia saya merasa sedang memainkan genealogi dengan obyeknya tokoh utama dalam folktale tersebut. Sayang sekali saya hanya mengandalkan sisa-sia ingatan seorang staf saya di Lamandau sebagai narasumbernya. Kalau ada di antara pembaca yang lebih mengetahui cerita sebenarnya, dipersilahkan ikut menyuntingnya. Wikipedia milik kita bersama kok.
Kisah Sampuraga
Konon, menurut cerita yang diwariskan turun temurun dalam keluarga suku Dayak Tomun, seorang bangsawan dari sebuah kerajaan di Sumatera berlayar sampai ke kerajaan Petarikan, di hulu sungai Belantikan, pedalaman Kalimantan. Namanya Patih Sebatang. Tidak jelas apakah Patih Sebatang ini sama dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang, tokoh legendaris masyarakat Minangkabau.
Di kerajaan yang bersahaja ini, Patih Sebatang dikisahkan berjumpa dengan seorang putri Kerajaan Petarikan yang cantik jelita. Namanya Dayang Ilung, yang digambarkan memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona, kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alis matanyanya bagai semut beriring, rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Singkat cerita Patih Sebatang jatuh cinta dan akhirnya menikahi sang putri.
Tidak lama kemudian, Dayang Ilung melahirkan seorang putra, yang dinamai Cenaka Burai. Entah bagaimana kisahnya Patih Sebatang akhirnya berpisah dengan isteri tercintanya. Selain buah cintanya yaitu Cenaka Burai, satu-satunya kenang-kenangan yang mempersatukan cinta mereka adalah cincin pernikahan yang selalu disimpan baik oleh Patih Sebatang.
Sampuraga dibesarkan ayahnya sebagai seorang pemuda yang berharkat dan bermartabat tinggi. Dan entah bagaimana asal-usulnya, Cenaka Burai juga kelak dipanggil sebagai Sampuraga. Kemudian ketika sudah dewasa Sampuraga diceritakan ayahnya bahwa ibunya ada di sebuah kerajaan nun jauh di hulu sungai Belantikan. Sampuraga berkeras ingin menjumpai ibu kandungnya tersebut, dan meminta apa ciri-ciri ibunya. Sang ayah pun menceritakan kecantikan ibu kandung Sampuraga, dan menunjukkan sebuah cincin pernikahan mereka.
Dibekali dengan cincin pernikahan ayahnya, Sampuraga pergi berlayar sampai ke kerajaan Petarikan. Sesampainya disana, masyarakat membawanya menemui sang ibu yang sudah tua. Dayang Ilung ternyata telah bertahun-tahun menantikan kembalinya anak kandungnya. Bukan main senangnya Dayang Ilung mengetahui buah hatinya menjumpainya langsung. Hampir saja ia memeluk Sampuraga, tapi Sampuraga menolak. Sampuraga tidak percaya bahwa wanita asing di depannya tersebut adalah ibunya sendiri. Ayahnya telah menceritakan kecantikan sang ibu. Bagaimana mungkin wanita yang tua renta tersebut adalah puteri cantik yang diceritakan sang ayah?
Sampuraga masih ingin membuktikan lagi. Dikenakannya cincin pernikahan ayahnya kepada wanita tua itu. Karena Dayang Ilung sudah dimakan usia, cincin tersebut menjadi terlalu besar untuk melingkari jari-jarinya. Sampuraga semakin yakin bahwa wanita itu bukan ibunya. Sampuraga memutuskan untuk pulang.
Dayang Ilung kecewa. Ia berkata kepada Sampuraga, "Nak, kamu sudah meminum susu dari tubuhku. Kalau kamu tidak mau mengakuinya, kamu akan terkena malapetaka!"
Dengan amarah di dalam dada, Sampuraga berlayar pulang. Dia tidak habis pikir, kenapa ada wanita tua yang bersikeras meyakinkan Sampuraga bahwa dia adalah ibunya, padahal ayahnya sudah jelas memberitahu ciri-ciri sang ibu.
Di tengah jalan, tiba-tiba badai menghadang. Kapalnya oleng diombang-ambingkan ombak besar. Ketika kapalnya hampir karam, Sampuraga teringat kutukan wanita tua tersebut. Hati kecilnya tiba-tiba disadarkan bahwa dia baru saja durhaka pada ibunya sendiri.
"Ibu, ibu, kamu memang ibuku!" demikian Sampuraga memohon ampun.
Tiba-tiba terdengar suara ibunya, "Nak, sudah jatuh telampai. Tidak mungkin keputusan ditarik kembali. Kutukan sudah terjadi."
Demikianlah Sampuraga membatu bersama kapalnnya
Dayak Tomun dan Patih Sebatang
Tidak adil rasanya membicarakan Sampuraga tanpa menyinggung suku yang menuturkannya: Dayak Tomun. Dayak Tomun (Tomon, atau Tumon dalam beberapa tulisan) bukanlah nama diri atau nama suatu suku. Dayak Tomun adalah penamaan untuk sekelompok suku Dayak yang mendiami Daerah Aliran Sungai Lamandau di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kata "Tomun' bisa diartikan "berbicara, bermusyawarah, bertemu, adanya perjumpaan untuk saling memahami, mengerti, dan mengetahui benar, serta memaklumi". Tomun artinya kaum yang mudah berhubungan satu sama lain dalam satu rumpun. Walaupun terdiri dari berbagai dialek yang berbeda, mereka masih bisa saling berkomunikasi seakan-akan satu suku. Karena kadang-kadang beda dialek antara desa-desa setetangga hanya pada huruf terakhir, kita tidak harus mempelajari semua dialek. Kalau di desa Tapin Bini bertanya Honak Kamuna artinya Hendak kemana, maka kalimat itu menjadi Honak Kamuno dalam dialek Delang. Begitulah pemahaman makna "Tomun".
Saya menghabiskan satu setengah tahun pengabdian saya di tengah-tengah masyarakat Dayak Tomun. Fenomena yang paling menarik saya bukanlah kuyang, alias hantu terbang yang pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi fakta bahwa salah satu desa di Kabupaten Lamandau mempunyai benang merah dengan suku Minangkabau di Sumatera Barat. Waktu pertama kali bertugas di Kalimantan, kami disambut dengan pesta adat di desa Kudangan, desa terpencil di Kabupaten Lamandau.
Desa Kudangan yang dihuni oleh suku Dayak Delang yang merupakan rumpun Dayak Tomun. Tapi bentuk rumah mereka mirip rumah gadang dengan atap melengkung sebagai tanduk kerbau seperti di Sumatera Barat. Ada lagi kebiasaan kaum laki-laki di Kudangan mengunyah daun sirih dan sebaliknya wanita mengisap rokok kelintingan buatan sendiri. Bahasa sehari-hari yang dipergunakan adalah bahasa suku Dayak Delang, namun dialek dan sebutan kata-katanya banyak kesamaan dengan bahasa daerah Minangkabau, yang selalu berakhir dengan huruf o dan Ik. Seperti contohnya antara lain duo = dua, sanjo = senja/sore, kepalo = Kepala, takajuik = terkejut dan lain sebagainya.
Penduduk Kudangan meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat sejak abad ke 14. Menurut cerita seorang bangsawan dari Kerajaan Pagaruyung yang bernama Malikur Besar Gelar Patih Sebatang Balai Seruang berlayar ke Kalimantan. Memasuki suatu alur sungai, Datuk Malikur Besar itu tertarik dengan suatu daerah dan mendirikan kerajaan kecil yang diberi nama "Kudangan". Rombongan Datuk Malikur Besar ini berbaur dengan penduduk asli setempat.
Bukti kerajaan Kudangan keturunan Pagarruyung itu, yang sekarang menjadi kecamatan Delang adalah adanya sejumlah peninggalan bersejarah antara lain suatu bendera berukuran 3 kali 1,5 meter dan hingga kini disimpan dengan baik di rumah adat Kudangan.
Saya juga memperhatikan bahwa kebanyakan warga suku Dayak Tomun mengakui diri mereka sebagai keturunan Patih Sebatang. Saya percaya bahwa Patih Sebatang yang mereka sebut itu adalah Datuak Parpatiah Nan Sabatang, tokoh terkenal dari Minangkabau.
Datuak Parpatiah Nan Sabatang

Siapa tokoh ini? Datuak Parpatiah Nan Sabatang adalah misteri bagi saya. Apakah dia pernah benar-benar ada dalam sejarah, atau sebagai legenda saja? Suku Minangkabau, dari dahulu hingga sekarang, mempercayai dengan penuh keyakinan, bahwa dia seorang tokoh adat terkenal yang berasal dari Limo Kaum dan dianggap pendiri Adat Koto Piliang dan Adat Bodi Caniago yang sampai sekarang masih hidup subur di dalam masyarakat Minangkabau, baik yang ada di Sumatera Barat sendiri maupun yang ada diperantauan.
Ada petunjuk bagi kita bahwa dia memang merupakan tokoh sejarah Minangkabau. Pitono mengambil kesimpulan bahwa dari bait kedua prasasti pada bagian belakang arca Amogapasa, antara tokoh adat Datuk Perpatih Nan Sabatang dengan tokoh Dewa Tuhan Perpatih yang tertulis pada arca itu adalah satu tokoh yang sama.
Dijelaskan selanjutnya bahwa pada prasasti itu tokoh Dewa Tuhan Perpatih sebagai salah seorang terkemuka dari raja Adityawarman yaitu salah seorang menterinya. Jadi tokoh Dewa Tuhan yang ada pada prasasti yang terdapat di Padang Candi itu adalah sama dengan Datuk Perpatih Nan Sabatang. Demikian kesimpulannya.
Dalam catatan sejarah, Datuak Parpatiah Nan Sabatang, hidup pada waktu pemerintahan Adityawarman, pada awal abad ke-14 (1315 M). Dalam salah satu versi sejarah disebutkan keberadaan Adityawarman menjadi raja di Kerajaan Pagaruyung, tercatat Datuk Parpatiah Nan Sabatang selaku patih kerajaan. Sudah berapa lama riwayat etnis Minangkabau terbentang, sekian banyak pula para ahli sejarah mencari tahu dimana makamnya, namun sedikit ahli sejarah yang dapat mengemukakan kehidupan beliau.
Nah, sebagai tokoh panutan dalam masyarakat Minangkabau, Datuk Parpatiah Nan Sabatang, mempunyai kesukaan mengembara, tidak saja di Minangkabau, tapi sampai ke tanah Jawa. Dalam pengembaraannya, beliau selalu menimba berbagai ilmu dari negeri-negeri yang dikunjunginya. Apakah dia sempat mengunjungi Kalimantan? Patih Sebatang saya dapati menjadi tokoh lokal pada beberapa suku di Indonesia yang karakternya disesuaikan dengan setting setempat. Herwiq dan Zahorka meyakini bahwa memang ada benang merah antara suku Minangkabau di Sumatera Barat dan Dayak Tomun di Kalimantan. Benang merahnya itu adalah Patih Sebatang.
Laksamana Cheng Ho versus Sampuraga

Tokoh ini begitu terkenal. Saya tidak perlu mengomentarinya lagi. Tapi sebagaimana cerita lain, tokoh legendaris ini muncul dalam beberapa tempat di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan satu fakta saja: Cheng Ho atau Zheng He disebut juga Dampu Awang atau Dampo Awang. Artinya, Dang atau Sang Puhawang yang menurut Mira Sidharta adalah nakhoda kapal.
Cerita tentang Dampu Awang terdengar baik di Lampung maupun Palembang. Di Lampung menyebut Dampu Awang sebagai Pangeran Sebatang. (Atau Patih Sebatang? Entahlah) Raja Iskandar, sang ayah, membuang Pangeran Sebatang ke laut. Bayi mungil itu terapung-apung, lalu diselamatkan burung garuda. Setelah besar, raja menyesal, lalu memberi Pangeran Sebatang sebuah kapal, lengkap dengan kelasi dan peralatannya. Dengan kapal itu, ia berlayar ke Majapahit dan diberi gelar Raden Puhawang atau Dang Puhawang atau Dampu Awang.
Apa hubungannya Laksamana Cheng Ho dengan kisah Sampuraga ya? Dengar baik-baik: Dalam cerita rakyat Palembang, Dampu Awang diceritakan sebagai anak durhaka. Dampu Awang dikisahkan pergi merantau, dan setelah berhasil pulang ke Palembang dia tidak mengakui ibunya. Ia dikutuk sehingga kapal besarnya berubah menjadi batu. Di muara sungai, ada daerah bernama Batu Ampar. Daerah itulah yang oleh penduduk sekitar disebut bekas kapal Dampu Awang. Betapa mirip dengan kisah Sampuraga, eh Malin Kundang, bukan? Silahkan baca dalam :
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2005/08/29/SEL/mbm.20050829.SEL116437.id.html
Saya tidak bisa membayangkan bagaimana tokoh sekelas Laksamana Cheng Ho membatu seperti Sampuraga.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI