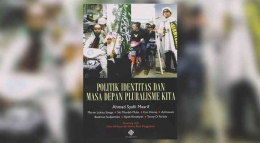Dalam konteks Indonesia, tulis Budiman, politik identitas merupakan antitesa dari politik sentralistik dan hegemonik selama Orde Baru berkuasa. Kelompok-kelompok yang menguat kemudian terkonsentrasi pada kekuatan politik Islam. Justru kondisi ini disebabkan oleh hidupnya demokrasi pasca tumbangnya rezim otoriter Soeharto.
Lalu fenomena populisme--di mana Budiman menyebutnya dengan politik kuantitas, yaitu kepemimpinan yang mementingkan kuantitas dengan jalan pencitraan--semakin menyebabkan menguatnya politik aliran, terutama Islam, yang mementingkan kualitas--lawan dari istilah politik kuantitas--yaitu kepemimpinan yang berdasarkan ideologi, idealisme, kompetensi, dan komitmen.
Setidaknya dalam analisa Budiman Sudjatmiko, ada peluang bahwa kelompok Islam progresif tidak semata berposisi sebagai objek yang dibicarakan, tetapi bisa menjadi subjek yang berbicara mengenai ketidakadilan suatu rezim. Dan rezim yang mendapat reaksi dari kelompok-kelompok seperti itu bisa jadi adalah "pelaku" dan bukan selamanya "korban" dari aksi-aksi perlawanan itu (paradigma "pelaku" dan "korban" ini sebagaimana yang sudah saya gambarkan pada tulisan terdahulu, dalam membedakan kerangka kultural dan kerangka rasional).
Sayangnya Budiman membatasi contoh pencitraan hanya pada era SBY, sedang fenomena pencitraan juga banyak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Blusukan, dekat dengan wong cilik, dekat dengan ulama (dibuktikan utamanya dengan diangkatnya K.H. Ma'ruf Amin sebagai Wapres), berjiwa nasionalis, anti-diskriminasi, tidak bagi-bagi kursi kekuasaan, dan tidak otoriter, menjadi kata kunci dalam citra sosok Jokowi.
Jika kita konsisten dengan menyebut politik identitas sama dengan politik aliran dan sama dengan politik berjubah, maka apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta lingkarannya juga adalah politik identitas, politik yang berjubah ideologi nasionalis, yang memusuhi kekuatan Islam radikal intoleran, yang saya kira sama potensi berbahayanya dengan politik identitas berjubah Islam.
Kalau Jokowi dicitrakan sebagai ikon politik yang nasionalis (bukan Islamis dan komunis), maka apa yang akan kita katakan jika nasionalis itu ternyata membungkam orang-orang kritis dengan UU ITE atau mematikan mik pada saat rapat; bahwa nasionalis itu membubarkan kelompok progresif semacam HTI yang masih menempuh jalan demokrasi dan dialog; bersikap tutup telinga terhadap suara rakyat dengan tetap mengesahkan Omnibus Law padahal rakyat menolak; bahwa nasionalis itu dihiasi dengan pembiaran buzzer-buzzer yang menyakiti hati lawan politik dan dibebaskan dari pasal ujaran kebencian?
Tidakkah politik identitas berjubah nasionalis itu juga pada akhirnya mengancam demokrasi?
***
Dengan demikian saya berkesimpulan bahwa politik identitas yang kerap disematkan kepada pihak di luar pemerintahan adalah tuduhan yang tidak fair. Karena sesungguhnya politik identitas juga tidak khas Islam dan seringkali ditempatkan pada posisi yang keliru.
Demikian juga kepada Anies Baswedan, tuduhan politik identitas hanya karena kedekatan dengan kelompok Islam progresif sudah cacat sejak dini. Pertama, karena kegagalan (atau bermasa bodoh?) dalam membaca sikap politik seorang Anies. Kedua, kegagalan membaca kepentingan politik dari lawan Anies. Ketiga, kurang memahami sejarah pergerakan kemerdekaan, di mana kekuatan Islam turut menentukan tercapainya kemerdekaan.
Keempat, generalisasi aneka kelompok Islam progresif ke dalam satu stereotipe tunggal: Islam radikal intoleran. Kelima, lupa kalau sekelas Presiden Soekarno saja pernah gagal melebur kelompok Islam progresif bersama komunis dan nasionalis dengan konsep nasakom, karena pikiran antar kelompok tidak dapat diseragamkan, hanya bisa didialogkan.