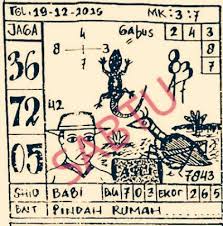Jinem menarik nafas. “Suara dari masjid, Saryun?”
Dan lelaki itu malah tersenyum sadar dengan ketidaknyambungannya. “Kalau kamu beli buntut togel, kamu bisa ditangkap!” ujar Jinem. “Sekali-kalilah, aku ingin lihat kamu ke masjid Jumatan. Biar punya ilmu. Jangan cuma waktu ada sembelihan hewan kurban!”
Saryun merasa dipojokkan. “Bukankah daging itu juga buat kamu. Buat makan enak kita sekali setahun?” Lelaki itu lantas berdiri, melangkah bergegas keluar rumah. Ia urung makan, dan mencari orang yang sama-sama belum terpanggil berjumatan.
Malam-malam berikutnya setelah hari jumat itu menjadi malam yang menggelisahkan Saryun. Ia tak lagi mendengar nada-nada indah tokek rumahnya. Suasana sepi. Tapi ada yang berkecamuk pada dada Saryun, ia seperti tengah kehilangan harapan. Harapan pada suara tokek yang bersahabat itu.
Saryun sudah mengelilingi rumah. Di atap rumah, di kolong tempat tidur, belakang meja dan entah tempat mana lagi, ia sudah menelisik mengendus keberadaan tokek. Hasilnya nihil. Sementara ia berusaha untuk tenang dan tidak melibatkan Jinem. Tapi pertahananya jebol!
“Kamu kemanakan tokek itu, Jinem?” tanya Saryun.
Dengan tongkat penyangga tubuhnya, perempuan itu menunjuk usuk bambu rumahnya. “Kemarin di sana!” perempuan itu pun menjawab cepat. Tatapan Saryun mengikuti arah tongkat istrinya. “Kemarin! Sekarang di mana?” lelaki itu gusar, seperti tengah dipermainkan istrinya.
“Kamu seperti kehilangan jimat saja, suamiku!” Jinem bersuara sambil tersenyum. Dan lelaki yang ada di hadapannya seperti sudah menguatkan dugaan, hilangnya tokek itu bukan karena pergi. Tapi karena istrinya. “Aku menyuruh Jumino menangkapnya.”
Saryun membatin: kurang ajar! Agaknya ia enggan melontarkan ujaran itu.
“Itu artinya kita tak ada harapan untuk berobat. Mengobati kulitmu, Jinem!” Saryun benar-benar kesal, itikad baiknya tidak bersambut.
Jinem tertawa lepas mendengar pembelaan suaminya. “Ya, itu menurutmu. Bagiku kini malah sangat punya harapan.”