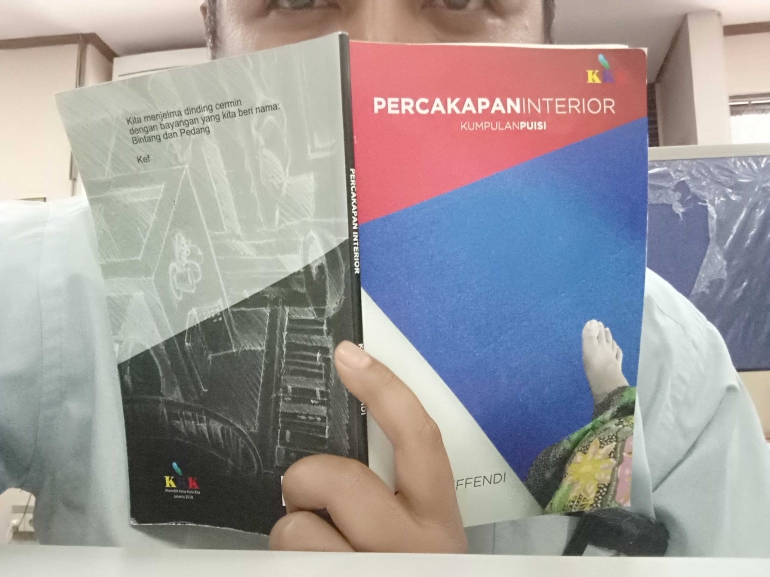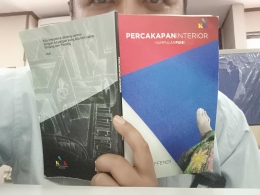Hampir tak punya nama
Di sini kerinduan Kef pada keutuhan diri sebagai manusia ditampilkan. Nama adalah persoalan identitas. Manusia akan tenggelam dalam hiruk-pikuk modernisasi dan menjadi tak berarti siapa dirinya. Pertanyaan "siapa diri" dalam konteks interior alam semesta adalah keberartian sebagai manusia. Kita adalah debu semesta raya. Namun, selaiknya, setitik debu pun memiliki makna.
Relasi modernisasi yang berlanjut ke pembebasan interior itu kita temukan dalam banyak puisi Kef. Dalam hal ini, kita pun dipaksa mengingat kembali ungkapan Seno Gumira Ajidarma dalam Menjadi Tua di Jakarta: "Alangkah mengerikannya menjadi tua dengan kenangan masa muda yang hanya berisi kemacetan jalan, ketakutan datang terlambat ke kantor, tugas-tugas rutin yang tidak menggugah semangat, dan kehidupan seperti mesin, yang hanya akan berakhir dengan pensiun tidak seberapa." Diam-diam, Kef ingin menanamkan rasa takut itu ke benak pembaca.
Beliau yang sudah mengalami pensiun kini kembali ke ruang di dalam dirinya. Di sana ia mengenang, sekaligus memikirkan ulang segala hal yang pernah ia lalui dan ia miliki. Tapi ia tidak otoriter terhadap tafsir. Ia membebaskan pemaknaan kepada pembacanya. Ia bahkan tetap membuka pintunya terhadap kemungkinan-kemungkinan penciptaan. Puisi dari kata poiesis berarti penciptaan itu. Dari Joko Pinurbo, GM, Afrizal, hingga Emi Suy ia jadikan tamu di ruang miliknya. Dengan kerendahan hati, ia biarkan para tamu itu menghiasi ruang.
Luasnya tafsir yang bisa hadir di benak pembaca bahkan sudah bisa kita saksikan sejak puisi pertama.
Masih berdesir harum itu, menetap di serat katun sofa,
Tempat dudukmu---dan bokong yang kuremas itu---
Sebelum jatuh senja
Seperti yang sudah-sudah, kautinggalkan jejak lain:
Sidik bibir pada lengkung cangkir,
Sebelum ciuman terakhir